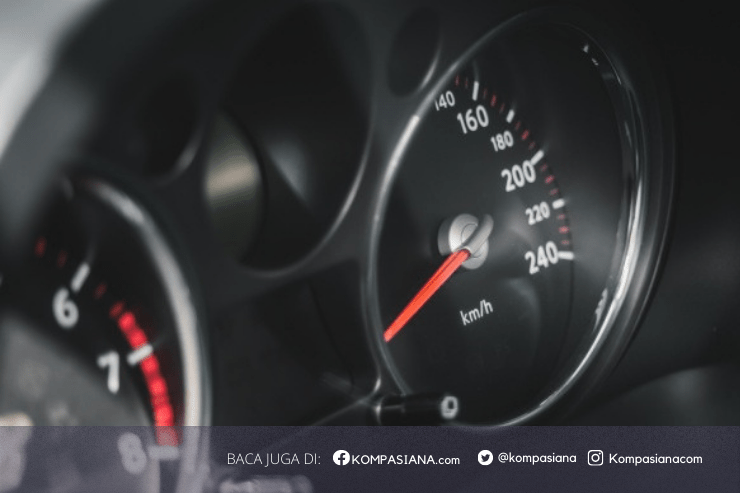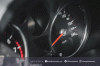Janji Hijau yang Setengah Matang
Rencana pamong negara memperluas penggunaan campuran ethanol dalam bahan bakar tampak seperti langkah hijau yang progresif. Katanya demi menekan impor BBM dan menurunkan emisi karbon. Ide yang tampak cemerlang---sampai orang mulai bertanya: apakah masyarakat sudah siap, atau ini sekadar proyek hijau di atas kertas?
Indonesia memang harus bergerak menuju energi bersih. Tidak ada perdebatan soal itu. Tetapi dalam setiap transisi energi, yang menentukan bukan semangat pejabat, melainkan kesiapan sistem dan hak masyarakat untuk memilih. Di sinilah logika kebijakan sering kehilangan arah: perubahan yang seharusnya bertumpu pada kesadaran publik justru dipaksakan lewat aturan top-down.
Belajar dari Negara Lain
Bahan bakar bercampur ethanol (E5 hingga E10) bukan hal baru. Banyak negara sudah menggunakannya. Bedanya, di sana masyarakat diberi pilihan.
Di SPBU Brasil, Thailand, dan Amerika Serikat, konsumen bebas memilih: bensin murni, campuran ethanol ringan, atau tinggi. Pasar yang memutuskan mana yang lebih efisien dan sesuai kendaraan. Pamong negara hanya mengatur standar dan pajak, bukan memaksa semua kendaraan menelan ethanol tanpa kompromi.
Masalahnya, tidak semua kendaraan di Indonesia siap dengan campuran ethanol. Sebagian besar motor dan mobil lama masih memiliki komponen karet dan logam yang mudah korosi. Konsumen yang salah isi tangki bisa menanggung risiko mesin kasar, konsumsi boros, bahkan kerusakan. Apakah pamong negara siap mengganti semua itu? Atau publik yang akan diminta menanggung konsekuensinya atas nama "energi hijau"?
Kebebasan di SPBU
Kalau pamong negara yakin ethanol adalah masa depan, biarkan keyakinan itu diuji di pasar.
Pertamina boleh menjadi pelopor menyediakan campuran ethanol, tapi SPBU swasta sebaiknya diberi ruang menentukan sendiri: apakah menjual bahan bakar ethanol atau non-ethanol. Masyarakat pun bisa memilih berdasarkan harga, performa, dan keyakinan.
Bukankah kebebasan memilih adalah esensi dari ekonomi pasar yang katanya kita junjung tinggi? Pendekatan berbasis pilihan ini jauh lebih masuk akal ketimbang pemaksaan administratif. Pamong negara tidak perlu menguras energi menjelaskan kenapa mesin mogok setelah kebijakan baru diterapkan. Publik pun tidak merasa jadi kelinci percobaan kebijakan yang belum matang.
Saatnya Bicara Pajak Karbon
Kalau tujuan utamanya memang mengurangi emisi karbon, mengapa tidak memakai instrumen yang sudah lebih dulu disiapkan: pajak karbon?
Sejak Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) disahkan tahun 2021, pamong negara sebenarnya sudah memiliki dasar hukum untuk mengenakan pajak tambahan pada aktivitas beremisi tinggi, termasuk bahan bakar fosil. Namun sampai kini implementasinya belum berjalan penuh. Padahal, di situlah peluang cerdas itu berada.
Daripada memaksa semua orang memakai bahan bakar bercampur ethanol, lebih baik pamong negara menyesuaikan harga energi dengan jejak karbonnya. BBM beremisi tinggi dikenakan pajak lebih besar, sementara bahan bakar rendah emisi---bioetanol, biodiesel, atau listrik---mendapat potongan atau insentif.
Masyarakat tetap bebas memilih, tapi pilihannya menjadi rasional karena mencerminkan biaya lingkungan yang sebenarnya.
Pendapatan dari pajak karbon pun bisa diarahkan untuk hal-hal yang konkret: pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik, subsidi riset biofuel, atau program penghijauan. Dengan begitu, transisi energi berjalan bukan karena paksaan, tapi karena logika ekonomi yang sehat.
Transisi Bukan Pemaksaan
Kebijakan pajak karbon juga lebih transparan dan adil. Ia tidak menuduh, tidak memerintah, hanya menempatkan harga yang jujur pada setiap liter bahan bakar.
Masyarakat yang memilih BBM konvensional tahu bahwa mereka membayar lebih karena efek karbonnya tinggi. Yang beralih ke bahan bakar hijau membayar lebih murah karena dampaknya lebih kecil. Tidak ada pemaksaan, hanya keadilan proporsional.
Dan jika pamong negara memang ingin "memaksa demi bumi," bukankah lebih logis sekalian mempercepat penggunaan kendaraan listrik? Sudah jelas bahwa listrik sangat mungkin dihasilkan dari sumber-sumber energi yang dimiliki oleh kita sendiri (termasuk ethanol 100%, biomasssa, bahkan sampah), sehingga akan sangat memgurangi ketergantungan energi import.
Itu langkah besar yang benar-benar menurunkan emisi, bukan sekadar mengganti 5 persen isi tangki. Setengah hati dalam transisi energi justru memperpanjang ketergantungan pada bahan bakar lama tanpa hasil nyata.
Energi Bersih dengan Logika Sehat
Transisi energi yang berhasil di negara mana pun dibangun lewat tiga pilar: regulasi yang adil, insentif yang cerdas, dan kebebasan memilih. Ethanol bisa menjadi bagian dari solusi, tapi bukan satu-satunya jawaban. Apalagi jika disodorkan dengan cara yang meniadakan opsi lain.
Masyarakat Indonesia cukup rasional untuk memahami manfaat bahan bakar hijau, asalkan diberi informasi yang jujur dan kesempatan yang setara.
Pada akhirnya, jalan menuju energi bersih bukan ditentukan oleh seberapa keras pamong negara memerintah, tapi seberapa cerdas mereka meyakinkan. Biarkan pilihan itu terjadi di SPBU, bukan di balik meja kebijakan.
Yang dibutuhkan publik bukan paksaan baru, melainkan kepercayaan bahwa transisi energi dijalankan dengan logika, bukan simbol.
*Pamong negara = pemerintah
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI