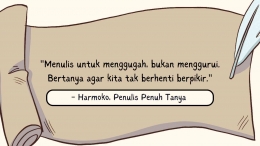"HRD yang baik itu ibarat wasit: tidak berpihak, tapi adil, dan tahu kapan meniup peluit---tanpa membuat pemain trauma."
- Penulis Penuh Tanya
Ekspektasi yang Melangit
Dalam banyak seminar motivasi atau konten di LinkedIn, HRD (Human Resources Development) kerap digambarkan sebagai sosok strategis: jembatan antara kepentingan manajemen dan kesejahteraan karyawan. Ia bukan sekadar penjaga absensi atau pemberi SP, tapi pemikir strategis, pendengar empatik, sekaligus partner bisnis.
Sayangnya, ketika realita mengetuk pintu, ekspektasi itu sering kali hanya jadi narasi cantik di slide PowerPoint.
Banyak pekerja, terutama Gen Z, menganggap HRD seharusnya:
1. Paham kesehatan mental karyawan.
2. Transparan dalam proses rekrutmen.
3. Menyediakan ruang diskusi tanpa intimidasi.
4. Menjadi pembela ketika ada ketidakadilan struktural di tempat kerja.
Namun di sisi lain, beberapa HRD sendiri merasa seperti "tali tambang di tarik ulur dua kapal". Mereka harus mengamankan kepentingan perusahaan, menjaga biaya efisien, namun tetap dipaksa tampil seperti pahlawan berkepala tiga yang bisa menangani konflik kerja, urusan legal, hingga drama pantry.
HRD, Jangan Cuma Jago Excel dan SP
Seorang karyawan pernah berkeluh kesah kepada saya, "Saya kena SP cuma gara-gara telat 15 menit. Tapi ketika saya mengeluh tentang beban kerja berlebihan, HRD bilang itu bagian dari loyalitas. Katanya kalau nggak kuat, ya cari kerja lain aja."
HRD idaman bukanlah yang bersenjata SP, tapi yang bisa membaca situasi. Telat kerja 15 menit bisa jadi pertanda burnout, bukan hanya soal ketidakdisiplinan. Perusahaan modern harus belajar membedakan mana pelanggaran kerja, mana sinyal distress dari pekerja yang terlalu lama menahan beban.

![[dpr] Gaji Tetap Mengalir, Tapi Hati Rakyat Sudah Pergi: Perlunya Etika dan Adab bagi Anggota Dewan](https://assets-a2.kompasiana.com/items/album/2025/09/02/file1b549156-2ec1-45a4-b331-a757f7fc9902-68b6499eed64152c5867fef4.png?t=t&v=100&x=100&info=meta_related)