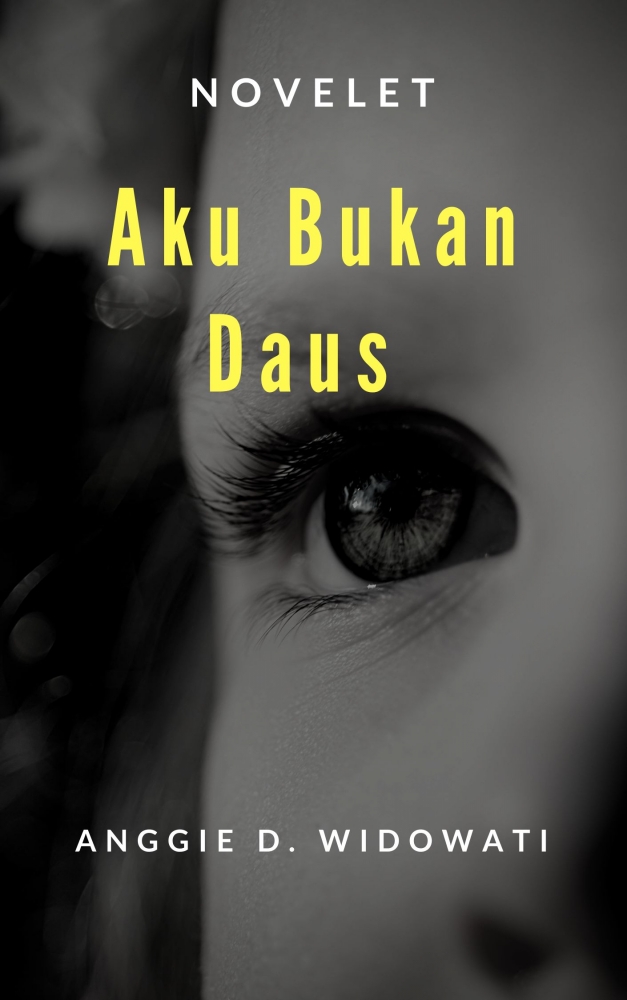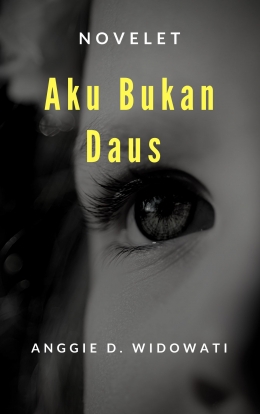(1)
Dari tiga saudaraku, aku yang paling kecil. Paling kecil dalam artian anak termuda, maupun paling kecil dari segi ukuran tubuhku. Tidak seperti orang kate, tetapi tubuhku seperti tak mau tinggi. Hanya setinggi anak-anak dan kurus kering. Aku lebih mirip anak TK ketimbang seorang siswa SMP.
Ayah meninggal karena paru-paru basah, alias TBC. Ibu pun kemudian menjadi wanita yang suka uring-uringan dan terpaksa bekerja untuk menghidupi kami sekeluarga. Ibu membuka lapak kecil di pasar pagi, berjualan makanan ringan dan kue.
Ibuku bertubuh normal, bahkan memiliki ukuran lebih besar ketimbang ayahku. Secara fisik ibuku tidak menarik. Gemuk, hitam dan berwajah muram. Ibuku selalu merasa manusia paling menderita, pengeluh dan tukang marah-marah.
Tumbuh dalam suasana hati yang tidak menyenangkan, gizi yang kurang, aku pun menjadi manusia mini. Dua kakakku tidak mini, mereka normal, hanya aku sendiri yang bisa dibilang bocah kurang gizi.
Ayah memberiku nama Adi Putra. Konon pada saat kelahiranku, ayah menyukai penyanyi bernama seperti namaku. Aku suka namaku. Diantara semua yang kumiliki hanya nama itulah sesuatu yang indah yang aku miliki.
"Adi, antarkan pesanan kue serabi ini ke bu Tono," kata Ibu.
"Adiiiiii..."
"Daus miniiiiii..."
Ibu berteriak dengan nada kesal. Aku bergegas mendekati ibu.
"Kalau dipanggil nyaut napa, enggak punya mulut?"
Aku mengangguk saja.
"Dasar Daus goblog," tambahnya pula.
"Aku bukan Daus," kataku membantah.
Lalu aku ambil kotak kardus dalam kantong plastik yang disodorkan ibu kepadaku. Tanpa berpamitan aku keluar dari dapur dan berjalan menyusuri jalan kampung menuju rumah bu Tono.
Ibuku pandai membuat kue, tetapi aku melihat dia seperti manusia yang resah entah karena apa. Sebelum ayah meninggal ibu tidak segusar itu. Mungkinkah ibu menganggap keberadaan anak-anaknya ini sebagai beban hidupnya.
Aku bukan anak yang sulit, tidak seperti dua kakakku Dayat dan Harun yang selalu keluyuran kemana-mana, aku lebih suka di rumah bersama ibuku. Aku selalu menonton televisi di ruang tengah. Setiap saat bisa disuruh kemana pun dan melakukan apapun untuk membantu wanita itu.
Ibu selalu sibuk di dapur untuk membuat kue. Kue-kue murahan seperti bakwan, timus, onde dan semacamnya. Kue-kue itu kadang pesanan tetangga, kadang dititipkan ke warung kecil di sekitar rumah. Kalau pagi ibu menjual sebagian ke pasar pagi. Sepertinya hanya itu hiburan ibu, jalan kaki ke pasar dengan mendorong gerobak kue.
Tidak ada yang tahu mengapa aku lebih suka berdiam di rumah daripada main dengan anak tetangga. Iyaa betul. Aku menghindari mereka, karena tubuh cacatku selalu menjadi bahan ejekan mereka.
Aku tahu bahwa dalam hati kecil mereka ingin menghinaku. Aku tahu bahwa mereka menganggap aku sampah karena tubuhku yang kecil dan aneh. Lebih baik aku di rumah daripada bertemu mereka.
Mulut mereka, bagiku seperti pedang tajam yang siap menguliti setiap inci tubuhku. Bukan hanya ibuku, tetanggaku sudah tidak memanggilku dengan nama bagus yang diberikan ayah. Mereka semua memanggilku Daus.
Aku tidak suka dengan panggilan itu. Tetapi bagaimana mengatakan ketidaksukaan itu. Kalau aku berbantah dengan mereka, mereka akan lebih ganas mengata-ngataiku. Anak-anak tetangga maupun orang tuanya sama saja, mereka itu otaknya sudah rusak.
Bagaimana aku harus melawan semuanya?
"Daus tuh keluar rumah," kata seorang ibu.
Aku berjalan melewati mereka sambil membawa kantong berisi kardus kue.
"Ya ampun tidak punya sopan santun, permisi kek," kata ibu yang lain.
Aku tetap tak menoleh. Siapa yang tidak punya sopan santun. Mereka saja seenaknya mengata-ngatai aku. Selama ini aku hanya tertawa, atau tersenyum, tetapi lama-lama aku lelah dan mendingan tidak usah menggubris mereka.
"Namanya juga kerdil, jangan-jangan tuli juga," kata si ibu.
"Tidak diajari sopan santun," sahut temannya sambil mencari kutu.
Anak-anak mereka yang bermain tak jauh dari para perempuan itu pun kemudian teriak-teriak memanggil nama bintang filem mungil itu.
"Daus..."
"Daus..."
"Daus..."
"Daus miniiiii..."
Aku mempercepat langkahku menghindari anak-anak kecil itu. Aku pun tidak lebih tinggi dari anak-anak TK itu. Aku terus berjalan menuju warung rumah bu Tono dengan perasaan kesal.
Sekarang anak-anak kecil pun sudah memanggil dengan sebutan Daus. Tidak ada sisa orang lagi yang mengingat namaku. Sepulang mengantarkan kue, aku kembali duduk di depan televisi. Ibuku masih sibuk di dapur sambil menggerutu entah karena apa. Aku membalik-balik acara televisi dan mengemil gorengan yang tidak layak jual.
"Dimana kakakmu?" tanya ibu muncul dari dapur.
Aku menggeleng.
"Tidak tahu Bu," kataku.
"Keluyuran saja, kayak gelandangan," keluhnya.
Aku benar-benar tidak tahu dimana kakak-kakakku yang drop out sekolah itu berada. Pernah sekali melihat Dayat di perempatan jalan mengatur lalu lintas. Sekali saja, setelahnya tidak lagi, konon dilarang oleh preman-preman yang sudah terorganisasi.
Begitu pun Harun, kadang markir di ruko atau menjadi sopir angkot cadangan. Pokoknya mencari uang dengan cara apapun. Tidak ada pilihan bagi keluargaku selain menghibur diri sendiri.
Mencari uang tanpa memiliki keahlian juga berat. Kadang dua kakakku rela berantem dengan para preman. Dikejar-kejar oleh preman karena mencuri lahan. Mereka hidupnya lebih berat ketimbang aku. Yah, kami semua adalah orang-orang yang hanya menjadi bulan-bulanan lingkungan.
Orang tidak melihat lagi perasaan dan hati kami tercabik-cabik oleh justifikasi masyarakat karena kondisi miskin. Masih untung punya rumah warisan nenek yang kami tempati ini. Setidaknya ada tempat untuk berteduh.
Rumah kami paling jelek di gang itu. Tembok-tembok tua yang lembab, dan genteng yang beberapa tempat sudah bocor. Atau lantai semen yang sebagian bolong. Lumayan kami tak perlu membayar sewa.
Meninggalnya ayah membuat kapal di rumahku menjadi oleng. Ayah bukan karyawan atau pegawai. Ayah berdagang baju bekas di pasar barang bekas. Dia memiliki gerobak besar yang ditariknya setiap hari pulang pergi ke pasar itu, sampai kemudian meninggal karena paru-parunya hancur oleh virus TBC.
Meskipun hanya jualan kue, ibu punya uang untuk membeli makanan dan keperluan. Kue-kuenya memang enak. Hanya dengan modal kecil, tetapi jarang membawa pulang kue yang dijual. Namun begitu tetap tidak mampu membiayai dua kakakku sekolah. Mereka terpaksa drop out dari sekolah.
Sekarang hanya tinggal aku yang bersekolah di sekolah negeri. Sekolah gratis. Kali ini aku diuntungkan oleh kecacatanku karena sekolah negeri harus menerima murid disabilitas. Bayangkan aku dimasukkan ke golongan disabilitas, meskipun panca indraku lengkap tapi memang tidak tumbuh normal seperti anak usiaku.
(2)
Sekolah itu bukan SMP favorit, tetapi proses pembelajaran sangat disiplin. Aku duduk dengan Romli di bangku paling depan kiri, dekat jendela. Tepat di depanku ada meja guru.
Awal-awal sekolah adalah masa-masa yang sulit. Aku bukan anak bodoh, tetapi aku selalu kesulitan menemukan teman. Entah mengapa aku selalu merasa minder. Bentuk tubuhku yang kecil, adalah salah satu penyebabnya. Kemiskinanku yang kedua dan semua masa lalu, lingkungan dan orang-orang disekitarku yang selalu merendahkanku itu yang ketiga.
Kebahagiaanku hanyalah semangat, semangat ketika pagi hari harus berangkat ke sekolah dengan jalan kaki. Pada saat melewati trotoar, dengan seragamku dan tas gemblok di punggungku, aku merasakan angin menyentuh wajahku dengan lembut.
Tetapi ketika memasuki gerbang sekolah, semua rasa itu berubah menjadi sebaliknya. Galau. Anak-anak yang baru sampai, orang tua yang mengantarkan mereka seakan tidak lepas memandangku.
Entah benar atau tidak namun begitulah perasaanku. Aku mempercepat langkahku, begitu masuk gerbang, agar bisa segera masuk kelas dan berdiam di sana. Sementara anak-anak bergerombol di halaman, di taman, atau di kantin, aku duduk di bangku ku sampai bel masuk berbunyi.
Demikian juga nanti kalau istirahat datang, aku disitu saja memakan bekal yang aku bawa dari rumah. Tidak ada uang saku, sebulan di sekolah itu, belum sekali pun aku menginjakkan kaki di kantin. Nasi soto, nasi uduk, ketoprak, baso, es nutrisari, milo atau pun seblak pedas, hanya kucium aromanya ketika ada teman yang jajan dan dimakan di kelas.
Aku selalu sembunyi dan sembunyi agar semakin banyak yang tak melihatku. Meringkuk di kelas dan membiarkan waktu mengalir. Aku senang bisa bersekolah, aku senang punya seragam, buku dan punya tempat duduk pasti di kelas. Aku punya hak atas itu. Tetapi aku lebih suka dalam kesendirianku.
Aku tidak suka ada orang yang melihatku. Biarkan-biarkan saja aku begitu. Aku tahu isi kelas itu 34 anak, tetapi tak satupun yang aku kenal. Aku tidak berminat untuk mengenal mereka.
Begitu pun para guru, mereka ada di depan kelas, mengajarkan ilmu mereka, tetapi aku tak perlu menjadi dekat dengan mereka. Cukuplah aku menjadi murid yang sedang mencari ilmu. Tidak ada niatan untuk dikenal mereka. Aku mau sekolah saja, tidak mau yang lainnya.
Kadang aku membayangkan meja dan bangku ku dipisahkan oleh tirai hingga tak ada yang bisa melihatku. Teman sebangkuku Romli, juga pendiam, aku tidak langsung percaya dia anak baik. Yang ada di kepalaku, semua orang pada akhirnya akan jahat.
Guru matematika, Bu Risti berbadan subur dengan rambut yang diikat ke balakang. usianya mungkin 40 tahun, dia terlihat tua karena pada sisi kanan dan kiri dari dahinya tumbuh banyak uban. Dia ramah dan pandai mengajarkan mata pelajaran Matematika. Mata pelajaran yang paling aku sukai.
Dengan cekatan dia menuliskan rumus-rumus di papan tulis. Dan biasanya diakhiri dengan tanya jawab. Di buku catatanku, semua soal yang dia berikan sudah aku jawab dengan cepat dan aku yakin pasti benar, karena aku menguasai pelajaran yang menyenangkan itu.
Bahkan ketika terjadi dialog, aku menghitungnya ulang untuk memastikan hasil kerjaku benar. Beberapa kali anak-anak maju ke depan untuk mengerjakan soal di papan tulis.
Tetapi semua salah. Sampai suatu saat ada murid yang duduknya paling belakang menunjuk kepadaku.
"Daus bisa Bu," kata anak itu.
"Daus?" bu guru bertanya.
"Itu Bu yang mini, yang duduk di depan."
Bangsat!
Anak yang duduk di belakang itu tak lain adalah tetangga dan satu SD dennganku. Karena itu dia memanggilku Daus. Dan sial, mulai hari ini seisi ruangan itu sudah tahu nama populerku.
Sekarang bu guru matematika melihat ke arahku. Matanya tajam seperti kawat yang seakan mengikatku.
"Adi, maju ke depan," kata Bu Guru memanggil nama asliku.
Aku diam menunduk.
"Daus, Daus, Daus..." anak tetangga itu berteriak, diikuti suara sekelas menyemangatiku dengan panggilan itu.
"Stt, diam anak-anak," kata Bu Guru.
Aku berdiri, dan berjalan ke papan tulis. Kelas masih riuh rendah dengan panggilan nama anehku itu. Aku mengerjakan soal itu dengan cepat. Bu guru berdiri di dekatku dengan melipat tangannya di dada.
Setelah selesai aku berikan spidol besar itu kepada Bu Guru. Bu guru masih melihat ke papan tulis.
Lalu dia pun berkata: "Bagus Daus, kau benar, kau pandai sekali," katanya.
Seperti dugaanku seluruh kelas pun menertawakanku karena ada kata Daus dalam pujian itu. Aku duduk dikursiku dan menunduk. Sekarang seluruh kelas ini akan memanggilku Daus. Ketika SD dulu, setiap naik kelas, aku akan dipanggil Daus, meskipun ganti-ganti teman.
Aku bangga bisa menyelesaikan soal di papan tulis itu dengan mudah. Bahkan bu Guru Risti memuji pekerjaanku. Kebahagiaan sesaat itu sempat kunikmati lalu hancur berantakan ketika ibu guru matematika itu meniru teman-teman yang lain dengan memanggilku Daus.
Hatiku menangis.
(3)
Romli anak yang baik. Dia pendiam, setidaknya tidak pernah mengata-ngataiku. Tubuhnya gemuk. Aku nyaris jarang berbicara dengan teman-teman sekelas. Satu-satunya yang masih aku ajak bicara hanya Romli.
Sama seperti aku dia anak orang tidak mampu. Ayahnya bekerja sebagai tukang bajaj. Saudaranya banyak. Perbedaannya hanya Romli bertubuh normal, jadi tidak pernah menjadi bahan bullyan di kelas.
Tetapi Romli mengaku kalau dirinya juga minder. Sebagai anak orang tidak mampu, dia menutupi semua itu dengan diam.
"Kamu harus ikut ekstra kurikuler," katanya padaku.
"Aku tidak mau."
"Kenapa?"
"Tidak apa-apa."
Tentu saja ada apa-apa. Bagiku mengurangi bergaul dengan siapapun itu adalah keputusan yang bijaksana. Kalau hanya untuk ekstrakurikuler, kurasa bukan program sekolah yang inti, jadi lebih baik tidak ikut.
"Kata bu guru harus ikut, minimal satu," kata Romli.
"Emang ada apa saja sih?"
"Pramuka, Palang Merah Remaja, Paskibra, Karate dan lain-lain, banyak sih."
"Oh, tidak aku tidak berminat," tegasku.
"Ikut pramuka saja seperti aku," kata Romli.
"Entahlah."
"Kakak pembinanya baik, namanya Kak Risa," ujar Romli.
"Guru?"
"Bukan, kakak pembina."
"Tiap hari apa?"
"Rabu sore, pakai saja sergam pramuka punyamu itu, tak perlu beli seragam baru, tidak ada iuran-iuran, langsung saja mendaftar."
"Aku males."
"Nanti kamu tak punya nilai di rapot lho."
Mendengar kata rapot, aku menjadi takut. Memang orang tuaku dan saudaraku tidak akan peduli seperti apa rapotku. Tapi aku peduli. Aku memiliki kesempatan sekolah ini, aku akan menjadi anak berbrestasi, biar pun badanku cacat.
Dan semua ambisi itu tidak boleh berantakan hanya karena nilai ekstra kurikuler. Aku sendiri tak berani membayangkan, aku yang tingginya hanya semeter ini akan berbaris bersama pramuka lain. Pasti keberadaanku akan merusak barisan.
Orang-orang pasti akan menertawakanku habis-habisan. Dan julukan Daus mini akan menyebar ke seluruh sekolah. Bukankah anggota ekstra itu juga dari kelas yang lain. Tapi bagaimana nilai ekstra kurilkulerku nanti?
Jujur aku mengalami dilema yang berat. Dan Romli kemudian memberikan jawaban yang aku butuhkan.
"Kalau nanti tidak cocok bisa pindah ekstra kurikuler yang lain, yang sesuai dengan minatmu."
"Oh gitu," kataku senang.
"Iya."
Aku ingin mencoba, dan nanti kalau tidak kerasan aku bisa pindah ke yang lain. Tentu saja aku tidak mungkin pindah ke ekskul yang lain. Mungkin lebih tepat disebut keluar. Kalau tidak kerasan ya keluar. Persetan dengan eskul yang lain, persetan dengan nilai rapot, yang penting ikut dulu. Selain tak perlu seragam baru, minimal ada Romli.
"Yaudah aku ikut pramuka saja."
Hari rabu sore latihan diadakan di sekolah. Aku mendaftarkan diri dengan mengisi blangko kosong. Romli sudah lebih dulu ikut latihan. Dia terlihat keren sekali, baju pramukanya pakai atribut yang komplit.
Aku masih punya pet, kacu, tali pramuka, dan alat-alat keperluan pramuka dari SD. Jadi aku tak perlu membeli yang baru. Ketika mematut diri di rumah tadi, aku terlihat gagah dengan seragamku. Namun setelah di sekolah dan berbaris dengan teman-teman, aku menjadi sama sekali tidak gagah, bahkan terlihat aneh.
Namun Kak Risa, dan Kak Wawang pembina pramuka tetap bersikap baik dan tegas.
"Itu anak TK nyasar ya," seseorang berteriak dari belakang.
Semua tertawa.
Kak Risa memperingatkan mereka untuk diam. Semua diam, sisa-sisa cekikikan masih ada, dan itu adalah hal yang biasa bagiku. Kak Risa tidak cantik, umurnya sekitar 22 tahunan, katanya sih masih kuliah. Istimewanya dia memiliki mata yang bersinar indah. Tubuhnya sedang. Cenderung kurus, tetapi bila sedang memimpin upacara terlihat gagah dan tegas.
"Semua diam, sikap sempurna," katanya.
"Kamu maju ke depan," tegasnya lagi.
Matanya menatap ke arahku. Aku balik menatapnya, dan dia mengangguk.
"Ayo ke sini."
Aku maju.
"Sebutkan nama dan kelas," perintahnya.
"Adi Putra, tujuh A," jawabku.
Entah mengapa rasa takutku hilang.
"Anak baru ini namanya Adi Putra, dia boleh bergabung dengan regu merpati," katanya menunjuk kelompok barisan dengan bendera bergambar burung merpati.
"Baik kak."
"Lari! Pramuka tidak boleh lemes," tegasnya.
Aku pun berlari. Semua mata memandangku. Ada tawa cekikikan di barisan belakang. Tapi entah mengapa, sikap Kak Risa membuatku bersemangat. Bahkan dia selalu menyebut namaku: Adi Putra, nama kesayangan sekaligus kebanggaanku.
Hari pertama pramuka menimbulkan kekagumanku sendiri pada kak Risa. Bila memberikan aba-aba barisan, suaranya keras dan tegas. Bila ada yang salah, dia akan mengingatkan dengan kata-kata yang lembut. Aku suka kakak pembina yang satu ini. Benar-benar anugerah yang luar biasa bisa mengenalnya.
Romli benar, Kak Risa adalah kakak pembina idola. Semua anggota pramuka menyukainya. Bila kak Risa memulai kegiatan, dia akan berdiri ditengah lapangan dan meniup peluitnya panjang. Semua anggota berlari ke arahnya.
Hari pertama pramuka itu, hari yang paling membahagiakan selama hidupku. Jujur saja, Kak Risa kaulah matahariku.
(4)
Kukira hari-hari berjalan seperti biasanya. Dan apa yang menjadi perkiraanku benar, sekarang bukan hanya teman sekelasku yang memanggilku Daus mini, tetapi seluruh sekolah ini memanggilku Daus.
Tetapi semua itu menjadi ringan karena ada hari Rabu. Hari yang paling aku nanti-nantikan karena pada hari itu ada latihan pramuka. Aku tidak peduli Asep, ketua reguku itu sangat mengesalkan.
Dia selalu memanggilku Daus Mini, lalu menyuruhku melakukan hal-hal yang tidak lazim, seperti mengambilkan tas dia, pergi ke tukang fotokopi, membelikan jajan untuknya, dan semacamnya. Seakan-akan aku ini hanyalah manusia rendah yang bisa disuruh-suruh.
Romli tidak satu regu denganku. Anak pendiam itu seperti asyik dengan dunianya sendiri. Namun mungkin itu yang menyelamatkan identitas pribadinya sebagai anak tukang bajaj. Aku yakin kalau ketahuan bisa saja dia dijuluki si Bajuri tukang bajaj karena tubuhnya yang subur itu.
Tubuhnya memang tidak menggambarkannya sebagai anak orang susah. Karena itulah dia aman di sekolah.
Mungkinkah aku jatuh cinta?
Jujur saja, wajah Kak Risa selalu ada di mataku dan pikiranku. Keberadaannya itu menjadikan hidupku yang selama ini berat menjadi ringan. Hinaan-hinaan itu serasa tidak ada artinya lagi bagiku.
Biarpun semua isi sekolah itu memandangku dengan rendah, aku tetap tegar dan belajar percaya diri. Aku yakin semua itu karena cinta yang tumbuh di lubuk hatiku. Kak Risa benar-benar menjadi cahaya yang membuat hidupku tidak suram lagi.
Saat semua orang melihatku dengan sebelah mata, dia menatapku dengan mata yang bersinaran, membuatku optimis. Saat orang melihat dan mengejek kecacatanku, sikap-sikapnya membuatku merasa berharga.
Terlebih lagi karena dia tidak seperti yang lainnya, yang menjulukiku Daus mini, Kak Risa selalu memanggilku Adi. Adi, tujuh A. Alangkah mulianya hatinya. Putih bersih seperti salju. Semua pribadinya, pesonanya itu membuat hidupku menjadi berharga.
Tanpa terasa enam bulan sudah aku mengikuti kegiatan pramuka di sekolah. Ujian akhir smester akan dilaksanakan minggu depan. Sebelum ujian, ekstra kurikuler yang diikuti siswa juga mengadakan tes. Karena banyaknya peserta eskul ini, tes dilakukan selama tiga hari. Selasa, Rabu dan Kamis.
Aku mendapatkan jadwal hari kamis. Otomatis hari rabu aku tidak perlu ke sekolah untuk latihan. Hari yang dinanti tiba. Semalaman aku sudah belajar, metode tali temali, menghapal sandi morse, menghapal simapor, dengan penuh semangat dan aku pelajari baik-baik.
Tentu saja aku tak mau mengecewakan Kak Risa. Dan tak mau nilai eskul di rapotku jelek. Karena melek sampai malam, pagi itu kepalaku pusing sekali. Ibu memberiku bodrek, karena aku bersikeras masuk sekolah.
Ya, aku harus masuk, karena nanti sore tes eskul pramuka. Hari ini tidak boleh dilewatkan. Aku berangkat sekolah dengan kepala yang berat. Aku sudah sarapan, karena ibu menyuruhku agar pusingnya segera hilang.
Ketika pelajaran, aku tidak bisa berkonsentrasi. Sudah dua jam tetapi rasa pusing itu belum juga hilang dari kepalaku. Saat istirahat aku sempatkan tidur di bangkuku. Lumayan, sedikit mengurangi.
Sorenya semua sudah berkumpul di lapangan. Sekarang bukan hanya pusing yang aku rasakan. Tubuhku panas dingin. Tetapi aku harus bertahan, karena hari ini hari tes.
Satu persatu tes dilakukan. Mulai yang tertulis sampai yang praktek. Aku masih menahan rasa kurang enak di badanku, tetapi sudah telanjur.
Aku tak berani bilang pada ketua regu, paling aku akan diomel-omelin. Tibalah saatnya aku maju tes simapor. Aku sudah menyiapkan sepasang bendera berwarna kuning dan merah dan berdiri tegak di depan Kak Risa dan Kak Wawang sebagai penilai.
Kak Risa mulai memberikan pertanyaan yang harus aku jawab dengan sandi bendera itu. Astaga, semalam aku sudah hapal semua gerakan, kenapa sekarang hilang semua?
"Ulangi, jawab pertanyaan ini, siapa nama presiden Indonesia," katanya.
Aku menggibas-gibaskan bendera untuk menjawab pertanyaan itu.
"Salah."
Aku makin gugup.
"Pertanyaan terakhir, berapa jumlah propindsi di Indonesia?"
Kepalaku pusing, dan suhu tubuhku meningkat.
"Salah semua!" tegasnya, "kamu tidak belajar?"
Aku diam.
"Daus mini, aku bertanya, tolong dijawab," kata Kak Risa dengan nada tegas.
Aku kaget bukan kepalang. Benarkah apa yang aku dengar itu. Dia memanggilku dengan sebutan Daus mini? Oh Tuhan, teganya dia padaku. Ternyata dia tak ada bedannya dengan yang lain. Seorang berhati salju yang aku kagumi itu ternyata sama saja. Kakiku melemah, pandangan di sekitarku gelap.
(5)
Ketika terbangun, aku tiduran di UKS. Harun kakakku menjemputku dengan sepeda motor pinjaman. Tidak ada orang lain, selain penjaga sekolah. Pramuka sudah bubar, tidak ada seorang pun di lapangan sekolah.
Aku berusaha mengingat-ingat apa yang baru saja terjadi. Kata penjaga sekolah aku pingsan. Dan anak-anak anggota palang merah merawatku di UKS.
Harun memboncengkanku di belakang, dan kami meluncur menyusuri keramaian Jakarta. Kakakku tidak berkata sepatah kata pun. Dia melajukan motornya dengan buru-buru, seakan-akan ada yang mengejar kami di belakang. Beberapa kali orang meneriakinya karena bersikap ngawur. Namun dia balas memelototinya.
Jangan tanyakan hatiku. Tubuhku mulai terasa enak dan nyaman karena anak-anak palang merah menggosokiku dengan minyak-minyak. Tetapi jiwaku hancur. Hatiku patah. Wanita idolaku itu telah membuat hatiku berkeping-keping.
Semua kekagumanku serasa hilang. pesonanya memudar, dan bagiku, dia seperti orang kebanyakan. Matahari itu benar-benar sudah padam di hatiku.
Sampai di rumah ibu menyruhku mandi dan terus-terusan ngomel karena aku nekad berangkat sekolah. Aku tidak menjawab. Aku biarakan saja semuanya.
Rasanya jalanan sudah senyap dan buntu, tidak ada lagi harapan. Aku mandi dan kemudian masuk kamar. Ingin menangis namun tak bisa.
Jadi tak ada gunanya lagi aku pramuka. Tak ada gunanya bersekolah. Semua ini tak ada gunanya. Aku membuka tas rangselku. Peralatan pramuka semua ada di sana. Anggota palang merah rupanya memasukkan semua milikku ke tas itu.
Aku mengambil tali pramuka. Aku memainkan beberapa teori dan cara yang berkaitan dengan tali temali. Tuhan, ketika hati dan jiwaku merasakan keindahan dan dihargai, kenapa kemudian Kau membiarkannya dihancurkan.
"Kenapa kau tak pernah membiarkan hatiku bahagia. Aku tak ingin dilahirkan cacat begini. Aku ingin seperti mereka. Lalu kau turunkan bidadari yang baik, yang memperlakukanku sebagai manusia. Namun itu hanya sekejap mata. Setelahnya dia tak jauh beda dengan yang lainnya. Kenapa Tuhan, kenapa Kau lakukan semua ini kepadaku."
Aku naik ke atas meja. Lalu tali itu aku ikatkan ke kayu-kayu penyangga genting.
"Setelah ini, tak ada lagi sekolah, tak ada lagi pramuka, tak ada lagi ibu, tak ada lagi tetangga usil, tak ada lagi kak Risa. Tak ada semua manusia yang selalu mengejek dan merendahkanku. Aku datang padamu Tuhan."
Aku mengikatkan tali itu kuat-kuat. Lalu aku masukkan kepalaku pada lingkaran, dan tali itu menjerat leherku. Pelan-pelan aku melangkah dari meja.
Kreekkk...
Itu adalah suara terakhir yang aku dengar. Inilah aku Tuhan, aku bukan Daus, aku Adi Putra.
Jakarta, 3 Agustus 20