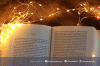Kolaborasi dalam Komunitas Praktik: Modal Sosial atau Sekadar Formalitas Akademik?
Pendahuluan
Perkuliahan semester Ganjil tahun akademik 2025/2026 segera dimulai pada 1 September hingga 19 Desember 2025. Di jenjang S1, penulis mengampu Metode Penelitian, sedangkan di S2, mengajar Manajemen Sumber Daya Pendidikan serta Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Fenomena yang menarik ialah meningkatnya kebutuhan terhadap kolaborasi nyata antara dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran dan riset. Di banyak kelas, kolaborasi masih terjebak dalam bentuk formalitas: kerja kelompok tanpa integrasi gagasan, atau diskusi daring tanpa tindak lanjut nyata.
Padahal, menurut Etienne Wenger, community of practice adalah jantung pembelajaran kolektif sebuah ruang di mana individu belajar melalui partisipasi aktif dan berbagi pengalaman. Pendekatan ini sejalan dengan teori sosial-konstruktivis Vygotsky yang menegaskan pentingnya interaksi sosial dalam perkembangan kognitif. Dalam konteks kerja, teori Job Demand--Resources (JD-R) juga menegaskan bahwa kolaborasi merupakan sumber daya psikososial yang meningkatkan work engagement dan produktivitas.
Namun, gap-nya jelas: praktik kolaboratif di perguruan tinggi masih sering lemah, terfragmentasi, dan belum menjadi budaya. Banyak pekerjaan dilakukan oleh individu yang tidak sesuai bidangnya muncul adagium klasik: "Suatu pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh ahlinya, tunggulah kehancurannya."
Tulisan ini bertujuan menegaskan pentingnya kolaborasi dalam komunitas praktik sebagai fondasi kepemimpinan ilmiah (scientist leadership) dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan (MSDM-P), sekaligus menunjukkan bagaimana dosen dan mahasiswa dapat membangun jejaring pembelajaran yang bermakna. Berikut, Lima Pilar Pembelajaran dari Kolaborasi dalam Komunitas Praktik:
Pertama: Pilar Integritas Akademik dalam Kolaborasi; Kolaborasi sejati lahir dari integritas akademik. Dosen dan mahasiswa harus berkolaborasi berdasarkan aturan, transparansi, dan etika profesi. Dalam konteks MSDM-P, misalnya, dosen tidak boleh menerima pemberian dari mahasiswa setelah ujian karena tergolong gratifikasi akademik. Keteladanan dosen menjadi fondasi moral dalam membangun komunitas praktik yang sehat. Kolaborasi yang berakar pada integritas melahirkan saling percaya (mutual trust), modal utama bagi kepemimpinan ilmiah yang berkelanjutan.
Kedua: Pilar Pembelajaran Autentik dan Konstruktif; Komunitas praktik memungkinkan pembelajaran berbasis pengalaman riil, bukan sekadar teori. Dalam kelas Metode Penelitian, mahasiswa dapat berkolaborasi lintas angkatan untuk meninjau proposal dan menganalisis data bersama. Dosen berperan sebagai fasilitator yang membuka ruang refleksi kritis. Proses ini menumbuhkan authentic learning di mana peserta belajar membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi sosial, sesuai dengan pandangan Vygotsky tentang zone of proximal development.
Ketiga: Pilar Kepemimpinan Partisipatif dan Reflektif; Scientist leadership tidak dibangun dari kekuasaan, melainkan dari partisipasi dan refleksi bersama. Dalam komunitas praktik, setiap anggota berperan sebagai pembelajar sekaligus kontributor. Dosen perlu membuka ruang bagi mahasiswa untuk memimpin sesi diskusi, menilai teman sejawat, dan merancang proyek bersama. Refleksi kolektif atas proses pembelajaran membentuk kepemimpinan ilmiah yang adaptif, solutif, dan rendah hati.
Keempat: Pilar Konektivitas Digital dan Soft Skills Global; Era digital menuntut kolaborasi lintas batas ruang dan waktu. Komunitas praktik kini menjelma menjadi ekosistem daring: Google Classroom, Moodle, hingga forum penelitian di ResearchGate atau Sinta. Kolaborasi digital memperkuat soft skills global seperti komunikasi lintas budaya, empati digital, dan literasi teknologi. Di sinilah branding akademik MSDM-P diuji: sejauh mana civitas akademika mampu menampilkan citra profesional berbasis kolaborasi terbuka dan produktivitas ilmiah yang terukur.