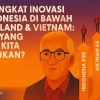Gajah mati meninggalkan gading. Dari generasi ke generasi, peribahasa ini diajarkan sebagai pengingat bahwa warisan, jasa, dan jejak baik yang ditinggalkan seseorang akan terus hidup meski ia telah lama tiada.
Tetapi, nasihat bijak itu kini terasa seolah terbajak. Pada kenyataannya, secara harfiah, masihkah gajah mati secara alami lalu meninggalkan gading, atau justru sengaja dimatikan untuk dirampok gadingnya?
Di hutan Sumatra, gajah yang sudah tergolong kritis, kematiannya justru dipicu atas ketertarikan terhadap gadingnya. Spesies dengan nama latin Elephas maximus sumatranus ini diburu dan dirampok, bukan mati secara alami.
Itu perlu dihentikan. Akan tetapi, jika hanya berfokus pada mereka yang mengokang senjata dan memperjualbelikan hasil buruannya ibarat memotong ujung daun tanpa menyentuh akar penyakitnya. Lebih dari itu, ada kekerasan struktural yang pada akhirnya memungkinkan perburuan terjadi.
Kebijakan yang Tak Bajik
Meracun, memasang jerat kawat, membedil, dan memenggal kepala gajah untuk dipanen gadingnya, jelas adalah bentuk kekerasan langsung. Namun, setiap tangan itu digerakkan oleh jemari tak kasatmata bernama kekerasan struktural---sebuah konsep yang diperkenalkan oleh sosiolog Johan Galtung. Konsep ini merujuk pada kekerasan yang tertanam dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik, yang lalu menciptakan lingkungan merugikan bagi kelompok tertentu.
Diperkirakan hanya sekitar 1.100 ekor gajah yang tersisa di seluruh Sumatra. Itu, pun, hidup terpecah-pecah dalam 22 lanskap berbeda. Ini menunjukkan bagaimana setiap gajah dipaksa untuk hidup seakan sebagai penyusup di tanah leluhurnya sendiri.
Bagaimana tidak? Hutan senantiasa dibelah, difragmentasi oleh kebijakan alih fungsi yang secara historis dan terus-menerus mengorbankan koridor hidup gajah untuk permukiman dan perkebunan monokultur seperti sawit. Ketika terjadi tumpang tindih antara keduanya, maka, konflik pun tidak terelakkan.
Kegagalan memandang gajah sebagai sesama makhluk hidup dengan manusia membuahkan pandangan bahwa mereka pengganggu belaka. Saat itulah, kehadiran mereka disetarakan dengan hama dan kematiannya hanyalah konsekuensi logis dari pembangunan. Benar bahwa pemerintah berkewajiban menyediakan kebutuhan tempat tinggal dan ekonomi warganya, tetapi, menjadi miris ketika solusinya adalah dengan menyerobot ruang hidup gajah yang telah lebih dulu tinggal, meski tidak membayar pajak.
Perburuan, pun, seakan mendayung sekali, dua tiga pulau terlampaui: memberantas yang dianggap hama sekaligus mengambil gading yang bernilai jual tinggi. Data antara 2010 hingga 2022 yang dihimpun Auriga Nusantara, menunjukkan setidaknya 183 individu ditemukan mati, dengan 33 di antaranya menunjukkan tanda jelas bahwa mereka diburu untuk diambil gading dan calingnya.
Bagi beberapa orang, gading yang bisa laku hingga puluhan juta itu seakan menjadi jawaban dari ketimpangan ekonomi yang terstruktur: ketika sistem yang tidak adil mempersempit pilihan mata pencaharian, mengekstraksi gading gajah adalah cara untuk terus mengepulkan dapur rumah. Bagaimanapun, tidak sedikit yang meminati. Entah untuk alasan estetika, kesehatan, maupun spiritualitas.
Seringkali, mereka bukan warga yang telah tinggal secara turun temurun di sana. Tapi, hei, jika ada yang membeli, kenapa tidak? Menjadi pemburu acapkali bukan semata-mata pilihan moral. Jerat dan racun yang disebar di hutan tidak lain adalah perpanjangan tangan dari jerat kemiskinan dan racun ketiadaan pilihan, ditemani kebijakan hukum yang tidak adil dan lemahnya penegakan, serta kebijakan tata ruang yang menempatkan manusia sebagai tokoh utama.
Wujud Termutakhir Perdagangan Gading
Meskipun kampanye dan larangan telah menunjukkan penurunan permintaan, masih ada kelompok pembeli yang persisten, yang menunjukkan kompleksitas dalam mengubah perilaku konsumen. Maka, jangan lagi dibayangkan transaksi jual beli gading melulu di tempat sempit, becek, dan tersembunyi. Ia kini terjadi di tempat yang amat terbuka, sama seperti di mana Anda membaca tulisan ini: internet.
Selama satu dekade terakhir, perdagangan satwa liar di Indonesia telah bergeser dari pasar fisik ke platform digital, yang dipercepat oleh pandemi COVID-19. Sebuah publikasi oleh Fidelis Eka Satriastanti dan Lusia Arumningtyas di 2023 mencatat bagaimana sepanjang 2022, terdapat 996 iklan satwa liar ilegal di platform Indonesia, dengan gading gajah menjadi barang yang paling banyak diperdagangkan. Di Facebook, ia disamarkan dalam beragam kode guna mengelabuhi panduan platform, misalnya, "pipa gg" untuk merujuk pada cerutu pipa yang terbuat dari gading gajah.
Struktur kekerasan yang sama---yang memandang gading semata-mata sebagai komoditas---kini memakai baju baru: algoritma. Kemudahan akses ini tidak hanya memperluas pasar secara eksponensial, tetapi juga secara halus nan pasti mewajarkan kejahatan terhadap alam di ruang publik. Platform teknologi, yang seharusnya menjadi penopang kemajuan, justru menjadi amplifier dari kekerasan struktural yang telah berlangsung lama.
Meninjau Kembali Peribahasa
"Gajah mati meninggalkan gading" dalam realitas hari ini telah direduksi menjadi logika pasar yang kejam. Warisan dari kearifan gajah kini malih dianggap simbol keperkasaan dan kekayaan manusia yang mampu mengoleksinya. Gading dianggap objek mati yang nilainya dianggap melebihi pemilik sejatinya.
Inilah pembalikan makna paling tragis yang dihasilkan oleh struktur yang salah: gajah mati karena gadingnya, sebuah proses yang didorong dan dimungkinkan oleh sebuah struktur sosio-ekonomi-politik yang melihat segala sesuatu, termasuk kehidupan, sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan dan dieksploitasi.
Peribahasa lahir dari pengamatan, pengalaman, dan cerita dari generasi ke generasi, yang disuling menjadi frasa-frasa ringkas dan mudah diingat yang menyampaikan kebijaksanaan, nasihat, atau kebenaran budaya melalui tradisi lisan.
Namun kini, tanpa disadari, peribahasa perihal gading gajah tidak lagi mencerminkan kemuliaan yang dimaksudkan saat ia dilahirkan dahulu kala. Ia telah menjadi ironi dari cara pandang yang sakit: sesuatu yang tidak lahir tiba-tiba, melainkan dibentuk dan terus diperkuat oleh struktur yang merusak.
Menulis Masa Depan
Jika akar masalahnya adalah struktural, maka solusi yang sesungguhnya dan berkelanjutan, pun, haruslah bersifat struktural. Menangkap pemburu individu, sementara penting sebagai penegakan hukum, hanyalah ibarat memberi plester pada luka yang telah menginfeksi hingga ke tulang. Ini tidak akan menyembuhkan penyakitnya.
Korupsi memiliki andil besar dalam menjadi fasilitator utama perdagangan ilegal. Sulit membayangkan jaringan kriminal memungkinkan beroperasi tanpa hambatan, bahkan mampu memasukkan gading ilegal ke pasar legal, jika tidak ada korupsi terjadi. Maka, memperbaiki struktur dengan kebijakan yang memprioritaskan keseimbangan ekologi adalah kewajiban mutlak. Bukan sekadar sertifikasi-sertifikasi yang hanya mengesampingkan rasa bersalah saat mengonsumsi produk-produk hasil hutan tanaman industri.
Mengatasi krisis ini membutuhkan pendekatan holistik yang tidak hanya menargetkan pemburu di lapangan, tetapi juga membongkar akar korupsi dan mengurangi permintaan gading secara efektif. Penegakan hukum harus diformulasi ulang, secara strategis merobohkan seluruh jaringan, termasuk perdagangan ilegal dari hulu ke hilir. Bahkan jika perlu, dengan menuntut akuntabilitas platform digital. Sebab, bagaimanapun, secara tidak langsung mereka telah memfasilitasi transaksi-transaksi itu.
Diperlukan keberanian untuk melakukan autokritik sejak tingkat individu hingga negara. Jangan sampai, gading yang dikenal generasi mendatang bukanlah sesuatu yang menempel di muka gajah, melainkan sebatas pajangan di museum. Atau bahkan, sebatas di buku pelajaran bahasa Indonesia bab peribahasa.
Itupun, jika generasi mendatang masih bisa terlahir. Sebab, kepunahan gajah berarti keruntuhan ekologi, yang juga mengancam kelangsungan hidup manusia pada akhirnya.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI