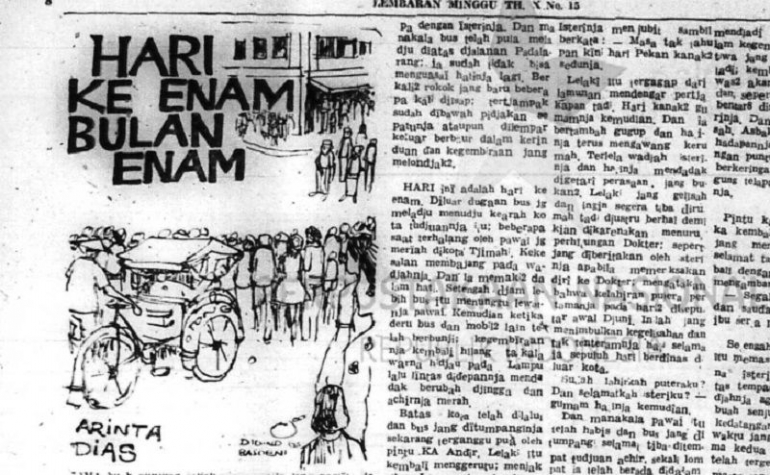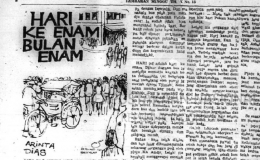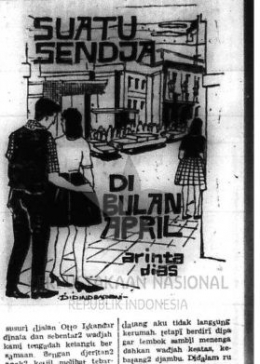Kota Bandung dalam beberapa cerita fiksi di harian Pikiran Rakjat pada 1965 menjelang peristiwa prahara 30 September 1965 digambarkan tidaklah menegangkan, tetapi masih merupakan kota yang romantis, kota yang pernah orang-orang terpelajar, ketegangan politik di kalangan elite tidak terlalu terasa di masyarakat kota.
Hal ini memperkuat asumsi saya bahwa gaduh Partai Komunis Indonesia dengan lawan-lawannya terutama dari kelompok Islam untuk di Kota Bandung lebih banyak di kalangan kampus, itu terasa sejak kasus pemberhentian Mochtar Kusumaatmadja pada 1962.
Masyarakat kota menurut para penulis memberikan respek mendukung kebijakan Sukarno, sekalipun kesulitan ekonomi juga diakui terasa oleh beberapa penulis. Moralitas timur masih dipegang kukuh, tetapi pengaruh Barat dalam mode busana dan cara berpikir juga menjadi keniscayaan.
Arinta Dias , merupakan salah satu penulis yang cukup produktif. Cerpen pertamanya bertajuk "Sahabat Karib" dimuat dalam Pikiran Rakjat 14 Maret 1965 mengkritik situasi sosial di Kota Bandung masa itu. Sahabat sang tokoh diceritakan maunya hanya bergaul dengan orang yang terkenal.
Padahal ada yang menjadi terkenal, menggunakan segala macam cara termasuk sekongkol dengan juri suatu lomba. Setting cerpen ini menarik saat Konferensi Islam Afrika Asia di Bandung (Maret 1965) dan pemutaran film di Dian Theater bertajuk "Peace to New Born"
Masih Arinta Dias dalam cerpennya bertajuk "Suatu Senja di Bulan April" yang dimuat di Pikiran Rakjat 20 Mei 1965 mengungkapkan betapa eksotisnya kota Bandung:
"Jalan Asia Afrika yang memanjang dari barat ke timur senja itu bermandikan warna sejuk dalam hiasan umbul-umbul dan banner di sepanjang jalan yang dilalui tokoh utamanya. Dia berpapasan dengan banyak manusia yang bergerak ke arah Barat."
Jelas settingnya Bandung menjelang peringatan satu dasawarsa Konferensi Asia Afrika (April 1965). Kota Bandung ramai di pusat kota, sekalipun menjelang malam.
Tokoh utamanya laki-laki ingin menepati janjinya bertemu seorang gadis di Jalan Naripan sehabis bekerja. Dia menelusuri trotoar melewati Grand Hotel Preanger dan lampu-lampu neon indah karena langit sudah kelam dengan secupan warna jingga di sebelah Barat. Begitu gambaran Arinta betapa cerahnya kota dan nyaman berjalan kaki.
Di depan etalase Toko Obor Baru, ia bertemu Ita, gadis yang kemudian membelikannya sebuah buku. Ita digambarkan berparas ayu. Kemudian mereka berdua berjalan menelusuri kota ke Jalan Oto Iskandar Di Nata. Mereka juga menyaksikan pertunjukan kembang api di langit.
Dalam obrolan keduanya, Nana menolak ikut rombongan misi kesenian karena kawannya Enong yang lebih mahir menari ditolak, karena tidak cantik. Padahal Ita justru berguru pada Enong di sekolah tari.
"Rakyat umumnya akan menyaksikan tarian dan memberikan penilaian jujur tentang baik dan buruknya tarian itu, tanpa ditambahi embel-embel lain. Dan aku lebih senang muncul di depan masyarakat kecil, seperti masyarakat di sini daripada muncul di gedung mentereng, tetapi mengikuti kemauan penyelenggaraan yang tak wajar."
Demikian sikap Ita yang mencerminkan sikap penulisnya, yang bagi saya cukup dahsyat pada masa itu. Perempuan (yang berpendidikan) mulai mempertanyakan, apakah seorang perempuan diapresiasi karena prestasinya atau kecantikannya. Secara tidak langsung mengkritik patriaki (waktu itu konsepnya belum dikenal).
Apa hubungannya nilai suatu tari dengan wajah penarinya? Gugat Ita.
Di akhir cerita Ita digambarkan seorang gadis yang dikenal tokoh utamanya, laki-laki sebagai gadis ketika memanjat pohon jambu. Seorang gadis manja tetapi punya wawasan luas.
Masih penulis yang sama Arinta Dias dalam cerpennya bertajuk "Hari ke Enam Bulan Enam" yang dimuat dalam Pikiran Rakjat, 20 Juni 1965 mengisahkan seorang pria yang baru saja menjadi ayah seorang putri, tepat pada tanggal 6 Juni 1965. Dia baru saja pulang dari dinasnya di luar kota, menumpang bus umum.
Mulanya perjalanan lancar dari puncak, melalui Rajamandala dan Gunung Masigit, tetapi mengalami kemacetan ketika memasuki Kota Bandung. Mulai dari pawai yang meriah sejak di Cimahi, pintu lintasan Kereta Api di Andir, dan akhirnya menemui kemeriahan perayaan hari kanak-kanak di Astanaanyar, Pasir Kaliki dan Jalan Padjadjaran.
Pada hari itu adalah hari uang tahun Bung Karno dan di akhir cerpen ayah itu menamakan anaknya Lusi Revolusiana. Jelas, cerpen ini menunjukan si penulis ingin menunjukan dirinya sebagai pendukung revolusi yang belum selesai yang dikumandangkan Sukarno. Dia berharap puterinya mewarisi watak agung "Pemimpin Besar Revolusi".
Sayangnya saya belum menemukan siapa Arinta Dias. Apa latar belakangnya?
Bagaimana dengan penulis lain? Min Resmana menulis "Sejuta Rupiah" dimuat dalam Pikiran Rakjat, edisi 4 April 1965 bercerita tentang seorang pendatang bernama Bandi dari desa ke Kota Bandung hanya punya uang Rp1.000. Dalam perjalanannya dia singgah di warung kopi dan melihat warga Bandung dengan baju wangi, perempuan dengan baju ketat, walau ada yang kebaya. Hal yang tidka ditemuinya di desa,
Di Kebon Tangkil Bandung, Bandi bertemu seorang perempuan yang minta uang sejuta rupiah. Mulanya dia sangka prostitusi. Ketika mengenal lebih dalam ternyata perempuan itu hanya ingin dilamar. Cerita ini secara tersirat kegamangan orang desa yang merantau ke kota dan desa masih digambarkan sebagai tempat orang yang polos dan jujur menghadapi orang kota yang punya karakter tidak bisa ditebak dan tidak lagi memegang norma.
Min Resmana ternyata penulis sejumlah novel pada tahun-tahun berikutnya. Dia menulis "Kabungkulengan", terbitan Sun Bandung pada 1965, kemudian "Sersan Mayor Maman", Pustaka Sunda, 1967, "Si Pelor", terbitan Pustaka Jaya, 1971, "Terpikat Gatot Kaca", 1975, "Kisah Pak Bidik", 1975 dan "Raja Bola", 1977 juga terbitan Pustaka jaya. Min juga menghidupkan kembali tokoh si Kabayan untuk mencapai kritik sosialnya dan Mohamad Toha, pahlawan Bandung Selatan.
Informasi mengenai penulis bahwa Min lahir di pada 1941 dan meninggal pada 1988 dalam sbeuah tulisan di Pikiran Rakyat pada 14 Maret 2019 (online). Berarti ketika mencuat sebagai penulis pada 1965 (yang saya temukan) usianya 24 tahun. Hal ini diungkapkan Hawe Setiawan dalam tulisannya "Ekologi Bocah Sunda" (1).
Lainnya adalah A Kuswita dalam cerpennya "Dosa Lama" di Pikiran Rakjat 1 Juli 1965 tidak eksplisit bercerita soal Bandung. Cerpen itu bertutur tentang Wawan meninggalkan istri bernama Nunung merantau ke kota. Di kota itu Wawan dapat pekerjaan yang mapan, tetapi kemudian terpaut dengan seorang gadis bernama Mini. Tentu saja Nunung merasa disakiti, karena diduakan.
Belakangan dia ingin balas dendam meninggalkan Wawan. Namun Mini dikisahkan meninggalkan Wawan dan lari dengan laki-laki lain. Walaupun merasa disakiti, Nunung menerima kembali Wawan. Dalam cerpen ini laki-laki itu begitu mudah mendapatkan kembali istrinya yang sudah dikihanatinya. Dalam kognitif si penulis, kasih sayang dan kehalusan jiwa perempuan mengalahkan rasa dendamnya.
Citra perempuan dalam cerpen ini terkesan bahwa perempuan desa yang diwakili Nunung pemaaf dan cenderung pasrah atas perilaku, sementara perempuan kota diwakili Mini pragmatif dan permisif terhadap nilai-nilai. Selain itu kota dipandang sebagai tempat untuk mengubah hidup secara ekonomi.
Rustam Effendy (2) menulis "Pertjakapan dengan Seorang Dokter" dimuat di Pikiran Rakjat pada 11 Juli 1965 agak pas menggambarkan kehidupan masa itu dari rakyat kebanyakan. Tokoh utama seorang bapak yang bekerja keras untuk menghidupi istri dan enam anak. Mereka tinggal di rumah bersahaja dengan bilik bambu. Tokoh itu disebut Effendy (kisah nyata?)
"Dengan langkah lebar aku terus masuk. Lampu gantung kunyalakan. Membetulkan selimut anak-anakku yang tidur lasak. Mereka tidur bertumpuk-tumpuk tak beraturan. Dan dari celah bilik bambu menerobos udara dingin mencekam suasana dalam kamar. Dalam dada bergulat perasaan getir yang selalu diiringi derita dalam kenyataan hidup yang harus diterima.."
Anak mereka yang bayi sakit panas, mereka tidak punya uang untuk membawa ke dokter.
Rustam menggambarkan kehidupan keluarga ini kontras dengan pedagang kaya, orang-orang yang mempunyai kedudukan terhormat, hampir tiap hari libur dengan mobil mengkilat memenuhi jalan raya, tanpa kerja keras apa-apa.
Sang Bapak hanya seorang buruh, hanya bisa membawa anak-anaknya piknik ke kebun binatang. Hanya bisa diam ketika anak-anaknya ada yang minta dibawakan kijang ke rumah untuk bisa dikasih makan kangkung, ada yang diminta dibelikan radio (barang mewah masa itu) dan ada yang minta dibelikan sepeda. Bahkan sepatu anaknya bernama Rini sudah tidak layak pakai.
Cerita ini diakhiri dengan percakapan dengan dokter tua yang mau menolong bayinya tanpa minta dibayar. Bahkan menggugah kesadarannya agar bia menerima keadaan dan tidak usah ikut-ikut cara hidup orang lain. Rustam menggambarkan seorang istri yang mengeluh kekurangan uang, tetapi bisa menerima keadaannya. Suami dan istri ini memilih hidup dalam cinta kasih walau dalam bersahajaan.
Penulis lainnya adalah Karlawati dengan cerpennya bertajuk "Alla" dimuat dalam Pikiran Rakjat, 18 Juli 1965 berkisah tentang seorang insinyur muda bernama Indra yang ditugaskan untuk membangun sebuah gedung, oleh sebuah yayasan di sebuah daerah pesisir.
Untuk membujuk insiyur itu mau membangun seorang perempuan bernama Alla mendekatinya dan bangunan itu selesai pada waktunya. Indra kecewa, ternyata adalah istri dari Sumantri penasehat hukum dari yayasan itu. Kekecewaanya dilampiaskan dengan berburu burung di pantai dengan senapan buatan Prancis, walau tak satu pun burung kena.
Kisah patah hati ini ditutup dengan kalimat-kalimat:
"Dia sering berbicara dengan burung-burung, sering berbicara kepada dirinya sendiri, sering berbisik-bisik pada laut. Dan hanya pernah menangis di antara deburan ombak yang membanting di pantai. Tetapi ia seorang pembangun yang hasil karyanya berbicara banyak kepada laut di depannya."
Cerpen ini mengisyaratkan perubahan sosial yang terjadi akibat munculnya kaum terdidik dari perguruan tinggi, yang saya sebut sebagai "neo menak". Indra lulusan teknik sipil, Sumantri lulusan hukum dan Alia juga mungkin orang terdidik.

Kedua, perempuan diceritakan tidak lagi dikukung, tetapi juga dinamis. Tati Pinowati , aktivis pers mahasiswa Bandung dalam tulisannya "Mahasiswa Puteri" dalam Pikiran Rakjat, 22 Juni 1965 membenarkan hal itu. Di satu sisi dia menulis:
"Wanita tidak lagi dikukung seperti zaman dahulu, tetapi sudah bergerak di segala lapangan berdampingan dengan kaum pria, akrab dengan romantika, dinamika dan dialetika revolusi."
Tati juga menyinggung, bahwa wanita terdidik tidak boleh melupakan sebagai ibu rumah tangga yang halus bisa membina kebahagian atas dasar cinta kasih pada sang suami.
"Khususnya kepada mahasiswi di samping sibuk menghadapi studinya dan organisasinya, tidak lupa memelihara kesehatan dan kecantikannya..."
Pada bagian lain Tati mendefinisikan kecantikan, "Arti kecantikan di sini tidak terbatas pada bentuk muka dan wajah, tetapi juga dalam tata cara membawakan diri dalam kepribadiannya..Pakaian yang dipakai harus cocok dengan tipe kita...bermake up jangan terlalu menyolok, cukup memberi kesegaran pada wajah dan pribadi kita." Konsep brain, beauty dan behavior untuk perempuan pada masa itu.
Namun yang terpenting Kota Bandung hingga masa itu masih merupakan kota yang berhawa sejuk, nyaman ditinggali, ruang hidup masih layak bagi warganya. Bahkan sebetulnya sampai sampai saya alami ketika masih kecil, berlibur di sana pada 1970-an hingga 1990-an awal.
Irvan Sjafari
Catatan Kaki.
- Hawe Setiawan "Ekologi Bocah Sunda" dalam Pikiran Rakyat 14 Maret 2019 menceritakan buku yang ditulis Min Resmana berjudul Hujan di Girang Caah di Urang (1973). Cerita mengenai edukasi ekologi. kisah keteladanan guru sekolah dasar di desa yang diramu dalam kisah petualangan sejumlah bocah di dalam hutan..... Latar cerita menghadirkan Tatar Sunda. Di situ mengalir Sungai Citarik dan Citanduy yang di sekitarnya terletak sejumlah desa seperti Sukamaju, Sirnasari, Cinangka, Cikondang, Babakan, Cilebak, dan Mand. Terbayang sasak alias jembatan Leuwiorok yang hancur diterjang banjir hingga beberapa bocah terlambat ke sekolah. Terbayang pula Pasir Cipait yang pokok-pokok kayunya bertumbangan oleh liarnya penebangan.
- Saya tidak tahu apakah penulis ini merupakan sastrawan Rustam Effendy? Mungkin juga iya, karena pada 1960-an sastrawan ini memang tinggal di Bandung dan aktivis politik Murba antara 1950-1965.