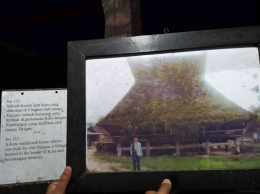Cingkes adalah salah satu nagori (sebutan lain untuk desa) yang berada di wilayah Kecamatan Dolok Silau, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Mengutip data pada portal Pusat Data Desa Indonesia, dijelaskan bahwa desa Cingkes yang tidak berbatasan dengan laut dan di luar kawasan hutan, saat ini tergolong desa berkembang menurut Indeks Desa Membangun dan Indeks Pembangunan Desa.
Walaupun secara administratif kini termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Simalungun, nagori Cingkes memiliki sejarah dan pertalian yang sangat dekat dengan Karo baik sebagai entitas budaya maupun geografis.
Desa Cingkes pernah Menjadi Bagian Wilayah Kabupaten Karo
Berdasarkan surat ketetapan tanggal 13 April 1911 Bijblad No. 7465, ditetapkan batas Tanah Karo dengan Tanah Simalungun, di mana urung Silima Kuta yang beribukota di Nagasaribu adalah daerah Karo yang kemudian dimasukkan menjadi daerah Simalungun.
Pemerintahan Kabupaten Karo terbentuk pada 13 Maret 1946. Pembentukan pemerintahan dengan sistem demokratis berdasarkan kedaulatan rakyat ini sekaligus mengakhiri sistem pemerintahan swapraja pribumi (semacam kerajaan) di Tanah Karo.
Pada masa awal terbentuknya, wilayah Kabupaten Karo mencakup daerah Deli Hulu dan daerah Silima Kuta Cingkes, di mana Rakutta Sembiring Brahmana sebagai Bupati pertama, KM Aritonang sebagai Patih, Ganin Purba sebagai Sekretaris, Kantor Tarigan sebagai Wakil Sekretaris. Para lurah diangkat sebagai pengganti raja urung yang sudah dihapuskan.
Sesuai dengan keputusan Komite Nasional Provinsi tertanggal 18 April 1946, diputuskan bahwa Tanah Karo terdiri dari tiga kewedanan dan tiap kewedanan terdiri dari lima kecamatan. Pada masa itu, Kecamatan Cingkes termasuk dalam kewedanaan Tiga Panah, dengan camatnya Babo Sitepu.
Dalam perjalanan selanjutnya, setelah terbentuknya NKRI, daerah Karo Jahe (Deli Hulu) dan Silima Kuta (Cingkes) yang sejak revolusi sosial pada Maret 1946 termasuk bagian Kabupaten Karo akhirnya dikeluarkan lagi dari wilayah Kabupaten Karo. Deli Hulu dimasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang, sedangkan Cingkes dimasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Simalungun.
Cingkes dan Kisah Asal-Usul Marga Tarigan
Menurut sumber-sumber sejarah, pada masa dahulu kala di Simalungun, Karo, dan Gayo terdapat kerajaan-kerajaan Nagur. Di sekitar Tiga Runggu sekarang adalah pusat kerajaan Nagur yang ada di wilayah kerajaan Haru, dan rajanya yang terakhir bernama Mara Silu.
Kerajaan Nagur di sekitar Cingkes yang sekarang, rajanya dari marga Tarigan. Setelah hancur pada pertengahan abad ke-13, kampungnya dipindahkan oleh marga Tarigan dan diberi nama Cingkes. Kuta Nagur Tarigan itu sekarang dinamakan Kerangen Nagur.

Mengutip penjelasan pada buku "Sejarah Karo dari Zaman ke Zaman Jilid I" yang ditulis oleh Brahma Putro (1995), bahwa ras Proto Melayu yang menjadi suku bangsa Haru sudah sejak ribuan tahun silam mendiami pegunungan Bukit Barisan. Suku bangsa Haru yang berasal dari ras Melayu Tua inilah yang menjadi nenek moyang asli orang Karo.
Artefak-artefak "gua umang" yang benyak terdapat di daerah Karo dan Pakpak sebagai tempat kediaman ras Proto Melayu, menjadi bukti bahwa masyarakat Haru yang menjadi nenek moyang suku Karo, Pakpak, Simalungun, Gayo, Singkel, Keluat bukan berasal dari keturunan seorang kepala keluarga di Sumatera, tetapi berasal dari beberapa kepala keluarga pada zaman Melayu Tua itu.
Arti kata "Tarigan" tidak ditemukan di dalam kamus bahasa Karo. Namun, ada catatan tersendiri mengenai asal usul marga Tarigan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Catatan itu bukan dalam bentuk tulisan di atas kertas atau di kulit kayu, tapi diwariskan dari mulut ke mulut, baik di Simalungun, Pakpak, Alas, Gayo, maupun di Karo.
Pada zaman pra sejarah nenek moyang Tarigan hidup di gua batu dekat kampung Tungtung Batu, Pakpak, Kabupatan Dairi (pada masa buku ini ditulis). Pada suatu ketika terjadi perkelahian antara nenek moyang si Tarigan ini dengan penduduk yang bermukim tidak jauh dari gua tempat tinggalnya itu.
Nenek moyang marga Tarigan ini melarikan diri ke sebuah gua batu. Pada pintu gua batu itu tumbuh pepohonan yang menutupi pintu gua.
Setelah nenek moyang si Tarigan itu bersembunyi di dalam gua, bertenggerlah seekor burung balam di pohon pada mulut gua, kemudian berkukuk dengan merdu, berulang-ulang.
Ketika musuh yang mengejar nenek moyang si Tarigan itu tiba di depan pintu gua, mereka mendengar suara kukuk burung balam yang merdu dan berulang-ulang itu. Mereka beranggapan bahwa tidak mungkin nenek moyang si Tarigan itu masuk ke dalam gua, karena di pintu gua hinggap seekor burung balam yang berkukuk merdu.

Bila ada manusia di dalam gua tentu burung balam itu tidak akan mau hinggap dan berkukuk dengan tenang di sana, pikir mereka. Mereka pun meninggalkan pintu gua dan melanjutkan pengejarannya. Selamatlah nenek moyang si Tarigan itu.
Sepeninggal para pengejar itu, burung balam itu pun terbang meninggalkan pohon di depan mulut gua. Burung balam itu tampak senang karena nenek moyang si Tarigan selamat dari pengejaran musuh-musuhnya.
Di dalam gua dekat Tungtung Batu itu nenek moyang si Tarigan itu erbilawan (bersumpah dalam bhs. Karo) bahwa ia dan keturunannya tidak akan pernah memakan daging burung balam sepanjang zaman. Itulah sebabnya sampai sekarang marga Tarigan memantangkan memakan daging burung balam.
Nenek moyang si Tarigan ini mendirikan barung-barung (gubuk dalam bhs. Karo) di dekat gua batu itu. Ia menikah dengan gadis dari desa yang berada tidak jauh dari tempat itu, dari pernikahannya lahirlah anak-anaknya laki-laki dan perempuan.
Barung-barung itu pun menjadi semakin ramai dihuni keluarga dan keturunannya. Mereka menamai kampung itu Kuta Tungtung Batu, artinya kampung lubang batu.
Keturunan nenek moyang si Tarigan ini antara lain Sipengeltep, Tarigan Sibero, Tarigan Purba di Simalungun, Tarigan Girsang, Tarigan Tua, Tarigan Silangit, Tarigan Tambak, Tarigan Tegur, Tarigan Bondong, Tarigan Tambun, Tarigan Pekan, Tarigan Gerneng, Tarigan Jampang, Tarigan Gana-gana.


Nenek moyang si Tarigan ini adalah orang dari ras Proto Melayu yang berdiam di gua batu, dan suku marga Tarigan termasuk asli suku Karo. Oleh karena dia termasuk keturunan ras Proto Melayu yang menjadi suku bangsa Haru, maka Tarigan ini turut membawa peranan penting dalam kerajaan tua Nagur di dekat Cingkes.
Namun, di daerah Tanah Tinggi Karo, marga Tarigan tidak turut membawa peranan penting. Dia tidak turut menjadi golongan raja Raja Berempat, hanya di Juhar dia sebagai perbapan (Raja Urung).
Semoga bermanfaat. Mejuah-juah.
Rujukan:
Sejarah Karo dari Zaman ke Zaman Jilid I, Brahma Putro, Penerbit Ulih Saber, Medan, 1995.
Sejarah Revolusi Sosial di Kabupaten Karo