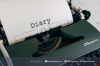Di suatu sore menjelang malam yang masih menyisakan sisa-sisa snar lembayung , sepasang kakek nenek berdiri berdesakan di gerbong KRL jurusan Cikarang. Keduanya naik dari stasiun Tanah Abang yang sibuk. Mungkin saya mereka baru transit dari Serpong atau Rangkasbitung. Sang nenek, tampak masih cantik dengan kerudung warna biru menutupi sebagian rambut yang sudah mulai memutih, sementara sang kakek memakai kopiah hitam yang juga tidak bisa menutupi rambut yang beruban.
Mereka tidak mengeluh, hanya mata mereka yang lelah. Tak ada kursi untuk duduk. Tak ada tangan muda yang terulur, hanya sorot cuek dan telinga yang tertutup headset. Bahkan kursi prioritas yang seharusnya menjadi hak mereka pun sudah diduduki orang-orang muda. Dalam situasi gerbong penuh sesak, status prioritas hanya ada secara simbolik---bukan substansi. Dalam situasi ketika masuk ke gerbong pun sulit, maka peraturan akan kursi prioritas tentu mendapat prioritas terakhir.
Indonesia adalah negeri yang kaya akan seremonial dan simbolisme. Kita punya kursi prioritas, tapi sering ditempati yang bukan prioritas. Kita punya jargon "hormati orang tua", tapi dalam praktiknya, kita membiarkan mereka berdiri di sudut gerbong sambil berpura-pura tidur.
Apa benar lansia harus selalu memaklumi?
Bukan itu saja, lansia juga belum mendapat tiket gratis untuk KRL. mereka memang sudah mendapat diskon khusus untuk kereta jarak jauh. Ironisnya TransJakarta pun hanya memberikan fasilitas itu untuk pemegang KTP DKI, seolah lansia dari Bekasi, Depok, atau Tangerang tidak berhak atas penghormatan yang sama. Pada hal dulunya mereka mungkin warga DKI juga, para pensiunan ASN, pensiunan guru, buruh, karyawan swasta atau bahkan veteran yang sebagian menghabiskan masa produktifnya di ibu kota, menyumbangkan tenaga, waktu, dan tentu saja sebagian penghasilan dalam bentuk pajak.
Apa salah mereka jika kini tinggal sedikit lebih jauh dari Jakarta?
Bandingkan dengan negeri lain yang kerap kita sebut 'keras' atau bahkan 'komunis' dengan nada sinis. Di beberapa kota besar Tiongkok, Shenzhen misalnya, lansia, bahkan yang bukan warga negara, bisa mendapatkan akses masuk gratis ke museum, tempat wisata, dan transportasi umum. Cukup dengan menunjukan paspor atau bahkan hanya dengan menunjukan wajah yang sudah berkerut kepada petugas.
Cukup berkata lembut: "tengo ms que sesenta anos" di Bogot, Kolombia, tiket masuk Museum Nasional langsung digratiskan---bahkan tanpa perlu menunjukkan paspor. Tidak ada syarat rumit, tidak ada wajah curiga dari petugas. Petugas hanya berkata lembut "Gratis senor " Lansia dianggap sebagai manusia yang telah melewati begitu banyak, sehingga mereka layak mendapatkan kemudahan---bukan kecurigaan.
Lucunya, justru di Museum Nasional Indonesia, seorang teman yang berbicara dengan Bahasa Indonesia yang fasih, pun sempat diminta membeli tiket turis asing yang jauh lebih mahal. hanya karena penampilannya dianggap "bukan Indonesia." Ketika ia berkata bahwa ia adalah warga Indonesia, petugas tidak percaya begitu saja. Harus dibuktikan dengan menunjukan KTP. Bukankah ini ironi negeri sendiri?
Lalu kita berbicara tentang keadilan. Tentang pelayanan publik. Tapi mengapa yang paling minim pelayanannya justru mereka yang paling dulu memberi? Apakah karena para pembuat kebijakan---meskipun mungkin sudah lansia juga---tidak pernah naik KRL? Tidak pernah menunggu TransJakarta di halte yang berdebu? Tidak pernah didesak-desak di gerbong penuh sambil membawa obat yang baru diambil selesai berobat menggunakan fasilitas BPJS?
Bandingkan dengan para pejabat yang naik mobil dinas dengan pelat khusus, lengkap dengan pengawalan khusus dan sirine meraung-raung meminta jalan di tengah macet, bahkan sesekali masuk ke jalur TransJakarta dan mendapat hormat dari petugas alih-alih diberhentikan.
Pada saat yang sama lansia yang ingin ke rumah sakit atau ke rumah cucu harus tetap membayar tarif penuh, berdiri tanpa kursi, dan berharap ada anak muda yang sudi bangkit dari tempat duduknya. Ironisnya ini terjadi di bus TransJakarta yang tetap terjebak dalam macet karena jalurnya juga diserobot sepeda motor atau kendaraan lain.
"Bagaimana kalau ada gerbong khusus lansia saja?" Mungkin ini adalah ide "out of the box" yang tidak pernah terlintas bahkan oleh pak Jonan sekali pun. Sementara di bus TransJakarta sebaiknya jangan hanya ada bagian khusus wanita, tapi ada bagian khusus lansia. Karena kalau hanya ada kursi prioritas yang menjadi satu dengan penumpang umum, kursi tersebut sudah pasti diisi oleh penumpang lain yang masih muda.
Pernyataan ini setengah canda, setengah serius. Tapi ia lahir dari kenyataan bahwa kursi 'prioritas' hanya istilah. Di dalamnya, tak ada prioritas. Yang ada hanyalah kompetisi diam-diam antar penumpang: siapa cepat dia dapat kursi. Bahkan penumpang juga sudah berebut masuk ke gerbong tanpa menunggu penumpang turun lebih dahulu.
Coba masuk ke gerbong khusus wanita. Harusnya ruang aman. Tapi kenyataannya? Kadang justru jadi arena paling keras: ibu-ibu saling dorong, saling sikut, bahkan saling melotot hanya demi sepetak kursi. Seolah solidaritas sesama perempuan luntur oleh tuntutan kenyamanan pribadi. Bahkan banyak perempuan yang senin suka masuk ke gerbong umum, terutama di jam sibuk.
Maka jika gerbong khusus lansia benar-benar disediakan, apakah akan menjadi solusi? Atau justru jadi versi lanjut usia dari gerbong wanita yang sudah duluan kehilangan nuansa "khusus"-nya? Walau secara resmi belum pernah ada statistik jumlah penumpang lansia di KRL atau Tije, tapi secara kasat mata jumlah mereka sangat sedikit, apalagi di jam sibuk, mereka lebih suka mengalah dan tidak naik transportasi umum. Mereka mungkin lebih suka menghabiskan uang tabungan untuk naik transportasi alternatif atau mengubah waktu perjalanan ke jam tidak sibuk.
Ironi semacam ini sebetulnya tidak perlu terjadi jika adab masih hidup. Di Jepang, kursi prioritas selalu tersedia, bukan karena ada hukum atau denda yang ketat, tapi karena ada rasa malu. Anak muda enggan duduk di sana meskipun gerbong kosong. Mereka paham, tempat itu bukan untuk mereka. Begitu pula di Korea atau bahkan Uzbekistan, kursi prioritas bukan sekadar label, tapi cerminan nilai budaya. Mereka tidak membanggakan religiusitas seperti kita, tapi justru lebih beradab dalam praktik harian.
Kita? Kita lebih fasih membaca kitab suci, lebih banyak mendirikan rumah ibadah, lebih sering bicara soal akhlak. Tapi di halte, di stasiun, di ruang publik---kita sering lupa makna dari kata-kata itu. Kita lebih pandai ceramah, tapi lebih cepat pura-pura tidur saat melihat nenek-nenek masuk gerbong.
Haruskah kita menciptakan gerbong khusus lansia? Atau haruskah kita mendidik ulang rasa malu, empati, dan tata krama?
Sebab gerbong khusus sebetulnya bukan solusi jangka panjang. Ia justru tanda bahwa masyarakat gagal menjaga rasa hormat secara sukarela. Kita membuat sekat-sekat baru karena tak lagi percaya pada kesadaran bersama. Dan ini menyedihkan.
Lansia seharusnya tidak perlu mengemis hak. Mereka tidak meminta dikasihani. Mereka hanya ingin sedikit dihargai, seperti dulu mereka menghormati dan menghargai generasi sebelum mereka. Transportasi publik yang baik tidak hanya diukur dari frekuensi kedatangan atau teknologi pembayaran digital, tapi juga dari seberapa manusiawi ia memperlakukan yang paling rentan: lansia, ibu hamil, disabilitas, dan anak kecil.
Ketika lansia masih harus membayar penuh untuk naik KRL, disuruh berdiri di sudut gerbong, diminta membeli tiket lebih mahall di museum karena dianggap turis, lalu disuguhi berita tentang pejabat yang korupsi, rasanya, ada yang sangat timpang di negeri ini.
Dan kita tidak bisa menyalahkan semua pada pemerintah. Sebab masyarakat juga punya tanggung jawab. Saat ibu-ibu saling dorong di gerbong wanita, ketika anak muda tetap duduk di kursi prioritas sambil pura-pura merem, saat petugas loket tidak percaya pada orang yang mengaku warga Indonesia hanya karena ia berkulit lebih terang---di situlah terlihat bahwa pendidikan moral belum meresap.
Mungkin sudah saatnya kita berhenti bertanya, "Apa hak lansia?"
Dan mulai bertanya:
"Apa yang membuat kita pantas disebut bangsa beradab?"
Bukan hanya karena kita punya fasilitas publik. Tapi karena kita punya ruang hati untuk menghormati mereka yang dulu pernah membangun semuanya---sebelum kita sempat naik KRL, duduk di TransJakarta, atau selfie di museum.
Dan jika semua itu masih terlalu sulit, maka mungkin memang kita perlu satu gerbong khusus.
Bukan karena mereka lansia,
tapi karena kita terlalu muda untuk tahu caranya menghormati mereka.
Rasanya KAI atau TransJakarta perlu sedikit belajar ke Imigrasi yang sudah memberikan pelayanan lebih baik kepada lansia.