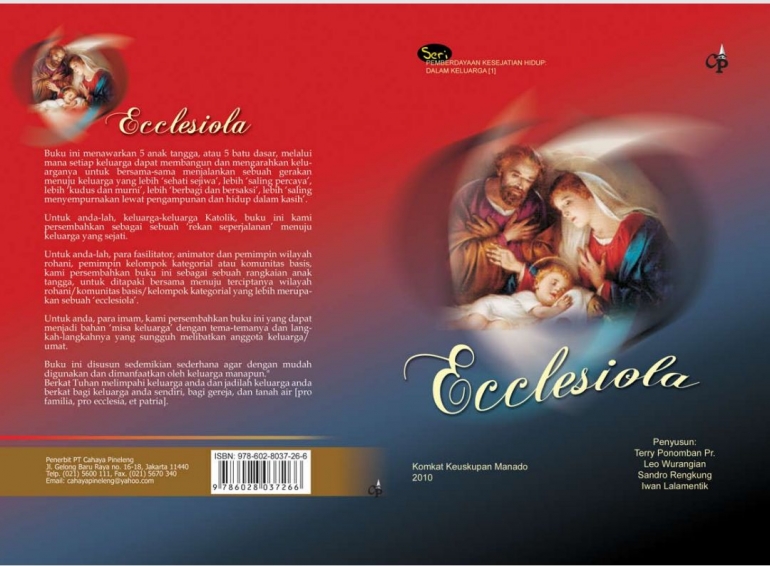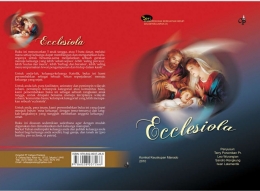Gereja Rumah, Konstruksi Baru hadapi Pandemi COVID-19 (?)
Tanggapan atas tulisan Sovian Lawendatu, "Gereja Keluarga, Gereja tanpa Institusi Formal"------------------------
Tulisan Bung Sovian Lawendatu dalam laman FB miliknya ditujukan untuk grup diskusi yang khusus dibentuk oleh tokoh Kawanua yang juga adalah Sekjen PIKI, Audy Wuysang, menghadapi sikon pandemi Covid-19 ini [https://m.facebook.com/groups/782641955598951?view=permalink&id=782717638924716] sangat menarik.
Sovian berangkat dari pengalaman dan refleksi tertentu. Istilah "gereja keluarga" atau "gereja rumah" ini sendiri bukan hal baru. Namun sangat aktual dan ditawarkan sebagai wacana strategis menyikapi zaman pandemi COVID-19 ini, Gereja domestik (Latin: domus = rumah) atau hauskirche (Jerman) atau ecclesiola (Latin) ini mesti diletakkan dalam konteks teologi khususnya eklesiologi di balik itu.
Dalam pengamatan Sovian rupanya ada fenomena elitisme tertentu dalam persekutuan gerejawi yang menjadi pengatur dan penentu jemaat, dan dengan efek-efek negatif turut menyertai dan membuat kegelisahan dan tanda tanya di kalangan Jemaat dan para pemimpin di lapisan "pelaksana" di bawah.
Sovian berusaha menunjukkan dalam sejarah reformasi sampai Calvin (karena menjadi rujukan tradisi teologi mayoritas denominasi Gereja Protestan di Indonesia) bahkan merujuk ke Gereja perdana (sebelum gereja negara ala Konstantin), bahkan Gereja para rasul sebagaimana bisa dilacak dalam kitab Kisah para rasul dan tulisan apostolik Paulus, dan tentu saja Injil synoptik itu sendiri yang mulai ditulis kira-kira sejak rasul dan lingkaran pengikut Yesus terakhir meninggal.
Dalam konteks Gereja Katolik Roma pada abad pertengahan (bisa dilacak sampai masa Kaisar Romawi menjadikannya sebagai agama resmi negara), elitisme itu nampak jelas dalam Hirarki terpusat dalam diri Paus di Roma. Hirarkisme itu adalah kuasa tak terbatas Paus sebagai penentu segalanya bahkan yang mengatasi para pemimpin bangsa di masa serba kerajaan di benua biru itu.
Hirarkisme ini pada akhirnya, atas kehendak sejarah dan Roh Allah sendiri, tiba pada zaman Modern sebagai puncak dari Abad Pertengahan (abad ke 5 - 15), yang kemudian mempersiapkan lahirnya zaman Aufklaerung, dan saatnya mendapat gugatan dan koreksi serta perlawanan yang melahirkan perpecahan dan pemisahan tertentu sampai kemudian menjadi "stabil" lagi seiring otonomi berpikir dan sekularisme serta otoritas negara menjadi penengah.
Sikon ini (dan segala masalah internal dan eksternal) telah memaksa gereja Roma terus berbenah sampai puncaknya dalam Konsili Vatikan Kedua (1962-1965), menghasilkan eklesiologi yang memberi tempat pertama kepada umat beriman, walau masih menempatkan Hirarki (Paus, Uskup, Imam) sebagai struktur yang menentukan. Bahkan prinsip "extra ecclesia nulla salus" (di luar gereja tidak ada keselamatan) dengan gugus terdepannya teologi apologetime mulai bergeser ke teologi dialogal dan ekumenis yang ramah. Dan kalau dihitung sejak konsili Trente (1545 - 1563) sebagai respons terhadap Reformasi Luther (1517) itu, pembaharuan-pembaharuan internal Gereja Roma ini butuh sekitar 500 tahun, sampai pada konsili ekumenis Vatikan Kedua dengan eklesiologi yang baru itu.
Semangat aggiornamento yang bermakna membuka jendela agar udara segar masuk oleh Paus pembaharu (Giovanni XXIII) yg menginisiasi konsili ini memang telah mengubah banyak hal dalam gereja bahkan dunia pada umumnya. Secara internal semangat keterbukaan ini adalah buah dari semangat inti pembaharuan pasca Kontra Reformasi: ecclesia semper reformanda et purificanda (Gereja selalu memperbaharui dirinya dan karena itu memurnikan diri).
Sejak Vatican II itu, paham eklesiologi sudah jauh berubah, yakni gereja bukan lagi disebut lembaga keselamatan (penekanan pada legal formal struktur pimpinan, ajaran, liturgi) tapi Sakramen keselamatan (tanda dan sarana). Persekutuan umat beriman itulah Gereja, bukan hirarki semata.
Sejauh Gereja umat beriman itu menghadirkan dan mewujudkan atau menandakan sang Yesus dalam kesatuan dalam Allah Tritunggal, maka layak dan pantas disebut Gereja. Kristuslah sebagai pemimpin, dan Gereja adalah sakramen Yesus Kristus sendiri. Pusat Gereja bergeser dari (Paus) Roma ke gereja lokal (Uskup) di seluruh dunia, dalam setiap paroki dan stasi, wilayah rohani atau kolom, bahkan sampai ke tingkat paling dasar sosialitas masyarakat manusia, yakni lembaga keluarga dengan teologi perkawinan yang ketat.
Saya jadi ingat tulisan Alm. YB Mangunwijaya dalam buku Gereja Diaspora (1999), salah satu kisah yang menginspirasi dia adalah suasana perang zaman Jepang di mana gereja lumpuh karena semua perkara sakramen termasuk urusan "seng dan semen" rumah tangga gereja diurus oleh hirarki yang mayoritas orang Belanda yang mesti masuk penjara bahkan dibunuh, dan justru dipertahankan bahkan dihidupkan dengan terseok dan perbekalan minim tapi pasti dan efektif oleh para pemimpin awam bersama keluarga inti dan besarnya.
Salah satu kisah pengalamannya di wilayah Ternate Maluku Utara (mungkin dalam rangka penulisan novel sejarah, Ikan-ikan Hiu, Ido, Homa, 1983), budayawan ini menyaksikan bagaimana sebuah keluarga Gereja Protestan Maluku berdoa dalam rumah, setiap hari saat makan bersama dan ibadah bersama di rumah. Ini sangat menyentuh hati Romo Mangun dan menjadi salah satu pengalamannya yang bagus sehingga diangkat sebagai contoh praktik ideal dalam sebuah Gereja yang selalu dalam status diaspora (berziarah di dunia ini), dan dalam konteks Indonesia yang luas dan dalam banyak wilayah, kekristenan itu minoritas.
Bro Sovian kembali mengingatkan kita untuk melihat Gereja Keluarga dan bagaimana itu bisa diperkuat sebagai bagian utama yang strategis menyikapi sikon pandemi COVID-19 dan segala "virus" lainnya yang memaksa orang untuk kembali ke rumah, dalam keluarga, persekutuan terkecil dan terdepan, sel dan benteng terakhir Gereja dalam situasi tidak normal ini.
Walau memakai sub judul wacana dekonstruktif, tapi tentu bung Sovian tidak sedang mendikotomikan Gereja domestik itu dengan Gereja Persekutuan, malah tetap memandang penting dan strategis peranan Institusi dan struktur yang selama ini telah menjadi tiang penopang yang sah dan berwibawa karena tugas pokok dan peranan khas mereka.
Pasalnya, istilah dekontruksi itu sendiri dalam wacana filsafat mengandung dua aspek yakni destruksi dan konstruksi. Kita tentu tidak sembarang medestruksi sebuah praktik yang punya dasar yang sudah mentradisi dan sangat alkitabiah! Rekonstruksi yang benar dan berguna tentu tak bisa dibuat bila kita tinggal pada upaya destruksi. Destruksi pun tak mesti dengan menghancurkan total, walau sudah pasti ada yang dihancurkan tak terhindarkan.
Dan pada akhirnya Sovian mengajak kita berefleksi sejauh mana Gereja benar itu secara mendasar adalah persekutuan beriman yang dibangun oleh ikatan sebagai satu tubuh, satu baptisan, satu iman, satu Roh, satu Tuhan... (surat Efesus), bukan pertama soal yang lain, apalagi elitisme atau hirarkisme, synodeisme dan komunitarianisme yang justru dalam kecenderungan ekstrimnnya akan membelenggu dan menyesakkan jiwa orang beriman sendiri, bahkan menjadi sebuah hujat pada Roh Kudus.
Mungkin ini semangat konstruksi yang hendak ditawarkan Sovian, bukan hendak menyudutkan institusi dan pemimpin resmi tertahbis, dan tentu siapapun bisa menerima dengan damai, tanpa peperangan wacana teologi yang tak berguna, malah mungkin hanya menunjukkan ego pribadi untuk sekedar keluar dari masalah.
Mungkin ungkapan bahasa bung Benni E. Matindas - - yang mendalami dokumen tebal Vatikan II - - dalam satu status di dunia maya belum lama ini, bahwa banyak orang gemar membuat tautologi atau pengulangan yang tak perlu dengan teodisea sendiri yang justru makin menyudutkan Allah sendiri. Sovian Lawendatu tentu jauh dari maksud hati dan pikiran semacam itu. Justru beliau menyentak kita untuk memakai iman dan rasio sekaligus, untuk mencari dan menegaskan identitas dan habitus baru, dari apa yang sudah ada tertulis dan tersirat dalam Alkitab sendiri.
Dalam dunia teologi bahkan bahkan kita menemukan ada banyak pemikiran dan mashab, yang masing-masing punya kecenderungan dan perspektif yang berbeda, tapi sesungguhnya hanya menunjuk pada totalitas yang satu dan sama tentang kristianitas itu sendiri yang berakar dalam tradisi bangsa Israel yang menjadi locus sejarah keselamatan (agama wahyu atau abrahamic tradition); Allah menyatakan diri untuk pertama kalinya dalam dan melalui sebuah bangsa dengan identitas dan sejarah kehidupannya.
Konsep Gereja Rumah bukan segalanya, walau menjadi semakin terasa relevansi dan kemendesakannya menghadapi situasi pandemi 3-4 bulan terakhir ini entah sampai kapan.
Dalam sejarah kita bisa belajar membaca tanda zaman, misalnya silih berganti konsep dan praktik menghadapi masalah bahkan yang berpretensi sebagai satu-satunya yang benar dan mendapat legitimasi Ilahi...
Pada akhirnya kita mesti tunduk hanya pada Dia yang telah berfirman dan memberikan kasih karuniaNya yang tak terbatas waktu dan tempat, tak terbatas bidang dan level, tak dibatasi oleh apapun termasuk oleh pandemi dan virus yang tak kasar mata ini. Ada tertulis, Roh Allah berhembus kemana saja Dia mau.
Para ilmuwan dengan tradisi berpikir rasional obyektif sedang berlomba mencari obat dan cara menyembuhkan atau menghindar dari serangan menyakitkan dan mematikan ini.
Semoga para agamawan yang mengaku dan percaya pada Tuhan tentu saja sudah jelas apa yang mesti dibuat sesuai Firman Tuhan sendiri yang sudah selalu direnungkan dan menggerakkan serta menghasilkan banyak tindakan kesalehan dan cinta kasih termasuk dalam menyikapi sikon seperti ini, yang ditunjukkan oleh para ilmuwan kristiani dalam banyak tradisi. Bahkan banyak ilmuwan yang ateis dan agnostik berbalik kepada teologi (refleksi iman bersumberkan Firman) untuk menjelaskan konsep teoritis dan praktis secara kreatif untuk menghadapi problematikanya di dunia yang satu dan sama ini.
Misalnya filsuf aliran Marxis, Slavoj Zizek, yang membuat refleksi filosofis berdasarkan kata-kata dalam peristiwa paskah, Yesus kepada Maria Magdalena: "Jangan Sentuh Aku!"... Rupanya menjadi judul bukunya: Noli Me Tangere, Touch Me Not. Bahkan info refleksi menarik ini pertama kali saya dapatkan dari budayawan penulis Reiner Emyot Ointoe, saudara Muslim yang tergabung dalam WAG PIKG, Perhimpunan Intelektual Kawanua Global baru-baru ini.
Solo Dios basta (Tuhan saja cukup)
I Yayat U Leos wo Lenas (tebarkan kebaikan dan kesucian)
/stefir