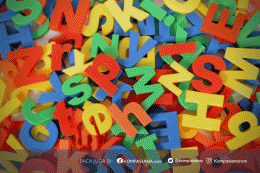"Dari mana lu, ke mana?"
Menyaksikan Lewat Djam Malam, saya bisa sedikit berasumsi bahwa pada masa itu fungsi bahasa Indonesia benar-benar sebagai alat pemersatu. Sekalipun para bintang filmnya itu barangkali "anak Jakarta" atau "anak Bandung", tapi mereka tetap mampu berbahasa Indonesia dengan baik. Dengan menggunakan bahasa Indonesia sesuai pakem, setiap orang di pelosok Nusantara akan memahaminya dengan mudah. Orang-orang di Aceh atau di Makassar tidak akan merasa ada semacam penjajahan budaya yang dilakukan oleh orang di Jakarta atau daerah lain. Apalagi kita tahu saat itu sentimen antardaerah masih cukup kuat. Pemberontakan DI/TII dan PRRI/Permesta terjadi pada dekade ini.
Tapi sekarang situasinya sudah berbeda. Jakarta menjadi pusat dari segalanya, termasuk industri hiburan. Semua "orang daerah" ingin identik dan merasakan Jakarta. Tidak hanya bahasanya, gaya hidupnya, tapi juga: menjadi gubernur Jakarta. Dalam keadaan seperti ini, segala yang datang dari Ibukota diterima dengan segala pasrah diri.
Alhasil, film atau sinetron Indonesia tidak perlu mencari bintang film dan sinetronnya yang berkemampuan bahasa Indonesia yang baik, pun bahkan berakting yang lumayan. Cukup mencari anak gaul Jakarta yang berwajah indo, lalu ajari sekilas ilmu akting, beres! Jikalau datang anak-anak muda dari Bumi Parahyangan atau Surabaya, yang bersangkutan akan dengan mudah berbahasa gaul ala Jakarta.
Mereka inilah yang kemudian menghiasi televisi dan layar lebar. Orang-orang di pelosok Indonesia tidak punya pilihan lain karena semua ditentukan oleh Jakarta. Lantas, bahasa Indonesia yang keren dalam pandangan orang-orang ini, bukanlah yang ada di buku-buku sekolah, tapi yang dipakai oleh "artis" di layar televisi.
***
"Ngapain pada bengong, ayo kita main?"
Coba tebak, siapa gerangan yang bicara seperti itu. Apakah seorang remaja yang tinggal di Kemang atau Pondok Indah? Ternyata bukan. Melainkan seorang anak Aceh yang selamat dari tsunami. Dialog ini berlangsung di sebuah film.
Perhatikan, alih-alih Si Inong (sebutan orang Aceh untuk anak perempuan) menggunakan logat Aceh, tapi sang sutradara dan penulis skenario memakai istilah-istilah ala Jakarta (minus gue dan elu). Sebagai jalan tengah supaya mudah dipahami, mengapa tidak dipakai bahasa Indonesia yang baku saja?
Mungkin, selain logat Batak dan Madura, sutradara di Indonesia merasa logat daerah lain di Indonesia kurang menjual (tak penting?). Terima kasih untuk pengacara-pengacara seperti Hotman Paris Hutapea, Hotma Sitompul (koruptorkah mereka gara-gara menjadi pengacara koruptor?), abang-abang preman terminal Kampung Rambutan, dan kondektur-kondektur angkot di Jakarta yang menunjukkan jati diri "anak medan"-nya sampai-sampai begitu beken dan terkenalnya logat kampungnya itu. Juga para tukang sate asal Madura yang menghiasi hari-hari orang Jakarta---pusat dari segalanya itu---di kala malam. Gara-gara kehadiran mereka di Jakarta, para sutradara merasa lebih terbiasa dan tak ragu memakai dua logat itu, baik jika dibutuhkan maupun sebagai penambah kelucuan belaka.
Sekali lagi: semua dilihat dari Jakarta. Film dan sinetron, sebagai ajang promosi budaya yang efektif, hanya berhasil memperlihatkan Jakarta dan bahasanya, bukan keindonesiaan secara umum. Saya membayangkan seorang yang tinggal di Pacitan ketika menonton Lewat Djam Malam, akan melihat kamus atau menanyakan kepada teman atau siapa saja yang memiliki kecakapan bahasa Indonesia di kampungnya tentang istilah-istilah baru. Dia akan menemukan istilah itu di kamus karena itulah kata-kata baku dari bahasa nasionalnya.