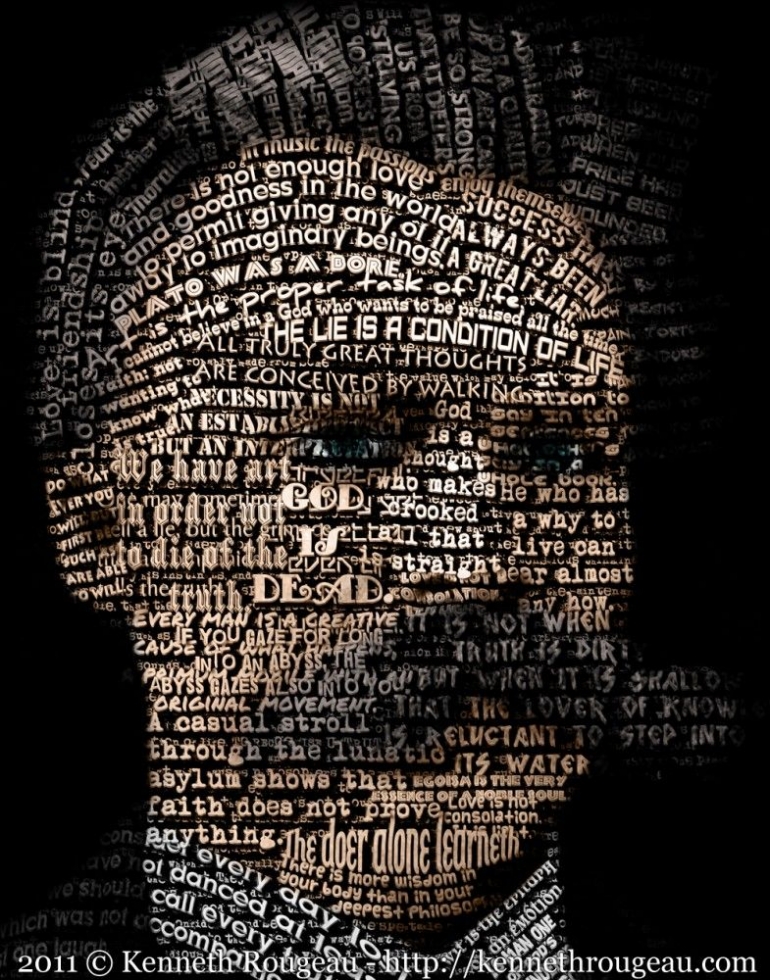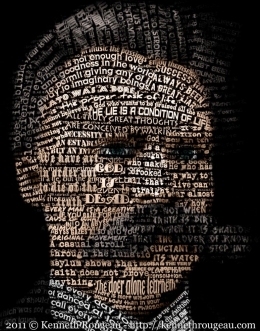Tulisan ini kubuat dalam rangka memeringati kematian sang filsuf besar bagiku, Friedrich Wilhelm Nietzsche, jadi tulisan ini kutulis pada tanggal 22 Agustus dan seharusnya diunggah pada saat hari kematiannya, yakni pada 25 Agustus. Nietzsche sebagai sosok filsuf besar tentu memiliki pengaruh yang luas, termasuk pada beberapa pemikiranku, setidaknya sedikit-banyaknya.
Nietzsche merupakan filsuf yang selalu dipertimbangkan ini, selama dua abad lebih -- mulai dari hari kematiannya, hingga hari ini! Kita tentu mengenal atau sedikit banyaknya pernah mendengar atau membaca "Nietzsche". Namun, selain filosof besar, siapakah Nietzsche itu? Bagi penulis pribadi, sosok Nietzsche merupakan Nabi, yang tentu saja ini merupakan pembaptisan pribadi olehku.
Aku membaptis demikian karena kegemilangan gagasan Nietzsche seperti suatu lorong yang sangat gelap dengan sedikit cahaya, dan kita berpetualang di dalamnya -- kita lah yang harus menyinari jalan kita sendiri.
Bagi Heidegger, Nietzsche merupakan ujung garis filsuf besar; dimulai dari Sokrates dan berakhir di Nietzsche. Bagi sebagian orang ateis, Nietzsche merupakan penggagas ateisme paling mutakhir, sedangkan bagi sebagian orang beragama yang mengenalnya, Nietzsche merupakan dosa besar bahkan tak lebih merupakan hanya orang yang di akhir hidupnya dipenuhi kegilaan, kegamangan.
Perkenalanku dengan Nietzsche nampaknya sudah bertahun-tahun lamanya, dan akupun lupa bagaimana perkenalanku dengan dirinya tersebut. Namun sering bayangan yang nampak di ingatanku adalah bahwa aku mengenalnya melalui pembacaanku terhadap ateisme Sartre, yang aku lupa dalam buku berjudul apa, namun yang jelas saat itu nama Nietzsche seketika membuatku menarik; tentu saja, seperti kebanyakan orang, akupun membaca "Tuhan Telah Mati"-nya Nietzsche, namun bukannya melancarkan kutukan, caci-maki atau menjauhinya, aku malah tertarik mempelajarinya.
Friedrich Wilhelm Nietzsche lahir di Rocken (Saxe-Prussia) pada 15 Oktober 1844 dan merupakan anak dari Karl Ludwig serta Franziska Oehler. Mungkin banyak orang yang mengira bahwa Nietzsche lahir dari keluarga ateistik, yang menerapkan filsafat rigor, dan sebagainya, tentunya orang seperti ini menggunakan peribahasa "buah jatuh tidak jauh dari pohonnya".
Baiklah, nampaknya itu tidak berlaku -- dan memang dalam beberapa kasus lebih sering tidak berlaku daripada berlaku, karena ayah Nietzsche adalah seorang pendeta Lutheran di Rocken, begitupun dengan kakek dan nenek buyut dari pihak ibunya.
Semasa hidupnya, Nietzsche telah banyak menerbitkan karyanya dan yang paling populer adalah Maka Bersabdalah, Zarathustra! (Thus Spoke, Zarathustra!), yang merupakan kunci untuk memahami Ubermensch dan Kehendak Berkuasa karena di dalamnya Nietzsche secara mendalam, namun dalam tulisan aforisme, memaparkan kedua hal tersebut -- meski pada kenyataannya kita akan dihadapkan pada serangkaian teks-teks yang tidak terduga bahkan membuat kita berpikir berkali-kali.
Dikisahkan bahwa Zarathustra, seorang tokoh dalam sebuah mitos, dalam buku ini dikisahkan sebagai seorang nabi yang telah lama berdiam diri di gunung kemudian turun ke bumi untuk mengajarkan Ubermensch. Zarathustra mengajarkan manusia yang ditemuinya untuk mencintai bumi dan alam sebagai kebaikan tertinggi, mengajarkan manusia untuk menerima segala macam baik-buruknya segala sesuatu yang ada di bumi agar manusia dapat melampaui dirinya.
Dalam karyanya inilah gagasan Nietzsche mengenai Tuhan Telah Mati sedikit-banyaknya diungkapkan -- setidaknya itulah yang aku rasakan saat membaca Maka Bersabdalah, Zarathustra. Pada prolognya, dikisahkan:
Tatkala Zarathustra berusia tiga puluh tahun, ia meninggalkan rumah dan danau rumahnya pergi ke gunung-gunung. Sepuluh tahun lamanya ia di sini bersukacita akan spiritnya serta penyendiriannya, sama sekali tidak merasa letih. Tetapi akhirnya hatinya berubah -- dan pada suatu pagi ia bangkit bersama fajar melangkah ke hadapan sang surya, lalu berseru padanya demikian:
"Bintang megah! Apa yang akan menjadi kebahagiaan kau, jika tidak ada mereka yang kau sinari! Kau telah datang ke atas guaku sini, sepuluh tahun: kau akan menjadi letih akan cahaya kau dan perjalanan kau, jika itu bukan untukku, elangku dan ularku.
Sungguh kami telah menunggu kau setiap pagi, telah mengambil dari kau, keberlimpahan kau dan memberkahi kau bagi ini. Perhatikan! Aku letih akan kebijaksanaanku, bak kumbang yang kebanyakan mengumpul madu; aku butuh lengan-lengan untuk menjangkau madu-madu ini. Aku mau berikan dan bagi-bagikan madu ini, hingga manusia bijaksana di antara para manusia akan bahagia lagi dalam kebodohannya dan manusia miskin bahagia dalam kekayaannya.
Bagi tujuan ini, aku musti turun ke kedalaman-kedalaman: bagai yang kau lakukan di sore hari, tatkala kau pergi ke belakang samudera dan memberi cahaya ke mercupada pula, wahai bintang maha berlimpah! Seperti kau, aku musti turun-kebawah -- sebagaimana yang manusia katakan, pada merekalah aku ingin turun!
Maka berkahilah aku, mata hening, kau yang bisa melihat kebahagiaan yang mahaberlimpahan tanpa rasa iri! Berkahilah cawan yang ingin meluap ini, semoga airnya yang keemasan itu mengalir darinya, membawa pantulan suka-cita kau ke seluruh penjuru! Perhatikan! Cawan ini mau menjadi kosong lagi, dan Zarathustra ingin menjadi manusia lagi."
Lalu mulailah Zarathustra turun-ke bawah.
Nampak bahwa Zarathustra turun ke bawah ingin turun ke bawah karena rasa cintanya kepada para manusia, ia melihat bahwa manusia telah lama berada dalam ketidaktahuan akan berlimpahnya potensi manusia di kehidupannya dalam menjadikan dirinya. Hal ini tentu berkaitan dengan Tuhannya manusia yang tentu saja tidak terbatas hanya pada Tuhan Allah, Yesus, Wisnu, Zeus serta Tuhan lainnya. Bicara mengenai Tuhan, ada banyak Tuhan di muka bumi ini.
Tuhan-tuhan yang menjadi semacam jangkar berlabuh bagi pelayaran manusia mengarungi samudera ketakterbatasan kehidupan ini. Zarathustra mencoba untuk membuka pandangan manusia, bahwa manusia mampu melampaui Tuhannya, bahkan membunuhNya, menerima segala suka-duka cita yang ada pada diri mereka, dan demi Ubermensch -- manusia yang melampaui.
Dalam Para Manusia Dunia-Kemudian, Zarathustra berkata :
"Ah, para saudaraku, Tuhan ini yang aku ciptakan ia adalah karya manusia dan kegilaan manusia belaka, seperti juga segala macam tuhan-tuhan! Ia adalah manusia, fragmen buruk sosok manusia dan Ego belaka. Dari api dan abuku, datanglah dia kepadaku hantu ini, inilah yang sebenarnya!
Dia tidak datang kepadaku dari alam 'luar' sana! Apa yang terjadi, para saudaraku? Aku, si penyengsara, mengatasi diri, aku bawa abuku ke gunung-gemunung dan aku membuat sebuah terang yang lebih benderang bagi diriku. Dan perhatikan! Lalu hantu itu lari dariku!"
Aku menangkap dari teks ini bahwa Tuhan yang ada di muka bumi ini merupakan Tuhan ciptaan manusia belaka atau tidak lebih daripada proyek antropomorfistik manusia terhadap sesuatu yang berada di luar dirinya. Tuhan, sebagai suatu proyek, tidak lebih merupakan cerminan manusia itu sendiri, suatu proyek eksternal yang oleh para manusia, pengikutnya, diberikan sifat kemahaan, sebagai suatu solusi terhadap ketidakberdayaan manusia dalam menghadapi realitas.
Sejauh manusia menghamba pada sesuatu, ia telah 'membakar' dirinya sendiri (kehilangan dirinya sendiri), lalu kita menyadari bahwa Tuhan hanya proyek antropomorfistik belaka, kita membawa diri kita (mengatasi diri kita) ke atas 'gunung-gemunung' di mana kita melampaui Tuhan, maka hantu (bekas diri kita yang dahulu menghamba) lari dari kita.
Penghambaan manusia terhadap sesuatu umumnya didasari oleh pemberian nilai-nilai yang lebih terhadap Tuhan tersebut. Penghambaan terhadap agama, negara, ideologi, sains, dan lain sebagainya tentu saja merupakan bentuk antropomorfistik manusia.
Sejauh tuhan-tuhan tersebut diberi nilai seperti "maha kuasa", "baik", "benar", "salah", "empiris", "benar-benar tidak ada" dan lain sebagainya, maka tuhan tersebut tidak lebih dari sekedar proyek antropomorfistik; bahwa ada sesuatu yang lebih berkuasa, lebih baik, lebih benar, lebih salah, lebih empiris, daripada manusia.
Bukankah manusia yang memberi nilai bahwa sesuatu tersebut lebih daripada dirinya? Ya! Karena binatang maupun tumbuhan tidak mampu melakukan demikian! Kalau begitu, bukankah berarti manusia lebih daripada apa yang mereka beri nilai karena jika tanpa manusia maka tuhan-tuhan tersebut tidak berarti apa-apa? Namun kita tidak menyadarinya, kita menghamba pada sesuatu yang bahkan kita beri nilai!
Ini merupakan salah satu bentuk ateisme, namun jika demikian bagaimana dengan hal-hal di luar sana banyak sesuatu yang memiliki kekuatan lebih dan memengaruhi diri kita? yang belum bisa dicapai oleh nalar manusia? Ini merupakan titik di mana manusia, yang belum memiliki segala pengalaman, masih terus belajar, mulai mengafirmasi isi kitab suci -- setidaknya sejauh ini, inilah yang dapat kurasakan dari mereka.
Manusia-manusia ini takut, mereka butuh percaya terhadap proyek antropomorfistik mereka, maka mereka menggunakan ketidaktahuan ini untuk mengafirmasi segala nilai "maha-" yang mereka berikan. Tentu saja hal ini tidak berlaku pada agama saja, namun pada hal lain yang disebutkan di atas, pada segala jenis tuhan yang manusia sembah.
Dari sini ateisme bisa mengatakan bahwa tidak ada Tuhan, yang ada hanyalah tuhan, namun dari mana kita bisa tau bahwa di sini atau di sana ada atau tidak ada Tuhan? Ini tentu merupakan perdebatan yang melelahkan namun terus berlanjut dan berulang bagi kita semua.
Namun menganggap bahwa Ubermensch merupakan tujuan manusia -- atau bahkan merujuk pada satu jenis manusia tertentu nampaknya bukan itulah tujuan Zarathustra turun. Zarathustra berkata:
"Manusia adalah tali, diikat di antara binatang dan Ubermensch -- seutas tali di atas jurang maha dalam. Bahaya pergi menyeberang, bahaya mengembara, bahaya menoleh belakang, bahaya gemetaran dan diam berhenti.
Apa yang megah dalam diri manusia bahwa ia adalah jembatan bukan tujuan; apa yang patut dicintai dalam diri manusia bahwa ia adalah perjalanan naik-keatas dan turun- kebawah. Aku cinta mereka yang tidak tahu bagaimana untuk hidup kecuali hidup mereka adalah turun-kebawah karena ada mereka yang naik-keatas."
Manusia merupakan jembatan, manusia tidak akan mencapai Ubermensch. Ubermensch bukanlah suatu jenis ras manusia, pun suatu sosok penyelamat umat manusia karena jika ditafsir demikian maka hanya utopia belaka yang kita dapatkan, karena sejak 2 abad kematian Nietzsche berlalu, Ubermensch sama sekali belum ada hingga saat ini.
Aku menangkap bahwa Zarathustra, melalui perkataannya tersebut, menginginkan manusia untuk selalu menjembatani dirinya sendiri, selalu menyebrangi dirinya sendiri, selalu mengatasi dirinya sendiri, untuk melampaui dirinya sendiri. Namun jembatan manusia ini tidaklah menjadikan manusia beranggapan bahwa dirinya hanya sekedar jembatan, manusia harus beranggapan bahwa manusia merupakan proses pelintasan itu, proses pelampauan itu.
Itu yang terpenting dari Ubermensch bagiku; proses untuk selalu melampaui kebaikan-keburukan dunia, menampung mereka, bukan lari dari mereka, tentu saja hal ini juga berarti untuk melepaskan serta melampaui kepercayaan mereka -- tidak terpaku pada kepercayaan tersebut. Ubermensch merupakan kehendak berkuasa yang lepas dari manifestasi kebutuhan akan percaya. Perumpaaan Zarathustra bahwa manusia adalah jembatan, manusia tidak seharusnya berhenti di suatu tempat; bahwa manusia harus terus melangkah melampaui dirinya, berproses sebagai Ubermensch.
Kepercayaan manusia terhadap tuhan-tuhan ternyata memengaruhi kehendak berkuasanya. Setyo A. Wibowo, dalam kuliah filsafat Nietzsche mengenai Kehendak Berkuasa dan Kebutuhan untuk Percaya berkata:
"bagi Nietzsche soal fanatisme atau relativisme di depan isi kepercayaan merupakan mekanisme internal kebutuhan untuk percaya yang ada di dalam individu itu sendiri, bukan oleh kuantitas atau isi kepercayaan yang diketahui. Investasi psikologis seseorang atas apa yang ia percayai itulah yang menentukan apakah dia menjadi fanatis atau relativis.
Soalnya bukan pada jumlah atau kuantitas isi kepercayaan yang bersifat bisa saling dipertukarkan serta diluar subjek, soal yang pokok adalah pada kualitas dari sesuatu yang membutuhkan kepercayaan tersebut, yaitu kualitas kehendak seseorang, dalam bahasanya Nietzsche.
Pekat-cairnya intensitas kebutuhan untuk percaya inilah yang mencerminkan kualitas kehendak -- apakah suatu kehendak itu utuh, kuat atau sebaliknya terserak-serak, cacat. Semakin kualitas kehendak seseorang cacat, kebutuhannya untuk pegangan atau percaya akan besar.."
Dari sini, aku mendapatkan bahwa kepercayaan itu tidak bermasalah, kepada agama, kepada sains, kepada ateisme, dan lain sebagainya, melainkan manusia itu sendiri yang bermasalah. Mengapa manusia ingin selalu benar dan tidak ingin sedikitpun salah? Karena kita ingin kebenaran (versi kita) berkuasa di atas segala macam kebenaran lain!
Tentu saja kehendak serta usaha dalam menegakan kebenaran dapat memicu seseorang untuk menjadi fanatis atau relativis. Kehendak akan kebenaran merupakan manifestasi kebutuhan akan percaya. Manusia memanifestasikan kebutuhan akan percaya-nya dalam serangkaian kehendaknya untuk berkuasa (membuat kebenarannya berkuasa).
Sebenarnya, melalui Maka Bersabdalah, Zarathustra! dan didukung oleh buku lainnya, kita dapat menarik bahwa untuk mendapatkan kehendak berkuasa yang kuat dan utuh kita harus menanyai kehendak kita sendiri.
Pada saat kita memiliki dan akan melaksanakan kehendak, Nietzsche menekankan pada semacam introspeksi diri yang mendalam bahwa pada saat manusia menghendaki sesuatu ia haruslah bertanya apakah ia benar memaui kehendak tersebut dan bertanya apakah kemauan terhadap kehendak tersebut benar-benar ia maui dan bertanya lagi apakah ia memaui kemauan terhadap kemauan kehendak tersebut dan bertanya lagi seterusnya seterusnya, apa yang terdalam dari diri manusia.
Lalu apakah ini berarti manusia akan selalu melakukan suatu penundaan terhadap suatu kehendak? Belum tentu! Manusia dapat selalu memperbarui kehendaknya selagi melakukan kehendaknya, mencari tahu apa yang sebenarnya dimaui selama melakukan kehendak karena kehendak merupakan diri; pemikiran, insting, dan nafsu.
Bagi Nietzsche, mekanisme terhadap kepercayaan-kepercayaan yang melingkupi kehidupan dalam hal apa saja ternyata sama saja; baik dalam agama, sains, filsafat, patriotisme, politik, ideologi, bahkan dalam ateisme. Kebutuhan untuk percaya secara langsung berkaitan dengan lemah atau kuatnya kehendak.
Saat kehendak cacat, kebutuhan akan kepercayaan menjadi sesuatu yang sangat urgen; saat orang tidak utuh, orang membutuhkan sesuatu untuk melengkapi dirinya. Dalam hal kepercayaan, saat seseorang semakin tidak mampu memerintah diri maka semakin dia merasa dengan urgen kebutuhan akan suatu realitas, akan sebuah otoritas, yang memerintahnya dengan rigor -- entah itu dalam wujud suatu Tuhan, pangeran, presiden, sistem sosial, dokter, bapa pengakuan, dogma atau suatu kesadaran partai.
Kebutuhan akan otoritas eksternal ini berfungsi untuk mengafirmasi kehendak yang dilakukan oleh manusia bersangkutan. Manusia yang bersangkutan membutuhkan semacam sandaran stabil dalam melaksanakan kehendaknya, sandaran tersebut berfungsi untuk mengafirmasi kehendak yang akan dilakukan, dan kehendak yang akan dilakukan pun harus mengafirmasi.
Dari sini dapat dilihat bahwa dalam hal kepercayaan, kita membutuhkan sesuatu yang afirmatif untuk mengafirmasi segala tindak-tanduk yang kita lakukan, dan sesuatu yang afirmatif tersebut harus diafirmasi dengan sesuatu yang afirmatif, kemudian harus diafirmasi kembali oleh sesuatu yang afirmatif, dan seterusnya, seterusnya.
Dari sini nampak bahwa kepercayaan merupakan serangkaian kegiatan mengafirmasi terus-menerus berulang kali, hingga membuat diri kita percaya padanya. Dari sini dapat pula digariskan bahwa masalah-masalah kepercayaan timbul justru bukan dari kepercayaan itu sendiri, melainkan dari manusia tersebut -- kehendak serta kebutuhan untuk percaya menentukan faktor apakah seseorang itu fanatis atau relativis.
Permusuhan Nietzsche terhadap ide fiks (idea fixee) bak berfilsafat dengan palu, ia menggebuk semuanya, hingga ke jeroannya -- bahkan ia menyatakan perang pada para insting idea fixe ini, khas teolog. Idea fixe dapat kita temui dalam beragam bentuk, seperti agama, pandangan politis, ideologi, dan lain sebagainya sehingga manusia mengesampingkan realitas yang ada bahkan hingga menciptakan realitas baru yang tentu saja non-sense.
Manusia yang tidak berani menghadapi realitas di hadapannya dan lari atau membuat realitas baru bagi Nietzsche merupakan suatu ketakutan akan fatalistik, akan kekecewaan. Ini merupakan bentuk nihilisme pasif, suatu dekadensi! Namun tentu saja nihilisme tidak melulu bersifat ateisme atau anti-teisme karena nihilisme juga terdapat dalam isme-isme, filsafat, agama, dan lain sebagainya.
Nietzsche merumuskan dua macam bagaimana orang menjalani nihilisme, yakni nihilisme pasif dan aktif. Nihilisme pasif merupakan suatu bentuk dekadensi (decadence), kemunduran, sedangkan nihilisme aktif kebalikannya; menaik, asendens (ascendence).
Sebagai manusia, kita takut berhadapan dengan sesuatu yang kita belum kenali sebelumnya, pun kita takut memasuki suatu kegelapan pekat yang kita tidak tahu ada apa di dalamnya dan pada dasarnya kita pun dihadapkan demikian. Namun, jika kita mengatasi nihilisme secara aktif, kita akan menemukan siapa diri kita dengan terus-menerus melakukan evaluasi kembali terhadap semua nilai yang ada di kehidupan kita terus-menerus.
Kita berani menjelajahi ketidaktahuan kita yang tentu saja kita akan menemukan diri kita, kita akan memiliki semangat serta optimisme dalam kehidupan, terlepas dari segala beban Kamu Harus yang kita tanggung dalam setiap kepercayaan, dalam setiap idea fixee. Lain halnya jika menjalani nihilisme secara pasif; kita hanya akan terus-menerus menjalani Kamu Harus, kehilangan kesempatan untuk mengenali diri kita sendiri, bahkan menjadi martir demi idea fixe tersebut.
Di sini timbul pertanyaan nihilistik, bagaimana kita bisa memercayai begitu saja dengan yakin kepada agama, ideologi politik, sains, dan lain sebagainya? Bukankah hal-hal tersebut merupakan sesuatu yang kosong, gelap, yang belum pasti, serta menuntut kepatuhan luar biasa? Bukankah hal-hal tersebut merupakan suatu yang nihil?
Bagi Nietzsche, orang-orang dekaden merupakan orang-orang sakit yang semakin sakit setiap harinya. Idea fixe bagi sebagian orang mungkin berfungsi sebagai obat, namun hal fiksatif ini jika dikonsumsi berlebihan hanya akan menjadi candu yang justru semakin membuat sakit -- ketergantungan hingga menjadi martir, pun tidak mengonsumsi hal tersebut merupakan hal yang tidak mungkin karena berpihak pada fiksatif ketidakpercayaan akan idea fixe juga merupakan konsumsi yang jika berlebihan pun akan menjadikan seorang ateis bergantung dan menjadi martir, menjadi dekaden.
Ketergantungan di sini berarti keengganan untuk mengevaluasi kembali nilai-nilai yang kita percayai -- teisme, ateisme, agama, ideologi politik, sains positivisme, sains naturalisme, dan lain sebagainya, singkatnya mereka menjadi dekaden. Manusia yang mengevaluasi setiap nilai terus-menerus, menanyakan segala idea fixe dan tidak berdiam diri di dalam idea fixe (percaya pada finalitas sesuatu, pada finalitas idea) bagi Nietzsche merupakan sosok manusia menaik, asenden.
Keengganan Nietzsche untuk memulai dengan jatuh dalam suatu fiksasi akan idea, menjadikan Nietzsche berada di antara tegangan Ya dan Tidak, membuatku sepakat dengan Romo Setyo A. Wibowo bahwa Nietzsche merupakan sosok yang saleh. Apakah Nietzsche beragama? Jelas tidak karena ia anti dengan yang namanya idea fixee, namun apakah ia ateis? Tentu namun perlu digarisbawahi bahwa ateisme Nietzsche di sini pun anti dengan idea fixe ateisme.
Nietzsche saleh karena ia tidak merusak realitas, ia mengajarkan kita untuk menerima serta menghadapi realitas apa adanya -- tentu saja realitas yang terserak dan merupakan campur-adukan dari kebenaran, kesalahan, kebaikan, keburukan. "Kebijaksanaan adalah serangkaian kejahatan atas alam!" begitu kata Nietzsche.
Apa maksudnya? Ya! Kebijaksanaan agama, teisme, ateisme, saintifik, dan lain sebagainya telah merusak alam -- merusak realitas yang campur-aduk ini. Nietzsche menganalogikan kehendak akan kebenaran (idea fixe) seperti suatu kota yang dijaga ketat oleh polisi yang menyensor setiap hal yang memasuki kota tersebut.
Manusia yang terpaku pada idea fixe cenderung selalu menginginkan dirinya untuk selalu benar, tidak pernah salah. Pertanyaanku pada mereka adalah kenapa sih mereka harus benar dan tidak mau salah? Toh, bukankah realitas ini merupakan campur-aduk antara kebenaran dan kesalahan, yang juga berguna? Bagiku, ini merupakan utopia manusia demikian.
Seandainya pun dunia hanya berisikan kebenaran, toh pada manusia akan selalu berdebat karena tentu saja kebenaran kapitalisme berbeda dengan kebenaran marxisme, bahkan kebenaran antara kapitalisme (subjek) A dengan B berbeda, bahkan kebenaran kapitalisme A1 dengan A2 berbeda. Di sini yang nampak justru bukanlah kesalahan, namun tipe-tipe kebenaran. Mengenai ini, nampaknya cukup aku akhiri dengan kutipan dari Nietzsche: "ada banyak pasang mata di dunia ini, bahkan Sphynx pun memiliki mata. Maka terdapat banyak kebenaran, dan oleh karena itu tidak ada kebenaran."
Permusuhan Nietzsche terhadap idea fixe juga nampak pada perdebatannya dengan Sokrates, namun yang nampaknya amat sengit perdebatannya dengan Platon. Nietzsche menolak gagasan mengenai idealisme Platon yang merumuskan bahwa ada banyak hal yang ideal di dunia ideal sana.
Bahwa ada semacam kuda ideal, aku ideal, yang tentu saja mengenai hal ini kalian bisa membaca makalah kelas filsafat yang ditulis oleh Romo Setyo, pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara yang berjudul Sejarah Filsafat Yunani Kuna: Platon yang terbit pada 19 Maret 2016 oleh Serambi Salihara. Konsep mengenai dunia ideal melahirkan konsep dunia-sana dalam agama-agama, serupa tapi tak sama seperti pemikiran bernuansa metafisika Platon.
Para agamawan, dalam mengajarkan atau menganjurkan sesuatu kerap diiringi dengan embel-embel dunia-sana, yang menuntut seseorang mematuhi para pemuka agama dengan membabi-buta bahkan menjadi martir untuknya. Tentu saja bagi Nietzsche ini merupakan suatu masalah!
Pendapat Nietzsche mengenai hal ini aku kutip dari karyanya Anti-Christ, sebagai berikut:
"... mengenai Tuhan -- Tuhan sebagai Tuhan mereka yang sakit, Tuhan sebagai laba-laba, Tuhan sebagai ruh -- adalah konsep mengenai Tuhan yang paling korup yang ada di dunia: barangkali bahkan menggambarkan titik surut terendah dalam proses kemerosotan tipe Tuhan. Tuhan merosot menjadi kontradiksi kehidupan, bukanya menjadi transfigurasi kehidupan itu dan Ya yang abadi! Dalam Tuhan itulah terdapat deklarasi permusuhan terhadap kehidupan, alam, kehendak hidup! Tuhan itulah resep untuk setiap fitnah terhadap 'dunia kini', untuk setiap dusta mengenai 'dunia nanti'! Dalam Tuhan itulah ketiadaan dituhankan, kehendak kepada ketiadaan disucikan!"
Nietzsche secara gamblang mengatakan bahwa seharusnya Tuhan dapat menunjang kehidupan -- tentunya bukan dengan penghambaan buta, apalagi menjadi martir. Tuhan dapat menunjang kehidupan manusia selama (apa yang kita sebut dengan) Tuhan tersebut tidak menghalangi kemanusiaan kita, tidak membuang apa-apa yang sekiranya nampak (dunia kini) untuk hal yang tidak nampak (dunia nanti).
Orang beragama kelak membuang dunia kini untuk dunia nanti, sehingga kemanusiaannya di dunia kini terpaksa dikesampingkan demi tujuan individualistik akan pencapaian dunia nanti dan Tuhan dimanfaatkan untuk tujuan ini. Tuhan menjadi suatu alat penentang, suatu kontradiksi dalam menjalani kehidupan di dunia kini.
Tuhan yang seharusnya menjadi penunjang kehidupan, bisa langsung menjadi kontradiksi dalam kehendak manusia bahkan membuat manusia meninggalkan realitasnya, menyangkal kehidupannya. Tentu saja hal ini tidak terbatas pada agama saja, dalam kasus fasisme, ateisme radikal, sains, dan lain sebagainya memiliki mekanisme yang sama.
Lalu bagaimanakah Tuhan di mata Nietzsche? Tentu saja sudah mati! Tuhan sebagai cahaya hidup manusia telah mati dan Ini tentu menggoncang para manusia. Namun kematian Tuhan jangan dianggap menyebabkan nihilisme, kematian Tuhan justru mempertegas, membuka tabir bahwa Tuhan tidak lebih daripada suatu hal yang kosong -- dan sekali lagi manusia dihadapkan pada ketiadaan pegangan, suatu kondisi nihil.
Mengenai kematian Tuhan ini, Nietzsche melukiskannya dalam narasi Si Orang Sinting (der Tolle Mensch) yang lumayan panjang, adapun narasi tersebut dikutip dari buku Menalar Tuhan yang ditulis oleh Franz Magnis Suseno dan berisikan sebagai berikut:
"Pada siang bolong, manusia gila itu menyalakan obor, lari ke pasar dan tak henti-hentinya berteriak 'aku mencari Tuhan! Aku mencari Tuhan! .... ke manakah Tuhan?' ia berteriak. 'Aku akan mengatakannya padamu! Kita membunuh-Nya! Kita semua adalah pembunuhnya! Tetapi bagaimana kita melakukannya? Bagaimana kita dapat meneguk habis samudera? Siapa yang memberikan spons untuk menghapus habis seluruh cakrawala? Apa yang kita lakukan waktu kita melepaskan bumi ini dari matahari? Ke manakah dia sekarang? Ke manakah kita sekarang? Menjauhi semua matahari? Bukankah kita terus-menerus jatuh? Dan ke belakang, ke pinggir, ke depan, ke semua sudut! Masih adakah atas dan bawah? Bukankah kita berkelana bagaikan dalam ketiadaan tak terhingga? Bukankah ruang angkasa kosong menghembusi kita? Bukankah semuanya terasa lebih dingin? Bukankah malam datang dan lebih banyak malam terus-menerus? Bukankah di pagi hari perlu dinyalakan lentera? Tidakkah kita mendengar, ribut-ribut para penggali kuburan mengubur Tuhan? Tidakkah kita mencium bau pembusukan Illahi? Dewa-dewa pun membusuk! Tuhan mati! Tuhan tetap mati! Dan kitalah yang membunuh-Nya! Bagaimana kita dapat melipur diri, para pembunuh semua pembunuh? Bukankah keagungan tindakan ini terlalu agung bagi kita?'...."
Kematian Tuhan, sebagaimana telah dibicarakan di atas, tentu mengguncang manusia. Peristiwa ini mengguncang manusia karena tidak ada lagi yang menaggung perbuatan manusia, manusia sendirian dalam menentukan segalanya, tanpa pegangan, terombang-ambing di samudera ketakterbatasan, nihilisme berkuasa. Namun sebagaimana dalam Zarathustra, bahwa manusia adalah sesuatu yang harus diatasi, maka Nietzsche berkata:
".... yang dapat mengatasi nihilisme harus manusia yang mengatasi manusia, Sang Ubermensch! .... Tuhan mati: sekarang kami menghendaki agar Ubermensch hidup. Dia lah yang akan berani menentukan sendiri apa yang bernilai baginya dan dengan demikian menjadi 'Pengalah Tuhan dan Nihilisme'...."
Dalam menghadapi nihilisme pasca kematian Tuhan, manusia haruslah mengatasi nihilisme secara aktif; Ya kepada dunia seadanya, tanpa dipotong, tanpa kekecualian dan dipilih-pilih, Ya terhadap apa saja yang membuat kuat, menyimpan tenaga, yang membenarkan perasaan kekuatan dan bukannya mengatasi nihilisme secara pasif: Tidak kepada segala sesuatu yang melemahkan -- yang membuat diri semakin capai, letih.
Dalam paragraf mengenai kematian Tuhan, nampak bahwa Nietzsche tidak membunuh Tuhan sendirian karena kita turut berpartisipasi dalam pembunuhan Tuhan. Kaum agamawan yang lebih percaya pada tafsir serta ajaran yang dibuatnya sendiri merupakan suatu fenomena pembunuhan Tuhan, demikian pun dengan kaum saintifik yang secara gamblang menolak segala metafisika, menolak Tuhan, begitu pun dengan kaum penyembah lainnya.
Kehadiran Tuhan ditafsirkan hingga memerlukan pengorbanan dari diri manusia; pengorbanan untuk berjihad, untuk empiris, untuk patriotis, dan lain sebagainya, yang tentu saja gagasan pengorbanan diri ini datang dari petinggi-petinggi paham tersebut. Namun kematian Tuhan tidak berarti buruk sama sekali.
Nihilisme yang terungkap melalui kematian Tuhan setelah beribu-ribu tahun kita hidup dalam belenggu kebohongan Tuhan, menjadikan kita sebagai pelaut yang kembali berlayar ke samudera tak terbatas, menarik jangkar dari kapal dan kembali berlayar dalam ketakterhinggaan luasnya serta bahaya samudera.
Alih-alih Nietzsche tampak materialistik karena menolak metafisika Platonisme, bagiku nampaknya Nietzsche justru religius dan metafisika. Hanya saja metafisika Nietzsche datang dari bumi sedangkan Platon datang dari langit. Religiusitas Nietzsche dapat kita lihat melalui Ubermensch, sedangkan metafisika Nietzsche dapat kita lihat melalui Kehendak Berkuasa.
Keyakinan akan nihilisme pasca kematian Tuhan yang akan berkuasa selama 200 tahun (yang mana hal ini juga merupakan keyakinan Nietzsche) dan menjadikan manusia sebagai Sang Ubermensch melalui fenomena ini bagiku nampaknya utopis jika ditafsirkan demikian, meski kuakui bahwa Nietzsche nampak menarasikan Ubermensch sebagai suatu tujuan manusia.
Merupakan sebuah utopia karena sudah lebih dari 200 tahun kematiannya namun belum ada satupun ras atau sosok Ubermensch, pun bersikap demikian justru bertentangan dengan sikap Nietzsche terhadap fiksasi idea fixe. Aku menafsirkan bahwa Ubermensch merupakan dalam diri manusia yang selalu bergerak-melampaui dirinya sendiri, sebagai suatu proses bukan suatu tujuan akhir, suatu finalitas.
Hal lain dari Nietzsche yang aku tangkap adalah Nietzsche mengajarkan kita untuk menemukan diri kita sendiri, bukan mengikuti dan menjadi Nietzsche atau orang lain, tapi mengikuti dan mejadi diri kita sendiri.
Nietzsche pun nampaknya tidak menerima sebutan pengikut 'Nietzschean' karena pada nyatanya ajaran Nietzsche bukanlah untuk mencari pengikut, melainkan untuk membantu kita menemukan diri kita, pun jika kita amat tertarik dengan Nietzsche, ia telah memperingatkan kita:
"Vadamecum-Vadatecum. Gaya dan bahasaku merayumu? Apa? Kau hendak mengikutiku langkah demi langkah? Lebih baik perhatikan dirimu sendiri, dan dengan cara begitu kamu akan mengikutiku -- dengan pelan-pelan!"
Mengenai inipun Romo Setyo berkomentar, melalui buku Gaya Filsafat Nietzsche:
"Tidak mengherankan bahwa proses semacam ini tidak bisa tidak hanya akan memunculkan pemikiran yang personal. Berfilsafat adalah memasukan diri dalam alur ziarah transformasi personal. Apa saja yang mengenai diri kita, dengan seluruh diri kita, ditransformasikan sedemikian rupa sehingga kita semakin menjadi diri kita sendiri: itulah definisi filsafat personal a la Nietzsche."
Nietzsche sadar betul bahwa kita selama berkepercayaan telah kehilangan diri kita; khususnya era otoritas keagamaan mencapai puncaknya, pun pada era otoritas saintisme mencapai puncaknya. Untuk mencapai kembali diri kita, Nietzsche merumuskan hal-hal kurang lebih seperti yang kutuliskan di atas.
Tapi bukankah dengan demikian, kita ditantang untuk terus mencari dan memperbarui diri kita yang dengan demikian justru menjadi rigoritas yang ketat karena tidak hanya menyangkut diri kita melainkan juga menyangkut sudut pandang kita? Namun itulah konsekuensi kita jika ingin terjun langsung ke dalam filsafat a la Nietzsche.
Tulisan ini merupakan suatu bentuk selebrasi dan apresiasi terhadap salah satu filsuf yang mampu mengubah cara pandangku terhadap hal-hal yang ada di depanku, ditulis dalam rangka memeringati kematian Nietzsche serta kurang lebih berisi gagasan filosofis Nietzsche yang aku rujuk dari beberapa literatur serta sumber, yang mungkin juga akan memunculkan diskusi di antara pembaca dan penulis, tentu saja ini bermanfaat untuk memperluas kedua belah pihak.
Tulisan ini kurang-lebih/sedikit-banyaknya terbatas pada Ubermensch, Kehendak Berkuasa, Tuhan Telah Mati dan tentunya masih sangat jauh dari kedalaman tiga gagasan tersebut. Di akhir, nampaknya tulisan ini tidak akan memuat semua gagasan Nietzsche karena tidak akan cukup beberapa lembar dan waktu saja untuk menulis Nietzsche.
Tentu saja tulisan ini juga jauh dari kata sempurna dan kritik serta saran dari para pembaca yang budiman sekalian sangat dibutuhkan. Jika ada sesuatu yang ingin dibicarakan, pembaca dapat melakukan diskusi melalui nomor WhatsApp penulis, yang tentu saja hal ini juga akan membantu penulis dalam memperluas pandangannya serta berbagi sudut pandang.
Bagi penulis, Nietzsche merupakan sosok filsuf yang ultim. Harapan penulis adalah semoga tulisan ini dapat menjadi pengantar menuju pintu memasuki pemikiran Nietzsche. Sekian dan terima kasih sudah membaca.
SUMBER:
Gaya Filsafat Nietzsche, A. Setyo Wibowo, Yogyakarta: Kanisius, 2017
Para Pembunuh Tuhan, A. Setyo Wibowo, dkk., Yogyakarta: Kanisius, 2015
Thus Spoke Zarathustra, Friedrich Wilhelmn Nietzsche, USA: Penguin Books, 1966