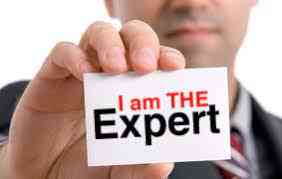Hari-hari ini kita dapat melihat bahwa, dalam kehidupan sehari-hari, terutama di media sosial, tiba-tiba setiap orang merasa dirinya pakar. Mereka bebas mengomentari, mengulas, menganalisis, bahkan menghakimi setiap fenomena, baik peristiwa ilmiah, spiritual, sosok, atau hal gaib sekali pun dengan berbagai argumen. Bahkan, jika ingin, mereka dapat menciptakan realitas palsu (pseudo reality) untuk kemudian disebarluaskan sebagai kenyataan yang hakiki.
Hari ini, tidak perlu kuliah jurusan politik selama empat tahun dan menyandang sarjana di bidang politik, misalnya, untuk ikut mengomentari peristiwa politik yang tengah hangat, bahkan dengan analisis yang terdengar sangat canggih. Ada juga contoh yang lain: tidak perlu menyandang gelar sarjana bidang astronomi, untuk dapat dengan gagah berani ikut mengklaim kebenaran teori bumi datar, lonjong, atau kotak.
Saat pandemi Covid 19 melanda, bermacam teori dan penjelasan berseliweran di sekitar kita tentang hal-ihwal bencana umat manusia tersebut, baik dari mulut ke mulut maupun di jagat maya. Ironisnya, tidak semua teori dan penjelasan tersebut berasal dari pihak atau orang yang memang memiliki kompetensi di dalam bidang terkait.
Lebih jauh, bahkan banyak dari pihak tidak berkompeten itu justru membangun opini atau argumen bahwa vaksin Covid tidak diperlukan karena: haram, merusak tubuh manusia, di dalamnya terdapat chip pihak asing, dan berkarung penjelasan lain yang jika sedikit saja dikaji dengan akal sehat membuat kita tersenyum geli. Namun, faktanya banyak orang yang terpengaruh, dan akhirnya menjadi seorang yang anti vaksin.
Mundur beberapa tahun silam, kita mengenal sosok Rangga Sasana, atau yang lebih dikenal sebagai Lord Rangga. Ia menghebohkan masyarakat dengan klaim dan teori-teorinya. Pentagon milik Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa bermula dari Bandung merupakan salah satu klaimnya.
Satu klaimnya yang lain mendistorsi pengetahuan sejarah tentang Nusantara, di mana ia mengatakan bahwa wilayah Nusantara tidak hanya Indonesia, melainkan mencakup 54 negara yang terbentang dari Korea sampai Australia. Pendidikan Rangga Sasana sendiri hanya sampai Sekolah Pertanian Menengah (SPM).
Suka-tidak suka, sepakat-tidak sepak, di sinilah kita sekarang. Era ketika kepakaran tidak lagi menjadi hal vital untuk melegitimasi keabsahan informasi dan penjelasan terkait suatu fenomena atau bidang kehidupan.
Era di mana siapa saja, bahkan orang awam sekali pun, dapat merasa memiliki argumen, pendapat, informasi, dan analisis yang lebih andal dari seorang ahli atau pakar, dan tidak segan-segan menyebarluaskannya dengan percaya diri. Lord Rangga dan teoretikus anti vaksin sudah membuktikannya.
Tom Nichols dalam bukunya yang berjudul Matinya Kepakaran mengulas berbagai fenomena terkait matinya kepakaran, mulai dari indikasi-indikasi dan pola penyebabnya.
Secara sedehana, melalui bukunya itu Nichols hendak menyampaikan pesan bahwa hari ini ilmu pengetahuan sebagai penopang kehidupan manusia, yang dihasilkan dari laku ilmiah, sedang dan sudah perlahan disuntik mati oleh bahaya laten anti kepakaran. Artinya, hari ini untuk menjelaskan berbagai hal-ihwal, seseorang tak perlu menyandang gelar pakar yang diraih melalui perjalanan akademis dan intelektual yang panjang.
Siapa Dalang Pembunuhan Kepakaran?
Pakar atau ahli, sebuah status dan bentuk kemampuan, yang hari ini mulai kehilangan wibawa dan eksitensinya. Setidaknya menurut Tom Nichols. Dalam bukunya, Nichols mengurai berbagai indikasi dan penanda terdelegitimasinya kepakaran. Tidak hanya mengurai indikasi dan penanda merosotnya peran kepakaran dalam kehidupan sehari-hari, Nichols juga menganalisis penyebab kemrosotan tersebut.
Salah satu penyebab yang disampaikan oleh Nichols dalam bukunya di mulai dari ruang pertarungan wacana yang terdapat di lingkungan akademik. Nichols menuduh dalam ruang-ruang diskusi dan dialog terbuka yang diadakan di lingkungan akademik (Nichols merujuk pada fakta yang terjadi di beberapa lingkungan akademik di Amerika Serikat) semata dilakukan hanya untuk mencari 'pemenang'.
Pemenang di sini oleh Nichols diasosiasikan sebagai pihak yang mampu membuat 'lawan' diskusinya mati kutu tanpa bisa berargumen lagi. Substansi diskusi atau dialog sesungguhnya, yakni lahirnya wacana dan pengetahuan yang bersih dari bermacam distorsi menjadi tujuan nomor sekian.
Artinya, kemampuan beretorika lebih diutamakan dari pada argumen yang dilandasi analisis dan rasionalitas unggul. Retorika hanya mengandaikan cara bertutur yang fasih dan meyakinkan, sedangkan telaah rasional dan berbobot dinafikan. Laku diskusi hanya bertujuan memuaskan ego individual. Kebenaran intersubjektif yang terbentuk melalui negosiasi berbagai perspektif sulit diwujudkan.
Fakta selanjutnya yang tidak kalah menentukan dalam konteks penyebab matinya kepakaran, setidaknya dari lingkungan akademik, adalah kebiasaan normatif beberapa individu pakar yang membiarkan 'lawan diskusi' mereka yang awam menguasai kontestasi di ruang diskusi.
Hal ini disebabkan beberapa pakar yang memang kompeten dalam isu yang sedang didikusikan tidak ingin terlibat konfrontasi dengan lawan diskusinya yang awam dalam ruang diskusi. Akhirnya, pendapat pakar yang mewakili kebenaran substansial terdsitorsi oleh pendapat awam yang kadang justru tidak kredibel, sebab tidak ditunjang dengan basis pengetahuan dan epistemologi yang ilmiah (Hal. 48-84)
Mahasiswa Calon Pakar vs Mahasiswa Pelanggan
Dalam salah satu bab yang berjudul "Sebagai Pelanggan, Mahasiswa Selalu Benar", Tom Nichols mengurai bahwa matinya kepakaran dapat juga disebabkan oleh fenomena umum yang terjadi di dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi, saat ini (Hal. 84-127). Dalam kehidupan kampus, menurut Nichols, sebagian mahasiswa tidak lagi memposisikan diri sebagai calon 'ahli atau 'pakar'.
Sebagai calon-calon ahli atau pakar seharusnya mahasiswa ditempa dengan keras dan penuh komitmen. Proses atau jalan menjadi seorang ahli tentu berbeda dengan yang ditempuh seorang awam. Mahasiswa dituntut untuk melalui proses yang penuh usaha, komitmen, keteguhan hati, dan berbagai tempaan yang menjadikan mahasiswa andal, tidak hanya terkait dengan kompetensi, tetapi juga mentalitas.
Namun, fakta yang terjadi di lapangan, menurut Nichols, justru sebaliknya. Mahasiswa lebih memposisikan diri sebagai pelanggan atau konsumen yang telah membayar sejumlah dana sehingga menuntut pelayanan layaknya konsumen kepada penyedia jasa.
Perguruan tinggi sebagai penyedia jasa yang telah dibayar seolah wajib melayani para konsumen mahasiswa ini tidak hanya terkait dengan proses transfer of knowledge semata, di beberapa kasus juga keluhan-keluhan mereka yang bersifat remeh temeh.
Dengan memposisikan diri sebagai pelanggan, dan bukan calon ahli yang perlu ditempa, sebagian mahasiswa pelanggan ini menganggap proses perkuliahan sebagai formalitas belaka. Penulis sering berhadapan dengan mahasiswa pelanggan semacam ini.
Di akhir semester, mahasiswa pelanggan ini menuntut diberikan nilai maksimal, sebab selalu hadir di kelas saat perkuliahan, mengikuti Ujian Tengah Semester dan Akhir Semester (UTS/ UAS), serta mengumpulkan berbagai tugas yang diberikan, tanpa mempedulikan kualitas jawaban mereka saat ujian dan di dalam tugas yang dikumpulkan. "Saya sudah membayar, mengikuti semua tahapan kuliah, maka sudah selayaknya mendapat nilai paling maksimal", mungkin itu yang ada di dalam pikiran mahasiswa pelanggan. Mahasiswa calon pakar tentunya tidak akan berpikir demikian.
Jika kita tarik hubungan antara fenomena 'mahasiswa pelanggan' dan kecenderungan berpikir pada masa saat ini akan ditemukan benang merah yang jelas. Mahasiswa pelanggan hanya menitikberatkan pada hasil akhir, yakni nilai akhir yang nantinya tertera di transkrip nilai, tanpa peduli dengan proses yang harus dijalani. Mahasiswa semacam ini berpikir semata prosedural, dan menafikan unsur substansial dalam pendidikan, yakni transfer of knowledge dan transfer of value. Layaknya cara berpikir era modern yang dikritisi habis oleh Mazhab Frankfurt (Martin Jay, 2005), mahasiswa pelanggan tersebut menerapkan suatu cara berpikir yang menekankan pada 'maksud-tujuan' (mean-end). Mazhab frankfurt yang dikomandani oleh Adorno dan Horkeirmer melabeli cara berpikir ini sebagai 'Rasio Instrumental".
Dalam perspektif Mazhab Frankfurt, Rasio Instrumental merupakan suatu kondisi di mana rasio dijadikan 'alat' belaka bagi terpenuhinya kebutuhan manusia (Shindunata, 2019). Rasio instrumental sejatinya terjadi dalam relasi Subjek-Objek, seperti ketika manusia menghadapi alam. Namun, ketika rasio instrumental diterapkan dalam relasi sosial antara Subjek-Subjek, maka yang terjadi adalah hilangnya nilai.
Pada tataran tersebut penindasan, peminggiran, eksploitasi, dan hilangnya nilai etis berpotensi terjadi. Relasi sosial antar subjek yang menggunakan rasio instrumental hanya akan menciptakan hubungan yang tidak seimbang, sebab satu pihak mendaku sebagai subjek yang lebih superior dari pihak yang lain. Hal ini dapat dilihat pada ruang-ruang kerja di sekitar kita, misalnya.
Seorang pimpinan yang menerapkan rasio instrumental dalam menjalin interaksi dengan rekan kerjanya di kantor cenderung akan memandang rekan kerjanya tersebut sebagai alat-alat belaka dalam menunjang kinerjanya.
Artinya, rekan kerja merupakan objek dalam relasi Subjek-Objek yang dapat diperlakukan sekendak hati demi suatu tujuan. Lebih jauh lagi, rasio atau akal sehat akan dipaksa memberikan 'pembenaran-pembenaran' bagi situasi yang tidak baik tersebut: Rasio Instrumental.
Mahasiswa yang memposisikan diri sebagai pelanggan dalam aktivitas kuliahnya berpotensi terjebak dalam rasio instrumental juga. Ia melihat universitas berserta seluruh yang ada di dalamnya, termasuk dosen, sebagai alat-alat yang harus dapat membantunya meraih tujuan.
Sebagai pelanggan yang telah membayar, mahasiswa cenderung memandang universitas semata objek yang telah ditundukkan. Apa yang diminta harus diwujudkan, termasuk nilai maksimal dengan proses yang minimal.
Rasio instrumental mengarahkan mahasiswa pelanggan untuk mendesak dosen untuk selalu memberikan nilai maksimal, apa pun kualitas proses yang telah ditempuhnya. Ketika mahasiswa mendesak, bahkan merongrong dosen, akhirnya muncul masalah baru, yakni etika.
Mahasiswa tidak lagi memandang perlu untuk berhati-hati dalam bersikap dan bertutur kepada dosen. Dosen merupakan rekan, atau bahkan yang lebih ekstrem, dosen adalah semata penyedia jasa yang telah dibayar. Tom Nichols juga memaparkan fenomena terkait etika dalam relasi dosen-mahasiswa di dalam bukunya (Hal. 119-126).
Berselancar Beberapa Jam Di Dunia Maya Lantas Seseorang Menjadi Pakar?
Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mengantarkan peradaban manusia ke titik yang belum pernah dicapai sebelumnya.
Dengan TIK, manusia saling terkoneksi dalam hitungan sepersekian detik sejauh apa pun mereka berada. Jarak menjadi kata yang tak bermakna. Di sisi yang lain, media sosial, sebagai anak kandung TIK, menjadikan setiap individu mempunyai kemampuan untuk memproduksi dan menyebarluaskan wacananya sendiri. Kemampuan tersebut sekilas menumbuhkan optimisme dalam konteks berdemokrasi.
Majunya teknologi informasi juga menghasilkan dunia digital yang memudahkan manusia memproduksi dan menyebarkan wacana serta informasi. Hari ini berbagai macam informasi dan data telah didigitalkan untuk dapat disimpan dan disebarkan melalui internet. Informasi tentang segala hal hampir semuanya ada di dunia maya.
Seiring berjalannya waktu, manusia memiliki ketergantungan kepada dunia digital atau internet dalam hal memperoleh informasi. Maka, tidak mengherankan jika hari ini orang akan membuka situs internet untuk mencari informasi terkait segala sesuatu. Mulai dari kuliner, politik, pendidikan, hiburan, bahkan sampai yang paling remeh seperti cara memasang galon air mineral yang benar, ada di dunia maya.
Dalam tataran ini, dunia maya atau internet menjadi sumber pengetahuan tak terbatas yang menyediakan berbagai macam jenis informasi. Untuk mengetahui bagaimana situasi politik terkini orang mencarinya di internet; Untuk mengetahui pengertian tentang konsep atau istilah terbaru, orang melacaknya di internet; Untuk mengetahui sejarah tentang suatu peristiwa atau hal-ihwal yang lain, orang juga mengorek internet; Untuk mencari sebab dan cara penanganan masalah kesehatan, orang menengok internet; dan bahkan untuk mengetahui seluk-beluk otomotif dan permesinan orang juga belajar melalu internet. Terlebih lagi dengan adanya mesin pencari: Google. Apa pun yang menjadi pertanyaan dan rasa ingin tahu orang dapat terjawab melalui google.
Jika dikontekskan dengan fenomena matinya kepakaran, maka dunia internet yang menjadi sumber jawaban tak terbatas bagi berbagai pertanyaan dan rasa ingin tahu juga menjadi faktor penyebab yang utama.
Orang yang merasa pusing dan lemas, atau memiliki gejala masalah kesehatan, pertama kali akan memilih mengunjungi situs kesehatan untuk berkonsultasi, dari pada langsung pergi ke dokter; Orang yang kendaraan bermotornya mengalami masalah merasa lebih praktis jika membuka chanel Youtube yang menyediakan video tutorial cara memperbaiki kendaraan dari pada pergi ke bengkel; Orang yang ingin tahu dan memahami peta politik hari ini akan memilih menonton chanel Youtube bertema politik dari pada berdiskusi dengan pakarnya, seorang dosen politik atau politisi, misalnya. Meskipun tidak sepenuhnya, hal-hal seperti ini yang akhirnya menyebabkan orang tidak perlu lagi merujuk pada sumber yang otoritatif terkait dengan isu yang sedang didalaminya.
Idealnya sumber otoritatif terkait permasalahan atau suatu isu adalah seseorang atau pihak yang memang memiliki kompetensi dalam bidang tersebut. Dokter merupakan sumber otoritatif terkait permasalahan kesehatan; Ahli ekonomi kredibel untuk mengulas permasalahan dunia ekonomi; Seorang astronom lulusan jurusan astronomi memiliki kompetensi untuk menjelaskan perihal dunia astronomi; dan seterusnya. Namun, hari ini yang terjadi tidak demikian.
Dalam platform media sosial, Youtube misalnya, orang bebas mengupload informasi apa pun, selama tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, video tutorial tentang bagaimana mengatasi secara instan suatu gejala gangguan kesehatan tertentu dari sesorang yang tidak memiliki kompetensi dan keahlian di bidang kesehatan dapat menjadi sumber otoritatif yang dirujuk banyak orang.
Terlebih lagi jika ternyata video tersebut sangat bermanfaat dan terbukti dapat membantu mengatasi gangguan kesehatan tersebut. Begitu juga masalah-masalah kehidupan sehari-hari yang lain. Maka, menjadi semakin kuat dugaan bahwa internet menjadi salah satu tersangka atas matinya kepakaran.
Elitisme di Ruang Pendidikan
Pandangan Tom Nichols di dalam bukunya memang terkesan sangat bernuansa elitisme. Kepakarann dan segala instrumen yang membentuknya (tingkat pendidikan, lingkungan sosial, dan habitus yang dimiliki) mengisyaratkan sebuah relasi sosial yang tidak seimbang, dalam hal ini dengan 'yang bukan pakar'.
Dalam hal hubungan Dosen-Mahasiswa, misalnya, Nichols menuntun pada sebuah hubungan yang terkesan superior-inferior. Nichols berpendapat: secanggih apa pun argumen dan pendapat mahasiswa, jika dibandingkan dengan pandangan dan argumen dosen, maka akan terlihat lemah.
Dosen, menurut Nichols, telah ditempa menjadi seorang pakar dalam hal tertentu melalui proses yang panjang dan terlegitimasi. Maka, pandangan dan argumen dosen sudah pasti lebih terlegitimasi paling dekat dengan kebenaran jika dibandingkan dengan milik mahasiswa.
Sekilas hal ini bertentangan dengan cara pandang Paulo Freire, penulis buku Pendidikan Kaum Tertindas. Freire justru berprinsip bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang memposisikan pendidik dan peserta didik dalam posisi yang setara.
Bagi Freire, pendidik tidak selalu tahu, dan peserta didik tidak selalu dalam posisi tidak mengetahui apa-apa. Dalam skema pendidikan Freire, pendidik bisa belajar juga kepada peserta didik, dan juga sebaliknya.
Dalam tataran ini, maka terlihat jelas jika konsep pembelajaran yang dikukuhi Nichols merupakan sebuah elitisme yang memposisikan satu pihak lebih tinggi dari pihak yang lainnya.
Dalam bukunya pun Nichols lebih jauh berpendapat bahwa demokrasi memang memberikan ruang berpendapat dan berargumen yang sama kepada semua pihak, namun tetap saja pasti ada pendapat yang paling baik dan sahih dibanding, dan itu milik para pakar atau ahli.
Maka, saat ini fakta yang sudah benar-benar terjadi adalah lunturnya kredibilitas kepakaran, digerus kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pertanyaannya adalah: apakah kepakaran perlu diperjuangkan untuk kembali menduduki singgahsananya, atau biarkan saja mati perlahan digulung tuntutan zaman.
Referensi
Tom Nichols, Matinya Kepakaran, 2017, Gramedia.
Martin Jay, Sejarah Mazhab Frankfurt, 2005, Kreasi Wacana.
Shindunata, Dilema Usaha Manusia Rasional: Teori Kritis Sekolah Frankfurt, 2019, Gramedia.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI