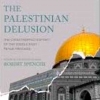Media sosial ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, ia menjadi ruang demokratis untuk berekspresi, berbisnis, dan membangun jejaring (Van Dijck, 2013). Begitulah saya menggunakan medsos, lebih sering untuk sebaran artikel opini.
Di sisi lain, media sosial juga menjadi tempat berkembangnya konten-konten destruktif yang menggerus moral, seperti kasus grup Facebook "Fantasi Sedarah" dan "Suka Duka". Komdigi melalui Wamen Angga Raka Prabowo langsung bertindak cepat memblokir akun tersebut.
Fenomena grup Facebook yang menyimpang ini menjadi titik kulminasi kegelisahan publik tentang moralitas di era media sosial.
Kasus ini bukan sekadar cerita tentang konten menyimpang, tetapi juga cermin dari dinamika sosial, psikologis, dan etis yang membentuk lanskap digital Indonesia hari ini.
Lalu, bagaimana menjelaskan munculnya ruang-ruang gelap semacam ini? Apa implikasinya terhadap ekosistem digital Indonesia? Apakah media sosial menciptakan monster ini, atau justru kita yang memelihara monsternya?
Dua Sisi Medali: Media Sosial Sebagai Ruang Publik
Sebagai seorang yang aktif melakukan pendampingan warga dan pegiat media sosial, saya menyaksikan sendiri bagaimana media sosial menjadi ruang yang powerful: dari menyuarakan opini minoritas, melawan kesewenang-wenangan hingga mendongkrak UMKM lewat strategi konten dan live commerce.
Tapi, kekuatan ini bersifat terbuka--bagaikan pisau bermata dua. Ia bisa menjadi alat emansipasi atau justru jembatan menuju dekadensi moral.
Media sosial telah merevolusi cara individu beropini, berdagang, hingga berpolitik. Platform seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp menjadi ruang terbuka bagi ekspresi diri, advokasi, bahkan pemberdayaan ekonomi.
Namun, di balik kemudahan dan kebebasan itu, terbuka pula peluang bagi perilaku menyimpang, polarisasi, dan penyebaran nilai-nilai yang bertentangan dengan norma masyarakat.