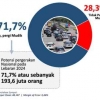Setelah Ibu Suzana dan Hansip Bokir mengalami penurunan peminat seiring dengan tumbangnya rezim Orde Baru, penikmat film horor Indonesia kembali ditantang nyalinya untuk menyaksikan "Jelangkung". Film yang menghadirkan beragam sosok lelembut"khas" Indonesia (termasuk sesosok hantu Belanda) ini berhasil menandai kebangkitan kembali film berkualitas di layar perak Indonesia. Beberapa saat setelah booming, Rizal Mantovani, sang sutradara diwawancari oleh sebuah stasiun televisi mengenai kisah sukses di balik kengerian filmnya yang membuat mayoritas penonton remaja (termasuk saya dan para sepupu kali itu) tak lagi berani ke kamar mandi sendirian.
"Hantu yang hadir di film Jelangkung itu hanya 20%, 80% nya diciptakan sendiri oleh penonton" Kata Bung Rizal. Rizal Mantovani menggoda imajinasi kita yang memang sering menerka-nerka. Hantu-hantu di dalam film Jelangkung hanya muncul sekelebat saja. Turah, hantu kecil di Angker Batu yang berpenampilan mirip tuyul, tak pernah hadir 100% jelas di dalam tangkapan kamera. Ia lari ke sana dan ke sini, menuntut imajinasi penonton untuk "lebih mandiri" dalam membangun gambaran atas Turah. Upaya kita untuk menciptakan hantu di dalam benak itulah yang menurut Rizal Mantovani membuat keseraman Jelangkung cukup bertahan lama. Sebab, 80% hantu justru ada di benak kita, bukan di dalam film.
Sebagai manusia abad ke-21 yang senang mengaitkan hal-hal yang tidak berkaitan, saya menggunakan kecerdasan Rizal Mantovani dalam membuat film Jelangkung untuk menganalisa fenomena ketakutan tahunan atas kebangkitan "setan" bernama PKI. Meskipun sebagai organisasi PKI sangat kompleks dan banyak "versi", mayoritas pengetahuan orang Indonesia tentang organisasi ini bersumber dari proyek sejarah yang disponsori oleh rezim Orde Baru. Proyek, di sini, mengacu kepada berbagai bentuk manifestasi sejarah publik dari historiografi versi Orde Baru. Tidak hanya buku sejarah nasional dan buku putih tentang pengkhianatan G30/S PKI, Orde Baru juga membangun monumen-monumen, museum, dan yang kembali diperbicangkan akhir-akhir ini: memproduksi film propaganda.
Pada semua proyek itu, PKI hadir sebagai "hantu" yang mengganggu ketentraman hidup masyarakat Pancasilais di Indonesia. PKI menyiksa, membunuh, menari telanjang, memberontak, memimpin kudeta, dan menistakan agama tanpa sedikitpun imaji tentang kepeloporan PKI dalam melawan pemerintah kolonial di Sumatera Barat pada pertengahan tahun 1920an. Setelah dipertontonkan semua tindakan tercela tersebut, masyarakat menyimpulkan bahwa PKI adalah "orang-orang biadab". Celakanya, label ini dipergunakan sepanjang waktu dan sesuai kebutuhan. Seorang pengurus masjid di komplek saya pun pernah melabeli supir truk yang membunyikan klakson ke arah masjid ketika Shalat Jumat sedang berlangsung sebagai "Supir PKI".
Contoh lain, seorang dosen di kampus saya mengakui bahwa ketika kecil, ia pernah meneriakkan "Wasit PKI!" pada hakim garis yang dianggap tidak memihak klub bola junjungannya pada pertandingan antarkampung . PKI sebagai kata umpatan berderajat lebih rendah dari umpatan nama hewan, hantu (misalkan sundal), bahkan alat kelamin.
"Kalau serius, dicap sebagai PKI itu bias berkonsekuensi nyawa" kata dosen saya menambahkan. Pernyataan dosen saya membuat saya penasaran, jangan-jangan ketakutan kita terhadap PKI ini lebih banyak dihasilkan oleh konstruksi imajinasi kita sendiri atas fragmen-fragmen sejarah cum mitos versi orde baru dibandingkan fakta sejarah? Tidakkah ketakutan kita pada "setan" berlogo palu arit ini mirip dengan ketakutan penonton terhadap film Jelangkung?
Kecurigaan saya nampaknya tidak meleset ketika melihat fenomena akhir-akhir ini. Beberapa kelompok Islam, misalnya, mempercayai bahwa PKI adalah label paling buruk untuk "semua musuh Islam". Alhasil, pada demonstrasi yang mereka adakan, PKI dianggap sama dengan liberalisme. Jelaslah bagi saya bahwa orang-orang ini sudah berpikir beyond sejarah perang dingin yang sarat pertentangan ideologis antara komunisme dan liberalisme. Sikap materialisme pada dua ideologi memang sering dianggap berujung pada pengabaian atas esksistensi tuhan, tetapi bukan berarti kita bisa bilang bahwa Lenin itu liberal atau John Locke adalah kuminis. Pihak lain, bahkan mengaitkan filsafat komunisme dengan pemikiran Plato pada era klasik Eropa.
Jangan-jangan ketakutan dan kebencian kita terhadap PKI adalah 80% imajinasi dan 20% fakta historis? Akhirnya, kita tak begitu peduli pada apa yang PKI lakukan dan tidak lakukan. Satu yang kita peduli, PKI adalah sinonim dari semua kata negatif tak peduli konteks dan waktu. Di masa depan, penipu yang tak kunjung memberangkatkan ribuan jemaah bisa kita cap "PKI", lelaki yang menikahi diva dengan fans sejuta umat bisa kita cap "PKI", dan tersangka yang tak memenuhi panggilan kepolisian dengan melarikan diri, juga, sebagai "PKI"?