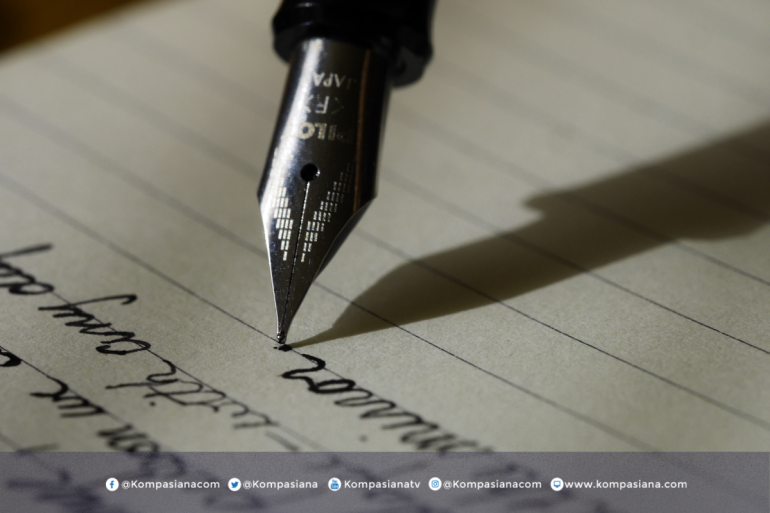Semua orang pasti memiliki imajinasi dalam dirinya. Ada yang berimajinasi secara logis dan terarah, tetapi ada juga yang berimajinasi secara liar. Imajinasi liar dalam masyarakat seringkali berperan sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi, ia dapat memicu kreativitas dan inovasi, tetapi di sisi lain, ia juga dapat menciptakan prasangka, ketakutan kolektif, serta membangun norma sosial yang tidak memiliki dasar rasional. Sebagaimana yang digambarkan oleh Seno Gumira Ajidarma di dalam cerpennya dilarang menyanyi di kamar mandi, masyarakat sering kali menciptakan norma sosial yang tidak adil berdasarkan imajinasi yang tidak terkendali. Hal ini menunjukkan bagaimana imajinasi yang tidak terkendali dapat menjadi alat kontrol sosial yang menggunakan kebebasan individu. Imajinasi liar bisa berakar dari ketidaktahuan, ketakutan, atau bahkan kepentingan politik dan ekonomi tertentu yang sengaja diciptakan untuk membentuk opini publik sehingga menguntungkan pihak tertentu.
Seno dalam cerpen dilarang menyanyi di kamar mandi, mengisahkan bagaimana nyanyian seorang perempuan di kamar mandi menjadi sumber keresahan bagi masyarakat di sekitarnya. Para suami dalam cerita itu membangun “imajinasi liar” mereka sendiri dan mengasosiasikan suara nyanyian itu dengan fantasi erotis. Padahal, tidak ada bukti yang mendukung asumsi tersebut . Seperti yang dikatakan Sigmund Freud dalam teori psikoanalisisnya, manusia memiliki tiga aspek kejiwaan utama: id, ego, superego ( Lestari, Permana, 2023: 110).
id adalah aspek biologis dalam kepribadian, berfungsi sebagai sistem orisinal yang sering disebut sebagai dunia batin manusia. Sistem ini tidak memiliki keterkaitan langsung dengan dunia objektif dan mengandung unsur-unsur bawaan sejak lahir yang berperan dalam mendorong kerja ego serta superego.( Ardiansyah, Sarinah, Susilawati, Juanda, 2022: 27).
Dalam konteks cerita ini, id para suami bekerja tanpa kontrol rasional, menciptakan prasangka yang tidak adil terhadap perempuan. Tanpa adanya tindakan nyata yang mendukung pikiran mereka, para suami membangun fantasi erotis yang liar. Imajinasi ini merupakan manifestasi dari dorongan seksual bawah sadar yang tidak terkendali, menunjukkan bagaimana id dapat menciptakan prasangka yang tidak rasional terhadap seseorang. Ego berfungsi sebagai penyeimbang antara dorongan id dan norma sosial. Dalam cerpen ini, peran ego terlihat dalam tindakan pak RT yang berusaha merasionalisasi situasi. Awalnya, ia mencoba bersikap netral dan tidak langsung menyalahkan perempuan yang bernyanyi. Namun, di bawah tekanan sosial dari ibu-ibu yang mengeluhkan kerusakan suami mereka, pak RT akhirnya memilih jalan kompromi dengan meminta perempuan tersebut berhenti menyanyi. Ini menunjukkan bagaimana ego seringkali dipaksa menyesuaikan diri dengan tekanan sosial meskipun menyadari bahwa sumber masalah sebenarnya bukan pada pihak perempuan tersebut, melainkan pada imajinasi liar para suami. Superego bagian dari kepribadian yang merefleksikan nilai-nilai moral dan norma sosial. Dalam, superego terlihat dalam tuntutan ibu-ibu yang menganggap bahwa masalahnya terletak pada perempuan yang bernyanyi, bukan pada suami mereka yang berimajinasi liar. Superego dalam konteks ini bersifat represif karena norma yang dibangun justru menyalahkan korban, yaitu perempuan yang tidak melakukan kesalahan apapun. Ini mencerminkan bagaimana norma sosial dapat meningkatkan individu dan menciptakan ketidakadilan berdasarkan asumsi yang tidak berdasar. Freud menekankan bahwa tanpa kontrol yang baik dari ego dan superego, dorongan bawah sadar ini dapat menyesatkan persepsi seseorang. (suprapto, 2018: 66).
Dampak imajinasi liar tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga mempengaruhi kebijakan sosial dan hukum. Dalam banyak kasus nyata, perempuan sering menjadi korban penghakiman moral hanya karena keberadaannya dianggap memicu respon tertentu dari laki-laki. Ini menunjukkan bagaimana ketakutan dan prasangka dapat membentuk norma yang tidak berpihak pada keadilan. Fenomena ini juga memperlihatkan bagaimana norma-norma patriarki seringkali mengalihkan tanggung jawab dari pihak yang berimajinasi ke pihak yang dijadikan objek imajinasi. Dengan kata lain, perempuan tidak hanya harus menghadapi stereotip dan penghakiman sosial, tetapi juga dipaksa menyesuaikan diri dengan ekspektasi moral yang tidak adil.
Lebih jauh, rekonstruksi imajinasi liar dalam masyarakat menjadi hal yang penting untuk dibahas karena dampaknya yang luas. Imajinasi liar tidak hanya terbentuk dalam konteks individu, tetapi juga dalam sistem yang lebih besar seperti politik, media, dan kebijakan sosial. Misalnya, dalam politik, imajinasi liar dapat digunakan untuk menciptakan propaganda atau memperkuat stereotip terhadap kelompok tertentu. Isu isu sosial seringkali diperburuk oleh penyebaran imajinasi liar yang tidak didasarkan pada fakta, melainkan pada asumsi dan prasangka yang telah dibentuk secara kolektif. Hal ini berbahaya karena bisa membentuk opini publik yang pada akhirnya memengaruhi keputusan-keputusan besar dalam masyarakat.
Kutipan dari cerpen:
“... jadi selama ini, ternyata para suami ini sepanjang gang di belakang rumah, membayangkan tubuh saya telanjang ketika mandi, dan membayangkan bagaimana seadanya saya berhubungan dengan mereka di ranjang, begitu?..”. ( Seno, 1991)
Pernyataan ini mengungkapkan absurditas imajinasi liar dalam masyarakat patriarkal. Perempuan menjadi korban dari persepsi kolektif yang tidak berdasar. Fenomena ini serupa dengan istilah victim blaming, yaitu keadaan di mana korban justru dipersalahkan dan dianggap bertanggung jawab atas sesuatu yang bukan perbuatannya. Dalam pernyataan ini, di mana perempuan disalahkan atas tindakan atau pikiran laki-laki yang tidak dapat mereka kendalikan sendiri. Imajinasi liar semacam ini berbahaya karena bisa menjadi dasar terbentuknya norma sosial yang menindas, terutama jika didukung oleh sistem hukum yang membela pihak yang berprasangka daripada korbannya sendiri. Hal ini mencerminkan ketidakadilan sistematis yang seringkali menempatkan beban moral dan sosial pada pihak perempuan, sementara laki-laki yang seharusnya bertanggung jawab atas pikiran sendiri justru dibiarkan tanpa konsekuensi.
Dalam konteks sosial yang lebih luas, fenomena ini juga memperlihatkan bagaimana ketimpangan gender terus berlanjut akibat pemahamannya keliru tentang moralitas dan tanggung jawab individu. Ketika perempuan harus menyesuaikan perilakunya untuk menghindari imajinasi liar laki-laki, berarti masyarakat telah membiarkan ketidakadilan terjadi dengan cara yang sistematis. Selain itu, normalisasi pemikiran seperti ini semakin memperkuat budaya kontrol terhadap tubuh dan perilaku perempuan, sehingga mengurangi kebebasan mereka dalam ruang publik maupun privat.
Oleh sebab itu, penting untuk menelaah bagaimana mekanisme sosial dapat melanggengkan ketidakadilan dan bagaimana individu dalam masyarakat dapat lebih aktif mengkritisi norma yang ada. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan menolak narasi yang menyalakan perempuan atas reaksi emosional yang ditunjukkan oleh laki-laki. Pendidikan tentang kesetaraan gender dan kesadaran akan bahaya sosial juga perlu diperkuat agar masyarakat lebih memahami bahwa masalah utama bukan terletak pada objek imajinasi, melainkan pada bagaimana seseorang dapat mengendalikan pikirannya sendiri. Dengan demikian, individu dapat lebih proaktif dalam menolak standar moral yang tidak adil dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih setara dan bebas dari prasangka berbasis gender.
Media juga memiliki peran besar dalam membentuk dan menyebarkan imajinasi liar. Berita yang disajikan tanpa dasar fakta yang jelas dapat memicu kepanikan dan histeria kolektif. Narasi yang dilebih-lebihkan, teori konspirasi, serta penyebaran berita hoax dapat mempengaruhi cara masyarakat memahami realitas. Akibatnya, masyarakat tidak lagi berpegang pada fakta, tetapi pada cerita yang telah dipolitisasi atau dimanipulasi untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk memiliki kesadaran kritis dalam mengonsumsi informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang belum tentu benar.
Dalam konteks yang lebih luas, pemilihan karakter perempuan sebagai pusat permasalahan dalam cerpen ini menunjukkan kerapuhan struktur sosial yang seringkali mengalihkan tanggung jawab dari pihak yang berimajinasi liar kepada perempuan. Hal ini mencerminkan realitas masyarakat patriarkal di dunia nyata, di mana perempuan sering dihadapkan pada stigma dan pengendalian moralitas oleh laki-laki dan komunitas. Cita-cita supremasi normatif yang ditegakkan melalui pengekangan individu seperti ini tidak hanya terjadi dalam narasi fiksi, tetapi juga berakar pada pola perilaku nyata yang sering kita saksikan, terutama dalam perdebatan mengenai moralitas perempuan dan kebebasan berperilaku.
Kutipan berikut semakin memperjelas absurditas ini:
“Tapi imajinasi porno itu tidak bisa dibendung pak.” (Seno : 1991)
Pernyataan ini memperlihatkan bagaimana masyarakat lebih memilih mengendalikan faktor eksternal daripada mengendalikan pikirannya sendiri. Banyak kebijakan atau aturan sosial dibuat bukan berdasarkan fakta, tetapi ketakutan yang muncul dari imajinasi liar. Hal ini menyebabkan kontrol sosial yang tidak adil dan menghambat kemajuan, karena lebih berfokus pada membatasi individu daripada mengatasi permasalahan yang sebenarnya. Fenomena ini semakin mempertegas bahwa dalam banyak kasus, penyebab utama kerajaan sosial bukanlah individu yang menjadi objek imajinasi, tetapi bagaimana masyarakat secara kolektif membentuk realitas berdasarkan asumsi dan ketakutan mereka sendiri. Imajinasi liar adalah fenomena yang dapat berdampak luas dalam berbagai aspek kehidupan, dari nama sosial hingga kebijakan publik. Imajinasi yang tidak terkendali dapat menciptakan ketidakadilan, memperkuat stereotip dan membentuk realitas yang tidak berbasis fakta. Untuk menghindari dampak buruk dari imajinasi liar, masyarakat harus lebih kritis dalam menerima norma sosial. Kesadaran tentang bagaimana persepsi terbentuk dan bagaimana imajinasi liar dapat mempengaruhi keputusan kolektif harus menjadi bagian dari diskusi publik. Dengan cara ini, kita bisa membangun masyarakat yang lebih berpikir logis dan berkeadilan. Salah satu cara konkret untuk mewujudkannya adalah dengan meningkatkan pendidikan kritis dan memperkuat budaya verifikasi informasi sebelum membentuk opini atau mengambil tindakan. Selain itu, penting untuk menciptakan ruang dialog yang lebih terbuka agar setiap individu dapat mendiskusikan dan menantang norma yang ada tanpa takut dikumpulkan oleh masyarakat. Hanya dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa imajinasi liar tidak menjadi alat penindasan, tapi justru menjadi pendorong inovasi dan kebebasan berpikir yang lebih sehat bagi masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
Ardiansyah, Sarinah, Susilawati, Juanda. 2022 “Kajian Psikoanalisis Sigmund Freud” dalam jurnal Kependidikan, Volume 07 No 1 (halaman 25-31) Sumbawa, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP, Universitas Samawa
Lestari Puji, Rendra Ardian, 2023, “pendekatan psikoanalisis dalam cerpen pelayatankarya d. Widya p.” Dalam Kampus Akademik Publising Jurnal Sains Student Research Vol.1, No.2 (halaman 1097-1101), Yogyakarta, Universitas Teknologi Yogyakarta
Suprapto. 2018. “kepribadian tokoh dalam novel jalan tak ada ujung karya muchtar lubis kajian Psikoanalisis sigmund freud” dalam Metafora jurnal pembelajaran bahasa dan sastra.,Volume V No 1 (halaman 54-69), Ponorogo, STKIP PGRI Ponorogo, Jawa Timur
Artikel Ensiklopedia, Si. (2016). Dilarang Menyanyi Di Kamar Mandi. Diakses Pada 9 Maret2025.https://ensiklopedia.kemdikbud.go.id/sastra/artikel/Dilarang_M enyanyi_di Kamar_Mandi
Alodokter. (2024). Playing Victim atau Vicim Blaming, Apa sih bedanya?. Diakses pada 18 Maret 2025. https://www.alodokter.com/playing-victim-danvictim-blaming-apa-sih-bedanya
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI