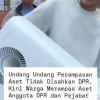Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menarik Rp200 triliun dana pemerintah dari Bank Indonesia menjadi sorotan publik. Uang yang sebelumnya “parkir” di BI kini dialirkan ke perbankan untuk mendorong likuiditas. Pemerintah berharap langkah ini mampu menggerakkan kredit dan mempercepat belanja negara.
Bagi masyarakat desa, kabar ini bagaikan angin segar. Selama ini, mereka kerap menunggu kucuran dana pembangunan yang melambat karena belanja kementerian dan lembaga tertahan. Harapan muncul bahwa injeksi likuiditas perbankan dapat menyentuh sektor riil, termasuk usaha mikro dan koperasi desa.
Namun, penyaluran dana dalam jumlah besar tidak otomatis menghadirkan pemerataan. Jika tidak diarahkan dengan jelas, efeknya bisa berhenti di bank, tanpa menjangkau masyarakat akar rumput. Desa berhak khawatir bila dana hanya menjadi permainan angka di pusat.
Di tingkat desa, akses pembiayaan adalah persoalan klasik. Bank memang ada, tetapi jarak, dokumen, dan bunga kerap membuat warga mengurungkan niat meminjam. Penempatan dana di bank perlu disertai inovasi akses kredit sederhana agar petani dan UMKM desa benar-benar merasakan manfaatnya.
Sejatinya, likuiditas hanya prasyarat. Yang menentukan adalah arah kebijakan dan keberpihakan. Bila perbankan tetap menyalurkan kredit pada segmen besar di kota, desa hanya akan kembali menjadi penonton pembangunan ekonomi nasional.
Jalan Panjang Menuju Kredit Inklusif
Dana besar yang berpindah dari BI ke bank memang bisa memperbesar ruang perbankan memberi kredit. Tetapi, pertanyaan utamanya: apakah kredit itu akan benar-benar inklusif? Bagi desa, inklusi berarti akses yang mudah, murah, dan sesuai kebutuhan riil masyarakat.
Kredit inklusif memberi kesempatan bagi usaha kecil tanpa harus memenuhi persyaratan rumit. Petani, nelayan, atau pengrajin desa kerap kesulitan menunjukkan jaminan formal. Padahal, mereka memiliki potensi usaha nyata. Kebijakan yang berpihak akan membantu desa memaksimalkan sumber daya lokal.
Koperasi desa dan BUMDes dapat menjadi mitra strategis penyaluran kredit. Melalui kelembagaan ini, dana bisa lebih aman sekaligus dekat dengan masyarakat. Tetapi, perbankan harus mau berbagi risiko dengan skema penjaminan sederhana, bukan hanya mengejar agunan fisik.
Persoalan bunga kredit juga tak bisa diabaikan. Likuiditas melimpah seharusnya membuat biaya dana lebih murah. Jika bunga tetap tinggi, desa akan kesulitan mengakses pembiayaan. Karena itu, keberanian pemerintah menekan bunga pinjaman menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini.
Desa membutuhkan kredit bukan sekadar untuk konsumsi, tetapi terutama produksi: membeli bibit, alat pertanian, perahu, atau mesin pengolahan hasil. Kredit yang murah dan mudah bisa mengubah wajah desa, dari konsumtif menjadi produktif.
Harapan Baru untuk BUMDes dan Koperasi Desa
Jika Rp200 triliun itu benar-benar mengalir hingga ke tingkat desa, harapan terbesar masyarakat adalah penguatan BUMDes dan koperasi. Lembaga ini dianggap paling dekat dengan kebutuhan warga. Mereka bisa menjadi perantara efektif menyalurkan kredit tanpa syarat perbankan yang rumit.
BUMDes yang sehat mampu mengelola berbagai unit usaha: mulai dari pengelolaan pasar desa, wisata lokal, hingga pengolahan hasil pertanian. Suntikan dana murah akan memperbesar kapasitas mereka. Masyarakat percaya BUMDes bisa membuka lapangan kerja lokal dan mengurangi ketergantungan pada kota.
Koperasi desa juga menanti dukungan serupa. Selama ini mereka menjadi wadah simpan pinjam dan usaha kecil berbasis anggota. Dengan modal tambahan, koperasi bisa memperluas layanan, menurunkan bunga pinjaman, serta memperkuat solidaritas ekonomi warga. Hal ini memperkuat daya tahan desa menghadapi guncangan.
Harapan lain adalah adanya sinergi antara BUMDes dan koperasi. Jika keduanya diperkuat, maka jalur distribusi ekonomi desa akan lebih kokoh. Produk petani, nelayan, dan pengrajin tidak lagi tergantung tengkulak, tetapi bisa dipasarkan melalui jejaring usaha milik desa sendiri.
Bagi masyarakat desa, hadirnya dana segar di BUMDes dan koperasi adalah simbol keberpihakan negara. Mereka tidak lagi hanya menonton perputaran dana besar di kota. Sebaliknya, desa bisa berdiri tegak sebagai pusat ekonomi baru, sesuai semangat pembangunan inklusif.
Infrastruktur dan Kapasitas Desa sebagai Penopang
Dana besar yang mengalir ke perbankan memang menjanjikan. Tetapi, tanpa infrastruktur memadai, dampaknya terbatas. Jalan desa yang rusak membuat hasil panen sulit dipasarkan. Air bersih dan listrik yang belum merata membuat usaha kecil mandek. Likuiditas saja tidak cukup.
Percepatan belanja pemerintah harus diarahkan ke fasilitas dasar yang selama ini masih kurang. Jalan, sekolah, puskesmas, dan pasar desa harus menjadi prioritas nyata. Tanpa infrastruktur ini, potensi dana besar tidak akan pernah sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat desa.
Selain infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia di desa juga penting. Banyak aparatur desa yang masih gagap mengelola program pembangunan, apalagi ketika menyangkut administrasi rumit. Tanpa peningkatan kapasitas, dana besar sekalipun bisa salah arah atau justru mengendap.
Koordinasi lintas level pemerintahan juga tak kalah penting. Sering kali dana dari pusat melambat karena terhambat di provinsi atau kabupaten. Desa akhirnya menunggu terlalu lama. Penyaluran dana ke bank perlu disertai reformasi birokrasi agar aliran ke desa lebih cepat.
Harapan desa sederhana: mereka ingin terlibat langsung dalam pembangunan. Bukan sekadar penerima pasif, tetapi juga aktor utama. Dengan kapasitas memadai, desa bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru, bukan sekadar objek pembangunan.
Antara Harapan dan Risiko
Meski desa menaruh harapan besar, risiko tetap ada. Likuiditas berlebihan berpotensi melemahkan rupiah dan memicu inflasi. Bagi desa, ini berarti harga kebutuhan pokok bisa naik. Alih-alih untung, justru menambah beban hidup masyarakat kecil yang sudah rentan.
Karena itu, keseimbangan moneter dan fiskal mutlak dijaga. Dana yang ditarik dari BI harus benar-benar produktif. Produktif berarti menciptakan lapangan kerja, menggerakkan usaha lokal, dan memperkuat kemandirian desa. Bukan sekadar memperbesar angka kredit di pusat.
Desa juga menginginkan transparansi. Mereka tak ingin dana Rp200 triliun hanya jadi wacana atau berhenti di bank. Masyarakat menunggu mekanisme jelas agar mereka bisa mengakses kredit, memantau alokasi, dan menuntut pertanggungjawaban jika ada penyimpangan.
Pemerintah pusat perlu memastikan distribusi manfaat merata. Jangan sampai desa tertinggal, sementara kota lebih dulu menikmati. Bila desa kembali terabaikan, kebijakan ini hanya akan memperlebar kesenjangan, bukan memperkecil.
Akhirnya, harapan desa kini berada di pundak Menkeu baru. Kebijakan Rp200 triliun akan diuji di lapangan: apakah sekadar menambah likuiditas, atau benar-benar mengubah wajah desa. Jawabannya akan menentukan seberapa besar keberpihakan negara terhadap akar rumput.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI