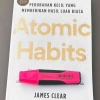Murid Tiri : Sebelum Aku Menjadi Statistik
Cerita Bu Sari, Ibu dari Anak dengan Disabilitas yang Saya Temui di Perjalanan "Disleksia Keliling Nusantara"
Saya bertemu Bu Sari di sebuah ruangan sederhana yang dijadikan kelas inklusi darurat. Dindingnya tak lagi putih bersih, hanya dipoles seadanya. Tapi hari itu, tempat itu menjadi ruang paling hangat yang pernah saya kunjungi. Di sinilah, Bu Sari memeluk kisah panjang tentang anaknya tentang luka, harapan, dan perjuangan yang tak pernah masuk ke dalam program prioritas negara.
"Anak saya bukan data, Mas. Dia nyata, dia hidup, dia berhak belajar," katanya saat kami duduk berdampingan.
Anaknya, Dafa, didiagnosa mengalami disabilitas intelektual ringan. Bukan gangguan yang langka, tapi tetap saja langka diperhatikan. Dafa sempat didaftarkan ke beberapa SD negeri, namun selalu kandas di gerbang pertama. Alasannya beragam : guru belum siap, kelas terlalu penuh, belum ada "fasilitas", atau dalih paling menyakitkan: "Anak ini akan ganggu ritme belajar."
Kementerian Pendidikan mencatat memang sudah ada 40.164 sekolah yang menampung murid berkebutuhan khusus per Desember2023. Tetapi hanya 5.956 (14,83%) di antaranya yang punya guru pembimbing khusus, sementara kajian Bank Dunia menegaskan kurang dari 13% sekolah inklusi memiliki pendidik yang terlatih.
Bagi Bu Sari, bukan hanya penolakan yang menyakitkan, tapi juga biaya yang mengiris pelan-pelan. Ia sempat mendaftarkan Dafa ke lembaga pendidikan inklusif swasta. Di sana, ia harus membayar iuran lebih tinggi dibanding orang tua murid reguler. Bukan cuma biaya sekolah, tapi juga "tambahan biaya kebutuhan khusus" yang tak pernah dijelaskan secara rinci. Jurnal Kebijakan Kemendikbud (2019) menghitung kebutuhan riil orang tua ABK transportasi, terapi, shadow teacher, seragam mencapai Rp16,6juta per tahun di SD, belum kebutuhan lainnya.
"Satu bulan saya bayar hampir satu juta. Gajiku cuma 1,5 juta, Mas. Tapi gurunya bahkan tak tahu cara mendampingi Dafa. Ia duduk sendiri di kelas, tak diajak diskusi, kadang malah disuruh menggambar saja dari pagi sampai jam pulang," cerita Bu Sari, matanya berkaca-kaca.
Saya tahu, ini bukan kasus tunggal. Dalam perjalanan Disleksia Keliling Nusantara, saya mencatat hal serupa di banyak kota. Orang tua ABK membayar lebih jauh lebih untuk layanan yang seringkali tak lebih baik. Mereka membeli kursi kosong dalam sistem yang belum siap menerima mereka.
Di satu sekolah di Jawa Barat, misalnya, saya menemukan anak dengan autisme ringan yang dipungut biaya bulanan dua kali lipat siswa reguler. Namun selama satu semester, tidak ada satu pun asesmen individu atau program pembelajaran yang disesuaikan. Di sebuah SD inklusi di Jawa Timur, seorang ibu mengaku harus membayar guru pendamping sendiri karena sekolah "tidak memiliki SDM khusus". Banyak orang tua seperti Bu Sari tidak tahu harus mengadu ke mana, karena belum ada mekanisme pengaduan yang berpihak dan aktif menampung keluhan orang tua ABK.
"Kalau memang kami harus bayar lebih, saya rela, Mas. Tapi setidaknya anak saya ditangani dengan benar. Jangan hanya bayar lebih untuk diminta diam di pojok kelas," ucap Bu Sari.
Ia lalu menunduk, menggenggam tangannya yang mulai gemetar. Saya bisa merasakan bagaimana ia menahan ledakan yang sudah lama ingin ia keluarkan: kemarahan, kekecewaan, rasa lelah, juga cinta yang begitu besar. Yang membuat saya semakin tercenung adalah satu kalimatnya yang sederhana namun menghantam keras:
"Kami membayar lebih, tapi dianggap kurang. Kami datang sopan, tapi dipandang beban."
Dafa kini bersekolah di sebuah komunitas belajar kecil yang tak punya fasilitas megah, tapi penuh kasih. Di sana, ia belajar menyebut nama-nama binatang lewat lagu, belajar mencocokkan bentuk lewat permainan. Tidak masuk standar asesmen nasional, tapi ia tumbuh. Ia merasa punya teman. Ia merasa tidak sendiri.
Bu Sari tidak berharap Dafa menjadi juara olimpiade. Ia hanya ingin anaknya tidak disingkirkan. Ia ingin negara hadir, bukan hanya lewat jargon inklusi, tapi lewat tindakan yang nyata.
Tulisan ini saya buat bukan untuk sekadar menyuarakan satu kisah. Tapi karena saya percaya, ada ribuan Bu Sari lain di seluruh Indonesia yang memilih diam karena tak tahu lagi harus bicara ke mana. Yang memilih bertahan karena tidak mampu menyerah.
Jangan biarkan anak-anak seperti Dafa hanya hidup di pinggiran data. Jangan biarkan ibu-ibu seperti Bu Sari hanya dikenal sebagai "pengadu masalah." Mereka bukan beban negara. Mereka adalah bagian dari wajah bangsa ini yang terus bertanya : adakah tempat untuk kami?
"Negara mungkin sibuk menghitung capaian, tapi kami para ibu hanya ingin satu: anak kami dihitung sebagai manusia."
Imam Setiawan
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI