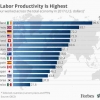"Bapak, Ibu, Hadirin sekalian," sapa seorang lelaki berjas hitam dan berdasi putih panjang seraya berdiri, "Kita tidak bisa melaksanakan perintah mendiang, jika semua belum kumpul. Kita harus menunggu. Bila Bapak Ibu ingin cepat, segera cari mereka!"
Ruang tengah rumah itu yang tadinya berisik seketika hening. Anak-anak kecil tiba-tiba berhenti bermain, seperti mengerti sedang ada kabar tidak enak. Ibu-ibu yang barusan asyik berbincang terdiam. Dua orang bapak memelotot tajam. Seusai memberi maklumat, lelaki itu kembali duduk.
"Tidak bisa begitu!" jawab seorang bapak yang paling tua, "Kita kan tahu sendiri masalahnya seperti apa?"
"Benar itu! Sudahlah, sekarang saja. Tidak perlu menunggu mereka," sahut seorang ibu yang lebih muda.
Lelaki itu sedikit menunduk. Matanya mengarah pada sebuah dokumen di atas meja. Ia mengambil dokumen lantas membukanya. Masih tersimpan rapi beberapa berkas yang sempat ia laminating agar tidak rusak.
"Di sini, seperti itu perintah mendiang!" jawabnya tegas seusai membaca. Tangannya menunjuk ke dokumen.
Bapak yang paling tua menghampiri ibu yang lebih muda yang sedang duduk di atas sofa biru.
"Bagaimana ini, ke mana lagi harus kita cari? Gara-gara kamu sih, semuanya jadi begini!" ujarnya kesal. Ibu itu menatap sinis. Ia memejamkan mata kiri. "Bukannya abang juga sepikir? Jangan salahkan saya saja!" jawabnya ketus.
"Tapi kamu sangat keterlaluan!" tukas bapak itu.
Situasi tiba-tiba panas. Beberapa pelayat masih berdatangan. Mendiang meninggal baru sepuluh hari lalu. Papan karangan bunga ucapan belasungkawa berwarna-warni, dari yang sederhana sampai yang begitu megah, dari orang biasa hingga pejabat teras, masih tertata rapi di halaman.
Ada beberapa roti terbungkus plastik tertumpuk dan barisan gelas air mineral di atas meja di teras. Seorang pelayan rumah tangga membagikan satu demi satu untuk para pelayat.
"Sudah, sudah! Kalian tidak malu, apa? Orang-orang masih datang, kalian malah marah-marah. Kalau kalian ingin cepat, dengarkan kata-kata saya. Cari mereka!" bentak lelaki berjas hitam.
Ia berdiri kembali. Kedua tangannya bersedekap di dada. Bapak yang paling tua dan ibu yang lebih muda tertunduk. Amarah meredam begitu saja. Mereka tidak berani melawan paman mereka. Alangkah sebuah kebetulan, paman yang bekerja sebagai pengacara ditunjuk mendiang menjadi pembagi warisan.
Mendiang adalah seorang pengusaha kaya raya di desa itu. Ia punya sebuah toko grosir, menjual berbagai keperluan rumah tangga. Toko cabangnya ada dua puluh, semua tersebar di pelosok desa. Ia juga punya sepuluh bengkel dan mempekerjakan puluhan montir. Sepertiga luas tanah di desa itu adalah miliknya.
Siapa yang tidak tergiur dengan harta itu? Siapa yang tidak berjuang untuk mendapatkannya? Jika pemiliknya sudah tiada, betapa beruntung orang-orang yang beroleh warisan darinya.
Dalam kaya rayanya itu, mendiang masih mengingat orang lain. Beberapa persen dari penghasilannya selalu ia berikan sebagai santunan untuk anak yatim piatu. Beberapa lagi ia sumbangkan untuk membangun dan memelihara tempat ibadah di seluruh wilayah desa.
Setiap ada kegiatan masyarakat, ia kerap menjadi penyumbang dana terbesar. Ia tidak pernah ragu dalam memberi. Baginya, seseorang tidak akan pernah miskin karena memberi. Tidak heran, sudah hari kesepuluh, orang-orang masih banyak berdatangan, menyatakan duka dan kehilangan yang mendalam.
Saya satu di antara mereka. Malam itu, saya datang ke rumah itu. Sendirian tanpa didampingi istri. Sempat saya ragu untuk masuk ke dalam. Saya berbincang sejenak dengan para pelayat.
Saya memakai kacamata hitam. Kumis saya pun hitam dan begitu tebal. Janggut saya memanjang ke bawah, juga hitam. Saya mengenakan topi hitam dan kemeja hitam pula. Kata orang memang, tidak ada lagi busana yang lebih menggambarkan kedukaan selain yang berwarna hitam.
"Kasihan ya, Pak, Pak Sarmin," kata seorang pelayat yang duduk di sebelah saya. Kami bercakap di bawah tenda hitam yang begitu lebar. Beberapa pelayat lalu-lalang di depan kami. Sebagian antre masuk ke dalam rumah.
"Memang kenapa, Pak?" jawab saya pelan. Saya membuka tutup gelas air mineral. Setelah makan roti, saya meminumnya.
"Bapak masak tidak tahu ceritanya?"
Pelayat itu memandang saya. Saya menelan ludah. Ia menatap lekat seperti ingin menebak-nebak siapa saya. Ia melemparkan pandangannya ke ujung topi saya, pelan-pelan ke bawah, sampai sepatu pantofel saya.
"Oh!" katanya lanjut, "Pantas Bapak tidak tahu. Bapak bukan warga sini. Bapak datang dari mana?"
Saya tersenyum kecil.
"Saya kenal mendiang sudah lama, Pak. Kebetulan, saya tahu setelah melihat berita duka mendiang dari surat kabar. Ini pun saya baru tiba tadi pagi di bandara."
Pelayat itu mendeham.
"Iya, Pak, coba bayangkan. Sampai mendiang meninggal, kedua anaknya tidak pulang. Bapak bisa bayangkan, bagaimana perasaan mendiang ketika menyambut ajal?"
Saya terdiam. Saya tahu, itu pasti menyedihkan. Meskipun ada masalah antara anak dan orangtua, tidaklah elok jika sampai menjelang kematian, sang anak masih bersikeras tidak mau pulang. Jika benar-benar tidak pulang, masalah itu pasti luar biasa berat dan sulit diselesaikan.
"Memangnya, ada masalah apa, Pak, sampai anak itu tidak pulang?" tanya saya.
Pelayat itu tidak menjawab. Ia lekas bangkit dari tempat duduk. Ia melihat antrean pelayat sudah sepi.
"Nanti kita lanjutkan ya, Pak. Saya mau melayat dulu," jawabnya.
Saya pun ikut masuk. Saya berjalan di belakang bapak itu. Mata saya melirik ke sekitar. Di ruang tamu, sebagian keluarga besar mendiang berkumpul. Mereka bersalam-salaman dengan para pelayat. Sementara keluarga inti -- anak-anak mendiang -- masih berada di ruang tengah.
Ruang tamu dan ruang tengah terpisah oleh sebuah pintu. Tanpa sepengetahuan orang-orang, saya menyelusup ke ruang tengah. Saya membuka pintu itu. Kebetulan tidak terkunci.
"Manto?"
Terdengar suara memanggil.
"Kamu Manto, bukan?"
Terdengar langkah kaki mendekat. Saya menatap lantai. Topi menutup sebagian wajah saya. Lelaki berjas hitam menghampiri. Sepertinya ia masih ingat perawakan saya.
"Ke mana saja, kamu? Kami sudah rindu. Masak bapak sudah meninggal, kamu baru pulang?" Paman memeluk saya. Saya meneteskan air mata di bahunya. Saya merasa bersalah. Masih bercampur dengan rasa takut, saya datang.
"Dasar anak kurang ajar! Ngapain kamu datang lagi ke sini?" Ibu yang lebih muda itu berkacak pinggang. "Kamu tidak tahu diri! Giliran bapak sudah mati, kamu baru datang!" sentaknya. Urat-urat lehernya tegang. Matanya membelalak. Saya masih menatap lantai.
"Kamu masih punya muka? Hah? Masih berani kamu menginjakkan kaki di rumah ini?" Bapak yang paling tua mengoceh. Tubuh saya mendadak berkeringat dingin.
"Sudah, sudah! Bukankah ini yang kalian mau?" jawab paman.
Sebetulnya saya tidak berani menghadap abang dan kakak, tetapi istri saya mendesak. "Sudahlah, lupakan perilaku mereka. Kali ini saja karena bapak meninggal, kamu sebaiknya pulang," begitu katanya.
Dia mendesak saya, tetapi dia sendiri tidak mau datang. Saya tahu, dia pasti lebih susah melupakan, karena tentu lebih sakit hatinya, dan sampai sebelum kepergian saya ke rumah bapak, dia masih terus saja menceritakan perilaku kejam itu.
Bagaimana kakak perempuan saya menjambak kencang rambutnya. Ia menampar berulang kali pipinya hingga memerah. Ia menjorokkan istri saya kuat-kuat, sampai kepalanya terjatuh membentur dinding. Ada bekas luka yang tergores. Ada dendam yang masih menyala.
Belum lagi umpatannya seperti kebun binatang. Sumpah serapah pun berserakan. Istri saya habis dimarah-marahinya. Saya hanya bisa terdiam melihatnya.
Saya tahu, kami salah. Tetapi, bagaimanalah, saya tidak bisa membendung perasaan cinta itu. Bagaimana seorang lelaki tertarik kepada seorang wanita, bukankah itu wajar? Saya pun tidak sanggup mengerti jika ternyata wanita yang saya cintai adalah adik kandung saya sendiri. Cinta memang sesekali tidak masuk akal, bukan?
Suatu kali, kami lari dari rumah untuk menikah diam-diam. Setelah beberapa waktu, kami kembali ke rumah untuk memohon ampun. Tidak ada yang menerima. Hanya perlakuan kasar dari mereka menyambut kami.
Situasi di ruang tengah kembali memanas. Masing-masing sudah duduk di kursi. Saya menunjukkan surat kuasa dari istri saya untuk mewakili kehadirannya. Paman lekas membaca dokumen warisan.
"Seluruh kekayaan atas nama saya selain rumah ini, saya wariskan ke Manto dan Surti. Untuk Ngatno dan Marti, kalian sudah mendapat hak selama saya hidup. Saya sudah membagikan harta untuk kalian. Biarlah anak saya yang hilang menikmatinya. Rumah ini saya sumbangkan untuk tempat ibadah."
Paman membacakan pesan bapak di surat wasiat. Saya terkesiap. Abang dan kakak berdiri. Ada gumpalan amarah yang ingin menyambar cepat. Kedua mata mereka nyalang. Wajah mereka begitu garang. Mereka memandang saya tanpa belas kasihan.
"Tidak perlu, Paman. Tidak perlu. Saya menolak warisan itu. Berikan saja ke anak yatim piatu asuhan bapak," jawab saya pelan. Saya memberanikan diri berucap. Saya tahu, saya telah durhaka sebagai anak. Saya pun tahu, saya tidak bisa membohongi dan tidak kuasa menolak rasa cinta dalam hati saya.
Saya tidak layak mendapatkan harta bapak. Saya datang hanya untuk melakukan kewajiban sebagai anak terakhir kalinya, meskipun sudah terlambat.
Entah, apa yang akan terjadi pada saya sebentar lagi.
...
Jakarta
16 September 2021
Sang Babu Rakyat