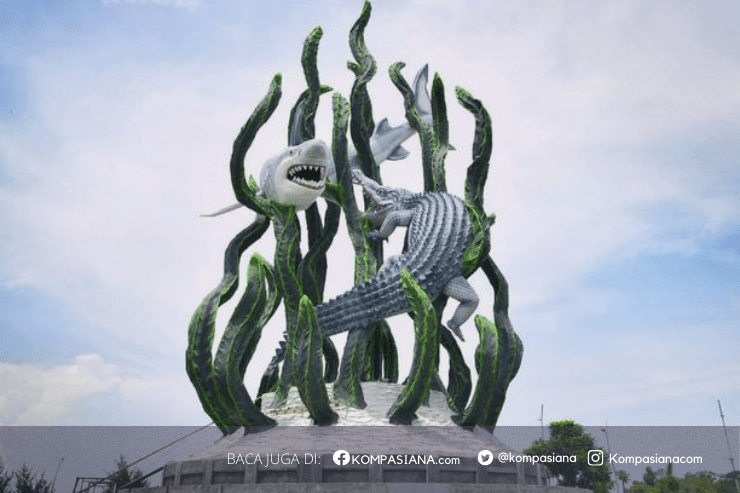Demo di Surabaya kemarin tak ubahnya sebuah panggung. Jalan raya menjelma teater terbuka. Pemeran utama: rakyat yang marah. Penontonnya: pejabat yang pura-pura tuli. Dan pertanyaan satir yang menggantung di udara: siapa sebenarnya sutradaranya?
Suara massa membelah kota, seakan-akan ingin mengingatkan bahwa "demokrasi" tak bisa hanya berhenti di meja rapat dan konferensi pers. Demokrasi butuh ruang nyata, bukan sekadar spanduk ucapan selamat. Tetapi ironisnya, suara yang riuh itu justru ditanggapi dengan gas air mata. Rakyat bicara, negara membungkam.
Apakah ini yang disebut dialog? Atau sekadar monolog rakyat yang ditulis di atas aspal, sementara penguasa sibuk menghafal teks sambutan?
Janji yang Membusuk
Kemarahan yang meledak kemarin bukanlah lahir semalam. Ia menumpuk dari janji yang tak ditepati, kebijakan yang dirasa berat sebelah, dan rasa ketidakadilan yang terus diulang. Janji itu seperti buah yang dibiarkan membusuk di meja makan: awalnya manis, akhirnya menyengat.
Tiap kali ada masalah, rakyat selalu disuruh bersabar. Tapi kesabaran itu, seperti sumbu, ada batasnya. Dan ketika sumbu habis, api menjilat ke mana-mana. Surabaya kemarin hanyalah salah satu ledakan.
Demokrasi yang Aneh
Kita selalu diajari bahwa demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Namun praktiknya sering kali berubah jadi: dari rakyat, oleh elite, untuk elite.
Rakyat turun ke jalan dianggap pengganggu ketertiban. Padahal, bukankah mereka hanya menagih janji yang diumbar dengan lantang menjelang pemilu? Lucunya, setelah demo, kita kembali mendengar jargon manis: "kami mendengar aspirasi." Tapi kalau benar mendengar, kenapa harus menunggu teriakannya menggema lebih keras daripada suara sirene polisi?
Siapa Sutradaranya?
Pertanyaan ini menggantung, penuh misteri sekaligus satir: siapa sutradara panggung jalanan kemarin?