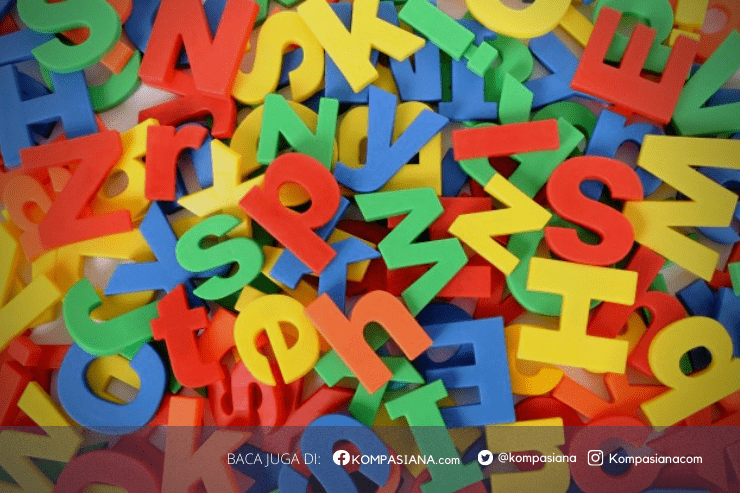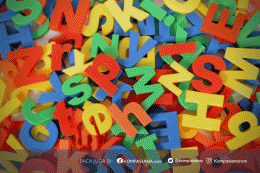Diramu oleh Yus Rusila Noor
Ketika menelusuri media sosial tadi pagi, ada sebuah FYP yang masuk, menunjukan seorang penutur Bahasa Hadzabe sedang berbicara. Bahasa itu terdengar eksotis, penuh bunyi klik dan ritme yang tak biasa. Saya sempat tercenung, berhenti scrolling, dan memutuskan untuk membuka percakapan pagi dengan AI, sekadar untuk tahu lebih jauh tentang bahasa Hadzabe yang baru saja menyentuh rasa ingin tahu saya. Ada sesuatu yang hangat sekaligus getir, hangat karena keindahan bunyinya, getir karena saya khawatir penutur bahasa tersebut semakin sedikit, sehingga sangat rentan untuk menghadapi kepunahan.
Bahasa Hadzabe adalah bahasa komunitas pemburu-peramu di Tanzania, salah satu yang masih menyimpan jejak "bunyi klik" khas bahasa-bahasa Afrika Selatan. Bagi telinga yang tak terbiasa, ia terdengar asing, bahkan seperti musik alam. Mungkin Anda teringat pada Xixo yang diperankan oleh Nixau, seorang petani Suku San dari Namibia dalam film lawas The Gods Must Be Crazy (1980). Pria kelahiran Tsumkwe, Namibia tersebut dengan segala keluguannya tampil memikat dengan bahasa penuh klik dan ritme aneh di telinga orang luar. Bahasa Hadzabe terdengar mirip, eksotis, ritmis, seperti suara hutan yang dijadikan bahasa. Namun, lebih dari sekadar sistem bunyi, ia adalah cermin hidup dari cara manusia memahami dunia. Setiap kata di dalamnya lahir dari hutan, dari perburuan, dari mata air, dari bulan yang dijadikan penanda. Bahasa ini mungkin tidak punya kata untuk "WiFi" atau "Zoom meeting", tetapi ia sarat dengan cara menghayati semesta.
Di satu sisi, penutur Hadzabe kini multilingual, artinya mereka bisa berbahasa Swahili untuk urusan sehari-hari yang lebih luas. Namun, inilah paradoksnya, multilingualisme yang menyelamatkan komunikasi justru bisa mempercepat kematian bahasa asli. Anak-anak muda Hadzabe bisa saja memilih Swahili sebagai bahasa sehari-hari yang lebih bisa mengekspresikan isi hati mereka, sementara bahasa leluhur mereka perlahan digeser ke ruang "museum budaya", untuk diingat, dihormati, tapi tak lagi dihidupi.
Fenomena ini bukan monopoli Hadzabe. Di Indonesia, kisah serupa sering terbaca dan terngiang dalam telinga kita. Kita punya ratusan bahasa daerah, banyak di antaranya hanya digunakan di satu desa, di satu lembah, atau di satu pulau kecil saja, seperti di Papua. Ketika bahasa nasional dan bahasa global semakin dominan, bahasa-bahasa kecil itu terpinggirkan. Bahkan bahasa besar sekalipun, seperti Sunda atau Jawa, mengalami "language shift", dimana anak-anak kota lebih fasih berbahasa Indonesia atau bahasa asing, dan kadang merasa kikuk jika harus menuturkan bahasa ibu mereka.
Lalu muncul pertanyaan pragmatis yang sering diajukan, "Memangnya kenapa kalau bahasa kecil itu punah? Bukankah orangnya masih bisa berkomunikasi dengan bahasa lain?"
Jawabannya tidak sederhana. Karena yang hilang bukan sekadar kata. Yang sebenarnya hilang adalah cara pandang dunia. Hilanglah metafora yang lahir dari pengalaman unik satu komunitas. Hilanglah cerita-cerita rakyat yang dituturkan dengan rasa humor khas bahasa tersebut. Hilang pula doa-doa yang disampaikan dengan suara hati terdalam, dalam bahasa yang tidak bisa digantikan oleh bahasa lain.
Saya merasakan hal ini secara pribadi. Saya lahir dan dibesarkan dengan Bahasa Sunda. Ketika berbicara dengan bahasa ibu, ada konteks yang erat, ada kedekatan rasa yang tidak tergantikan oleh Bahasa Indonesia sekalipun. Bahkan dalam doa, saya merasakannya. Shalat tentu saya lakukan dengan Bahasa Arab sesuai tuntunan. Tapi ketika berdoa bebas untuk mohon kekuatan dan meluapkan isi hati, saya kerap menggunakan Bahasa Sunda.
Di saat itulah saya sadar bahwa Bahasa Sunda bagi saya bukan hanya sekedar alat komunikasi, melainkan bahasa batin. Dengan bahasa ibu tersebut, doa terasa tulus, mengalir, tanpa jarak. Saya bisa berbicara dengan Sang Penguasa Kehidupan sebagaimana anak kecil berbicara dengan orang tuanya, jujur, tanpa formalitas, tanpa protokol. Sedangkan jika saya berdoa dalam Bahasa Indonesia, atau bahkan bahasa Arab, nuansanya lebih "protokoler". Benar secara liturgis, tapi terasa ada jarak.
Dan bahasa, ternyata, juga adalah identitas seseorang. Saya pernah berbicara di sebuah forum internasional PBB tentang perubahan iklim, menggunakan Bahasa Inggris yang sudah saya latih berulang kali. Saya kira semua lancar, sampai setelah sesi itu seorang peserta menghampiri saya, seorang Indonesia yang baru saya kenal. Ia menatap sebentar lalu bertanya pelan, "Kawit ti mana?" (Bahasa Sunda, artinya asal dari mana?). Saya terkejut, bagaimana ia bisa tahu saya berbahasa Sunda? Rupanya, sekalipun berbicara dalam bahasa asing, cengkok Sunda saya tetap menempel, menjadi jejak identitas yang tidak bisa disamarkan. Di situlah saya sadar, bahasa bukan hanya tentang komunikasi, melainkan juga sidik jari kultural yang membentuk siapa kita.
Mungkin itulah alasan mengapa hilangnya sebuah bahasa bukan hanya soal hilangnya kata-kata, tapi juga hilangnya satu jalan unik manusia untuk menyapa Tuhannya, dan satu warna identitas yang tak tergantikan.