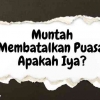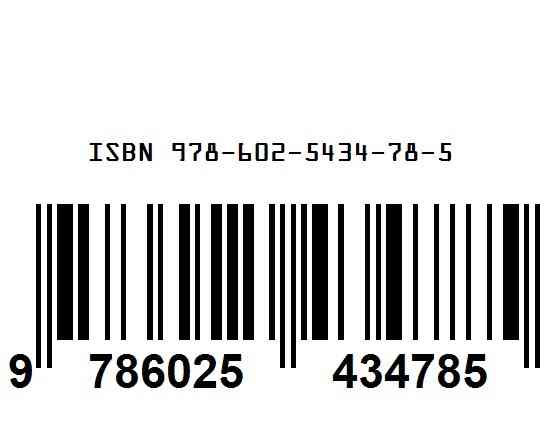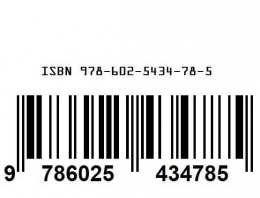Oleh Doddi Ahmad Fauji
Sekira tahun 2008, kami (kantor Jurnal Nasional) menerima tamu dari Filifina, seorang jurnalis yang gigih memperjuangkan tegaknya jurnalisme warga (citizen journalism) di negeri Joze Rizal itu. Tahun itu, jurnalisme warga masih samar-samar di Indonesia, meski facebook yang bisa menjadi sarana jurnalisme warga, makin bertumbuh penggunanya sejak 2007.
Jurnalisme warga itu artinya, warga melaporkan sesuatu kepada publik berdasarkan kesaksian panca-indra-nya, isinya akurat dengan menerapkan rukun 5WH, dan laporan jurnalistik bukan sekedar meneruskan kata orang, kecuali hal yang diteruskannya itu memang sangat penting, yang berdampak pada kepentingan sebanyak-banyaknya public, semisal musibah, bencana alama, kriminalitas, dll.
Meneruskan berita, sebaiknya diuji dulu isinya, dimaknai dan dipahami dulu, bahkan bila mampu, diberi tafsir walau hasilnya bersifat opini. Asal meneruskan berita, karena terkesiap atau terkelabui oleh judulnya yang bombastis, bisa jadi malah kita meneruskan sebuah informasi yang keliru, ternyata hoax, pushing, atau penipuan. Sekarang mulai jarang yang meneruskan berita semisal berketerangan: 'Dalam rangka ulang tahun ke-50, A bagi-bagi pulsa gratis'. Artinya, ada kesadaran yen judul-judul yang membujuk rayu itu, ternyata menipu. Kenapa atuh kita teh mudah tergiur oleh sesuatu yang seakan memberikan keuntungan?
Bisa jadi, karena godaan materi, ingin dapat gratisan atau keuntungan kecil-kecilan, tanpa dicermati dan disadari, kita jadi terlibat ke dalam viralisasi kebohongan. Bisa jadi pula, karena memang ilmu atau perangkat untuk melacak keabsahan sebuah berita, yaitu ilmu jurnalistik, tidak dikuasai oleh masyarakat. Seluruh kementerian yang menyelengarakan pendidikan, sudah waktunya memasukan materi jurnalistik ke dalam kurikulum ajar.
Kini kita memasuki era pelesetan kedua dari jargon filusf Renne Descartes, yang berujar: cogitu er go sum (aku berpikir maka aku ada). Seorang penulis dan pengamat sosial dari Singapura, pernah memelesetkan artinya menjadi: Aku berbelanja maka aku ada.
Mark Zuckerber, meski tak mengucapkannya, namun kehadiran facebook dan percanggihan teknologi visual termasuk kamera foto kemudian video, telah melahirkan pelesetan kedua dari cogito er go sum: Aku narsis, maka aku eksis.
Saya sedang introspeksi, jangan-jangan selama ini saya pun dinilai narsis, disebabkan seringnya meneruskan hasil tafsir atau permenungan atas peristiwa atau fenomena yang terjadi. Dengan eksis, memang jalan menuju fulus makin dekat. Untuk eksis di era sosmed, ya harus memperbanyak 'show up', alias narsis. Lembaga advertising atau periklanan, menurut saya, banyak yang mengedepankan narsisme, namun materi yang disajikan ternyata tidak substansial. Tentang glorifikasi iklan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang diiklankan, pernah marak dibicarakan beberapa kurun yang lewat.
Apa yang salah dengan narsis? Secara sekilas, narsisme itu mengandung sifat riya atau sirik kecil. Dan, bila merujuk pada tokoh Narcisus dalam mitologi Yunani, si Narcisus itu, hanya mencintai dirinya, setelah melihat bayangannya sendiri pada kolam.
Ia melihat bayangan dirinya, lebih gagah dan ganteng dibandingkan dengan wajah dan tubuh asli orang lain. Maka ia memandang orang lain dengan rendah, disebabkan ia merasa paling ganteng, walau perasaannya itu muncul hanya dari melihat bayangan. Kala itu, cermin belum ditemukan, apalagi kamera yang bisa bikin glowing. Di era sosmed, si Narcisus bisa kalah ganteng oleh yang tidak ganteng, asal punya kamera penyulap dan peng-glowing.
Sifat narsis kemudian dinilai sebagai racun psikologis, sebab racun itu melahirkan super-ego yang mencuat, yang bisa berdampak pada sikap arogan, paling benar sendiri, dan menjai penguasa tafsir paling ulung. Namun, ujung-ujungnya, semua yang disebut 'paling' itu, kadang terselip dalam jiwa mereka sifat komersialistik. Ketika tokoh agama memasang tarif, sejujurnya, saya kehilangan kepercayaan pada tafsir-tafsir yang dijejalkannya.
Untuk menakar seseorang yang disebut 'paling' itu, bisa dilihat pekerjaannya apa, berapa gaji resminya, dan bandingkan dengan kekayaan material yang dimilikinya. Bila gajinya kecil namun ia kaya dan raya (bukan warisan juga bukan usahawan), maka bisa ditarik sekian asumsi yang bisa memuakkan.
Tentu saya juga memiliki perasaan dan keyakinan harus sejahtera, supaya tidak merepotkan orang lain, dan supaya tidak berhimpun dalam lembaga pengumpul sodakoh. Saya akan memilih berhimpun dengan lembaga perniagaan yang jujur, yang dibenarkan oleh berbagai ajaran agama dan tradisi. Sialnya, di era kapitalisme yang didukung oleh media ini, banyak pedagang yang curang, yang berdampak pada keadaan 'yang kaya makin melimpah, yang miskin makin terdesak'.
Jargon 'cogito er go sum', di era sosmed ini, telah melahirkan pelesetan 'aku narsis maka aku eksis' itu, dan dengan eksistensinya itu, seseorang memang bisa meraih fulus.
Namun di era jurnalisme warga ini, fulus yang bisa dimaknai pula sebagai keteranan, telah melahirkan pula suatu sikap yang perlu dikaji ulang. Para pelaku industri jurnalistik 'mainstream' menilai, telah banyak perbuatan clickbait, yang aritnya, judul tidak sesuai isi, agar mendorong orang mengklik link yang dikirimkan, dan hal tersebut telah menjadi wabah yang membahayakan kewarasan, kesadaran, dan kewajaran.
Bahkan di era permudahan meraih informasi, asalkan rajin, bukan hanya clickbait yang kian merebak, tapi juga jurnalistik 'mulung muntah'. Misalkan seseorang membaca berita di portal terdepan, dari sumbernya langsung, lalu berita itu diolah, diganti judulnya dengan yang lebih bombastis, lalu di-upload ke weblog, maka jadilah berita. Itulah metode jurnalistik mulung muntah, memang tidak copy paste sih. Ia melakukan hal itu, banyakan alasannya. Namun apapun alasannya, terdapat keuntungan. Yang akan menyedihkan, demi mengejar keuntungan, orang-orang melakukan hal itu, dan hilanglah daya kreatif, atau terjadi pendangkalan terhadap substansi kreatif, jika sekedar asal utak-atik.
Tak masalah asal utak-atik, namun perlu dimaknai dan dicermati, apakah yang kita pulung itu, sudah benar-benar berita yang akurat? Yang bahaya adalah, ternyata kita mulung yang keliru, dan tanpa dimaknai, tentu menghasilkan muntahan yang keliru.
Jurnalisme makna diusung oleh almarhum Kiyai Jakob Utama, salah satu pendiri Kompas Grup. Dulu sekali, di awal dekade milennium ketiga ini, Jakob mengatakan perlunya memaknai sebuah berita, sebelum disebarluaskan. Untuk sampai pada makna, tentu harus ditafsir terlebih dulu. Jadi, jurnalisme makna adalah kelanjutan dari jurnalisme tafsir. *
Tulisan ini pernah tayang di https://jurdik.id/2022/06/25/antara-jurnalisme-tafsir-dan-jurnalisme-mulung-muntah/