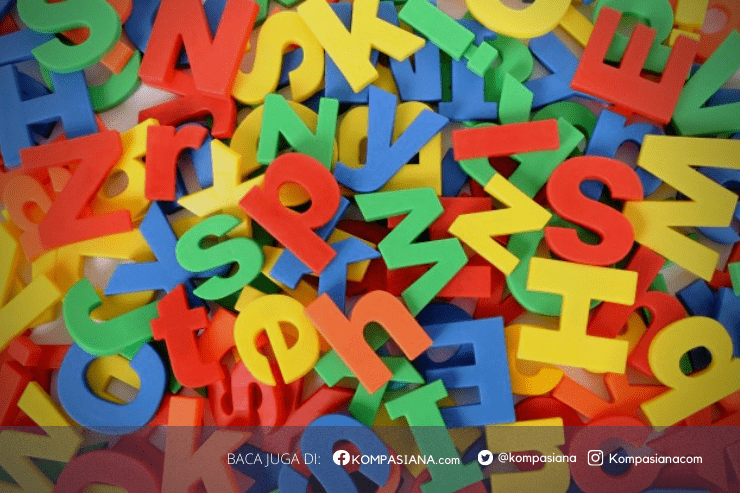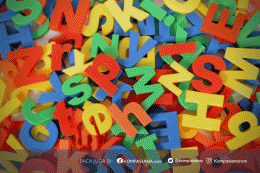Beberapa waktu terakhir, ruang maya dipenuhi perbincangan mengenai pernyataan seorang guru dari Malaysia yang mengutarakan keresahan terhadap maraknya penggunaan kosakata bahasa Indonesia dalam karangan siswa di negaranya. Pernyataan tersebut menuai tanggapan beragam, terutama dari warganet Indonesia yang merasa heran, bahkan tersinggung, atas nada curiga yang ditujukan kepada bahasa Indonesia yang digunakan oleh generasi muda negara jiran.
Jika dicermati secara saksama, keresahan tersebut tidak sepenuhnya tanpa alasan. Bahasa memiliki fungsi yang lebih dari sekadar alat komunikasi. Ia merupakan medium pewarisan nilai, simbol jati diri, sekaligus instrumen pembentuk identitas kolektif suatu bangsa. Perubahan struktur bahasa nasional akibat akumulasi pengaruh eksternal secara terus-menerus dapat memunculkan kegamangan terhadap otentisitas identitas kebahasaan. Dalam kerangka inilah kekhawatiran sejumlah pendidik di Malaysia menjadi relevan untuk dikaji.
Fenomena penggunaan bahasa Indonesia oleh siswa Malaysia dalam bentuk yang tidak sadar atau tidak terstruktur dapat dipandang sebagai indikasi awal kontaminasi linguistik. Jika kondisi ini berlangsung dalam kurun waktu yang panjang dan tidak disertai intervensi yang memadai dari otoritas pendidikan, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi ambiguitas pemahaman publik terhadap batas antara bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Indonesia. Situasi semacam ini mengandung sensitivitas tersendiri, terutama bila diletakkan dalam konteks sejarah hubungan kultural dan politik antara kedua negara yang tidak selalu harmonis.
Meski demikian, pendekatan yang terlalu reaktif terhadap fenomena tersebut berisiko menyederhanakan persoalan. Perlu diperhatikan bahwa dominasi konten berbahasa Indonesia dalam ruang digital, khususnya pada platform berbasis algoritma seperti YouTube, TikTok, dan Instagram, tidak dapat disimpulkan sebagai upaya ekspansi kebahasaan secara sistematis. Kehadiran Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia dan tingginya tingkat partisipasi warganet dalam memproduksi konten menjadikan Indonesia secara faktual sebagai pusat gravitasi digital kawasan Asia Tenggara. Dengan demikian, eksposur masyarakat Malaysia, khususnya generasi mudanya, terhadap konten berbahasa Indonesia merupakan konsekuensi langsung dari arsitektur teknologi informasi dan budaya digital yang saling terhubung. Bukan merupakan hasil dari suatu agenda politis kebahasaan yang terencana.
Di sisi lain, sejumlah studi informal dan pengamatan lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar anak muda di Malaysia menunjukkan keakraban yang tinggi terhadap bahasa Indonesia. Banyak di antara mereka secara aktif mengonsumsi tayangan hiburan asal Indonesia dan menjadikannya bagian dari praktik budaya keseharian. Fenomena ini memperlihatkan adanya proses asimilasi kultural yang bersifat timbal balik dan tidak sepihak. Sementara itu, masyarakat Indonesia tidak memperlihatkan gejala yang sama. Meskipun produk-produk hiburan Malaysia tersebar di Indonesia, anak-anak Indonesia tetap menggunakan bahasa nasional mereka secara konsisten dan tidak serta-merta mengadopsi gaya tutur khas Malaysia. Hal ini mengindikasikan bahwa daya lenting bahasa Indonesia cukup tinggi dan telah terbentuk ekosistem kebahasaan yang kokoh di berbagai sektor kehidupan publik. Pertanyaan yang patut diajukan kemudian adalah, sejauh mana otoritas pendidikan dan budaya di Malaysia telah mampu membangun kebanggaan linguistik di kalangan generasi muda? Apakah bahasa nasional telah dihadirkan dalam bentuk yang relevan, adaptif, dan memikat bagi mereka yang tumbuh di era digital?
Dalam kerangka pemikiran tersebut, sesungguhnya momentum ini dapat dijadikan bahan refleksi bersama. Alih-alih menempatkan bahasa Indonesia sebagai pihak yang patut dicurigai, mungkin sudah saatnya dilakukan evaluasi terhadap kapasitas internal dalam menghidupkan bahasa nasional masing-masing. Bahasa yang kuat bukanlah bahasa yang disterilkan dari pengaruh luar, melainkan bahasa yang tetap digunakan secara luas, dicintai oleh penuturnya, dan terus berkembang melalui interaksi dinamis dengan dunia luar.
Pelestarian bahasa tidak dapat bergantung pada regulasi semata. Ia harus dibangun melalui proses edukatif yang berkelanjutan, didukung oleh kebijakan budaya yang progresif, serta diperkuat oleh produksi konten berkualitas tinggi yang mampu bersaing secara global. Dalam konteks ini, keberhasilan bahasa Indonesia menyebar ke luar batas teritorialnya bukan semata hasil dari kuasa demografi, tetapi juga karena kemampuannya menjadi medium komunikasi yang produktif dan kontekstual.
Namun keberhasilan tersebut sebaiknya tidak memupuk sikap superioritas linguistik. Sebaliknya, ia dapat dijadikan titik tolak untuk membangun dialog kebahasaan yang setara, saling menghormati, dan bertumpu pada semangat kolaboratif. Dalam dunia yang terus bergerak menuju konektivitas global, kekuatan bahasa justru terletak pada kemampuannya untuk menjembatani, bukan membatasi.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI