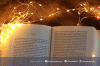Dari LMS ke-Merancang Masa Depan: Cermin Kedisiplinan Digital Mahasiswa?
Oleh: A. Rusdiana
Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 menjadi momentum baru bagi dunia akademik. Berdasarkan SE Rektor UIN SGD Bandung No. B.1611/Un.05.I.1/PP.009/08/2025 (30 Agustus 2025), seluruh perkuliahan wajib menggunakan Learning Management System (LMS), dengan proporsi 30% daring dan 70% luring. Di Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI), berbagai mata kuliah mulai dari Metode Penelitian di S1 hingga Manajemen Sumber Daya Pendidikan di S2 telah melaksanakan kebijakan ini. Namun, pengalaman lapangan menunjukkan bahwa disiplin akademik digital masih rendah. Dalam sesi Part 5 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan, misalnya, dari total 31 mahasiswa, hanya sebagian kecil yang mampu menyelesaikan unggahan tepat waktu di LMS, padahal setiap ketua kelompok dan KOSMA telah diberi otoritas penuh untuk mengontrol kinerja anggota. Hal ini menunjukkan bahwa kedisiplinan di LMS adalah cermin kecil dari kedisiplinan berpikir dan inilah akar dari persoalan literasi digital akademik kita.
Secara teoritis, tulisan ini berpijak pada Teori Job Demand--Job Resources (JD--JR) yang menekankan keseimbangan antara tuntutan kerja dan sumber daya untuk membangun work engagement, serta teori Social Learning (Vygotsky) dan Community of Practice (Wenger) yang menegaskan pentingnya pembelajaran kolaboratif.
Kesenjangannya (gap), banyak dosen menuntut mahasiswa menulis dan berinovasi secara individu, sementara dirinya abai terhadap praktik kolaborasi akademik lintas strata. Padahal, kolaborasi adalah akar dari lahirnya soft skills global sebuah prasyarat menuju Indonesia Emas 2045. Maka tujuan tulisan ini untuk mengeksplorasi bagaimana aktivitas di LMS dapat menjadi jembatan menuju perancangan masa depan digital yang disiplin, kolaboratif, dan berkarakter. Berikut, Lima Pilar Pembelajaran dari "Dari LMS ke-Merancang Masa Depan...?":
Pilar Pertama; Disiplin Digital sebagai Modal Awal Profesionalisme; Setiap klik dan unggahan di LMS merefleksikan responsibility mindset. Mahasiswa yang disiplin mengisi kehadiran, mengunggah tugas tepat waktu, dan memperhatikan etika digital sesungguhnya sedang berlatih menjadi tenaga profesional. Disiplin digital membentuk self-regulated learner yang sadar bahwa dunia kerja nanti menuntut kecepatan, ketepatan, dan tanggung jawab. Di sinilah LMS berfungsi bukan sekadar alat, tetapi ruang pembiasaan karakter akademik.
Pilar Kedua; Kolaborasi sebagai Sumber Kekuatan Akademik; Dalam perkuliahan MPI, setiap kelompok memiliki ketua dan anggota yang bertugas memonitor kinerja bersama. Sayangnya, lemahnya sinergi membuat waktu unggah belum ideal. Padahal, kolaborasi digital adalah inti dari pembelajaran abad ke-21. Seperti diungkap Wenger, community of practice terbentuk ketika individu berbagi praktik dan pengalaman untuk memecahkan masalah bersama. Mahasiswa yang mampu bekerja lintas kelompok dan strata akademik sejatinya sedang belajar kepemimpinan partisipatif bukan hanya teknis.
Pilar Ketiga; Soft Skills Global: Dari LMS ke Branding Akademik; Aktivitas di LMS dapat diubah menjadi portofolio digital yang menunjukkan kompetensi mahasiswa: tanggung jawab, komunikasi, kerja tim, dan inisiatif. Di era job market global, mahasiswa dengan rekam jejak digital yang positif lebih mudah membangun personal academic branding. Seperti teori Job Resources, sumber daya digital dan sosial yang dimiliki akan meningkatkan engagement dan ketahanan terhadap tekanan akademik.
Pilar Keempat; Tutor Sebaya dan Pembelajaran Sosial; Menariknya, ada contoh inspiratif dari tiga mahasiswa kelas I/E yang dalam 24 jam mampu menjadi tutor sebaya lintas kelas dalam membantu rekan mereka menyelesaikan LMS. Fenomena ini membuktikan kebenaran teori Vygotsky, bahwa pembelajaran terbaik terjadi melalui interaksi sosial dan scaffolding antar rekan. Dalam konteks ini, LMS bukan sekadar sistem, tetapi laboratorium sosial untuk melatih solidaritas akademik.
Pilar Kelima; Literasi Digital sebagai Ekosistem Masa Depan; Data Kemkominfo--KIC (2021) menunjukkan indeks literasi digital Indonesia masih di angka 3,49 (kategori sedang). Rendahnya literasi ini adalah ancaman serius, apalagi McKinsey (2019) memperkirakan 23 juta pekerjaan akan diautomatisasi pada 2030. Jika mahasiswa hari ini tidak mengasah kemampuan digitalnya, mereka akan kehilangan relevansi. LMS adalah miniatur dari dunia kerja digital dan mahasiswa yang mampu memanfaatkannya dengan disiplin, aman, dan produktif sedang merancang masa depan mereka sendiri.
Kedisiplinan di LMS bukan sekadar memenuhi tugas, tetapi bagian dari membangun self-leadership dan kesiapan menghadapi dunia kerja digital. Dosen perlu memosisikan LMS sebagai ruang tumbuh bersama, bukan sekadar tempat unggah tugas. Mahasiswa perlu melihatnya sebagai laboratorium pembentukan karakter profesional. Institusi pun harus memperkuat sistem feedback, mentor sebaya, dan publikasi akademik digital agar pembelajaran tidak berhenti di ruang daring, tetapi berlanjut ke kolaborasi lintas strata.