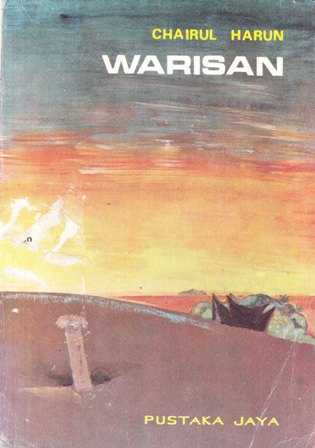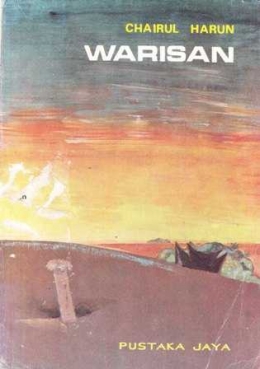CHAIRUL HARUN,melalui tokoh Rafilus dalam novel "Warisan" menyampaikan otokritik terhadap urang awak dengan bahasa yang lugas: "Di atas permukaan,dalam kehidupan masyarakat,semuanya tampak demikian ketat,demikian fanatik dengan nilai-nilai adat dan kesusilaan. Tetapi jauh di bawah,mengalir deras arus kebebasan untuk menikmati kehidupan duniawi."
Saya membaca bagian cerita itu berulangkali,seakan tak percaya dengan pernyataan yang dikeluarkan Chairul Harun (yang menulis novel ini pada tahun 1970-an) namun di saat bersamaan tak ada alasan bagi saya untuk menolaknya mentah-mentah. Apa yang dilontarkan Chairul Harun agaknya ada benarnya juga. Oh,atau memang seperti itukah wajah masyarakat kita?
Bagi yang pernah membaca makalah Mochtar Loebis tentang watak orang Indonesia,hal ini tentu tak asing lagi. Bedanya,Mochtar memberikan stereotip tentang orang Indonesia secara universal,sementara Chairul Harun lebih spesifik menyinggung tentang orang Minang.
Novel "Warisan" berlatar kehidupan masyarakat pedesaan di Kuraitaji,Pariaman. Namun tentu saja pesan yang ingin disampaikan Chairul tak hanya sebatas ruang lingkup kecil itu saja.
Di permukaan,semua tampak penuh sopan santun,beretika,namun jauh di dalam hati masing-masing tersimpan kerak benci dan saling dengki. Mulut tentu bisa dioles manis gula tapi hati yang membusuk siapa yang tahu? Bermuka-dua dan (maaf) munafik.
Di hadapan orang-orang kita tentu saja bisa berpura-pura baik dan tampil sebagai pejuang moral,tapi wajah sesungguhnya dari seorang manusia tentu hanya dia dan Tuhannya yang tahu. Wajah lugu penuh tatakrama kadang justru menyimpan bara jahat dan kerak nista.
Kita katanya menjunjung tinggi adat namun nyatanya kita sering menunjukkan perilaku tak beradab. Kita mengutuk kelakuan orang-orang di kota yang semakin liar,namun kita seakan menutup mata bahwa kita justru telah menjadi bagian dari itu semua. Kasus kehamilan di luar nikah semakin meningkat. Seks bebas di kalangan remaja sudah menjadi keseharian. Suami istri punya selingkuhan masing-masing. Seperti itukah adat? Kadang,adat hari ini tak lebih hanyalah tinggal polesan bibir belaka.
Kadang,saya berpikir,apa gunanya kita berkoar-koar tentang masyarakat kita yang beradat dan dekat dengan agama jika pada akhirnya perbuatan kita tak mencerminkan semua itu? Apakah gunanya petuah adat dan kutipan-kutipan ayat suci jika dalam keseharian kita justru tak pernah melaksanakannya?
Apa gunanya kita mengaku orang beragama jika semua itu hanya muncul di permukaan saja? Apa gunanya kita sembahyang jika hati masih dipenuhi rasa iri dan dengki? Apakah gunanya Anda membaca ayat suci jika bahkan makna bismillah saja tak bisa Anda amalkan dalam keseharian?
Di permukaan kita bisa menipu mata manusia. Di dalam hati,apakah kita juga akan menipu Tuhan? Cobalah kalau Anda bisa...