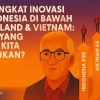Setelah menelusuri jejak prasejarah Indonesia, masih dengan benak penuh kekaguman akan kehebatan leluhur di zaman tersebut, langkah kaki saya seolah memiliki pikirannya sendiri, menuntun keluar dari lorong waktu purbakala. Rasa takjub pada fondasi peradaban yang begitu tua dan maju itu masih membekas kuat. Namun, Museum Nasional masih menyimpan begitu banyak lapisan cerita. Kini, saatnya beralih dari era tanpa tulisan menuju masa di mana peristiwa mulai tercatat, terekam dalam aksara, peta, dan benda-benda peninggalan yang menjadi saksi bisu berbagai babak penting dalam pembentukan Indonesia. Saya memutuskan untuk menjelajahi bagian Koleksi Sejarah.
Jika ruang prasejarah terasa seperti menyelami samudra sunyi penuh misteri, memasuki bagian sejarah terasa seperti membuka lembar-lembar buku raksasa yang terkadang penuh warna kejayaan, namun tak jarang diwarnai tinta kelam perjuangan dan pertumpahan darah. Suasana hening Lebaran di museum ini terasa semakin kontras dengan riuhnya peristiwa yang coba dihadirkan oleh koleksi di hadapan saya.
Dari Kejayaan Nusantara ke Belenggu Kolonialisme: Membaca Ulang Sejarah
Sebelum pengaruh kerajaan-kerajaan Islam menguat dan peta politik Nusantara tergambar ulang, kepulauan ini pernah menyaksikan puncak kejayaan sebuah imperium agraris-maritim yang legendaris: Majapahit. Memasuki abad ke-14, di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk (bertahta 1350-1389 M) dan ditopang oleh kecakapan Mahapatih Gajah Mada dengan Sumpah Palapa-nya yang terkenal, Majapahit mencapai masa keemasannya. Ini bukan sekadar kerajaan lokal, melainkan sebuah kekuatan besar yang pengaruhnya menggema di seantero Asia Tenggara. Wilayah kekuasaannya, menurut tafsir kitab Negarakertagama, membentang luas melampaui batas Indonesia modern, mencakup sebagian besar Nusantara hingga ke Semenanjung Malaya. Kekuatan maritimnya disegani, jaringan perdagangannya menjangkau berbagai bangsa, dan pengaruh budayanya terasa kuat. Meskipun arca-arca megah dan peninggalan candi-candinya lebih banyak mengisi ruang Arkeologi Klasik, membayangkan era ini melalui peta wilayah pengaruh, replika prasasti, atau narasi sejarah yang tersaji, adalah bukti tak terbantahkan akan keperkasaan dan visi besar leluhur bangsa Indonesia yang mampu membangun sebuah imperium adidaya di jantung Asia.
Namun, roda sejarah terus berputar, dan lanskap politik serta keagamaan Nusantara perlahan berubah. Jejak-jejak peradaban yang lebih muda mulai tampak kuat dengan menguatnya kerajaan-kerajaan Islam. Saya melihat naskah-naskah kuno, beberapa di antaranya adalah salinan Al-Quran dengan iluminasi yang indah, atau kitab-kitab babad yang mengisahkan silsilah raja-raja dan peristiwa penting di tanah Jawa atau Sumatera. Ada pula senjata-senjata pusaka, seperti keris dengan pamor yang rumit atau meriam-meriam kecil peninggalan kesultanan seperti Banten atau Aceh, yang menjadi simbol kekuatan militer sekaligus artefak diplomasi pada masanya. Membayangkan kapal-kapal dagang dari Demak, Aceh, Makassar, atau Ternate yang merajai lautan, membawa rempah-rempah dan menyebarkan pengaruh budaya serta agama, membangkitkan kembali citra Nusantara sebagai kekuatan maritim dan pusat perdagangan yang disegani di era berikutnya.
Narasi kejayaan itu perlahan mulai bergeser saat etalase menampilkan artefak dari era kedatangan bangsa Eropa. Peta-peta kuno buatan kartografer Belanda menunjukkan bagaimana pengetahuan mereka tentang geografi Nusantara semakin detail, seiring dengan ambisi mereka untuk menguasai jalur rempah-rempah. Koin-koin VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) yang dipamerkan menjadi simbol dimulainya era korporasi dagang raksasa yang perlahan tapi pasti mencengkeram ekonomi dan politik lokal. Meriam-meriam bertuliskan lambang VOC menjadi penanda pos-pos dagang yang kemudian berubah menjadi benteng pertahanan, saksi bisu persaingan dagang yang seringkali berujung konflik bersenjata.
Memasuki periode Pemerintahan Hindia Belanda, suasana terasa semakin kompleks. Di satu sisi, terpajang potret-potret para Gubernur Jenderal dengan pakaian kebesaran mereka, atribut-atribut pemerintahan kolonial, dan benda-benda yang menunjukkan adanya pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jalur kereta api, atau gedung-gedung pemerintahan. Namun, di sisi lain, terselip narasi perlawanan yang gigih dari berbagai penjuru Nusantara. Meskipun pusaka Pangeran Diponegoro atau rencong Cut Nyak Dien tidak dipajang tepat di sini (diletakkan di bagian khusus Etnografi/Harta Karun), aura perjuangan mereka seolah terasa.
Saya membayangkan bagaimana kebijakan Tanam Paksa (Cultuurstelsel) mencekik rakyat, memaksa mereka menanam komoditas ekspor demi keuntungan penjajah. Koleksi ini mungkin tidak secara eksplisit menampilkan penderitaan itu, tetapi benda-benda peninggalan era tersebut seperti alat pertanian sederhana, foto-foto kondisi perkebunan menjadi pengingat akan masa-masa sulit itu. Ini adalah periode dualitas: penindasan dan eksploitasi berjalan beriringan dengan modernisasi yang semu, yang pada akhirnya justru turut membangkitkan kesadaran baru di kalangan kaum terpelajar bumiputera.
Api Perjuangan: Menuju Indonesia Merdeka
Bagian yang paling membangkitkan semangat nasionalisme tentu saja adalah periode Kebangkitan Nasional dan Perjuangan Kemerdekaan. Di sini, semangat persatuan mulai terasa denyutnya. Foto-foto hitam putih menampilkan wajah-wajah para tokoh pergerakan awal seperti Dr. Wahidin Soedirohoesodo, H.O.S. Tjokroaminoto, atau para pemuda yang terlibat dalam Kongres Pemuda II tahun 1928. Walaupun mungkin hanya replika atau dokumentasi, melihat visualisasi momen Sumpah Pemuda, ikrar bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, Indonesia, tetap memberikan getaran tersendiri.
Semangat juang semakin membara saat melihat artefak dari masa Revolusi Fisik (1945-1949). Etalase menampilkan kesederhanaan namun kegigihan perjuangan: bambu runcing yang legendaris bersanding dengan senapan hasil rampasan dari tentara Jepang atau Belanda. Poster-poster propaganda perjuangan dengan slogan "Merdeka atau Mati!" atau "Sekali Merdeka Tetap Merdeka!" menyuarakan tekad yang bulat. Mungkin ada replika bendera Merah Putih pertama, atau dokumentasi detik-detik Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Setiap benda di bagian ini bukan lagi sekadar artefak sejarah, melainkan relikui suci dari sebuah perjuangan kolektif merebut dan mempertahankan kedaulatan bangsa. Berdiri di sini, di tengah keheningan museum saat Lebaran, kontemplasi tentang harga sebuah kemerdekaan terasa begitu mendalam.
Refleksi di Persimpangan Sejarah
Menyusuri Koleksi Sejarah di Museum Nasional terasa seperti menaiki rollercoaster emosi. Ada rasa kagum pada peradaban maritim dan kesultanan masa lalu, rasa miris dan geram saat menyaksikan jejak-jejak kolonialisme, dan akhirnya rasa bangga yang meluap-luap melihat api perjuangan kemerdekaan yang tak kunjung padam. Bagian ini dengan gamblang menunjukkan betapa berliku dan penuh tantangan jalan yang harus dilalui bangsa ini untuk menjadi Indonesia yang kita kenal hari ini.