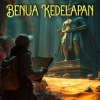Bagi Siswa: Suasana belajar menjadi lebih relevan dengan kebutuhan mereka. Siswa merasa lebih diperhatikan, baik secara akademik maupun non-akademik.
Bagi Orang Tua dan Masyarakat: Mereka dilibatkan sebagai mitra sejajar dalam pendidikan. Ini memperkuat ikatan emosional dan sosial antara sekolah dengan komunitas.
Bagi Kepala Sekolah: Ia bukan hanya administrator, melainkan pemimpin yang visioner dan mampu mendorong perubahan. Kepala sekolah menjadi fasilitator, mediator, dan motivator bagi seluruh warga sekolah.
Dengan demikian, MBS menempatkan manusia sebagai pusat perubahan. Ia menumbuhkan sense of belonging (rasa memiliki) dan sense of responsibility (rasa tanggung jawab), yang sangat penting bagi keberlangsungan pendidikan.
Tantangan di Lapangan
Meski memiliki banyak kelebihan, implementasi MBS tidak lepas dari berbagai tantangan:
Perbedaan Kapasitas Sekolah: Sekolah di daerah maju dengan sumber daya memadai cenderung lebih berhasil, sedangkan sekolah di daerah tertinggal kerap kesulitan.
Kapasitas Manajerial Kepala Sekolah: Tidak semua kepala sekolah memiliki kemampuan kepemimpinan partisipatif dan keterampilan manajemen yang memadai.
Partisipasi Masyarakat yang Minim: Di beberapa tempat, orang tua dan masyarakat masih enggan atau belum terbiasa terlibat aktif dalam pengelolaan sekolah.
Potensi Penyalahgunaan Otonomi: Tanpa pengawasan, fleksibilitas bisa disalahgunakan, misalnya dalam pengelolaan dana.
Budaya Resistensi terhadap Perubahan: Guru atau staf sekolah kadang merasa nyaman dengan pola lama dan enggan menerima model partisipatif.