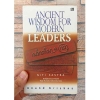Pada mulanya kisah ini menjadi lelucon, bahan tertawaan tiada ujung.
Begitu juga yang terjadi pada diri kami. Akan tetapi, sebagaimana kesedihan, ujung dari menertawakan sejujurnya bisa ditransformasikan menjadi permenungan.
Itulah juga yang terasa ketika seorang kawan menyampaikan kabar ada seorang kawan yang tersesat di mall (?). Sebuah mall kecil di kota Manado, Sulawesi Utara.
Untuk memasukkan cerita ini kesadaran, mari mulai dengan membayangkan diri Anda sendiri sebagai subyek yang mengalami kejadian itu.
Katakanlah, dalam satu kesempatan waktu, Anda meniatkan diri untuk ke mall. Mungkin yang anda cari hanyalah suasana dan gaya. Atau, barangkali yang Anda ingin dapatkan adalah gengsi sosial: bisa menghabiskan waktu dengan nongkrong di salah satu kafe.
Mungkin juga Anda hanya ingin sekedar ‘mencuci mata, melelahkan betis’ saja. Jelasnya, apapun motivasi anda, paling tidak, Anda sedang mencari sesuatu disitu, dan tak harus berbelanja (shopping).
Meminjam bahasa George Ritzer dalam Globalization Of Nothing (2004), mall adalah pasar sekaligus bukan pasar.
Mall memang menjual, tetapi ia bukan sebatas ruang berjumpanya penjual/pemilik barang dan pembeli. Selain juga, bukan hanya menjual barang.
Melampuai barang-barang, mall juga menjual sekaligus mengkonstruksi: gaya hidup, ideologi tubuh, hingga perayaan hasrat.
Dengan peringatan yang demikian, kehadiran mall jangan semata-mata dipandang urusan ekonomi kota (baca: demi mengejar target PAD).
Jika sudah demikian, maka mall yang ‘diproblematisasi secara kebudayaan’ mengisyaratkan penanganan kultural, intelektual, politis, hingga teknis yang kompleks dan melibatkan banyak kepentingan di dalamnya.
Evers dan Korf (Urbanisme di Asia Tenggara : Makna dan Kekuasaan Ruang-ruang Sosial, Yayasan Obor Indonesia, 2002) mengatakan:
..keberlanjutan perkembangan kota tergantung pada aturan-aturan dan regulasi yang diberlakukan pemerintah. Aturan-aturan dan regulasi ini adalah keputusan politis negara dan pemerintah kota. Penyusunan dan pemberlakukannya didasarkan pada perjuangan politik dimana aliansi, pemenang dan pecundangnya sering berganti-ganti. Pembuat rencana Kota dan arsitek terintegrasi kedalam hubungan produksi ruang dan pertentangan antar kelompok strategis’.
Hubungan produksi ruang.
Kiranya aspek inilah yang seringkali menjadi sumber sengketa dan pertentangan antara kelompok-kelompok dalam sebuah kota.
Untuk kasus Manado, dengan melihat fakta perubahan geografi pesisir dan aktivitas ekonomi kota Manado tengah menempuh jalan ekonominya dengan berpayung pada, apa yang disebut dengan, Waterfront City.
Menjadi penting juga untuk melihat akibat-akibat yang ditimbulkannya terhadap kota ini secara umum.
Beberapa akibat yang bukan saja berciri ekonomistik, tetapi juga sosial-kultural yang bisa diidentifikasi itu diantaranya adalah sebagai berikut ini.
Pertama, kawasan pesisir teluk yang dahulunya merupakan wilayah pemukiman, tradisi kenelayanan, juga pusat rekreasi terbuka warga kota lantas berubah fungsi menjadi kawasan ekonomi pantai, khususnya perdagangan dan konsumsi warga yang dikenal dalam teori perkotaan sebagai Central Bussines District (CBD) yang lebih mewakili dominasi kekuatan ekonomi bermodal besar (kapitalisasi kota).
Kedua, pertumbuhan dan perkembangan kawasan ekonomi itu, selain didominasi oleh kekuatan modal besar, juga menjadi kawasan dari pertumbuhan satu moda (corak) konsumsi ekonomi baru bagi warga kota yang ditandai dengan kehadiran pusat perbelanjaan super modern seperti mall, dan hypermart, butik, distro, gerai pijat dan kecantikan, dll.
Ketiga, kawasan ekonomi pantai pun berkembang menjadi suatu kawasan ‘panggung bagi ekspresi selera kelas’, yang terutama berkaitan dengan gaya hidup (life style), pola makan, berpakaian (fashion), dan konsumsi hiburan.
Kesadaran yang Tersesat
Kawan yang tersesat di mall sebaiknya tidak dimaknai sebagai pribadi yang terlepas dari warga dalam satu dunia sosial tertentu (labenswelt).
Karena itu dirinya mewakili kewargaan yang lebih besar dan luas dimana di dalamnya pengetahuan sosial dibentuk dalam tiga moment dialektis: internalisasi, obyektifasi dan eksternalisasi.
Dalam sosiologi pengetahuan, seperti yang diuraikan Peter Berger, juga terdapat jenis pengetahuan sehari-hari atau resep tadi.
Yakni, jenis pengetahuan yang dibentuk oleh praktik sosial yang berulang hingga menjadi rutin.
Pengetahuan sehari-hari menuntun individu ke dalam rutinitasnya sekaligus juga menyambungkan dengan lokasi-lokasi dari tujuannya.
Makanya, kesadaran individu selalu berciri intension, dimana dunia di luar sana sudah terpetakan dalam gugus kesadaran; dunia diluar sana tak sepenuhnya berwatak eksternal dan memaksa seperti yang dimaksud penganut fungsionalisme.
Sebab itu, ketersesatan kesadaran dalam pengertian yang luas tidak sepenuhnya adalah soal geografis.
Tetapi ketersesatan barangkali lebih dahulu disebabkan oleh ketersesatan maknawi yang juga bergantung pada pengetahuan resep sehari-hari tadi.
Sebagai ilustrasi, seorang pendatang dari desa yang memasuki kota besar memiliki benturan di level pengetahuan resep yang bisa mengguncang kenyamanan kognitif dan psikis.
Di taraf kognitif, ia harus bisa, paling kurang, mengingat alamat dan alur transportasi yang memungkinnya mencapai tujuan.
Sedang, di taraf psikis, ia harus bisa melawan perasaan khawatir, cemas dan rendah diri berhadapan dengan jalan raya yang besar, pergerakan lalu lintas yang padat, sikap siapa lu, siapa gue penduduk urban, hingga angkuh gedung-gedung yang menjulang tinggi.
Bagi mereka yang mengalami benturan itu, sering disebut, bahasa sekarangnya dengan kurang gaul.
Kurang gaul, atau sebutan yang lebih nyiyir dari itu, kampungan/ndeso, sering dilekatkan pada tipe orang yang gagap sekligus gugup ketika masuk dalam ruang-ruang konsumsi urban.
Dari sisi yang ‘lebih politis’ sebagaimana kesimpulan Evers dan Korf di atas, menyebut kurang gaul atau kampungan/ndeso sebenarnya juga sedang menampilkan sisi lain dari perbedaan-perbedaan politik, ekonomi dan status diantara warga urban; seperti menegaskan relasi pemenang dan pecundang.
Pada ujungnya, kehendak untuk terlibat dalam konsumsi kolektif produksi ruang adalah suatu perjuangan sekaligus pertaruhan dunia makna subyektif yang bergulat kedalam produksi ruang perkotaan.
Oleh karenanya kesadaran yang tersesat di dalam mall, bisa juga dipandang sebagai pantulan kecil dari pergulatan politik-eksistensial dalam konteks besar hubungan produksi ruang.
Individu bisa terjerembab ke dalam anomi dan alienasi yang pejal. Singkat kata menjadi pecundang.
Tentang kawan saya yang tersesat di dalam mall itu, saya kira bukan semata disebabkan kealpaannya mengingat pintu masuk dan keluar.
Lebih dari itu, ketersesatannya mewakili sesuatu yang lebih subtil: dunia makna subyektif yang terbentur oleh perubahan lingkungan karena hubungan produksi ruang yang tak sepenuhnya mengikutsertakan warga kota secara demokratis.
Salam.