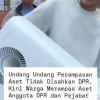Pemerintah berupaya menjawab tantangan-tantangan tersebut khsusunya perihal petani secara kuantitas melalui Program Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP) di 2015 lalu. Program ini dirancang untuk menumbuhkan kesadaran kewirausahaan pertanian di kalangan muda, membuka peluang usaha agribisnis, serta mengembangkan lembaga pendidikan pertanian sebagai inkubator agrisosiopreneurship, yakni kewirausahaan yang menggabungkan dimensi sosial dan keberlanjutan (PWMP, 2025). Meskipun demikian, keberhasilan program ini masih terancam oleh dua tantangan utama, yaitu keterbatasan inklusivitas segmen sasaran dan ketimpangan geografis dalam akses sumber daya serta pelatihan dasar. Saat ini, sasaran PWMP masih terbatas pada generasi muda dan petani muda (KUB), santri tani milenial (KSTM), penggerak petani milenial daerah (DPM/DPA), serta siswa dan alumni lembaga pendidikan pertanian (Peserta Didik dan Alumni).

Padahal, kajian potensi menunjukkan adanya kelompok lain yang strategis namun sering terabaikan, seperti perempuan muda di pedesaan yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga tetapi terhambat oleh norma budaya dan minimnya akses literasi kewirausahaan; mahasiswa non-pertanian dengan minat interdisipliner di bidang teknologi, desain, atau bisnis yang berpotensi mendorong inovasi agritech dan agro-ecommerce; pemuda 4 penyandang disabilitas yang memiliki potensi kreatif, tetapi terhalang akses pelatihan, permodalan, dan jaringan bisnis; komunitas pemuda adat di NTT, Papua, dan Maluku (termasuk daerah 3T lainnya) yang menguasai kearifan lokal adaptif terhadap perubahan iklim; serta pemuda berbasis agama selain santri yang memiliki jaringan sosial kuat untuk menggerakkan transformasi agribisnis berbasis komunitas. Fokus kebijakan yang sempit ini berpotensi menciptakan "gerbang eksklusif" dalam program, sehingga membatasi diversifikasi inovasi sosial. Memperluas inklusivitas berarti menghadirkan wirausaha agribisnis yang lebih kreatif, merata, dan tangguh secara sosial, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Tantangan berikutnya adalah ketimpangan geografis. Data Podes menunjukkan bahwa provinsi-provinsi di wilayah timur seperti Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara memiliki rasio fasilitas serupa PWMP (pendanaan dan pelatihan dasar tani) yang jauh lebih rendah dibandingkan wilayah Jawa dan Sumatra (BPS, 2019; BPS, 2020). Ironisnya, wilayah-wilayah ini tergolong daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) yang justru paling membutuhkan dukungan pembangunan kewirausahaan. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan minimnya pusat pelatihan keterampilan di sektor vital seperti bahasa asing, komputer, mekanik, dan pengolahan pangan di wilayah timur (BPS, 2018). Tanpa pelatihan dasar, modal usaha yang diberikan berisiko tidak produktif dan justru menjadi konsumtif. Ekosistem kewirausahaan memerlukan capacity building dari hulu agar modal benar-benar menjadi investasi produktif dan mendorong keberlanjutan usaha.
Untuk menjamin keadilan dan efektivitas, PWMP sudah semestinya perlu mengadopsi prinsip fairness dalam tiga dimensi utama dikeberjalanannya. Pertama, fairness geografis, yakni memastikan alokasi sumber daya berbasis pada kebutuhan daerah dengan menetapkan baseline minimal untuk wilayah 3T. Kedua, fairness segmentasi sosial, yang memperluas penerima manfaat pada kelompok perempuan, penyandang disabilitas, komunitas adat, mahasiswa lintas disiplin, dan pemuda berbasis agama. Ketiga, fairness aksesibilitas, dengan merancang pelatihan dan skema permodalan khusus yang mempertimbangkan hambatan fisik maupun sosial, seperti pelatihan keliling desa atau penyediaan materi pembelajaran dalam format braille dan audio.
Lalu, bagaimana peran anak muda dapat menjadi penggerak utama agar PWMP benarbenar menjawab tantangan regenerasi petani? Dari segi peran anak muda sebagai subjek utama, efektivitas PWMP akan jauh lebih optimal jika mereka terlibat aktif di enam domain six domains of youth co:lab's ecosystem diagnostic framework yang potensial tersedia/disediakan (Semeru Research Institute, 2021). Program ini tidak boleh berhenti sebagai inisiatif top--down yang sebatas sosialisasi dan penyaluran modal, melainkan harus menumbuhkan ekosistem wirausahawan muda pertanian yang berkelanjutan. Pada domain kerangka kebijakan dan regulasi, pemuda dapat menjadi suara aktif dalam youth policy forum atau musyawarah desa untuk mengusulkan, misalnya perihal perlindungan harga komoditas ataupun regulasi menyangkut otomatisasi proses produksi.

Di bidang modal manusia dan budaya kewirausahaan, mereka dapat membangun komunitas belajar lintas komunitas/desa untuk berbagi keterampilan agritech, pemasaran 6 digital, dan menumbuhkan kebanggaan bertani. Pada aspek akses pembiayaan dan insentif, pemuda dapat inisiatif dalam membentuk koperasi atau crowdfunding komunitas mandiri lanjutan yang menjangkau hingga daerah minim layanan. Untuk dukungan pengembangan usaha dan infrastruktur, kolaborasi dapat dijalin dengan perguruan tinggi, BUMDes, dan sektor swasta guna menghadirkan pusat pengolahan bahkan jaringan distribusi. Dalam ranah inovasi dan teknologi, mereka bisa memimpin pengembangan aplikasi monitoring tanaman, sistem irigasi pintar, atau kemasan ramah lingkungan. Terakhir, pada akses terhadap pasar, pemuda dapat menghubungkan produk pertanian ke marketplace, retail chain, atau pasar ekspor dengan strategi branding dan sertifikasi mutu yang tepat
Tanpa penerapan prinsip inklusivitas dan keterlibatan aktif anak muda di ekosistemnya, bukan tidak mungkin PWMP justru terjebak melahirkan wirausahawan muda "elit urban" yang terputus dari akar desa, mengabaikan potensi besar di komunitas adat dan kelompok marjinal. Sebaliknya, jika cakupan penerima manfaat diperluas, wilayah 3T diprioritaskan, dan pendekatan pasar diperkuat dengan inovasi yang lahir dari kolaborasi lintas sektor, PWMP berpeluang besar menjadi katalis regenerasi petani sekaligus transformasi agribisnis berkelanjutan. Dengan demikian, program ini tidak hanya menyinergikan target swasembada pangan dengan tumbuhnya ekonomi kreatif berbasis anak muda, tetapi juga menjadikannya jawaban konkret atas krisis regenerasi petani melalui inovasi yang berakar pada kekuatan komunitas lokal.
Referensi-referensi