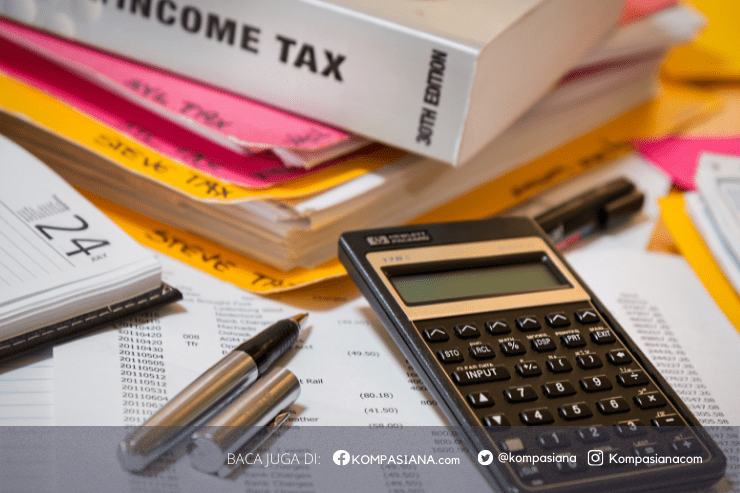Selama ini, banyak negara masih terperangkap dalam pandangan tradisional bahwa salah satu indikator utama mengukur kesuksesan kinerja ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi. Memang, pertumbuhan adalah faktor penting, tapi bukan yang terpenting dan justru bisa melenakan. Mancur Olson bahkan mewanti-wanti tentang bahaya "paradoks kesuksesan".
Terlena sama dengan Bencana
Beberapa dasawarsa yang lalu, Mancur Olson menulis buku berjudul The Rise and Decline of Nations (1982) untuk menganalisa paradoks yang terjadi setelah Perang Dunia II (PD II). Itulah paradoks di mana Inggris yang keluar sebagai pemenang perang justru akhirnya terjerembab ke dalam stagnasi ekonomi, sementara Jerman sebagai pecundang malah tumbuh pesat tahun demi tahun. Keterpurukan Inggris kian mengherankan karena negeri ini adalah pelopor Revolusi Industri.
Berdasarkan analisanya tersebut, Olson lantas mendapati bahwa kesuksesanlah yang sejatinya menghempaskan perekonomian Inggris. Sebab, kejayaan Inggris membuat negeri ini terlena, cepat berpuas diri, alpa melakukan inovasi, dan bahkan mengembangkan penataan ekonomi dan politik yang kaku dan mahal lewat program subsidi, kebijakan proteksionis, dan penarikan dana utang yang berlebihan.
Alhasil, Inggris abai terhadap perkembangan kompetisi yang begitu pesat di luar sana dan menjadi tertinggal dalam medan persaingan dunia. Singkat kata, Inggris yang terlena adalah Inggris yang di masa depan menuai bencana.
Berbeda dengan Jerman. Kekalahan habis-habisan negeri Panzer ini justru memberinya peluang untuk membangun kembali infrastruktur fisiknya secara besar-besaran dan memperbaiki penataan politik serta pranata-pranata yang dimilikinya, mulai dari sistem politik hingga ekonomi, secara modern. Dengan kata lain, kekalahan membuat Jerman tertantang untuk kreatif dan bahkan membangun ulang dari nol segala infrastruktur fisik dan mental yang dimiliki bangsa ini.
Nah, belajar dari paradoks kesuksesan ini, Indonesia kini seyogianya harus mulai menyadari bahwa angka-angka makro-ekonomi tidak boleh semata-mata dijadikan ukuran kesuksesan pembangunan ekonomi. Lebih celaka lagi jika pemerintah bahkan mengemohi kritik terhadap arah pembangunan yang berlangsung sekarang ini, apalagi jika pembangunan disinonimkan dengan peminggiran kebebasan politik. Sebab, penafian kritik justru akan memerangkap Indonesia ke dalam lingkaran paradoks kesuksesan sebagaimana dialami Inggris di masa silam.
Relevansi bagi Indonesia
Maka itu, jika kita mengamini tesis Olson---ekonom sama yang juga berpendapat bahwa demokrasi di suatu negara akan berlangsung baik apabila pendapatan per kapita negara itu sudah mencapai $6.600---Indonesia harus mengadopsi sejumlah solusi untuk menghindari jebakan paradoks kesuksesan. Pertama, Indonesia harus berperilaku fleksibel dalam merancang kebijakan-kebijakan ekonominya. Artinya, pemerintah tidak boleh takut melakukan eksperimen-eksperimen terobosan sekaligus harus berani membatalkan program-program gagal. Juga, pemerintah mesti mencanangkan pengembangan teknologi-teknologi baru seraya membenahi infrastruktur fisik dan mental yang dimiliki bangsa ini.
Sebagai contoh konkret, dari segi kebijakan energi, Indonesia harus cepat membulatkan tekad untuk melaksanakan bauran energi (energy mix) yang mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil (fossil fuel) seraya mengutamakan penggunaan dan pengembangan energi alternatif seperti gas, panas bumi, etanol, nuklir, dan lain sebagainya.
Tak lupa, pemerintah pun perlu menyeleksi program populis secara lebih ketat, seperti progam Makan Bergizi Gratis (MBG) yang lebih baik jika difokuskan pada kluster daerah dengan malnutrisi parah atau seleksi program beasiswa maupun program Kartu Indonesia Sehat (KIS) supaya tidak salah sasaran hingga dinikmati justru oleh orang mampu. Penghematan akibat seleksi dan kurasi program populis itu kemudian bisa dialokasikan ke proyek-proyek riil yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh rakyat, seperti perbaikan transportasi umum, perbaikan jalan raya, pemberian kredit berbunga rendah,pembangunan akses Internet murah, dan lain sebagainya.
Kedua, pemerintah seyogianya berani menggelontorkan dana besar bagi ikhtiar-ikhtiar kewirausahaan (entrepreneurial), keilmuan dan inovasi, teknologi, dan pengembangan infrastruktur yang bermanfaat dalam penciptaan pertumbuhan dan lapangan pekerjaan dalam jangka menengah dan panjang.
Umpamanya, pemerintah perlu menggalakkan pengembangan kluster-kluster industri kreatif seperti Lembah Silikon (Silicon Valley) demi melahirkan pengeksplorasian dan pengadopsian teknologi mutakhir yang cemerlang di masa mendatang. Kita tidak perlu takut upaya semacam ini akan terpeleset menjadi rencana mercusuar mengingat pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator, sementara yang ada di kluster itu tentulah perusahaan-perusahaan swasta yang tidak akan mau mengembangkan sesuatu yang tidak menghasilkan produk massal (mass products) berorientasikan laba.
Ketiga, kita perlu menciptakan iklim demokrasi sehat yang menurut Nurcholish Madjid (1999) memiliki dua sendi penting, yaitu kebebasan dan supremasi hukum. Kebebasan politik dilindungi dengan kesediaan pemerintah menerima kritik, memberikan ruang bagi oposisi, dan memfasilitasi aspirasi masyarakat. Sementara itu, supremasi hukum diwujudkan dengan mewujudkan sistem yudisial yang bersih mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga peradilan sehingga mumpuni dalam memberantas tindak kejahatan seperti korupsi.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI