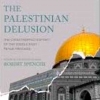Pendahuluan
Permasalahan lingkungan terkait pembukaan/alih fungsi lahan hutan atau deforestasi hutan menjadi salah satu masalah serius yang masih Indonesia hadapi. Sepanjang tahun 2024, laju deforestasi hutan Indonesia semakin memprihatinkan dengan catatan kehilangan hutan seluas 261.576 Ha berdasarkan data Non-Government Organization (NGO), Auriga Nusantara (Alfathi, 2025). Hal ini tercatat sebagai peningkatan deforestasi hutan yang sebelumnya juga terjadi pada tahun 2023, yaitu seluas 257.384 Ha. Peningkatan dalam sebuah kemunduran lingkungan ini membuat Kalimantan yang tercatat sebagai wilayah Indonesia yang mendominasi populasi hutan hujan tropis juga harus tercatat menjadi wilayah dengan deforestasi terluas tahun 2023-2024 setelah wilayah nominasi lainnya yaitu Sumatra, Sulawesi, Papua, Kepulauan Maluku, Bali & Nusa Tenggara, dan Jawa (Alfathi, 2025).
Berdasarkan data tersebut, sebuah organisasi non-pemerintah, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) sebagai organisasi yang bergerak di bidang lingkungan berlingkup nasional, mengangkat isu deforestasi hutan sebagai bentuk eksploitasi sumber daya alam. Isu eksploitasi sumber daya alam yang diangkat tidak hanya ditunjukkan sebagai aksi memperkuat komitmen kepedulian WALHI terhadap isu lingkungan, tetapi juga mengkritik demokrasi era ini dengan mengunggah postingan instagram atau yang biasa disebut feeds dengan headline “Deforestasi Cerminan Demokrasi Hari Ini”.

Melalui unggahan tersebut, WALHI memberikan informasi bahwa ditemukan indikasi terjadinya ancaman regresi serius pada demokrasi Indonesia terkait lingkungan seperti; pembukaan hutan demi bisnis hutan sawit, tambang, HTI, PSN dan lain lain yang masih menjadi pondasi bisnis bagi pemerintahan Indonesia hari ini, indikasi pengebirian demokrasi lewat pernyataan Presiden Prabowo agar rakyat tidak perlu takut akan dilakukannya deforestasi 2 juta Ha untuk lahan sawit yang sebelumnya justru telah banyak menuai kritik keras dari masyarakat, indikasi adanya inkonsistensi keputusan pemerintah mengenai pemenuhan hak atas lingkungan hidup sebagai sebagian dari HAM yang telah konstitusi amanatkan kepada negara melalui Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, juga perilaku pejabat yakni Menteri Kehutanan, Raja Juli yang disorot akrab dengan pelaku perusakan lingkungan (pembalakan).
Menurut Alexander Flor (2018), komunikasi lingkungan adalah penerapan pendekatan komunikasi, prinsip, strategi dan teknik untuk pengelolaan dan perlindungan lingkungan (Ronianysah et al., 2023). NGOs sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki fungsi untuk memainkan peran komunikasi lingkungan, salah satunya yaitu untuk mengangkat isu lingkungan ke media agar mendapat perhatian publik. Kehadiran NGOs juga membantu memastikan bahwa kebijakan pembangunan memperhitungkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Rahman et al., 2023). Dalam konteks ini, NGOs juga ada untuk bertindak sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Rahman et al., 2023).
Di sisi lain, pemerintah sebagai stakeholder sekaligus decision maker juga memiliki fungsi dan peran dalam komunikasi lingkungan salah satunya yaitu untuk menjembatani kepentingan ekonomi (investasi) dengan kepentingan ekologi (keberlanjutan). Namun dalam isu deforestasi ini, melalui data-data yang WALHI tampilkan, peran tersebut justru terindikasi hanya menjembatani kepentingan ekonomi pemerintahan saja dan melupakan kepentingan ekologi (keberlanjutan).
Rumusan Masalah