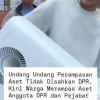Suatu hari saya berbincang dengan seorang teman. Dia penulis buku yang juga sedang bekerja di bidang kreatif pada sebuah perusahaan swasta. Saat mengobrol, wajahnya terlihat murung bahkan dahinya seringkali berkerut. Sembilan puluh persen isi dari diskusi siang itu adalah keluh kesah yang ia rasakan di kantornya. Bukan tentang teman yang toxic, atau gaji yang belum sampai UMR. Tapi ini tentang atasan baru yang berbeda visi dengannya.
Sebagai seorang yang pernah kuliah di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI), teman saya ini sangat gigih sekali dalam menerapkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam setiap materi publikasi yang dibuat oleh perusahaan. Namun bak cinta bertepuk sebelah tangan, hal itu tidak diamini atasan barunya. Menurutnya, lebih baik menggunakan bahasa yang sudah umum di masyarakat. Meski tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), yang penting masyarakat mengerti, katanya.
Usut punya usut, ternyata atasannya memang tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang bahasa. Ditambah dengan sikap yang menurut teman saya sedikit otokratis. Perusahaan itu memang aneh, karena menempatkan seorang karyawan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengalaman apalagi keahliannya. Kondisi teman saya dengan atasannya seperti minyak dan air yang secara logika sulit menyatu.
Saya, meski kuliahnya di jurusan Desain Komunikasi Visual, dan tidak lebih canggih pemahaman bahasa Indonesianya jika dibanding teman saya yang sebentar lagi akan meluncurkan buku keduanya itu, tapi punya paham yang sama bahwa bahasa Indonesia harus terus dilestarikan dengan berpedoman pada KBBI dan PUEBI. Caranya, yakni sebisa mungkin dalam setiap karya yang kita buat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Misalnya saat menulis artikel, membuat materi presentasi, atau bahkan hal kecil seperti mencetak spanduk untuk kegiatan bersama warga.
Cukup disayangkan memang, di era digital yang serba cepat banyak pembuat konten yang abai akan hal ini. Entah disengaja atau tidak. Kalau diingat-ingat, dulu kita melihat kesalahan penulisan hanya sebatas pada toko-toko kecil, warung-warung pinggir jalan. Misalnya ada tulisan "Jual Sepedah" yang seharusnya adalah "Jual Sepeda". Atau "Rumah Ini Di Kontrakan", yang seharusnya menjadi "Rumah Ini Dikontrakan". Tapi sekarang, kesalahan penulisan dilakukan oleh pemilik akun media sosial dengan jumlah pengikut yang banyak.
Pembuat konten yang membuat materi publikasi tanpa memperhatikan kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar bisa disebut sebagai bagian dari fenomena liberalisme bahasa, terutama pada konteks dunia digital. Secara umum, liberalisme bahasa merujuk pada kebebasan berlebih atau tanpa batas dalam menggunakan bahasa, seringkali mengabaikan aturan, kaidah atau norma yang berlaku. Ini bukan liberalisme dalam pengertian ideologi politik, melainkan ke arah kebebasan dalam penggunaan lingusitik.
Saat menonton video di YouTube bersama anak-anak misalnya, saya sering melihat penulisan judul video yang tidak tepat penggunaan huruf kecil dan kapitalnya. Para pembuat konten seperti memiliki kecenderungan untuk mengabaikan kaidah tersebut, entah demi efisiensi atau karena ketidaktahuan.
Mengapa kesalahan penggunaan bahasa yang marak dilakukan pada era digital ini termasuk liberalisme bahasa? Karena ada kebebasan yang diambil dalam penggunaan bahasa yang menyimpang dari norma atau kaidah yang sudah ditetapkan. Meski tujuannya untuk komersial atau kreatif, konsekuensinya adalah penyebaran bentuk bahasa yang tidak sesuai dengan KBBI atau PUEBI kepada khalayak luas.
Apakah fenomona liberalisme bahasa ini berbahaya? Ketika praktik ini makin merajalela, terutama oleh pembuat konten atau influencer yang memiliki banyak pengikut, ada beberapa bahaya bagi kemurnian pedoman bahasa Indonesia, yaitu:
a. Masyarakat, terutama Gen Z atau Gen Alpha akan terbiasa melihat dan menggunakan bahasa yang tidak sesuai kaidah, sehingga norma-norma bahasa baku akan menjadi luntur.