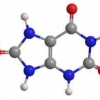[caption id="attachment_233462" align="aligncenter" width="620" caption="Andi Mallarangeng/Lucky Pransiska (Harian Kompas)"][/caption] Sebagai wartawan, bentakan atau hardikan sudah biasa. Pukulan pun siap saya terima. Di masa Orde Baru, ada seorang Jenderal bernama Feisal Tanjung (di manakah dia sekarang?) yang biasa menghardik wartawan "Taik kau!" kalau kepepet tidak bisa menjawab pertanyaan. Kami, para wartawan, biasa mafhum atas ucapan jenderal bintang empat ini, sebab kami selalu menganggap isi kepalanya sama dengan apa yang diucapkannya, hahaha.... Ya, itu sekadar menghibur diri karena kalau diladeni kita bisa ditembak mati di tempat. Di panggil ke ruangan tertutup oleh menteri untuk sekadar dimaki-maki pun pernah saya alami, yang kelak saya ceritakan dalam serial "SAYA DAN ...." lainnya. Kalau di lobi hotel di Helsinki ini saya dipanggil untuk mendekat dengan nada yang tidak biasanya, itu saya anggap panggilan "mesra" saja. Bahwa di sana sudah banyak kerumunan, saya pun sudah siap. Toh Feisal Tanjung biasa menghardik "Taik kau!" juga di depan kerumunan orang banyak. Jadi, saya langsung saja mendekat dengan kedua tinju terbenam di dalam saku jaket. "Hallo, selamat pagi semua," sapa saya kepada kerumunan. Andi Mallarangeng berwajah tegang dan hal yang tersulit dilakukan baginya saat itu adalah menyembunyikan rasa geramnya. "Kenapa kamu bikin berita itu?" sambarnya tanpa berbasa-basi. Dalam hati, berita yang saya bikin kemarin itu sudah "bereaksi" seperti kerja kimia dan kalau itu gas air mata, sudah banyak orang yang tersengat merasakan pedih di mata. Saya langsung menjawab dengan suatu upaya yang paling sulit saya lakukan sepanjang hidup saya, "memanis-maniskan wajah" (bukankah wajah saya sudah cukup manis?). "Loh, kemarin 'kan Pak Andi tidak bilang itu 'off the record' atau 'background', jadi saya anggap itu informasi penting," jawab saya. Dan Andi menyambar lagi, "Iya tapi bukan untuk berita, itu informasi buat kita-kita saja!" Got it! pikir saya. "Informasi buat kita-kita" menjadi kalimat kunci yang saya pegang. Saya merasa menjadi Einstein kedua atas kecepatan berpikir saya dan menemukan jawaban kala itu. "Saya tidak mau informasi itu sekedar 'buat kita-kita', saya mau informasi penting ini untuk orang banyak, jangan hanya kita-kita. Orang-orang berhak tahu." Andi Mallarangeng terlihat mulai berpikir. Orang sepert Eep, Muhaimin, Dimly, Meutia, dan Anas tidak banyak bereaksi, mereka menyimak dan bisa memaklumi percakapan antara narasumber yang geram dengan wartawan yang nakal di depan mereka. Kecuali Widjanarko Puspoyo yang menunjukkan raut tidak senang dengan apa yang saya lakukan. "Payah nih wartawan," celetuknya sambil menjauh. (Kelak di kemudian hari saya baru paham ternyata Widjanarko seorang yang "payah banget", sepenggal hidupnya harus dihabiskan di penjara kena cokok aparat akibat korupsi besar-besaran dan makan uang rakyat di Bulog yang dipimpinnya. Saat penggerebekan, aparat menemukan gepokan dollar Amerika yang disimpan dalam beberapa ember di WC-nya, yang tidak keburu dibawa pergi, itu baru sebagian kecil dari uang rakyat yang ditilapnya. Naudzubillah...). Saya tidak berurusan dengan Widjanarko yang bagi saya dia sudah menunjukkan sikap "alergi" atau "antiwartawan" karena mungkin sudah berpikir suatu waktu dia akan berurusan dengan wartawan yang mengejarnya sampai ke jeruji tahanan. Saya harus membesarkan diri sendiri bahwa Widjanarko sebagai "kecil" saja karena selama ini saya biasa berhadapan dan jalan dengan bigboss-nya di partai, Megawati Soekarnoputri (kelak saya akan mempostingkan serial jurnalistik SAYA DAN MEGAWATI di lain kesempatan). Kembali ke lobi hotel di Helsinki, saya menunggu reaksi dan jawaban Andi...
Dinginnya cuaca Helsinki pagi itu sudah menulang, tetapi suhu di balik jaket tiba-tiba memanas atas peristiwa ini, di mana Andi Mallarangeng masih belum bisa mengelabui rona wajahnya. Raut mukanya yang “smiling face” dan bersahabat tiba-tiba menguap cepat dan belum kembali ke wujud semula. Saya pikir, wajarlah Andi marah sedemikian hebat, yang pasti melupakan persahabatan yang terjalin sedemikian erat. Dia mungkin lupa, sebulan sebelum berangkat ke Finlandia, saya menulis sosoknya di Harian Kompas edisi 15 Februari 1999 dengan judul “Andi Mallarangeng, Terkenal Berkat Mendalami Ilmu Kering”. Setidak-tidaknya kiprah Andi di rubrik Sosok itu telah membuatnya menjadi lebih dikenal. Tentulah pertimbangan ini akan tertutupi amarahnya sendiri. (Sekadar intermezzo, naskah buku “Menulis 36 Sosok” yang saya susun saat ini sedang dalam proses diterbitkan oleh Penerbit Buku Kompas, di mana saya memasukkan Andi Mallarangeng sebagai 1 dari 36 sosok inspiratif yang saya tulis di rubrik “Sosok” Harian Kompas. Seluruhnya ada sekitar 60 sosok yang pernah saya tulis). Di Helsinki dengan kemarahan Andi Mallarangeng yang belum jua reda, saya siap dengan segala risiko yang bakal menimpa, dengan segenap argumen yang saya punya. Tidak ada cara lain. Kalau pun dia mulai main fisik, saya takkan pernah membalasnya. Ini risiko sebuah pekerjaan, terlebih lagi risiko kerja jurnalistik. “Kamu tahu, Pak Rudini marah besar atas berita itu dan barusan dia menelepon saya,” Andi mengabarkan sesuatu yang menarik lainnya. Pikiran jurnalistik nakal saya kembali meloncat-loncat di kepala. Ehem... bukankah ini berita asyik lainnya? Bocoran yang tak kalah penting dan menariknya dari yang kemarin: Pak Rudini menelepon Andi Mallarangeng dan marah-marah atas berita yang saya buat. Ini berita! Rudini yang disebut-sebut Andi Mallarangeng adalah Ketua KPU wakil parpol MKGR, sebuah partai yang dibentuknya. Dia mantan Menteri dalam negeri periode 1988-1993 sebelum kemudian digantikan Jogie S Memet. Entah apa pertimbangannya, Presiden Soeharto selalu mengangkat pembantunya sebagai menteri dalam negeri dari kalangan militer, khususnya para pensiunan jenderal. Sebelum Rudini seingat saya ada Jenderal Amir Machmud. Setelah pensiun sebagai menteri dalam negeri, Rudini “turun gunung” ke kancah politik melihat peluang keterbukaan yang ditawarkan Reformasi. Saya ingat, kala itu para jenderal membuat partai baru berkat terbuka lebarnya kran demokrasi pasca reformasi itu. Seperti tidak terbendung. Jenderal Edi Sudradjat, misalnya, dengan sokongan Jenderal Try Sutrisno, mendirikan PKP setelah ia kalah bersaing melawan Akbar Tandjung sebagai Ketua Partai Golkar. Sedangkan Rudini bergabung bersama Mien Sugandhi, mantan menteri di era Soeharto, yang sudah berada di MKGR sebelumnya sebagai sebuah Ormas yang kemudian bermetamorfosa menjadi parpol. Itulah ingatan saya yang tercecer tentang sosok Jenderal Rudini yang konon menurut Andi marah kepadanya gara-gara berita yang saya tulis.
(Bersambung)
Catatan: tulisan bisa diikuti di Nulis bareng Pepih