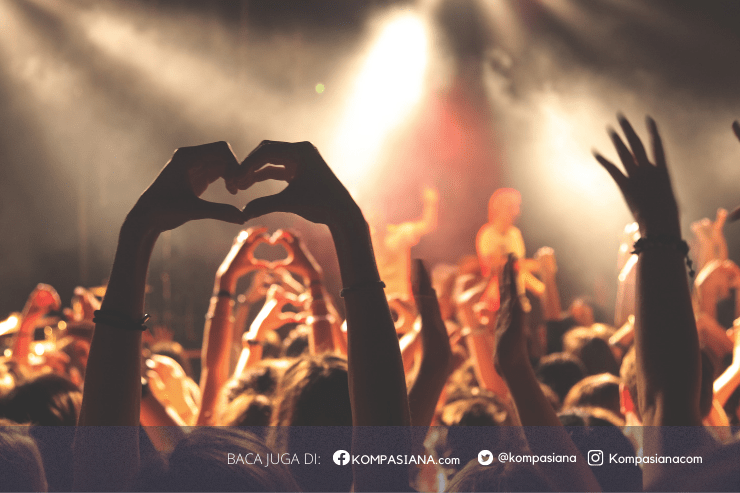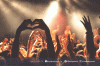Ketika lagu Tabola Bale menggema di Istana Merdeka pada peringatan HUT RI ke-80, suasana yang biasanya khidmat dan penuh tata protokol tiba-tiba berubah menjadi ruang penuh tawa dan tarian. Presiden, pejabat, hingga tamu undangan ikut bergoyang mengikuti irama khas Nusa Tenggara Timur. Fenomena ini tak berhenti di istana --- dunia maya pun ikut menari. Video Tabola Bale viral di berbagai platform media sosial, disukai jutaan orang, ditiru, dan dirayakan sebagai simbol kebahagiaan nasional.
Namun di balik euforia itu, tersimpan makna yang lebih dalam.
Dari Lirik Lokal ke Ruang Nasional
Lirik Tabola Bale dibuka dengan bahasa daerah Nusa Tenggara Timur:
"Lia ade nona makin gaga bikin kaka jadi suka. Dulu ade rambu kepang dua sekarang rambu mera mera..."
Ungkapan sederhana itu menggambarkan kehangatan, keluguan, dan humor khas masyarakat Timur. Lagu ini tidak hanya bicara soal cinta, tapi juga tentang ekspresi budaya yang bebas, cair, dan apa adanya. Saat berpadu dengan bahasa Indonesia dan sedikit logat Minang, Tabola Bale menjelma menjadi simbol keberagaman yang hidup.
Ketika lagu ini dibawa ke jantung kekuasaan negara --- Istana Merdeka --- maknanya pun melebar. Ia tidak lagi sekadar lagu cinta, tapi pernyataan simbolik tentang Indonesia yang bahagia, inklusif, dan penuh energi muda. Negara seolah berkata: "Inilah wajah Indonesia hari ini."
Budaya Populer sebagai Bahasa Politik
Dari kacamata komunikasi kritis, Tabola Bale menunjukkan bagaimana budaya populer bisa menjadi alat politik. Ketika ekspresi lokal diangkat ke panggung nasional, ia tidak hanya merayakan keragaman, tetapi juga menjadi simbol legitimasi politik: gambaran Indonesia yang damai dan bersatu.
Namun, pertanyaan penting muncul: apakah representasi ini sebanding dengan kenyataan di lapangan?
Apakah masyarakat Indonesia Timur yang menjadi sumber inspirasi lagu ini benar-benar merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan yang sama dengan simbol yang mereka wakili?
Antara Pengakuan dan Keadilan



![[publicspeaking] Omongan Pejabat Bukan Sekadar SUARA, Ia Cermin ETIKA Bangsa](https://assets-a2.kompasiana.com/items/album/2025/09/05/chatgpt-image-sep-5-2025-01-27-47-pm-68ba8302ed64151e1c3c86a2.png?t=t&v=100&x=100&info=meta_related)