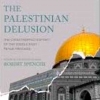Memahami Islam tidak cukup hanya lewat teks, tetapi juga harus memahami konteks. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Kalau kita hanya terpaku pada teks, maka kita akan terjebak pada huruf demi huruf, kehilangan makna yang lebih luas, dan akhirnya mengulang sejarah ke masa lalu. Sebaliknya, kalau kita hanya berpegang pada konteks tanpa teks, maka kita akan meluncur tanpa arah, seperti anak panah yang lepas dari busurnya.
Di sinilah pentingnya jalan tengah: membaca teks sesuai dengan konteksnya. Para kiai di pesantren sudah lama mengajarkan prinsip ini. Ada kaidah terkenal: al-muhafazhatu 'ala al-qadim al-shalih wal akhdzu bi al-jadid al-ashlah---memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil hal-hal baru yang lebih baik. Prinsip ini membuat Islam tetap relevan tanpa kehilangan akar. Dengan demikian, kita tidak terjebak pada dua ekstrem: terlalu literal atau terlalu liberal.
Para ulama pesantren tidak sekadar membaca Al-Quran dan hadis secara tekstual, tetapi juga dengan perangkat ilmu yang kaya: qawa'id ushuliyah dan qawa'id fiqhiyah. Mereka terlatih menyeimbangkan antara wahyu dan akal; teks dan konteks; nash dengan budaya; mantuq (yang tersurat) dan mafhum (yang tersirat); 'azimah (hukum utama) dan rukhshah (keringanan); serta dalalah (makna tekstual) dan maqashid (tujuan syariat). Pola pikir seperti ini melahirkan corak keberagamaan wasathiyah, jalan tengah yang menyejukkan.
Sayangnya, di era digital sekarang, corak keberagamaan semacam itu semakin jarang mendapat tempat. Media sosial lebih sering menampilkan perdebatan hitam-putih, seolah Islam hanya bisa dipahami dengan satu cara saja. Ada yang begitu kaku menafsirkan agama hingga hampir setiap perilaku sehari-hari dianggap "bid'ah" kalau tidak sesuai teks. Di sisi lain, ada pula yang menafsirkan agama terlalu longgar sehingga hampir semua ajaran dianggap bisa dinegosiasikan atas nama kebebasan. Keduanya sama-sama bermasalah, sebab melupakan keluwesan Islam yang kaya tradisi intelektual.
Contoh sederhana bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang menganggap mengikuti sunnah berarti harus 100 persen meniru gaya hidup Nabi Muhammad Saw., mulai dari cara berpakaian, model rambut, sampai makanan. Padahal, jika dipahami dengan kacamata maqashid, sunnah itu lebih kepada meneladani semangat dan nilai, bukan sekadar bentuk luar. Nabi memelihara jenggot bukan karena jenggot itu inti ajaran Islam, tetapi karena saat itu jenggot adalah simbol kerapian dan kewibawaan di masyarakat Arab. Maka, esensi sunnah bukanlah panjang jenggotnya, melainkan menjaga penampilan yang pantas dan terhormat dalam konteks sosial kita hari ini.
Di titik inilah kearifan pesantren penting untuk dihidupkan kembali. Para kiai mengajarkan bagaimana teks suci dipahami tanpa kehilangan pijakan realitas. Islam menjadi agama yang membumi, hadir menjawab problem bangsa, dan tidak asing dengan tradisi lokal. Itulah yang menjadikan Islam di Indonesia bisa tumbuh harmonis berdampingan dengan budaya Nusantara. Tanpa pemahaman kontekstual, agama bisa menjadi kaku dan sulit diterima masyarakat. Tanpa teks, agama bisa kehilangan otoritasnya. Jalan tengah selalu menjadi pilihan terbaik.
Refleksi ini sangat relevan ketika kita bicara soal bangsa Indonesia yang majemuk. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, Indonesia adalah rumah bersama berbagai agama, budaya, dan suku. Memahami Islam secara tekstual saja mungkin akan membuat kita mudah jatuh pada klaim kebenaran tunggal, menutup ruang dialog, bahkan menganggap orang lain salah hanya karena berbeda. Sebaliknya, memahami Islam hanya secara kontekstual tanpa berpijak pada teks suci akan mengikis identitas kita sebagai umat beragama.
Di sinilah pentingnya sikap wasathiyah. Jalan tengah bukan berarti kompromi dangkal, melainkan kemampuan menempatkan teks dan konteks dalam dialog yang sehat. Sikap inilah yang membuat Islam selalu relevan di setiap zaman dan tempat. Tanpa sikap moderat, umat akan terjebak pada polarisasi yang melelahkan. Dengan sikap moderat, umat bisa membangun bangsa yang damai, adil, dan sejahtera.
Tantangan kita hari ini bukan hanya soal memahami teks suci, melainkan juga bagaimana menghadirkan nilai-nilainya dalam kehidupan berbangsa. Islam tidak boleh hanya berhenti di mimbar khutbah atau majelis taklim, tetapi harus menuntun etika sosial, mendorong keadilan ekonomi, serta menguatkan solidaritas kebangsaan. Seperti pesan Al-Quran: "Dan demikianlah Kami telah menjadikan kamu umat yang wasath (moderat), agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas kamu" (QS. Al-Baqarah [2]:143).
Kemerdekaan Indonesia yang kita rayakan setiap Agustus adalah buah dari perpaduan antara doa, perjuangan, dan kearifan membaca konteks. Para ulama, santri, dan pejuang bangsa tidak memisahkan teks agama dari realitas sosial. Mereka berjuang dengan doa, tapi juga dengan strategi politik dan diplomasi. Mereka meneladani Nabi, tapi juga membaca zaman dengan jernih. Dari merekalah kita belajar: memahami teks dan konteks bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan, melainkan dipadukan untuk melahirkan kemaslahatan.
Hari ini, ketika kita berhadapan dengan arus globalisasi, polarisasi politik, dan perubahan sosial yang cepat, pesan itu kembali relevan. Kita tidak boleh hanya terpaku pada teks, tapi juga tidak boleh hanyut dalam konteks. Jalan tengah selalu ada, dan di situlah letak kekuatan Islam Indonesia. Seperti kata pepatah bijak: "Air yang mengalir mengikuti wadahnya, tetapi tetap menjaga kejernihannya." Demikian pula Islam---ia bisa hadir dalam berbagai konteks budaya, politik, dan sosial, tanpa kehilangan kesucian ajarannya.