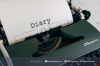Agustus selalu membawa cerita tentang kemerdekaan. Bendera berkibar, lagu perjuangan bergema, dan kisah pahlawan kembali hidup. Namun di banyak pelosok negeri ini, ada satu bentuk “penjajahan” yang belum kita menangkan: krisis air bersih.
Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, pendidikan, kesehatan, bahkan ibadah pun terganggu. Saya merasakan sendiri, sejak kecil, bahwa perjuangan untuk mendapatkan air tak kalah berat dari perjuangan di medan perang.
Masa Kecil: Penampung Air Hujan yang Tak Pernah Cukup
Saya lahir di sebuah desa di lereng gunung. Meski dekat sumber mata air, alirannya justru mengalir ke sungai di bawah lembah, tak pernah singgah di kampung. Di kampung kelahiran, warga mengandalkan satu penampung air hujan besar. Airnya dikumpulkan dari atap rumah dan dialirkan ke tandon bersama. Tapi untuk satu kampung, tentu tidak cukup. Talang air dari sumber sempat dipasang sejauh 6 km, namun debitnya sering kecil, apalagi di musim kemarau.
Jika tandon kosong, warga terpaksa turun ke lembah yang curam untuk mengambil air. Perjalanan itu melelahkan, apalagi sambil memikul ember penuh.
Saya sendiri tak lama tinggal di sana — baru setahun sudah pindah ke kampung lain yang dekat jalan raya. Tapi kami sering kembali ke kampung kelahiran karena punya beberapa kebun, termasuk sebidang lahan yang kelak dibangun masjid jami.
Titik Balik: Sumur Bor yang Menginspirasi
Bertahun-tahun kemudian, saat membangun masjid jami di atas tanah wakaf orang tua, kebutuhan air meningkat drastis. Seorang kawan arsitek menyarankan membuat sumur bor di bawah lembah dan memompanya dengan mesin submersible sejauh hampir 200 meter ke masjid.
Saat pengeboran dimulai, sambutannya luar biasa. Kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, dan warga setempat hadir, menyaksikan proses yang diharapkan bisa mengubah kehidupan mereka. Rasa optimisme itu seperti mengalir bersama suara mesin bor yang bekerja hingga selesai.
Hasilnya memang luar biasa. Air dari sumur bor dan talang berjalan berdampingan. Inspirasi ini menyebar — warga membuat sumur bor lain di beberapa titik, desa tetangga pun ikut meniru. Ada yang mengelola seperti PDAM, ada yang iuran bulanan Rp35–50 ribu, jauh lebih murah dibanding tarif PDAM Rp200–400 ribu.
Pelajaran dari Kegagalan di Kampung Kawan
Dua tahun lalu, daerah kawan saya — terkenal dengan banyak tumbuhan koyal — dilanda kekeringan. Kami membentuk panitia penanggulangan dan memutuskan membuat sumur bor di dua titik. Sayangnya, keduanya gagal total. Air tak keluar sama sekali, padahal biaya sudah keluar besar.
Evaluasi menunjukkan titik pengeboran kurang akurat dan mesin yang dipakai hanya semi-manual. Untuk hasil maksimal, dibutuhkan mesin besar. Di kampung itu ada pesantren dengan ratusan santri. Kebutuhan air mereka sangat besar, sementara sumber utama hanya talang air sejauh 5 km yang harus berbagi dengan warga beberapa kampung. Saat musim hujan, mereka mengandalkan panen air hujan sebagai penyelamat.
Kondisi Pesantren Kami Saat Ini
Pesantren kami kini mengandalkan sumur bor untuk kebutuhan utama. Air hujan tetap dimanfaatkan, namun khusus untuk menyiram tanaman pekarangan dan kebun kecil. Cara ini membuat penggunaan air tanah lebih hemat, sambil memanfaatkan setiap tetes hujan yang Allah turunkan.