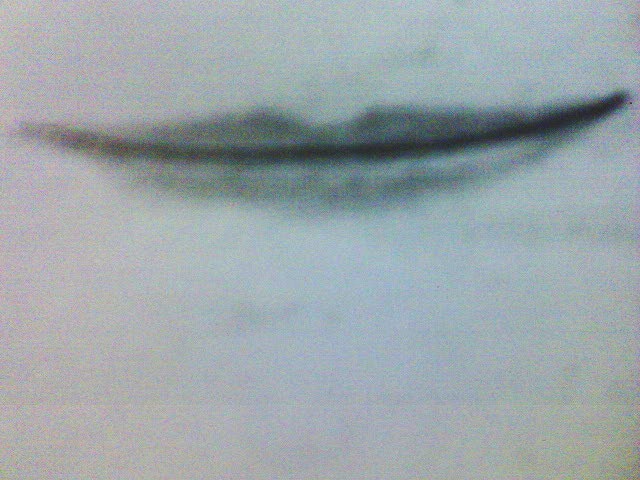Suatu kali di depan kanfas, tangannya memegang kuas yang ditariknya ke atas dibiarkan berlama - lama tergantung, seperti sudah terbiasa atau memang ahli, ia dapat menahan lengannya tak bergerak. Sedang matanya memutar sebidang ruang datar berwarna putih, lalu dibayangkannya sebuah wajah berada di sana, dengan senyum tersungging yang tak mampu dijelaskannya dengan kata - kata.
Di tarik garis lurus dari atas kebawah, digeserkan kuas itu dari kanan ke kiri, hampir saling bersinggungan kedua garis itu ia lalu berhenti, ah terlalu kaku, katanya dalam hati. Kanfas itu digeser, kini tubuhnya dapat nampak dari sudut penonton, tak utuh hanya setengah badan lalu ia kembali mengernyitkan dahi, mencari titik pertemuan antara estetika dan etika melukis dengan dua buah garis yang terlanjur ia gores memanjang, hampir membentuk sebuah gasing yang berpusing.
Tangannya kembali terangkat, matanya kini terpejam begitu dalam. Melukis bukan hanya sekedar imajinasi, ia berfikir lebih dalam bahwa seni bukan sekedar khayalan, matanya semakin dalam tenggelam dalam gelap, tubuhnya tetap tenang, dengan lengan tertahan menggantung di udara.
"Ada apa?"
"Apa kau telah kehilanganku?"
"Tidak aku tidak kehilanganmu!"
"Maksudmu?
"Andai saja"
"Andai saja apa?"
"Andai saja aku kehilanganmu"
"Aku masih di depanmu!"
"Tidak, kau harus pergi, pergi jauh!"
"Kenapa? Apa aku ada salah gerak?"
"Tidak!"
"Kenapa tidak?"
"Tidak!"
"Aku masa depanmu, dan kau memintaku pergi? Jangan bercanda!"
"Kau harus pergi!"
"Kenapa?"
"Hanya dengan kehilanganmu, aku bisa mengenangmu dengan jelas"
~~~~
Apa melukismu itu filosofis, atau kenangannya saja yang membekas, aku tidak ingin mengingatmu tapi mereka memaksaku melukis senyummu, dan kau tau karena kaupun benci pada kekejaman seperti itu. Ia masih dengan mata terpejam, kepalanya menggeleng dengan bibir tersungging teriris sebuah senyum dibibirnya, kemudian ia membuka mata lalu dipandanginya kanfas di depannya, dicarinya bagian yang kurang dari setiap sudut yang tertinggal, meskipun sama sekali tak pernah ia menggaris seraut wajah di sana.
Beberapa saat ia ragu, lalu kemudian badannya ia geser sedikit ke kiri dan kini nampak utuh keraguan itu di depan para penonton. Lirik matanya terganggu oleh seorang lelaki tua yang bergerak memandang arloji di pergelangan tangannya, waktunya hampir habis dan ia masih belum melukis sesuatupun di atas kanfas itu.
~~~~
Bayang wajah itu masih di depannya, tersenyum manis duduk di bangku kosong yang ia minta pada panitia. Beberapa orang mengira ia melukis hantu, seorang yang tak nampak telah duduk di bangku kosong itu. Meskipun begitu ia tetap seorang pelukis profesional, tak peduli ia melukis hantu, pohon, burung, wanita atau melukis sesuatu yang hanya membuat seseorang mengernyitkan dahi, atau berpikir ulang untuk mengunyah dengan baik maksud dari lukisannya. Ia tetap seorang pelukis berkelas dunia yang bertangan dingin membuat seni tak tertandingi dan membuat segala pelukis iri karena merasa dipecundangi, ia tak peduli.
Hari sebelumnya ia mendapat surat undangan, surat berlabel sebuah lembaga seni bergengsi. Ia diminta melukis didepan seratus seniman dunia, yang ia tak kenal dan tak saling mengenal baik di antara satu sama lain, kecuali kemahsyuran dan nama yang teringat. Kini ia berada di depan seratus seniman itu, dan mereka mulai meragukan kemampuannya yang mengguncang nama - nama seniman tua, ragu pada kemampuannya menuangkan imajinasi, ragu pada kemampuan mengendalikan jemari dan kuasnya, dan ia tak peduli.
~~~~
Tidak ada yang tahu menahu ia melukis kenangan, sesosok bayang duduk di depannya, memandanginya, tersenyum, dan mengerlingkan mata padanya. Ia tetap ragu, karena tidak biasa melukis kenangan seperti itu, ia pernah melukis sebuah luka menganga, kenangan masa kecilnya ketika melihat ayahnya mati dengan sabetan pedang di pundak, ia juga pernah melukis air mata, air mata ibunya yang tersimpan di dalam dada ketika ayahnya pergi meninggalkan derita hati tak tertahankan, dan dendam yang tak bisa terbalas seumur hidupnya. Namun kali ini ia ragu pada dirnya sendiri, ia tak bisa melukis kehilangan seperti ia juga tak kuat untuk merasakannya lagi.
Ia kemudian bangkit dari tempat duduknya, memandang sebentar ke bangku kosong di depannya lalu kembali duduk dan mengangkat lengannya ke atas, menahan lama tangannya di udara kemudian melepaskannya di atas kanfas. Perlahan ia seperti membuat sebuah rumah, karena dari arah penonton nampak sinar sorot lampu membuat bagian belakang kanfas seperti menjelaskan apa yang hendak ia lukis, namun perkiraan itu meleset, ia kemudian menggaris ke arah lain membentuk sebuah gugus senja yang muram dengan sepasang camar di atas ombak, penonton tak sabar menunggu hasil, mereka berfikir ia adalah pelukis alam dengan rona jingga yang dipaksa menjadi kelabu, dan kemudian lengannya kembali bergerak, kini seolah membentuk irisan jeruk dan penonton berhasil dibuatnya mengernyit.
Satu jam kemudian ia selesai, dan segera meninggalkan tempat duduknya. Beberapa orang wartawan datang mengerubunginya, didesakan padanya microphone dan pertanyaan - pertanyaan yang melompat keluar dari mulut - mulut koran.
"Apa yang anda lukis itu pak?"
"Sebuah senyum!"
"Apa kau yakin pak?"
"Lalu, apa yang membuatmu ragu?"
"Itu tidak seperti senyum, itu seperti sebuah rumah, sebuah senja dengan rona abu - abu dengan sepasang camar di atas ombak, dan seiris bulan sabit"
"kau benar!"
"Lalu dimana senyum itu pak?"
Lelaki itu hanya tersenyum, ditatapnya sekali lagi wartawan di depannya lalu berkata.
"Di hatiku!"
Wartawan itu mengernyitkan dahi.
"Kenapa begitu pak?"
"Aku sudah mencobanya, melukis senyum itu di atas kanfas!"
"Lalu?"
"Gagal, karena kehilangan tak bisa dilukiskan dengan apapun"
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI