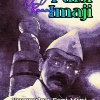Bantul selama ini dikenal sebagai daerah yang penuh dengan cerita muram. Kemiskinan, dan ketertinggalan menjadi problem klasik Bantul dalam konstelasi pergaulan antarwilayah di Jogja. Padahal Bantul menawarkan pesona yang tak kalah menarik ketimbang episentrum Kraton-Malioboro. Selain pantainya yang sambung-menyambung di selatan, Bantul bergeliat dalam kreativitas kriya. Kasongan sebagai sentra industri gerabah dan keramik memang telah mendunia. Tetapi siapa yang tahu bila Bantul memiliki lebih dari itu.
Bersama teman-teman kelas saya berkesempatan menjelajah Bantul, pada satu hari yang cerah di bulan Mei dua tahun lalu. Perjalanan yang tak biasa karena kami tak hendak ke Pantai Parangtritis, Parang Kusumo, atau Samas maupun Krakal, seperti biasa bila kita menyebut obyek wisata Bantul. Kali ini kami akan belajar dari sejumlah sentra seni kriya, berturut-turut Manding, Wukirsari, Tembi, dan Sewon.
Perjalanan dimulai semenjak pagi. Jogja sedang bergembira hari itu. Langit bersih, matahari memancarkan sinarnya cenderung terik. Jalur Jogja-Parangtritis kami lalui dengan meninggalkan petak-petak sawah yang sedang menghijau. Saya tak ingin melepas pandang. Membebaskan angan pada satu mimpi sejak dulu, yang kini harus diimpit pelan-pelan dalam hati. Semenjak pertama kali menjejak pulau ini, hati saya telah kepincut. Pulau ini memberikan kehangatannya bagi seorang pendatang-padahal-bukan seperti saya.
Karena itu pula saya sempat berjanji pada diri sendiri untuk menjadikan Jogja, atau Solo sebagai pangkalan hidup keluarga saya kelak. Setidaknya, di Jawa Tengah, atau paling kurang di Jawa. Meski hari ini saya belum berkesempatan memiliki KTP Jogja atau Solo, saya cukup puas berdamai dengan takdir untuk menjadi warga Jawa Tengah, di bagian paling jauh dari sentrum Mataraman. Tak apa. Setidaknya saya masih dapat menikmati Jogja dan Solo dalam perjalanan pagi itu. Melintasi Bantul.
Saya menghela napas berkali-kali. Sawah tampaknya bukan primadona Bantul, karena di wilayah ini hanya 60% lahannya saja yang produktif dicetak menjadi sawah. Selebihnya perbukitan yang kurang subur. Justru karena itu lanskap Bantul menjadi cantik. Lembah yang hijau rapi oleh jajaran padi, dipagari bukit-bukit yang juga hijau dengan berjenis-jenis pohon. Saya belum puas mengkhayal ketika bus yang kami tumpangi membelok di pelataran parkir kawasan Manding.
Manding tak pernah saya dengar sebelumnya. Dari tanya-tanya dan dengar kiri-kanan saya mendapat sedikit informasi soal sentra kerajinan kulit ini. Manding merupakan andalan industri kecil Bantul yang menyumbangkan Produk Domestik Regional Bruto melalui produksi dan ekspor kulit. Macam-macam jenis kerajinan diproduksi seniman Manding yang memulai usahanya dari kepeloporan tiga pemuda sejak tahun 1947.
Saya sebenarnya cenderung tak menyukai kerajinan tangan. Saya masih kesulitan menikmati keindahan jenis seni satu ini. Terutama karena produknya seringkali dibandrol dengan harga yang melebihi batas psikologis dompet saya. Kebutuhan utama saya masih pada sektor primer, belum pada skema-lanjut berupa kebutuhan aktualisasi diri atau prestise. Saya sudah cukup puas melihat-lihat produk kerajinan pada showroom yang tersebar di seantero desa.
Puas menyambangi Manding kami melanjutkan perjalanan menuju Wukirsari, sentra industri batik tulis Bantul. Untuk tiba di Wukirsari kita dapat menikmati perjalanan yang menyenangkan. Wukirsari berada di sebuah lembah yang dikelilingi perbukitan di semua sisinya. Wukirsari juga dekat dengan Imogiri, tempat dimakamkannya raja-raja Mataram hingga dinasti Ngayogyakarta, Surakarta, Pakualam, dan Mangkunegara. Saya tak menemukan banyak hal menarik di Wukirsari kecuali tiga bungkus ramuan wedang uwuh yang saya beli sebagai buah tangan. Wedang uwuh merupakan minuman hangat yang diperoleh dari seduhan rempah-rempah dan gula batu. Rempah-rempah yang menyerupai sampah, sehingga disebut uwuh; alias sampah dalam bahasa daerah.
Menjelang siang kami meninggalkan SWukirsari menuju Tembi. Tembi kini didesain sebagai desa wisata, menawarkan kerajinan kulit sebagai jualan utamanya. Saat mengunjungi Tembi saya sempat melirik poster Festival Jazz Tembi tahun lewat yang masih ter(di?)tempel pada dinding joglo Tembi. Saya menggumam dalam hati, tampaknya Tembi telah melangkah lebih jauh dari sentra industri kerajinan menjadi desa wisata sesungguhnya. Mungkin jazz bukan janis musik yang dimengerti masyarakat Tembi, namun setiap pertunjukan seni dan budaya sudah sepantasnya diapresiasi.
Di Tembi saya hampir saja membeli oleh-oleh untuk istri. Tetapi apa? Saya sama sekali tak berpengalaman membelikan oleh-oleh kepada orang lain. Beberapa kali saya membeli oleh-oleh dan tampaknya gagal menjadi buah tangan yang menggetarkan bagi penerima. Sampai hari ini saya berkesimpulan bahwa saya tak perlu membeli oleh-oleh, kalaupun istri saya menginginkannya, kapan-kapan saya akan mengantarkannya saja ke tempat oleh-oleh itu dapat dibeli. Saya kira ini mekanisme paling baik bagi orang tak-paham-seni macam saya.
Manding sudah, Wukirsari telah didatangi, Tembi kemudian kami tinggalkan menuju sentra industri batik lurik di bilangan Sewon. Sesaat sebelum tiba saya berkesempatan melewati satu bangunan persegi di perempatan kecil Krapyak. Beberapa teman bertanya pada guide yang mendampingi kami. Tiga orang guide yang kesemuanya orang Bantul itu menggeleng: kami juga sebenarnya tidak tahu itu bangunan apa. Mungkin Ka’bah-nya Bantul. Saya tersenyum dalam hati. Pastilah bangunan serupa benteng itu adalah Panggung Krapyak, panggung yang digunakan raja-raja Mataram untuk membidik hewan buruan yang sebelumnya dengan susah payah digiring prajurit mendekati panggung. Itulah enaknya menjadi raja, mau berburu saja tinggal duduk manis di atas panggung mengarahkan bidikan pada hewan yang didesain berkeliaran di bawahnya. Saya mengkhayal, bila raja sedang jenuh oleh persoalan intrik yang membayang kraton, bolehlah satu dua anak panah dilesatkan pada prajurit yang lugu atau pintar-namun-sok. Biar tahu rasa. Siapa tahu. Dan itulah enaknya menjadi raja.