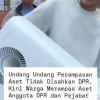Polemik pembiayaan proyek Kereta Cepat Indonesia--China kembali mencuat setelah pemerintah dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara saling melempar tanggung jawab atas tumpukan utang yang menjerat proyek tersebut.
Saya memiliki perspektif lain.
Masalah utama proyek kereta cepat bukan semata pada utang atau mekanisme pembiayaan, melainkan pada cara negara mengelola ruang kekuasaannya. Hudalah, Talitha, dan Lestari dalam artikel Pragmatic State Rescaling: The Dynamics and Diversity of State Space in Indonesian Megaproject Planning and Governance menjelaskan bahwa negara sering menyesuaikan skala kekuasaannya secara pragmatis untuk merespons tekanan politik dan ekonomi jangka pendek. Proses reskalasi ini melahirkan ambiguitas peran antara pemerintah pusat dan lembaga semi-otonom seperti BPI Danantara. Ketika negara memperluas intervensinya tanpa membangun kapasitas kelembagaan yang sepadan, tanggung jawab menjadi kabur. Akibatnya, otoritas politik tetap berada di tangan pusat, sementara beban administratif dan risiko keuangan dialihkan ke lembaga pelaksana.
Pergeseran tanggung jawab semacam ini bukan fenomena khas Indonesia semata. Liliana Andonova dan Ronald Mitchell dalam artikel The Rescaling of Global Environmental Politics menunjukkan bahwa dalam konteks global, desentralisasi tanggung jawab tanpa koordinasi yang jelas sering menimbulkan kekosongan akuntabilitas. Pola ini terlihat pula dalam proyek kereta cepat: pemerintah mempertahankan posisi simbolik sebagai pengarah pembangunan, tetapi pelaksanaan diserahkan kepada lembaga yang tidak memiliki kekuatan politik memadai untuk mengelola konsekuensinya. Dalam kondisi seperti ini, negara tampak kuat secara formal, namun lemah dalam dimensi substantif pengelolaan kekuasaan.
Bob Jessop melalui karya Capitalism and Its Future: Remarks on Regulation, Government and Governance menguraikan bahwa kapitalisme modern mendorong negara untuk bergeser dari peran penyedia menjadi pengarah, dari government ke governance. Pergeseran tersebut menyebabkan tanggung jawab publik tersebar di berbagai aktor yang tidak selalu memiliki legitimasi setara. Dalam situasi ini, koordinasi menjadi krusial, namun justru sering diabaikan. Pemikiran ini berkelindan dengan pandangan Susana Borrs dan Jakob Edler dalam The Roles of the State in the Governance of Socio-Technical Systems' Transformation, yang menegaskan bahwa negara harus mampu menyeimbangkan dua peran sekaligus: sebagai motor perubahan dan sebagai penjamin keadilan dalam proses transisi. Ketika keseimbangan itu gagal dijaga, negara kehilangan arah, dan kebijakan publik yang dihasilkan menjadi inkonsisten serta tidak efektif.
Kondisi tersebut sejalan dengan pengalaman Indonesia dalam proyek infrastruktur lainnya. Jamie S. Davidson melalui tulisan Driving Growth: Regulatory Reform and Expressways in Indonesia mencatat bahwa proyek jalan tol sering kali gagal karena lemahnya koordinasi antarlembaga. Ia menunjukkan bahwa negara kerap terjebak pada logika komando tanpa mekanisme kolaborasi yang efektif. Dalam konteks serupa, Hendrik Sandee dalam Improving Connectivity in Indonesia: The Challenges of Better Infrastructure, Better Regulations, and Better Coordination menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur nasional menghadapi hambatan utama berupa tumpang tindih regulasi dan ego sektoral antarinstansi. Jika dua pandangan ini diletakkan berdampingan, kita bisa melihat pola berulang: negara ingin mempercepat pembangunan, tetapi justru terhambat oleh kelemahan institusionalnya sendiri.
Siwage Dharma Negara, dalam tulisannya Indonesia's Infrastructure Development under the Jokowi Administration, menyoroti bagaimana strategi percepatan pembangunan di era Jokowi berhasil mendorong investasi besar-besaran, namun mengabaikan kesiapan administratif dan fiskal. Pemerintah mengutamakan kecepatan realisasi proyek, tetapi tidak membangun fondasi kelembagaan yang kokoh untuk mengelola kompleksitasnya. Lembaga seperti BPI Danantara pun menjadi "penyangga risiko", menanggung konsekuensi dari keputusan yang diambil oleh otoritas yang lebih tinggi. Temuan ini sejalan dengan analisis Yifan Qiu, Haibo Chen, dan Zhibin Sheng dalam Governance of Institutional Complexity in Megaproject Organizations, yang menegaskan bahwa semakin banyak aktor terlibat dalam proyek besar, semakin besar pula risiko disfungsi jika koordinasi dan mekanisme pengawasan tidak diperkuat.
Gambaran ini semakin jelas ketika dikaitkan dengan pandangan J. Samuel Barkin dalam bukunya International Organization: Theories and Institutions. Barkin menjelaskan bahwa negara modern beroperasi di bawah dua tekanan yang saling bertentangan: mempertahankan kedaulatan politik sekaligus memenuhi tuntutan efisiensi ekonomi global. Proyek kereta cepat Indonesia--China berada di tengah ketegangan itu. Ia dirancang sebagai simbol kemandirian nasional sekaligus instrumen diplomasi ekonomi. Namun, ketika dua kepentingan tersebut tidak diseimbangkan dengan baik, negara justru terjebak dalam dilema: berdaulat secara simbolik, tetapi rentan secara fiskal.
Analisis ini memperlihatkan satu benang merah: kegagalan proyek besar bukan semata akibat kesalahan teknis, melainkan karena ketidaksinambungan antara desain kekuasaan dan kemampuan kelembagaan untuk mengelolanya. Bob Jessop menegaskan bahwa peralihan dari sistem pemerintahan berbasis kontrol menuju tata kelola berbasis kolaborasi memerlukan disiplin institusional yang kuat. Namun, seperti diingatkan Davidson, reformasi kelembagaan di Indonesia sering berhenti di level wacana tanpa perubahan substansial di tingkat praktik. Akibatnya, lembaga semi-otonom seperti BPI Danantara beroperasi dalam wilayah abu-abu: menanggung beban keputusan tanpa memiliki otoritas penuh untuk menentukannya.
Dengan demikian, polemik pembiayaan proyek Kereta Cepat Indonesia--China tidak hanya menggambarkan pertikaian administratif antara dua institusi, tetapi juga memperlihatkan arah evolusi kekuasaan negara di era kebijakan publik yang semakin kompleks. Megaproyek semacam ini menuntut lebih dari sekadar investasi dan infrastruktur fisik; ia membutuhkan tata kelola yang mampu mengintegrasikan tanggung jawab, transparansi, dan kolaborasi. Saya ingin mengutip kembali tulisan Hudalah, Talitha, dan Lestari menutup refleksi mereka dengan satu gagasan yang relevan bagi konteks ini: megaproyek selalu menjadi ruang uji bagi negara untuk membuktikan keseimbangan antara ambisi politik dan kapasitas kelembagaan.
Dalam konteks itu, proyek kereta cepat bukan hanya soal transportasi cepat antarkota, tetapi tentang bagaimana negara belajar menata kekuasaannya agar tidak berhenti pada simbol kemajuan, melainkan menjadi cermin kedewasaan dalam mengelola tanggung jawab publik.