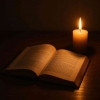"Murid Tiri: Ketika Hanya Jadi Catatan Pinggir Kurikulum"
Apa yang akan kau lakukan jika seorang anak kecil berdiri di depan kelas, memandangi papan tulis, tapi huruf-huruf di sana menari dan membingungkannya?
Apa yang akan kau pilih, saat seorang murid tak bisa diam di kursinya, bukan karena nakal tapi karena otaknya bekerja begitu cepat, begitu sibuk hingga dunia sekitarnya jadi terlalu lambat untuk diikuti?
Nama saya Imam Setiawan.
Saya seorang guru, aktivis pendidikan inklusi, dan seorang penyandang disleksia dan ADHD.
Saya tahu persis rasanya menjadi murid tiri dipinggirkan, dilupakan, dianggap beban hanya karena cara belajar saya berbeda.
Sudah lebih dari 15 tahun saya mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus. Saya melihat dengan mata kepala sendiri: mereka tidak butuh dikasihani. Mereka hanya ingin dimengerti. Tapi sayangnya, mereka sering tidak dianggap. Ditinggalkan dalam sistem pendidikan yang sibuk mengejar angka, akreditasi, dan kurikulum yang katanya merdeka, padahal justru membelenggu anak-anak seperti mereka.
Saya pernah diundang memberi pelatihan pada lebih dari 100 guru di sebuah kabupaten terpencil, di luar Pulau Jawa. Karena keterbatasan jarak, saya membuat aplikasi sederhana. Tujuannya: agar setelah pelatihan, para guru tetap bisa saya dampingi dalam menangani anak-anak dengan kebutuhan khusus. Saya buatkan folder-folder khusus: satu guru, satu folder, tempat mereka bisa mencatat perkembangan siswa, bertanya, atau sekadar berbagi cerita.
Tapi, berminggu-minggu kemudian, semua folder itu masih kosong.
Tak satu pun terisi.
Saat saya tanya mengapa, sebagian besar guru menjawab:
"Kami masih sibuk menyusun kurikulum deep learning, pak."
"Kami sedang mengejar program kementerian."
"Yang kami kerjakan ini lebih penting dulu daripada urusin satu anak ABK."
Saya diam. Hati saya tercekat.
Anak-anak yang saya perjuangkan anak-anak yang selama ini dianggap "aneh", "pemalas", atau "tidak bisa diajar" sekali lagi ditinggalkan. Seperti biasa.
Mereka murid tiri.
Padahal menurut data Kemdikbudristek (2022), diperkirakan ada lebih dari 1,6 juta anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Dan hanya sekitar 18% yang teridentifikasi dan mendapat penanganan yang layak.
Sisanya?
Hilang dalam statistik. Tersisih dalam sistem.
Sebuah penelitian dari Yale Center for Dyslexia & Creativity juga menyebutkan, disleksia bukanlah tanda ketidakmampuan, tapi perbedaan dalam cara otak memproses informasi.
Anak-anak disleksia sering punya kekuatan luar biasa dalam berpikir visual, kreativitas, dan pemecahan masalah. Tapi jika guru hanya fokus pada nilai, ejaan, dan lembar jawaban pilihan ganda kapan mereka punya ruang untuk menunjukkan kemampuannya?