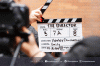Sejak tahap prolog Pengepungan di Bukit Duri (2025), sang sutradara, Joko Anwar, langsung menampilkan montase kesengsaraan yang perlahan mengerucut pada satu gambar: Edwin remaja terkulai lemas menatap rumahnya yang hangus terbakar, wajahnya tertutup jelaga, tubuhnya gemetar dalam tangis serak memanggil-manggil orangtuanya. Potret derita total ini menjadi isyarat awal bahwa film ini akan mengikuti kisah seorang penyintas kekerasan rasial yang tumbuh dalam sistem sosial yang menindas. Artinya, Joko menempatkan "korban" sebagai poros utama narasi. Ini adalah sebuah pendekatan bercerita yang oleh Roy Brand dalam "Identification with Victimhood in Recent Cinema" (2008) disebut sebagai rhetoric of victimhood.
Frasa itu terbagi dua kata: 'retorika' dan 'korban'. Retorika, kata Aristoteles, adalah seni berbicara untuk membujuk dan meyakinkan audiens (persuasi) dengan memperhatikan logos (logika), pathos (emosi), dan ethos (etika/kredibilitas). Aristoteles menyebut retorika bersifat universal (tidak terikat pada satu subjek keilmuan), namun pada masanya, seni retorika digunakan untuk memoles pidato pengadilan, pidato politik, hingga pidato seremonial.
Sementara 'korban', definisi yang ditawarkan Peter Utgaard terasa paling relevan (dalam konteks Pengepungan di Bukit Duri). Menurutnya, seseorang atau sekelompok orang hanya dapat disebut korban jika memenuhi dua syarat: pertama, mereka menjadi sasaran dari tindakan dengan niat menyakiti. Kedua, penderitaan yang dialami tidak layak ditimpakan kepada mereka (undeservedness). Status korban harus lahir dari adanya agresi atau niat jahat yang jelas dari pihak lain, sehingga ia (status korban) tidak dapat diklaim begitu saja.
Maka, rhetoric of victimhood dalam sinema dapat dipahami sebagai strategi penceritaan yang secara sadar membentuk karakter atau kelompok tertentu -- beserta konteks sosialnya -- sebagai korban, demi membangkitkan simpati, empati, bahkan solidaritas dari penonton. Senjata persuasinya ada dalam bentuk narasi (karakter, plot) dan sinematik (editing, suara, sinematografi, mise-en-scne) yang dirangkai sedemikian rupa untuk "merayu" penonton.
Praktik 'retorika korban' dalam film kerap terbaca melalui penggunaan bahasa atau penyampaian cerita dramatis nan menyentuh yang bertujuan memantik rasa simpati atau belas kasihan terhadap karakter atau sekelompok karakter yang dianggap (atau, dipilih) sebagai korban dalam cerita. Retorika ini sering kali menyoroti penderitaan, kerugian, atau ketidakadilan yang dialami oleh korban untuk mempengaruhi emosi audiens.
Tentu, Joko bukan orang pertama yang mengadopsi narasi model begini. Dalam esai yang sama, Brand mengutip kritikus sastra Tzvetan Todorov yang mencatat, sejak pertengahan abad ke-20 telah terjadi pergeseran paradigma naratif dalam budaya populer: dari kisah-kisah heroik yang mengidealkan komunitas sendiri, menjadi kisah-kisah melankolis yang berfokus pada penderitaan dan posisi sebagai korban.
Todorov memang tidak secara spesifik bicara film, melainkan tren kultural dalam narasi secara umum -- khususnya budaya barat. Tetapi pernyataannya bergema dalam praktik sinema global, termasuk Indonesia. Jika dalam narasi klasik pahlawan adalah sosok yang menaklukkan musuh (tak lepas dari pengaruh perang dunia), dalam sinema kontemporer, pahlawan adalah mereka yang bertahan hidup sambil membawa luka. Dengan kata lain, 'korban' sering kali menjadi hero of the story.
Dalam perjalanan sinema nasional, sosok korban selalu punya ruang tersendiri dalam narasi. Dari film-film patriotik era Usmar Ismail, film-film religi Chairul Umam, sampai film-film seksploitasi (yang seringnya membingkai perempuan sebagai korban) dengan judul-judul sensasional, pernah menyematkan atau memanfaatkan figur korban untuk tujuan tertentu. Beberapa menampungnya dengan penuh sensitivitas sebagai penggerak utama cerita, lainnya sebagai karakter pasif yang menanti sang 'penyelamat' datang. Sisanya, tak jarang, sebatas subjek yang dieksploitasi habis-habisan dalam rangka mengemis air mata (atau bahkan dalam semangat memantik berahi penonton).
Sementara Joko, secara filmografi, sebenarnya cukup konsisten menampilkan korban sebagai poros konflik, seperti dalam Pintu Terlarang (2009), Modus Anomali (2012), A Copy of My Mind (2015), Perempuan Tanah Jahanam (2019), hingga Siksa Kubur (2024). Dalam deretan film tersebut, korban merupakan pintu masuk menuju kehidupan sosial yang traumatik dan sistemik. Tetapi bukan hanya korban. Dalam deretan film-film itu juga ada kekhasan berulang yang terbaca, yaitu: ruang (chamber) dan kekerasan (violence). Dalam Siksa Kubur, misalnya, ruang-ruang seperti pesantren, panti wreda, hingga liang lahat bukan sekadar latar, tetapi juga cerminan konflik sosial dan spiritual. Sementara unsur kekerasan, tampil frontal dan kerap menyimpan tafsir sosial yang kompleks -- menciptakan ketegangan antara ngeri dan kagum.
Namun ironisnya, dalam banyak praktik representasi, kemunculan korban tak selalu menjamin mereka benar-benar "berbicara". Gayatri Spivak, dalam "Can the Subaltern Speak?" (1988), menyatakan suara-suara kaum subaltern (kelompok masyarakat yang termarginalkan dan tertindas -- sering kali karena identitas mereka) yang tersebar dalam gaung-gaung masyarakat merupakan suara-suara yang seolah-olah sebagai representasi kepentingan kaum subaltern, padahal nyatanya hanyalah kepentingan dominasi yang hegemonik. Maka, meski Pengepungan di Bukit Duri tampak memberi ruang bicara bagi korban, kita juga perlu bertanya: atas nama siapa suara itu dimediasi? Dan, apakah korban memang benar-benar "berbicara" atau sekadar menjadi wajah sedih yang diperagakan dalam montase kekerasan?
Di sisi lain, dalam masyarakat visual seperti sekarang, film Joko juga bersinggungan dengan apa yang oleh Guy Debord disebut sebagai spectacle -- pertunjukan sosial yang menenggelamkan makna dalam citra (The Society of Spectacle, 1967). Kekerasan dan penderitaan yang ditampilkan, yang jadi salah satu ciri khas rhetoric of victimhood, alih-alih memperkuat empati, bisa tergelincir menjadi komoditas tontonan semata. Pandangan Guy Debord ini sejalan dengan pendapat Susan Sontag dalam "Regarding the Pain of Others" (2003) yang mengingatkan bahwa paparan berulang terhadap gambar penderitaan justru bisa menumpulkan empati atau bahkan menimbulkan kenikmatan estetis atas luka orang lain.
Dari sana, Pengepungan di Bukit Duri dapat diterjemahkan bukan hanya sebagai kisah tentang korban kekerasan rasial, tetapi sebagai refleksi tentang bagaimana 'korban' itu dihadirkan -- baik sebagai tokoh maupun sebagai representasi. Tapi, Sebelum menyelami lebih jauh bagaimana film ini membangun narasi tentang 'korban' dan 'kekerasan', penting untuk terlebih dahulu memahami intensi ideologis sang sutradara atas film terbarunya ini.
Peringatan dari Joko Anwar
Sastrawan Rosihan Anwar pernah mengkritik banyak dari film Indonesia hanya menyuguhkan tontonan basic yang simplistik -- atau, sebut saja menyederhankan realitas -- dengan mengeskploitasi sensasi-sensasi dasar manusia (horor, seks, juga kekerasan). Jejak-jejak eksploitasi sensasi itu bahkan bisa kita rasakan sampai sekarang. Banyak di antaranya mewujud dalam genre horor.
Dalam Pengepungan di Bukit Duri, meski dipenuhi adegan kekerasan, Joko menolak menggunakan sensasi tersebut sebagai alat eksploitasi. Unsur-unsur kekerasan itu disandingkan dengan narasi "bercelah" yang relevan yang menuntut partisipasi aktif dari penontonnya.
Lewat adegan-adegan eksplisit penuh kekerasan verbal dan fisik, Joko tak hanya membingkai kekejaman sebagai tontonan artistik, tapi juga sebagai pengalaman emosional yang mengharuskan penonton turut merasa, terusik, dan berpikir. Joko berupaya menempatkan bioskop bukan sekadar ruang tonton, tapi juga tempat perenungan dan perlawanan atas "lupa kolektif".
Hal ini sejalan dengan pandangan Julian Hanich dalam "The Audience Effect on the Collective Cinema Experience (2018)", bahwa bioskop berpotensi mengubah cara kita memandang, merasakan, dan bereaksi terhadap realitas sehari-hari. Dan, itu yang coba dilakukan Joko lewat Pengepungan di Bukit Duri.
Pendekatan ini punya akar lebih dalam jika ditelusuri lewat sejarah pertemanan dan diskusi kreatif Joko. Sekitar tahun 2007, Joko sempat berdiskusi dengan Edwin -- sutradara Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas (2021). Kala itu, Edwin bercerita kalau film debutnya, Babi Buta yang Ingin Terbang (2008), adalah manifestasi dari serangkaian pertanyaan menyangkut keresahan soal identitasnya sebagai, kata Edwin "keturunan Cina", yang tumbuh dalam bayang-bayang diskriminasi.
Ketika Joko bertanya apakah film itu bisa menjawab kegelisahan identitas tersebut, Edwin tak memberi jawaban pasti. Tapi paling tidak, kata Edwin, proses kolektif pembuatan film telah memberinya semacam ruang terapi, terutama saat ia berbagi pengalaman serupa dengan rekan setimnya, Sidi Saleh. Filmnya sendiri tak sampai menemukan jawaban atas pertanyaan identitas tadi.
Kesadaran akan "ketiadaan jawaban" itu terasa berkelanjutan dalam Pengepungan di Bukit Duri. Seperti Edwin, Joko tidak memberi penjelasan lugas atas musabab kebencian rasial yang menjadi latar cerita filmnya. Ia memilih membiarkan narasi itu menggantung, agar penonton bisa menyusun sendiri rantai kausalitasnya.
Kerusuhan yang tiba-tiba pecah (tanpa eksposisi) itu menyiratkan film ini tidak sedang bicara soal "sebab" dengan gaya didaktis-preachy. Pengepungan di Bukit Duri hadir sebagai proyeksi "akibat", sebagai sebuah peringatan, sebagai sebuah sentilan. Joko menyodorkan distopia sosial, di mana intoleransi, kekerasan, dan pengucilan etnis menjadi bagian dari lanskap hidup yang sudah "jadi".
Dan, seperti Edwin yang menggunakan film sebagai ruang penyembuhan personal, Joko pun, baik secara sadar maupun tidak, memosisikan film ini sebagai ruang trauma bagi penontonnya -- tempat di mana luka sejarah etnis Tionghoa bisa dikenang, dibicarakan, dan "dirasakan" ulang, khususnya bagi generasi yang tak mengalaminya.
Fungsi sosial ini terasa semakin penting ketika Joko menyadari banyak penonton muda -- khususnya Generasi Z -- tidak mengerti isu apa yang coba direpresentasi oleh film ini. Banyak dari mereka, lanjut Joko, tidak tahu tentang kerusuhan 1998. Beberapa bahkan tidak pernah mendengarnya. Maka, film ini tak hanya jadi produk ekspresi artistik, tetapi juga sarana edukasi sejarah, sebab "Kita tidak akan pernah bisa tumbuh sebagai bangsa jika tak mau dan tak berani membicarakan hal-hal sulit seperti ini," kata Joko dalam podcast di kanal YouTube What Is Up, Indonesia? (WIUI).
Melalui film ini, Joko sebenarnya tengah membentuk prosthetic memory (memori buatan) yang memungkinkan generasi yang lahir setelah tragedi untuk turut merasakan dan memahami trauma yang tak mereka alami langsung. Film, dalam hal ini, menjadi alat politik ingatan. Ia bukan hanya menuturkan kembali masa lalu, tapi menghubungkannya dengan krisis yang masih hidup hari ini. Lewat Pengepungan di Bukit Duri, Joko menggunakan film sebagai alat perubahan agar masyarakat keluar dari kesadaran palsu dan mulai memahami sejarah bangsanya sendiri secara lebih kritis.
Di tengah potret negara yang gagal, dunia penuh kekerasan, dan kehancuran moral itu, film ini memberi ruang bagi refleksi penonton akan arah masa depan bangsa. Seperti kata Joko dalam beberapa kesempatan promo filmnya, Pengepungan di Bukit Duri adalah seruan 'peringatan'; tentang apa yang pernah terjadi, tentang apa yang bisa terulang, dan tentang pentingnya merawat ingatan.
Bagian I: World Building
Sebelum melaju ke pembahasan soal 'korban', di bagian pertama ini saya akan terlebih dahulu menelusuri dunia cerita (tempat karakter/korban hidup) serta aturan-aturan yang berlaku di dalamnya. Sehingga di bagian selanjutanya kita dapat lebih memahami posisi 'korban' dalam dunia cerita.
Near Future Republik Preman
Pembedahan atas intensi Joko menunjukkan bahwa Pengepungan di Bukit Duri secara khusus ditujukan untuk penonton Indonesia. Karenanya, perlu bagi Joko untuk menghadirkan realitas rekaan yang akrab bagi target penontonnya: sebuah realitas yang terkonstruksi, mencerminkan pola-pola sosial tertentu, untuk sebuah relevansi. Demi relevansi itu, Joko menghadirkan sebuah lanskap kekerasan dan ketertindasan yang pernah terjadi, atau mungkin, masih terjadi di kehidupan nyata. Singkatnya, kekacauan yang disuguhkan Joko bisa saja terjadi di kehidupan nyata. Ini adalah satu keunggulan yang lekat dengan film-film realisme.
Sejalan dengan rhetoric of victimhood, film realisme mampu menciptakan keterlibatan emosional yang kuat dengan penonton sebab ia menyajikan pengalaman yang dapat dipahami dan dapat dihubungkan. Lewat penggambaran kehidupan sehari-hari karakter yang relatable dan aspek-aspek dunia nyata, film realis dapat membangkitkan empati dan resonansi pada tingkat pribadi. Pararel dengan itu, aliran seni ini mampu memberikan kritik sosial dan mengeksplorasi problem psikologis secara mendalam dengan fokus pada keaslian dan kejujuran dalam penggambaran tanpa fantasi atau distorsi.
Lalu, apakah dengan tampilan kekerasan dan ketertindasan, serta poros cerita yang berpusar pada korban atau minoritas, menjadikan Pengepungan di Bukti Duri sebuah realisme?
Secara umum, realisme dalam film adalah upaya menampilkan dunia dan peristiwa sebagaimana adanya, memberi kesan bahwa yang terlihat di layar benar-benar dapat terjadi -- meski dalam praktiknya selalu ada proses seleksi dan interpretasi (pilah-pilih kenyataan mana yang mau direkam).
Setidaknya ada dua pemikir populer yang pernah mengutarakan pandangannya terkait realisme serta prinsipnya: (1) Andr Bazin menekankan kontinuitas ruang-waktu dan teknik (long take, deep focus) yang memberi kebebasan pada realitas untuk hadir; (2) Siegfried Kracauer menyoroti fungsi dokumenter film (kemampuannya merekam gejala sosial dan material dunia nyata).
Contoh kecil penerapan prinsip dari kedua pemikir tersebut, dalam Pengepungan di Bukit Duri, bisa dilihat saat prolog tahun 2009 yang menampilkan long take (adegan Silvi dan Edwin diseret perusuh untuk turun dari bus) yang mempertahankan tensi emosional sekaligus menangkap detail sosial kerusuhan anti-Tionghoa -- perpaduan Bazin dan Kracauer.
Hanya saja, penggunaan time jump (lompatan waktu) dari 2009 ke 2027 berpotensi menjadi "jarak" antara film ini dengan prinsip realisme Bazin dan Kracauer yang menekankan kontinuitas -- kendatipun keduanya tak pernah menolak pendekatan itu secara mutlak. Di titik ini, pandangan Andrei Tarkovsky dapat menjawab. Sutradara Ivan's Childhood (1962) itu menganggap pemadatan waktu dapat mencerminkan ingatan yang traumatis. Tarkovsky memandang waktu di film sebagai materi artistik yang dapat "diukir" untuk mengungkap kebenaran batin tokoh.
Oleh sebab itu, meskipun realitas yang disuguhkan dibalut time jump ke masa depan, Pengepungan di Bukit tidak serta merta menanggalkan jejak-jejak realisme. Realisme adalah soal cara pandang dan pendekatan estetika, bukan waktu atau genre. Realisme dalam film dapat muncul melalui penggunaan mise-en-scne yang meniru kehidupan sehari-hari, karakter yang mengalami konflik sosial-psikologis yang relevan, serta narasi yang dibangun secara kausal dan meyakinkan.
Alih-alih berpaling dari semangat realisme, konsep near future Pengepungan di Bukti Duri justru jadi sarana untuk menyoroti realitas sosial-politik kontemporer secara alegoris. Kekerasan komunal, diskriminasi terhadap minoritas, serta absennya negara jadi kritik terhadap kondisi sosial masa kini yang dikemas dalam bingkai waktu spekulatif.
Oleh karena itu, rasanya tepat membaca film ini sebagai bentuk realisme distopik -- pendekatan yang menggunakan fiksi masa depan untuk mengungkap kondisi sosial yang sedang berlangsung. Contoh lain penggunaannya dapat dilihat dalam film lain, seperti Children of Men (2006), atau bahkan series anime Neon Genesis Evangelion (1995) yang menggunakan narasi masa depan untuk menggambarkan dampak perkembangan sains yang mencaplok kemanusiaan.
Dengan demikian, Pengepungan di Bukti Duri memadukan realisme fotografis (Bazin), dokumenter sosial (Kracauer), dan realisme batin (Tarkovsky). Kerja editingnya tidak memutus keterhubungan dengan realitas, melainkan memperluas pengertian realisme dari sekadar visual ke ranah psikologis dan afektif.
Realitas dalam film ini dikemas sebagai bentuk peyoratif dari konsep republik: Republik Preman. Bentuk negara distopik ini adalah istilah (atau, mungkin sindiran) yang saya pinjam dari sosiolog Ariel Haryanto saat ia menguraikan sekaligus mempertanyakan bagaimana permisifnya Indonesia, berikut pejabat pemerintah, terhadap premanisme dalam dokumenter The Act of Killing (2012) arahan Joshua Oppenheimer (Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia, 2015).
Dalam tulisannya, Ariel menguraikan beberapa adegan di film Joshua yang memperlihatkan mesranya hubungan antara kelompok preman dengan pejabat tinggi pemerintahan. Kata Ariel, dalam tulisan lain yang dimuat di Tempo, preman yang menguasai suatu wilayah tertentu menganggap wilayahnya bak 'negara' -- dalam negara -- dan mereka (preman) rajanya.
"Dalam keadaan stabil, preman adalah mitra terbaik bagi pejabat maupun pengusaha," tulis Ariel, dikutip dari Tempo.
Sejalan dengan Ariel, sebagai sebuah film 'peringatan', agaknya realitas yang mengadopsi Republik Preman ini sengaja dipilih untuk -- seperti kata Roy Armes saat memaparkan tujuan dari karya realisme -- mempertanyakan (sekaligus menguraikan) realitas yang tak kondusif di Indonesia. Film ini terasa dibangun dengan fondasi berbahan baku pembentukan sebuah negara preman. Indikasinya hadir dalam; aksi premanisme, kuasa yang gratis, pemerintah yang absen, sampai interaksi sosial disosiatif yang, selain tampak dari kerusuhan massal, juga ada pada pecakapan-percakapan off/on screen dan visual bangunan termasuk coretan vandalisme (grafiti) bernada pengenyahan.
Republik Preman itu terbentuk sejak babak prolog (dalam struktur skenario, jelang akhir babak pertama film, merupakan tahap terbentuknya dunia cerita yang baru bagi karakter: Republik Preman). Adegan pokoknya ada saat kamera menampilkan telapak tangan karakter Panca digores oleh perusuh yang dilanjutkan dengan perobekan baju Silvi, kakak Edwin, dalam adegan rudapaksa yang enggan disorot kamera (panning).
Pembacaan atas adegan ini bisa saja metaforis meski terkesan wagu: Panca dan Silvi sebagai wujud Pancasila yang "terluka". Tapi yang pasti, aksi nista terhadap Panca dan Silvi, pada gilirannya, memicu kemunculan seorang "anak haram" (meski merujuk pada Jefri, sebutan ini, secara luas, saya gunakan untuk mendefinisikan Jefri sebagai simbol dari generasi yang lahir dari trauma sosial dan kebencian rasial) di masa depan, yang terpaksa hidup dalam lingkaran kekerasan dan kebencian.
Tragedi itu berlangsung cepat. Narasi loncat ke tahun 2027 di mana Edwin (Morgan Oey) sudah dewasa. Trauma masa lalu itu telah membentuknya menjadi pribadi. Sebagai guru seni, Edwin berpindah dari sekolah ke sekolah untuk menemukan si "anak haram" demi -- seperti janjinya kepada Silvi -- menyampaikan permintaan maaf kakaknya karena telah menelantarkannya.
"Anak haram" itu menjadi cerminan dominan republik buatan Joko. Representasi kondisi masyarakat yang sibuk pada perdebatan usang mana yang "Indonesia" dan mana yang "tak-Indonesia". Masyarakat yang mempertahankan prinsip "mayoritas di atas minoritas". Ia gandrung akan kuasa, rasa hormat, dan ditakuti; lewat aksi persekusi etnis Tionghoa. Tapi di sisi lain, "anak haram" itu juga menawarkan perlindungan bagi mereka yang mau bergabung dengan kelompoknya dalam memberantas apa yang dikonfirmasi masyarakat sebagai yang "bukan bagian dari kami". Dan, "anak haram" itu adalah Jefri (Omara Esteghlal), anak yang selama ini dicari-cari oleh Edwin.
Itulah cerita utama yang ditawarkan Joko yang ditampung dalam Republik Preman: Edwin sebagai penyintas trauma, dan Jefri yang hidup dalam lingkaran kebencian. Dengan demikian, aturan hidup yang berlaku dalam realitas ini dapat dibaca melalui kacamata maskulintas. Sebab, di samping Edwin dan Jefri, Republik Preman ini juga sesak oleh karakter laki-laki penuh aksi.
Tubuh Laki-laki dan Otoritas
Ketika kisah beralih ke masa near future, Republik Preman itu telah terbentuk secara utuh. Untuk bisa bertahan di republik ini, setiap individu perlu mengukuhkan otoritasnya melalui kekerasan. Dalam kacamata gender tradisional, power atau kekuasaan selalu diasosiasikan dengan laki-laki -- hal ini juga tercermin dalam dunia buatan Joko yang didominasi laki-laki. Dan, ini seakan jadi aturan tak tertulis untuk dapat bertahan di Republik Preman: antara memangsa atau dimangsa. Tanpa power, mereka akan berakhir sebagai 'korban'.
Salah satu tokoh yang merepresentasikan power itu adalah Kepala Sekolah SMA Duri, Darmo Sumitra (Landung Simatupang). Darmo memosisikan dirinya sebagai penentu masa depan para murid -- seorang figur kuasa yang tidak boleh atau tidak perlu disentuh oleh murid-murid SMA Duri. Namun, seiring adegan (di ruang kepala sekolah) berlanjut, otoritas Darmo justru tampak canggung dan kehilangan daya. Ini terjadi saat ia mengungkap prinsipnya, "Sampai saat ini, saya mungkin satu-satunya orang yang masih tidak peduli dengan perbedaan suku," yang lantas dibarengi gerakan menutup pintu ruangannya. Tindakannya justru menandakan ketakutan dan isolasi -- mereduksi kuasanya. Dari adegan ini, penonton belajar bahwa power itu berjalan beriringan dengan rasa takut.
Otoritas dan perasaan takut juga menjadi isu sentral bagi karakter utama cerita. Sebagaimana Darmo, Edwin juga hadir dalam dua versi. Di tempat-tempat publik (di luar sekolah), ia tampil inferior: berjalan menunduk, mengenakan topi, dan terkadang kamera tampak kesulitan menemukannya (adegan Edwin keluar dari stasiun kereta). Dengan gaya hidup tersebut, Edwin punya kehidupan sosial yang sempit, interaksinya terbatas, dan kehadirannya nyaris tak dianggap. Perasaan takut dan alienasi ini mereduksi otoritas pribadi dan power Edwin sebagai individu.
Versi lain Edwin tampak saat ia berada di SMA Duri. Di sekolah, Edwin dan kamera tampak memahami otoritasnya (sebagai guru). Ia berjalan tegap menuju kelas, diiringi musik dengan komposisi (Edwin) di tengah kamera yang menekankan kewibawaannya. Di tempat ini, Edwin adalah sosok berotoritas. Tetapi, lagi-lagi, otoritas ini tidak netral lantaran identitas etnisnya, kehadirannya pun dianggap ancaman oleh Jefri.

Konflik otoritas antara Edwin dan Jefri turut divisualisasikan lewat elemen sinematik. Begitu Edwin memasuki kelas 3F sambil diiringi musik latar, kamera memutari Edwin, lalu, berhenti dengan sudut over-the-shoulder. Tak ada yang menghiraukan kehadirannya, sebelum akhirnya ia membanting tasnya ke atas meja dan seketika musik latar berhenti terdengar, semua murid menatap Edwin penuh skeptis. Di momen ini, Edwin seketika menjelma pengganggu suasana -- pengusik otoritas yang telah terkonvensi dalam kelas itu -- dan dengan segera mendapat perhatian Jefri.
"Main lempar aja kayak berak," kata Jefri.
Ketegangan di antara dua karakter ini hadir secara konsisten lewat elemen-elemen mise-en-scene. Penempatan aktor (blocking) dalam adegan two shot (Edwin-Jefri), misalnya, jarang menempatkan mereka secara sejajar (salah satu biasanya dalam posisi lebih rendah), seperti saat Edwin menegur Jefri yang menolak menggambar, atau adegan lain ketika Jefri mendongak menatap Edwin yang berada di kamar kosnya. Rentetan adegan seperti ini, mempertegas jarak identitas dan kuasa di antara keduanya. Maka gejolak antara Edwin dan Jefri bukan lagi sekadar rivalitas otoritas, tapi juga prasangka satu sama lain.
Otoritas Jefri dalam kisah ini cenderung tak terbatas. Ia adalah "raja" baik di dalam maupun di luar sekolah. Kamera pun seakan tunduk padanya: menyorot wajahnya secara close-up, menempatkannya dalam bingkai cowboy shot, bahkan sampai memperlakukan codet di tubuhnya bak suatu "kebanggaan".
Sorotan istimewa pada luka-luka itu mengkonstruksi tubuh Jefri sebagai simbol kekuasaan dan luka sejarah. Dalam satu adegan penyanderaan, Jefri bahkan memamerkan bekas luka di tubuhnya sambil berkata: "Lu kenapa, sih? Cengeng banget, gitu doang. Itu enggak ada apa-apanya dibanding yang ini," kata Jefri sambil menarik bajunya dan membiarkan kamera mengabadikan tubuhnya.
Perlakuan kamera terhadap tubuh Jefri (tubuh laki-laki) mirip dengan pandangan Laura Mulvey dalam "Visual Pleasure and Narrative Cinema" (1975) di mana kamera dalam sinema konvensional sering kali menempatkan perempuan sebagai objek erotis bagi mata laki-laki (male gaze). Hanya saja, dalam film ini, kamera mengalihkan gaze itu ke tubuh laki-laki penuh luka dengan framing yang tidak erotis, melainkan heroik dan traumatik. Tubuh laki-laki menjadi situs pembuktian maskulinitas melalui penderitaan. Adegan Jefri memperlihatkan luka di tubuhnya kepada kamera (dan penonton), merupakan bukti bahwa ia pantas ditakuti dan dihormati.
Seiring dominasi visual terhadap karakter laki-laki, Pengepungan di Bukit Duri membuka ruang analisis tentang relasi kuasa yang bekerja melalui tubuh. Sebab tubuh bukan sekadar entitas biologis, melainkan lokasi strategis di mana kuasa bekerja dan ditanamkan.
Dalam film ini, tubuh Jefri bukan hanya tempat luka tertanam, tapi juga simbol prestise sosial. Kamera menyorotnya secara intens (termasuk saat adegan Jefri menurunkan celananya di hadapan Edwin dan Darmo), memperlakukan bekas luka sebagai tanda legitimasi dalam hierarki kekerasan. Luka, dalam Pengepungan di Bukit Duri, menjadi bahasa kekuasaan: semakin dalam bekasnya, semakin tinggi posisinya di piramida premanisme.
Menariknya, perlakuan film ini terhadap Jefri dan Edwin juga dapat dibaca melalui lensa hegemonic masculinity. Maskulinitas dominan -- yang diasosiasikan dengan kekuatan, dominasi, dan penguasaan ruang publik -- menjelma secara ekstrem dalam karakter Jefri. Sedangkan, karakter seperti Edwin justru mewakili bentuk maskulinitas subordinat: terpelajar, minoritas, dan sering kali berada di ruang domestik atau aman. Dengan begitu, pergulatan Edwin dan Jefri -- yang menjadi suguhan utama film ini -- bukan hanya soal kekuasaan etnis, tapi juga tentang dua model maskulinitas yang saling menegaskan satu sama lain.
Namun, seperti juga Edwin dan Pak Darmo, "rasa takut", yang menjadi hantu dilema dalam Republik Preman, juga berlaku pada maskulinitas dominan Jefri.
Menjelang akhir film, identitas Jefri terungkap (sebagai keturunan Tionghoa). Tubuh Jefri (yang diasosiasikan dengan maskulinitas dominan) yang di-framing sebagai laki-laki perkasa, nyatanya menyimpan kerapuhan. Di titik ini, tabiat Jefri dengan berlagak membenci, memburu, dan memukuli siswa keturunan Tionghoa, bahkan memanggil mereka dengan sebutan "babi", menjadi kompleks dalam ranah tafsir.
Selain dapat dibaca sebagai manifestasi atas otoritas serampangan khas preman, perilaku tersebut juga dapat diterjemahkan sebagai cara dia menyembunyikan identitasnya. Ini adalah mekanisme pertahanan, penyangkalan, bahkan bentuk ekstrem dari internalized racism Jefri. Pengungkapan identitas Jefri sebagai keturunan Tionghoa pun disuguhkan dalam adegan yang penuh ledakan emosi: Jefri merekam sendiri adegan pembunuhannya lantas memaki (penonton) sambil menatap kamera ponsel yang ia gunakan; "Emang iya gue Cina. Nyokap gue Cina, diperkosa ramai-ramai. Senang elo? Bokap gue banyak. Gue kayak kolam p*ju, kayak tempat sampah. Senang elo anjing. Ngento* elo semua!" teriak Jefri.
Jika disatukan, aspek-aspek ini -- Republik Preman, relasi gender dan maskulinitas, serta tubuh sebagai medan kuasa -- memperlihatkan bahwa Pengepungan di Bukit Duri bukan sekadar film aksi distopik. Ia adalah refleksi multidimensi atas kondisi sosial Indonesia di mana kuasa tidak diperoleh lewat legitimasi moral atau institusional, tetapi lewat tubuh yang terluka dan sistem yang merawat kekerasan sebagai norma.
Tapi, dengan dunia cerita yang sarat aksi dan politik tubuh laki-laki itu, apakah film ini, dalam lingkup rhetoric of victimhood, membuka ruang empati bagi penontonnya atas 'korban' yang ditampilkan atau justru menawarkan visual yang menyulap penderitaan itu menjadi tontonan yang menghibur?
Bagian II: Para Korban dan Kekerasan
Catatan penting dalam esai Brand mengenai paradigma narasi kekorbanan ini, ia mengeksplorasi keterkaitan erat antara trauma, kekerasan, dan proses identifikasi diri sebagai korban dengan mengklaim bahwa dalam era modern, figur korban dan pelaku terus berputar (perebutan status korban) menciptakan konflik baru.
Maka pada bagian ini, saya akan membagi analisis korban dalam tiga kategori, yakni etnis Tionghoa, mayoritas, dan perempuan. Ketiga korban ini -- dengan dunia cerita dan aturan bertahan yang telah dibahas sebelumnya -- memiliki akar ketertindasan dan penggambaran yang berbeda-beda. Selanjutanya, akan dibahas juga bagaimana unsur kekerasan tampil dalam film.

Ruang dan Citra Korban Kelompok Tionghoa
Bagi Edwin dan kelompok etnis Tionghoa lainnya, hidup dalam Republik Preman berarti harus terus bersembunyi dan mencari ruang aman. Otoritas yang ia tampilkan di sekolah tak berlaku di luar. Begitulah cara rhetoric of victimhood bekerja. Sebesar apa pun usaha bersembunyi dan mencari ruang aman, sosok dan penderitaan 'korban' selalu dibutuhkan untuk mempertahankan tatanan yang rusak dalam narasi yang dibangun.
Dengan meminjam kerangka "Segitiga Korban" yang dipopulerkan Stephan Karpman, yang mengklasifikasikan seseorang atau sekelompok orang dalam salah satu dari tiga peran (lihat gambar 3), maka Edwin (etnis Tionghoa) adalah 'korban' dalam kisah ini. Apabila kerangka Karpman diuraikan dalam premis naratif, maka: Edwin (korban) menjadi target kekerasan dari Jefri (pelaku) dan gengnya, yang kemudian diselamatkan oleh Panca (penyelamat).
Posisi Edwin sebagai 'korban sejati' ini sudah ditegaskan sedari babak prolog. Afirmasi visual terhadap narasi ini hadir dalam rentetan adegan: Edwin menyaksikan kakaknya diperkosa massal di depan matanya; Edwin dipukuli dan menjadi sasaran kekerasan masyarakat; Edwin menyamarkan identitasnya lewat jelaga di wajahnya; Edwin menatap rumahnya yang hangus terbakar (asumsi orangtuanya turut menjadi korban kebakaran).
Tapi, kendati struktur naratif awal itu tampak mengafirmasi skema ini secara ketat, narasi Edwin justru bergerak ke arah yang lebih kompleks. Semisal tetap berpegang pada kerangka Karpman, maka peran korban -- yang menurut Karpman dapat menjerumuskan seseorang pada ketidakberdayaan dan ketergantungan serta membuat mereka merasa 'tak lebih dari sekadar korban' -- tak berlaku secara total pada Edwin.
Sebagai korban, Edwin dalam narasi ini adalah karakter berdaya. Luka dan trauma yang dipikulnya -- yang mewakili memori kolektif diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia -- tidak digambarkan sebagai beban yang melumpuhkan. Trauma itu justru menjelma sebagai sumber kekuatan yang membentuk kepribadiannya yang kukuh dan tegar. Perhatikan bagaimana Edwin berjalan tegap (dibingkai dengan teknik kamera tracking low angle), cara dia menatap lawan bicara (Jefri) tanpa gentar, serta bagaimana ia mempertahankan prinsipnya sebagai guru yang tak mau tunduk pada teror muridnya sendiri.

Dengan begitu, meskipun film ini mengusung retorika korban yang berporos pada Edwin, ia menghindari jebakan dramatisasi sentimental yang mengemis air mata penonton. Inilah bentuk politik identitas dalam Pengepungan di Bukit Duri, wujud rhetoric of victimhood yang tak jatuh pada representasi korban sebagai subjek yang hadir hanya untuk dikasihani. Dengan cara ini, Joko berupaya mendobrak dominasi representasi minoritas arus utama lewat karakter Edwin.
Hanya saja, kompleksitas Edwin sebagai korban tak serta-merta mencerminkan keragaman representasi etnis Tionghoa secara menyeluruh. Rasanya terlalu dini dan tak adil untuk menyimpulkan penggambaran korban (representasi etnis Tionghoa) hanya lewat Edwin.
Walaupun memang, apabila boleh mengidentifikasi etnis Tionghoa lewat tampang oriental dan/atau aktor yang berperan, maka bisa dikatakan komunitas Tionghoa dalam film ini hanya diwakilkan lewat dua karakter saja (mengecualikan Edwin dan Silvi remaja di babak prolog), yakni Edwin (versi dewasa) dan bartender di Bar Wijaya, Vera (Shindy Huang).
Namun di luar Edwin dan Vera, kita juga bisa melihat kelompok ekstras berwajah oriental yang muncul di latar dan dibingkai sebagai bagian dari komunitas Tionghoa. Mereka dihadirkan dari "jarak jauh", dalam komposisi kamera yang cenderung netral (objective perspective) sebagai bagian dari dunia film semata. Dan, selayaknya fungsi objective perspective dalam film -- untuk membangun situasi dan dunia tempat karakter berada -- kehadiran kelompok etnis Tionghoa dalam Pengepungan di Bukit Duri tak lebih dari pelengkap suasana.
Dalam istilah yang relevan dengan kajian media, ini dikenal sebagai tokenisme -- praktik simbolik yang menghadirkan kelompok minoritas hanya untuk menciptakan ilusi keberagaman tanpa memberi mereka peran yang signifikan. Representasi semacam ini berisiko menjebak karakter/kelompok minoritas dalam potret yang stereotipikal, dangkal, dan tidak realistis.
Di film ini, kelompok etnis Tionghoa tampak hadir hanya untuk dianiaya atau menambah nuansa realisme penderitaan, bukan sebagai subjek naratif yang otonom. Kekosongan "wajah" Tionghoa dalam film ini -- terutama untuk peran-peran signifikan -- justru "mengganggu" upaya representasi minoritas Joko. Jika memang Joko memilih menempatkan Edwin dan Silvi sebagai representasi Tionghoa, Joko pun tetap berhenti pada pemaknaan 'korban' terhadap karakter yang mewakili ini. Mereka (Jefri dan Silvi) muncul sebagai korban dan berakhir sebagai korban.
Keberagaman yang ilusif itu turut diperkuat oleh cara ruang (chamber) digunakan di film ini. Keterkungkungan etnis Tionghoa dalam ruang terbatas menjadi semacam tema visual yang konsisten. Perhatikan bagaimana ruang Edwin semakin lama (terasa) semakin menyempit: sekolah > ruang kelas > kamar rumah sakit Silvi > Bar Wijaya > kos > gudang olahraga > jalur ventilasi > toilet > mobil. Permainan ruang dalam film ini pun seakan menjadi refleksi atas warisan sosial politik "masa lalu" yang melihat etnis Tionghoa sebagai pihak yang 'lain', 'terpisah', dan tak pernah sepenuhnya diterima.

Ambil contoh, Bar Wijaya, satu-satunya tempat bagi komunitas Tionghoa berkumpul, terletak di kawasan pecinan dan berlokasi underground -- secara literal berada di bawah tanah. Ini bukan semata keputusan artistik, tetapi memuat warisan historis dan simbolik. Jika ditarik ke belakang, sejak masa kolonial Hindia Belanda, pemukiman etnis Tionghoa dipisahkan dari penduduk asli lewat kebijakan Wijkenstelsel. Pecinan menjadi ruang segregatif yang, tak jarang, hingga kini masih menyisakan stigma eksklusivitas dan keterpisahan sosial.
Dalam film Joko, jejak itu muncul kembali: etnis Tionghoa secara harfiah ditempatkan di ruang bawah tanah, tersembunyi, dan gelap. Bar Wijaya (yang muncul dua kali dalam film) pun direkam dengan pencahayaan remang bernafsu (pendar warna merah dan ungu menyorot wajah mereka) yang turut menciptakan atmosfer yang cenderung negatif, membingkai mereka sebagai komunitas yang gemar menghabiskan waktu/menghilangkan penat dengan mabuk-mabukan dan kesia-siaan. Ketika mereka keluar dari ruang (bawah tanah) ini, mereka, lagi-lagi, berakhir sebagai korban (korban bully Jefri, salah satu contohnya).
Penekanan ruang ini juga hadir dalam persepsi karakter lain. Jefri, misalnya, menjebloskan siswa Tionghoa ke dalam ruang sempit di sebuah bangunan terbengkalai (sebelumnya, oleh geng Jefri, siswa keturunan Tionghoa ini dimasukan ke bagasi mobil) -- dua ruang sempit yang melambangkan penyingkiran literal. Atau, Bu Dinda (Hana Malasan) yang menyiratkan wacana keterpisahan sosial lewat dialog: "Semua orang Cina pada ke sana tiap malam," -- merujuk pada Bar Wijaya di pecinan. Dialog ini adalah secuil gema dari stereotip lama yang masih hidup hingga hari ini.

Jika kita meletakkan representasi ruang ini dalam persinemaan Indonesia yang lebih luas, kontras antara ruang etnis Tionghoa dan masyarakat mayoritas memperkuat kesan eksklusivitas dan keterpisahan yang tak sehat. Mirip dengan representasi komunitas Tionghoa dalam film lain seperti Ca-Bau-Kan (2002) karya Nia Dinata atau Cek Toko Sebelah (2016) arahan Ernest Prakasa.
Di film Ca Bau Kan, Nia Dinata menggambarkan kehidupan kelompok Tionghoa sebagai komunitas yang terus-menerus ditawar posisi sosial dan kulturalnya -- oleh penjajah maupun masyarakat bumiputra. Karakter Tan Peng Liang, hadir sebagai bentuk perlawanan stereotip dari representasi Tionghoa era orde baru dengan mengangkat figur Tionghoa yang politis, rentan, tapi juga penuh ambivalensi. Sementara, di film Ernest, meski konflik etnis tetap terasa, narasi identitas dibingkai dalam dinamika keluarga dan ekonomi, bukan penindasan struktural yang brutal. Kedua film ini, turut mengamini eksklusivitas dan keterpisahan sosial tersebut dengan cara dan gaya masing-masing.
Meskipun sejalan dengan narasi Tionghoa dari kedua film tersebut di mana Tionghoa masih dianggap sebagai yang "lain", terlihat bahwa Joko mengambil pendekatan yang lebih kelam, struktural, dan pesimistis melalui permainan ruang.
Tapi di balik itu semua, sejalan dengan dampak Wijkenstelsel dalam sejarah, ruang-ruang ini terkadang dapat dibaca sebagai perwujudan solidaritas antar-Tionghoa, seperti yang tampak pada Bar Wijaya. Vera, meskipun perannya kecil, menjadi satu dari sedikit karakter perempuan Tionghoa yang berbicara. Dalam momen singkat, ia memberi semangat pada Edwin: "Di sini gak boleh ada yang sedih. Lihat sekitar, gak ada yang sedih, kan." Kalimat ini, disertai sorakan semangat dari pengunjung lain, live music, atraksi bartender, sampai desakan pengunjung untuk melanjutkan musik di tengah jeda berita kerusuhan, telah menciptakan ilusi ruang aman -- sebuah dunia kecil yang bebas dari kekerasan dan rasa takut, meskipun sifatnya sementara.
Pergumulan Tionghoa dengan ruang terbatas dalam film Joko pun sebenarnya coba dibayar (pay-off) dengan simbol harapan saat Edwin mengalahkan Jefri dalam adegan duel, lalu diselamatkan oleh Panca dengan mobilnya.
Hanya saja, mempertahankan gaya chamber-nya, kemenangan itu dikesankan tidak merdeka, tidak mengubah status quo. Ujung-ujungnya Edwin dan para Tionghoa yang diselamatkan itu berakhir di ruang sempit (lagi), di sebuah mobil yang sesak bersama 'korban' lainnya. Mereka (etnis Tionghoa) tetap berada dalam bingkai 'korban' dan tetap terkungkung dalam Republik Preman yang semakin subur. Dunia seolah tetap berjalan seperti biasa, padahal kekerasan dan luka kolektif belum usai. Edwin bahkan masih mengenakan topi untuk menyamarkan identitasnya. Sebuah siklus yang berulang, yang membingkai narasi ini dalam melankolia yang tak selesai.
Jika merujuk tradisi estetika sinema, Pengepungan di Bukit Duri tampak bersinggungan dengan konsep chamber films yang dikembangkan sutradara eksperimental, Maya Deren. Selain karena bujet, 'chamber' dalam film-film Deren menjadi ruang refleksi eksistensial -- Deren biasa berlakon di filmnya sendiri. Refleksi ini, dalam bentuk yang lebih massal, salah satunya, pernah dipraktikkan secara ambisius oleh Lars Von Trier dalam Dogville (2003) yang mengangkat ruang minimalis sebagai cermin moralitas komunitas.
Baik karya Von Trier yang eksentrik, maupun karya Deren yang filosofis, chamber films dalam tradisi estetika sinema seringnya mengusung gagasan soal "rumah". Barangkali permainan ruang terbatas dalam film Joko pun menjurus pada gagasan serupa: 'Rumah' sebagai ruang emosional dan simbolik. Jika demikian, gagasan ini menyeret kita pada sebuah pertanyaan: apakah 'rumah' itu masih mengingat dan menerima Tionghoa sebagai bagian dari sejarah, atau justru, sebagai tamu tak diundang?
Mentalitas Korban Kelompok Mayoritas
Sebagaimana rhetoric of victimhood yang identik dengan perebutan status korban, peran 'korban' dalam film ini juga melekat pada mereka yang mengidentifikasi diri sebagai "orang Indonesia asli".
Sejak masa kolonial, tak sedikit masyarakat bumiputra mewarisi mindset 'korban' kekuasaan asing. Di film ini, warisan itu mewujud sebagai perasaan menjadi korban dari kebijakan-kebijakan kolonial yang dianggap mengistimewakan etnis Tionghoa. Perasaan sebagai korban itu perlahan menjadi identitas, bahkan senjata ideologis untuk menjustifikasi kekerasan terhadap yang dianggap sebagai 'pelaku' (etnis Tionghoa).
Jika etnis Tionghoa adalah korban secara literal, maka kelompok mayoritas di film ini adalah korban secara pikiran.
Michael Ovey dalam artikelnya "Victim Chic? The Rhetoric of Victimhood (2006)" memperingatkan bahaya ketika victim-thinking atau mentalitas korban menjadi identitas permanen. Ketika seseorang atau sekelompok orang melihat diri sendiri sebagai korban secara kontinu, mereka rentan menempatkan diri sebagai pihak yang paling benar -- menjadikan pihak lain sebagai pelaku atau pihak yang salah. Ini adalah "ilusi kekorbanan mayoritas" yang justru memperkuat dominasi. Sementara minoritas, tetap dalam posisi yang lebih rentan secara struktural.
Penyandingan etnis Tionghoa sebagai 'korban' bersama kelompok mayoritas menjadikan ketimpangan itu semakin kentara. Ketegangan inilah yang memunculkan efek dramatis bagi penonton, sekaligus membuka kemungkinan pembacaan atas mayoritas sebagai 'pelaku' retorika kekorbanan. Dengan menyandingkan keduanya, penonton punya ruang untuk menentukan siapa 'korban sejati' -- atau dalam istilah Peter Utgaard: real victimhood -- di antara keduanya.
Lalu, setelah kita memisahkan antara korban sejati dan korban semu, pertanyaan selanjutnya, siapa mayoritas ini? Adakah simbol-simbol narasi yang membahasakan identitas mayoritas tersebut?
Sebagai film yang mengakrabkan diri dengan penonton Indonesia, identitas mayoritas itu akan dengan mudah dilekatkan pada Islam. Sebab, seperti kata Eric Sasono, di negara ini Islam sudah menjadi kultur, menjadi bagian dari sejarah. Dengan begitu, film ini pun tidak lagi perlu menghadirkan Islam sebagai sistem nilai eksplisit.
Dalam Pengepungan di Bukit Duir, praktik keagamaan absen; tidak ada visualisasi karakter berhijab, salat, atau membaca Al-Quran. Yang ada hanya ekspresi keislaman yang implisit -- baik sebagai "candaan" maupun dekorasi visual.
Izinkan saya menafsir kondisi ini sebagai apa yang oleh Asef Bayat disebut post-islamisme: fase (transisi islamisme) di mana nilai-nilai Islam tidak lagi menjadi pusat dari gerakan sosial-politik, tapi tetap bertahan dalam gaya hidup, simbol, dan retorika. Pembacaan post-islamisme (yang menyimpang) ini khusus saya gunakan dalam penerapannya di film Pengepungan di Bukit Duri (bukan universal).
Asef Bayat menguraikan post-islamisme sebagai sebuah kecenderungan atau proyek untuk mengonsepkan dan mengintegrasikan Islam dengan nilai-nilai demokrasi dan pluralitas modern, melampaui ideologi islamisme yang berusaha membentuk tatanan Islam yang "kaku". Post-islamisme menekankan pentingnya pluralitas dan inklusivitas dalam tatanan sosial-politik (hibrida antara Islam dan demokrasi).
Post-islamisme dari pernyataan Asef Bayat mencerminkan gerakan islam yang, dampaknya, cenderung bersifat positif. Tetapi, kita juga tak bisa begitu saja melupakan bahwa dunia Joko adalah dunia distopia masa depan di mana fase post-islamisme ini turut terseret menjadi bagian dari elemen distopia yang menguatkan lanskap kekacauan di dalamnya.
Simbol-simbol seperti grafiti gambar kepala babi, tulisan "babi ngepet", sampai umpatan rasis, menjadi elemen yang menyiratkan kekerasan simbolik. Dialog-dialog bernada candaan seperti, "Dia juga rajin salat karena habis ento*in anak orang" memperkuat impresi bahwa nilai-nilai keislaman telah bergeser menjadi semacam identitas kosong: hadir di permukaan, tapi kehilangan kedalaman moralnya.
Karakter di film ini bisa dengan lantang menyebut babi sebagai haram, sambil menormalisasi perzinaan, kekerasan, dan pencitraan religius yang dangkal. Perhatikan dialog-dialog yang dilontarkan teman-teman Jefri, seperti saat salah seorang dari mereka bercerita: "Ya elo kasih aja duit bokap elo ke orang miskin, biar jadi halal,", "Ya kalau itu, mah, bokap gue juga udah sering. Dia sering nyumbang ke masjid. Bahkan gak cuma masjid, yang penting masuk berita." Ini menunjukkan bahwa amalan keagamaan telah direduksi menjadi ajang pencitraan.
Sementara dalam dialog lainnya, salah seorang anggota geng Jefri ingin menjadi hacker supaya bisa "Rebut duit-duit orang kaya yang haram, gue masukin ke rekening orang yang lebih butuh, anjing. Gue gak pengen kayak bokap gue," menjadi pembacaan agama yang terputus dari proses etik -- sebuah bentuk "tujuan islami, lewat cara yang tidak islami".
Kondisi post-islamisme yang kehilangan nilai (Islam) itu pun telah menanggalkan toleransi. Umpatan "babi" jadi name calling untuk merendahkan karakter Tionghoa.
Babi, dalam imaji ini, menjadi lambang dari yang haram, hina, dan "terlarang". Film ini memotret bagaimana kelompok mayoritas secara kolektif menciptakan hierarki nilai yang menindas minoritas melalui simbol-simbol yang tak perlu dijelaskan secara eksplisit. Sederhananya, masyarakat di film ini berbondong-bondong menurunkan nilai dari "menjadi Tionghoa", lantas menormalkannya.
"Iih darah babi," ucap salah seorang geng Jefri saat menghajar seorang remaja Tionghoa.
Kondisi ini diperkaya lewat ruang-ruang off screen (diegetic). Perhatikan bagaimana suara pertikaian antara kelompok muslim dan non-muslim, saat adegan Edwin mandi, yang berpusar soal izin ibadah:
"Bapak ada izin apa enggak di rumah?"
"Tapi kan gue kalau mau ke gereja juga disegel. Terus gue mau ibadah di mana?"
"Elo ada izin apa enggak bikin ibadah di rumah?"
Lewat pertikaian tersebut, Joko seperti menekankan bahwa kondisi seperti inilah yang mewarnai sebuah negeri tanpa toleransi. Konflik sektarian itu menjadi kenyataan kecil yang berserakan, seakan kamera tak memiliki cukup ruang dalam memotret hancurnya toleransi antarumat.
Korban yang Tak Bersuara
Di tengah logika kekorbanan dan krisis toleransi dalam Pengepungan di Bukit Duri, film ini juga menyisipkan korban lain yang bisa saja luput dari perhatian: perempuan. Dalam film yang didominasi laki-laki dan kekerasan ini, tokoh-tokoh perempuan hadir sebagai figur sekali pakai dan mudah digantikan (disposable women).
Peran karakter perempuan di film terbaru Joko ini agaknya mengalami pergeseran jika dibandingkan dengan beberapa film ia sebelumnya (besar kemungkinan karena kebutuhan dunia cerita). Di film-film Joko sebelumnya, Joko cukup sering menampilkan karakter perempuan dengan "suara" yang mempengaruhi narasi.
Karakter Dini, misalnya, di film Perempuan Tanah Jahanam, muncul sebagai sosok perempuan kelas pekerja urban. Meski perannya tidak sepanjang Maya (protagonis), kehadirannya penting karena menandai representasi perempuan marginal yang tetap "bersuara". Dini bukan perempuan dengan privilese atau kekuasaan sosial; ia hadir sebagai warga pinggiran yang terhimpit ekonomi. Namun, dalam kerentanannya, Dini tampil tegas, kritis, dan penuh inisiatif, baik ketika mempersoalkan rencana Maya pulang kampung, maupun saat menyikapi keganjilan-keganjilan yang mereka temui. Dini menolak untuk diam atau hanya menjadi pendamping pasif bagi protagonis.
Karakter Dini merupakan contoh bagaimana kelompok subaltern bisa tetap bersuara, meski tidak berada di pusat kuasa. Ia memilih untuk tetap berpikir, bersuara, dan bertindak. Dalam Perempuan Tanah Jahanam, Joko memberi ruang bagi karakter perempuan dari kelas bawah untuk tetap memiliki agensi (kapasitas bertindak secara mandiri) -- meskipun, seperti yang kerap terjadi dalam narasi horor, agensi itu berujung pada tragedi.
Sebaliknya, karakter-karakter perempuan dalam Pengepungan di Bukit Duri muncul sebagai figur-figur yang nyaris tanpa agensi. Sebagian besar karakter perempuan hadir sekilas, lalu perlahan disingkirkan, baik secara simbolik maupun naratif. Sosok-sosok seperti Silvi, Vera, dan Dotty, tak pernah betul-betul diberi ruang untuk memengaruhi jalan cerita. Mereka jadi pengisi kekosongan emosional laki-laki atau pemantik konflik yang segera terhapus.
Silvi, misalnya, hanya tampil untuk mengalami kekerasan seksual, lalu menghilang dari cerita setelah menjadi motivasi tokoh laki-laki, Edwin.
Vera, yang bekerja di bar, hadir sebagai "pemberi semangat" bagi Edwin yang sedang suntuk, tanpa latar belakang yang jelas atau agenda personal yang menonjol (padahal jika dibaca melalui kacamata interseksionalitas, Vera berada dalam posisi yang rentan: ia perempuan, Tionghoa, dan berprofesi di ruang sosial yang rawan stigmatisasi -- jika saja ia diberi kesempatan lebih dari sekadar "ada").

Dotty, juga terjebak dalam pola serupa. Ia tampil cukup lama dalam film, namun hanya sebatas 'tangan kanan' Jefri, bukan pemilik agenda sendiri (walaupun ia "merdeka" menjelang akhir film). Dalam satu adegan, Dotty diminta Jefri untuk mencekik siswa Tionghoa yang ia sandra. Adegan lain, Dotty mendapat apresiasi (berupa tepuk tangan) dari anggota geng Jefri setelah ia melakukan kekerasan (adegan Dotty memukuli siswa Tionghoa) -- sebuah logika patriarkal yang mengafirmasi eksistensi perempuan hanya ketika ia "mengikuti" atau "meniru" laki-laki.
Satu-satunya karakter perempuan yang diidealkan dengan rasionalitas dan visi adalah Bu Dinda. Ia menjadi tokoh yang mewakili pemikiran progresif yang sinis terhadap dominasi maskulinitas dalam sistem kekuasaan.
Bu Dinda menolak diantar pulang oleh Edwin dan menyarankan masing-masing dari mereka meningkatkan survival skill. Komentarnya, "Lebih gampang lagi, jadi guru perempuan di sini. Anak laki-lakinya gak ada yang musuhin. Karena mereka gak perlu lomba gede-gedean biji. Mereka gak perlu ngerasa terintimidasi." menyiratkan bahwa perebutan kekuasaan dalam film ini, bagi Bu Dinda, tak lebih dari adu ego kekanak-kanakan yang memuakkan. Namun sayangnya, Bu Dinda pun tak luput dari jebakan peran pendukung. Kehadirannya lebih sebagai penyokong emosional Edwin saat Edwin kalang kabut di tengah kepungan geng Jefri (atau, sebagai penghantar kritik patriarki yang ingin diutarakan Joko).
Kondisi ini menunjukkan kecenderungan film untuk menempatkan perempuan sebagai figur pelengkap, bukan penggerak. Sebagaimana dikritik Gayatri Spivak, perempuan dalam sistem representasi dominan kerap tak diberi suara untuk berbicara. Mereka menjadi subaltern yang, tidak hanya tertindas, tetapi juga dilenyapkan dari kapasitas bicara dan agensi. Mereka diperlukan untuk menambah kedalaman emosi, bukan menantang struktur kekuasaan.
Ironi yang mengemuka dari semua ini adalah bagaimana film yang mengangkat isu penindasan struktural, baik secara sadar maupun tanpa sadar, justru mereproduksi penindasan simbolik terhadap perempuan di dalam narasinya sendiri. Ini bukan sekadar soal durasi tampil atau jumlah dialog, melainkan tentang siapa yang memegang kendali atas makna, arah cerita, dan pemaknaan atas penderitaan. Di Pengepungan di Bukit Duri, yang memaknai penderitaan perempuan tetaplah laki-laki.
Dengan pendekatan narasi itu, tak sedikit karakter perempuan berakhir menjadi latar, minoritas menjadi suara sumbang yang tak perlu didengar, dan kekerasan, ada kalanya, menjadi gambar. Lantas, apakah Pengepungan di Bukit Duri membawa kita pada kesadaran, atau hanya pada kenikmatan visual atas penderitaan korban?
Kekerasan sebagai Tontonan
Seperti telah disinggung sebelumnya, Pengepungan di Bukit Duri adalah proyeksi 'akibat' -- dan, film umumnya berurusan dengan 'akibat' dari suatu fenomena sosial yang terjadi di dunia nyata (adalah berlebihan menagih solusi atas isu sosial dari sebuah film). Keistimewaan inilah yang dimanfaatkan Joko untuk bercerita dengan longgar dan luwes.
Meskipun banyak dikritik sebagai plot hole, ketidaktahuan penonton atas musabab kerusuhan rasial, bagi saya, justru jadi alat ampuh untuk memberi statement bahwa: tak ada alasan apa pun yang mampu membenarkan/melogiskan tindak kekerasan dan diskriminasi. Sehingga, kalaupun dipaksa mencari 'sesuatu untuk disalahkan', maka akan dengan mudah menunjuk 'sistem' sebagai tersangka utamanya. Trauma terhadap sistem kekerasan yang mencekik masyarakat menjadi tema besar film ini. Trauma membentuk karakter-karakter seperti Edwin dan Silvi, dan menjadi motivasi utama Edwin untuk mencari Jefri. Skema karakter-tujuan-halangan pun disusun berdasarkan luka sosial itu.
Sebagai proyeksi 'akibat', Joko menyajikan film ini dengan pendekatan ala sinema postmodern. Seperti para sutradara pasca 1970-an yang gemar mendobrak ekspektasi publik akan gaya dan struktur naratif, Joko dengan sadar menggunakan ironi dan kekerasan eksplisit untuk menggambarkan trauma secara immersive.
Dengan keluwesan postmodern, unsur kekerasan dalam rhetoric of victimhood Pengepungan di Bukit Duri jadi ironi yang perlu untuk diumbar dan dipertontonkan. Kamera tidak berpaling dari adegan sadis seperti pembacokan, pembakaran, dan pengeroyokan. Gaya sinematografi Jaisal Tanjung (Dop) -- kamera handheld, zoom, pan, dan tilt yang spontan -- mempertegas estetika kekerasan yang realis dan mentah. Kekerasan ini tidak ditampilkan ala Quentin Tarantino, misalnya, yang penuh koreografi, melainkan sebagai pengalaman visual yang menyuntikkan rasa takut ke tubuh penonton. Atau, dengan kata lain, gambar yang sadis ini menjelma perasaan tidak nyaman yang entertaining.

Perasaan "terhibur" ini sejalan dengan studi "Violent Film Characters' Portrayal of Alcohol, Sex, and Tobacco-Related Behaviors" (2014), yang menemukan sekitar 90% film yang berpendapatan tinggi menampilkan adegan karakter utama yang terlibat dalam kekerasan. Unsur kekerasan dalam film kerap jadi jaminan keseruan cerita.
Efek ini senada dengan gagasan Susan Sontag, bahwa gambar-gambar kekerasan dapat sekaligus mengguncang dan menghibur. Ada paradoks dalam menyaksikan penderitaan sebagai tontonan. Kekerasan dalam film Joko ditampilkan bukan hanya untuk menggambarkan realitas, tapi juga untuk memancing efek emosional: keterkejutan, keterpukauan, atau bahkan kenikmatan estetis.
Pada tingkat sinematik, Pengepungan di Bukit Duri memperkuat paradoks ini. Kita menyadari bahwa kekerasan dan penderitaan dalam film ini dipoles menjadi bagian dari estetika visual. Ia indah, dramatis, tapi juga tak jarang menumpulkan empati.
Ketegangan situasi melalui penggambaran ruang-ruang yang penuh grafiti bernada pengenyahan, umpatan rasis, konflik sektarian, serta adegan kekerasan yang, tak jarang, tampil beriringan dengan musik atau dialog humor, dapat menjelma bentuk estetisasi kekerasan. Adegan pemukulan remaja Tionghoa yang diiringi musik up beat adalah contoh paling mencolok bagaimana kekerasan disulap menjadi tontonan yang nyaris menghibur (adegan yang saya maksud adalah adegan saat dialog "Iiih darah babi" terlontar).
Dalam lanskap budaya visual yang sarat spectacle seperti Indonesia kontemporer, kekerasan menjadi komoditas visual yang menjual. Guy Debord, dalam esai yang telah disebut di muka, mengingatkan bahwa masyarakat modern hidup dalam representasi yang telah menggantikan realitas itu sendiri. Selain sebagai fakta sosial, kekerasan dalam film jadi semacam pertunjukan: sesuatu yang ditonton, dikonsumsi, dan dirayakan.
Namun, sedari awal Joko sudah mewanti-wanti penonton bahwa semua bentuk kekerasan yang mereka saksikan adalah semata film atau realitas rekaan yang, dalam satu dan lain hal, adalah bagian dari "hiburan". Itu tampak, misalnya, melalui lagu "Guruku Tersayang" yang non-diegetic, atau manipulasi pergerakan waktu dari 2009 ke 2027, yang hanya bisa dilakukan oleh film (kerja editing). Maka, kekerasan yang disaksikan dapat dipahami penonton sebagai sebuah atraksi filmis semata (yang telah dijahit sedemikian rupa di ruang edit).
Tapi justru di situlah jebakannya. Dalam permainan "hiburan kekerasan" ini, figur korban bisa tergelincir menjadi ornamen. Kekerasan berakhir menjadi spectacle. Condongnya film ini dalam menyajikan alternatif 'hiburan' berupa kekerasan realis yang atraktif penuh tegang terkadang menjadi selimut yang terlampau tebal. Penuhnya wujud 'korban' dalam film ini pun -- baik simbolik maupun literal -- jadi sulit ditampung dan diberi "suara" dan/atau "wajah" oleh Joko.
Salah satu film yang mampu keluar dari jebakan spectacle itu adalah film debutan Rungano Nyoni, I Am Not a Witch (2017). Di Film ini, Nyoni meramu kekerasan struktural dan budaya terhadap perempuan di Zambia dengan latar dan pemain non-profesional dalam bingkai visual yang penuh ironi dan nyaris surealis. Kisah Shula, gadis kecil yang dituduh sebagai penyihir dan diasingkan ke kamp bersama para "penyihir" lainnya, memang disampaikan dengan pendekatan estetika yang mencolok, seperti panorama gersang kering kelontang Zambia, kostum dengan warna-warna kontras, serta penggunaan musik klasik yang memberi nuansa teatrikal.
Tetapi, alih-alih menjadikan penderitaan Shula sebagai tontonan "indah" yang menjauhkan penonton dari kenyataan brutal yang ia alami, pendekatan estetis ini justru punya peran penting dalam mempertegas absurditas sistem masyarakat yang menindasnya. Kekerasan yang dialami Shula dibingkai sebagai rutinitas banal yang memilukan. Visual yang tampak "indah" itu justru memperbesar ketimpangan antara bentuk dan isi: memaksa penonton merenungkan absurditas sistem patriarki dan kolonial yang masih hidup dalam tubuh negara postkolonial. Shula jarang bicara, namun kehadirannya yang diam -- sering diposisikan secara visual sebagai pusat komposisi gambar -- menjadi bentuk perlawanan. Di tangan Nyoni, estetika itu menjadi alat untuk mendedahkan trauma dengan cara yang menuntut keterlibatan penonton secara emosional maupun etis.
Adegan-adegan kekerasan yang atraktif dan shocking itu memang identik Joko. Menyaksikan film Joko berarti harus siap dengan unsur-unsur eksplisitnya. Mungkin beginilah cara Joko mendudukan kembali film sebagai "media hiburan" -- seperti yang sering ia katakan. Joko ingin penonton terhibur setelah meluangkan waktu menyaksikan karyanya, sembari berharap, social commentary dalam film dapat terbaca dan memantik diskusi di kalangan penonton.
Dengan mendudukan kembali film sebagai "media (hiburan)", tentu penggambaran korban akan selalu dibarengi etika. Mungkin sisi etika ini menjadi rem bagi film Joko ketika kehadiran korban -- yang beberapa hadir tanpa "suara" dan berkali-kali menjadi sasaran kekerasan -- rentan dan nyaris terjerumus menjadi "keindahan sinematis" semata yang menumpulkan empati.
Korban dalam lingkup "media" mendapat perlakukan khusus guna menyelamatkan mereka dalam bingkai eksploitasi. Dan sebagai generasi 'anak nakal' perfilman Indonesia, Joko bermain di batas bingkai itu.
Dalam penelitian lain (The Role of Graphic and Sanitized Violence in the Enjoyment of Television Drama, 2009), ditemukan bahwa, baik film yang memuat adegan kekerasan maupun ketika adegan kekerasan itu dihilangkan (sampel film yang sama), tidak mereduksi kepuasan penonton dalam menonton filmnya. Maka rasanya cukup sahih untuk mengatakan, barangkali, yang dinikmati oleh penonton adalah menyaksikan karakter jahat mendapat ganjaran setimpal, bukan kekerasan itu sendiri. Atau, dengan kata lain, penonton menantikan semacam poetic justice (keadilan puitik). Di sinilah bingkai etika itu terlihat.
Joko tampak berupaya menyeimbangkan daya hibur dengan tanggung jawab etis. Ia hadirkan semacam poetic justice yang menyamankan hati penonton: Jefri yang penuh kekerasan akhirnya mati. Tapi bentuk poetic justice yang lebih retoris muncul ketika tokoh-tokoh yang sebelumnya tunduk pada kekerasan (Dotty, dan dua anggota geng Jefri lainnya) memilih pergi dan mengejar "masa depan" (meninggalkan Jefri) dengan diiringi teriakan Edwin: "Dia ini pembunuh. Kalian bukan pembunuh. Kalian masih punya masa depan. Pergi!"
"Masa depan" menjadi kata kunci dari kemungkinan membebaskan diri dari warisan kekerasan dan trauma. Tetapi jalan menuju ke sana tidak pernah mudah. Dialog Khristo menunjukkan bahwa rasa takut dan keengganan berempati telah menjadi penghalang kolektif, "Harusnya kita gak ikut lari, kita gak ada masalah apa-apa sama mereka," kata Khristo saat adegan awal pengepungan.
Pendirian Khristo ini pun tak mengalami perubahan. Saat ia dan Bu Dinda berhasil melarikan diri, lalu Bu Dinda hendak kembali untuk membantu Edwin, Khristo kembali berujar, "Kalau saya sendiri, nanti saya ditangkap sama mereka, Bu," Kalimat ini menandai bahwa dalam masyarakat yang kehilangan solidaritas, masa depan selalu dibayangi rasa takut dan ketidakpedulian.
Sampai akhir film, Pengepungan di Bukit Duri tidak menawarkan solusi apa pun (dan memang tak perlu). Tetapi film ini berhasil menginterogasi struktur yang melanggengkan budaya kekerasan: sistem, simbol, dan spectacle. Ia juga menyibak ironi kekorbanan -- yang merasa diri korban, tetapi justru menjadi pelaku. Ia menyentil budaya populer yang menikmati kekerasan, sembari menampilkan bagaimana perempuan dan minoritas tetap menjadi yang paling bisu di antara kerumunan.
Bagian III: Epilog
Sepulang menyaksikan film ini di bioskop bersama teman saya, seperti biasa, kami mampir ke warung kopi terdekat -- ritual wajib yang kami lakukan untuk membicarakan film yang baru kami tonton, mumpung ingatan masih segar. Setelah berlarut-larut membicarakan yang asyik dan yang tidak asyik dari film ini, obrolan kami makin lama mengerucut ke soal respons penonton, faktor yang kerap luput dari perhatian kami, dua orang penggemar film Jokan; "Gimana ya perasaan orang Tionghoa kalau nonton film ini? Kesel gak ya?" Pertanyaan ini bukan cuma soal materi filmnya, tapi juga soal menatap kembali luka sejarah itu.
Sebagai orang yang juga minoritas (Arab), cukup lama saya memikirkan pertanyaan itu. Bahkan konyolnya, saya sempat mengandaikan Pengepungan di Bukit Duri mengambil sudut pandang karakter keturunan Arab di Indonesia yang mengalami kekerasan rasial di filmnya. Sampai akhirnya, terlintas salah satu adegan paling powerfull di jagat perfilman (atau, tentang) Indonesia, terutama yang membahas luka sejarah; The Look of Silence (Senyap, 2014) karya Joshua Oppenheimer.
Adegan yang saya maksud ialah adegan menjelang akhir dari dokumenter ini. Dalam adegan itu, Adi Rukun -- adik dari Ramli, salah satu korban pembantaian 1965 -- bertemu keluarga Amir Hasan, seorang pelaku eksekusi. Ketika Adi bersama Joshua menyampaikan kisah tentang tragedi yang menimpa keluarga Adi, salah satu anggota keluarga Amir Hasan memotong, "Tak usah dibuka-buka. Tak usah dipanjang-panjangkan masalah, Joshua!" Adegan rekonsiliasi penuh canggung itupun ditutup dengan potret wajah Adi dalam tatapan yang menggantung -- bisu tapi sarat makna.
Adegan ini, menariknya, justru menjadi cerminan bagaimana sebagian publik memandang film Senyap. Di antara banjir dukungan dan gemerlap apresiasi puluhan ajang perfilman internasional atas upaya pengungkapan sejarah yang penuh distorsi itu, sebagian kalangan justru mengkritik film Joshua sebagai karya provokatif, ditafsirkan sebagai upaya mengorek luka lama yang berpotensi memicu perpecahan di masyarakat (Laporan Komnas HAM).
Dan agaknya, Pengepungan di Bukit Duri menempuh jalur serupa -- meski berbeda isu dan bentuk (film). Jika Joshua menelusuri luka 1965 melalui dokumenter yang kontemplatif, Joko menyiasati sejarah lewat distopia fiksi near future yang menyimpan gema 1998. Keduanya menggunakan bingkai serupa: negara sebagai sponsor kekerasan, masyarakat yang dicekam rasa takut dan benci, serta impunitas yang membekas di tubuh sosial.
Film Joko maupun Joshua menghadapi dilema yang sama: apakah mengingat artinya menyembuhkan, atau justru mengoyak kembali?
Film semacam ini -- yang menggali ingatan kolektif -- tak bisa dielakkan dari tuduhan "mengorek luka lama". Akan tetapi, itu jugalah paradoksnya. Sebab, tidak akan ada pemulihan tanpa keberanian mengingat. Tak mungkin menyembuhkan luka sosial tanpa menatap bekasnya, meski dengan risiko menimbulkan rasa sakit. Dalam konteks ini, pengalaman menonton sudah bukan sekadar peristiwa konsumsi visual, melainkan bentuk partisipasi dalam ingatan kolektif -- sebuah "ritus trauma" dalam kemasan sinema.
Maka, yang penting bukanlah "seberapa akurat" film ini terhadap catatan sejarah 1998, melainkan: bagaimana ia memilih untuk mengingat, dan ingatan macam apa yang coba dibangkitkan dalam diri penontonnya. Seperti yang ditulis Lauren Ball dalam artikelnya "The Historical Value of Film", keakuratan bukan satu-satunya ukuran dalam film berdasar sejarah. Yang lebih esensial adalah bagaimana film mengaktifkan narasi-narasi yang ingin dikenang. Film bukan pengganti arsip, tapi jembatan emosi yang membuat sejarah itu terasa dekat, hidup, dan personal.
Dari sini, Pengepungan di Bukit Duri bisa dilihat sebagai kerja ingatan. Sebuah ajakan untuk menyaksikan ulang betapa kekerasan rasial bukan sekadar episode masa lalu, tapi bayang-bayang yang selalu mungkin datang kembali. Lewat ketegangan, kekerasan, dan konflik etnis yang digarap Joko dengan gaya dan estetika sinematiknya yang gamblang, film ini menyuguhkan semacam "spektakel trauma". Kita sebagai penonton diajak menatap penderitaan untuk memahaminya. Dan, beginilah cara film berbicara.
Maka, pertanyaannya bukan lagi: "Apakah film ini akan diterima semua orang?" Jawaban siapa pun tak akan cukup. Namun barangkali, trauma yang muncul dari tindakan menonton ini justru adalah harga yang sepadan demi kembali membuka ruang dialog, memperdebatkan sejarah, dan merawat ingatan akan sejarah bangsa yang, ada kalanya, diwarnai distorsi ini.[]
Daftar Referensi
Buku
- Aristoteles. 2018. Retorika (Seni Berbicara). Yogyakarta: Penerbit Basabasi.
- Bazin, Andr. 1967. What Is Cinema? Vol. 1. Berkeley: University of California Press. (Vol. 2, 1971).
- Bordwell, David & Kristin Thompson. 2013. Film Art: An Introduction (10th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Hanich, Julian. 2018. The Audience Effect: On the Collective Cinema Experience. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Heryanto, Ariel. 2015. Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Imanjaya, Ekky & Hikmat Darmawan (eds.). 2019. Tilas Kritik: Kumpulan Tulisan Rumah Film (2007--2012). Jakarta: Komite Film Dewan Kesenian Jakarta.
- Kristanto, J. B. 2004. Nonton Film, Nonton Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Pratista, Himawan. 2017. Memahami Film: Edisi 2. Yogyakarta: Montase Press.
- Sontag, Susan. 2003. Regarding the Pain of Others. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Spivak, Gayatri Chakravorty. 1988. "Can the Subaltern Speak?" Dalam Cary Nelson & Lawrence Grossberg (eds.), Marxism and the Interpretation of Culture, hlm. 271--313. Urbana: University of Illinois Press.
Artikel Jurnal / Prosiding
- Bleakley, Amy; Romer, Daniel; Jamieson, Patrick E. 2014. "Violent Film Characters' Portrayal of Alcohol, Sex, and Tobacco-Related Behaviors." Pediatrics 133(1): 71--77. https://doi.org/10.1542/peds.2013-1922
- Brand, Roy. 2008. "Identification with Victimhood in Recent Cinema." Culture, Theory and Critique 49(2): 165--181.
- Mulvey, Laura. 1975. "Visual Pleasure and Narrative Cinema." Screen 16(3): 6--18.
- Todorov, Tzvetan. 2001. "In Search of Lost Crime: Tribunals, Apologies, Reparations, and the Search for Justice." The New Republic, 29 Januari, hal. 29--36.
- Weaver, A. J., & Wilson, B. J. 2009. "The Role of Graphic and Sanitized Violence in the Enjoyment of Television Dramas." Human Communication Research 35(3): 442--463.
Laporan / Organisasi
- Komnas HAM. 2014. Senyap (The Look of Silence): Katalog Film Dokumenter. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Sumber Daring
- Ball, Lauren. "The Historical Value of Film." Metahistory -- An Introductory Guide to Historiography. Diakses 23 Juni 2025 dari https://unm-historiography.github.io/metahistory/essays/thematic/film.html
- Bedard, Mike. 2025. "What Is Postmodernism? Definition and Examples for Filmmakers." StudioBinder, 2 Februari. Diakses 5 Juli 2025 dari https://www.studiobinder.com/blog/what-is-postmodernism-definition/
- Dunham, Brent. 2020. "What is Poetic Justice? Definition and Examples for Screenwriters." StudioBinder. Diakses 5 Juli 2025 dari https://www.studiobinder.com/blog/what-is-poetic-justice-definition-and-examples/
- Firdausi, Fadrik Aziz. 2020. "Wijkenstelsel & Passenstelsel: Mula Stigma Eksklusif Orang Tionghoa." Tirto.id, 29 Januari. Diakses 19 Juli 2025 dari https://tirto.id/wijkenstelsel-passenstelsel-mula-stigma-eksklusif-orang-tionghoa-euU6
- Heryanto, Ariel. 1999. "Republik Preman Indonesia: Analisis Sekumpulan Pengamat Asing tentang Situasi di Indonesia." Tempo, edisi 28 November, hlm. (PDF 1--2). Diunduh dari https://arielheryanto.wordpress.com (akses: 11 Juli 2025).
- Novita, Maychaella. 2020. "Menyingkap Distorsi Realitas di Media Sosial Bersama Guy Debord." Kumparan, 9 Desember. Diakses 6 Agustus 2025 dari https://kumparan.com/maychaella-novita/menyingkap-distorsi-realitas-di-media-sosial-bersama-guy-debord-1ukOMHEKwUA
- Prabangkara, Hugo Sistha. 2022. "Asyiknya Menjadi Masyarakat Penonton: Refleksi Konsep Spectacle ala Guy Debord." Nalarasa, 3 Maret. Diakses 6 Agustus 2025 dari https://nalarasa.com/2022/03/03/asyiknya-menjadi-masyarakat-penonton-refleksi-konsep-spectacle-ala-guy-debord/
- Pengepungan di Bukit Duri. 2025. IMDb. Diakses dari https://www.imdb.com/title/tt33479839/
- StudioBinder. "Postmodern Cinema." StudioBinder. Diakses 5 Juli 2025 dari https://www.studiobinder.com/blog/what-is-postmodernism-definition/
- Tranouli, Eleni. 2021. "Entering Maya Deren's 'Chamber Films'." Medium, 17 Maret. Diakses 28 Juli 2025 dari https://elenitranouli.medium.com/entering-maya-deren-chamber-films-bd14b6fdd092
- What Is Up, Indonesia? (WIUI). 2025. "Indonesia & the Horror That Hits Too Close to Home -- Joko Anwar." What Is Up, Indonesia? YouTube, 19 April. https://www.youtube.com/watch?v=K7QpXiTclO4 (diakses 23 Agustus 2025).
- Muzakki, Ahmad Zidan. 2023. "Tradisi-Tradisi Pinggiran: Perspektif Subaltern." Komplek-eL, 11 Mei. Diakses 2 Agustus 2025 dari https://komplek-el.com/tradisi-tradisi-pinggiran-perspektif-subaltern/
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI