Konflik Besar: Penjajahan Dan Pengambilan Paksa Tanah Rakyat
Setelah kerajaan besar dari luar berhasil menanamkan pengaruhnya di wilayah pesisir timur Jawa, kehidupan rakyat berubah drastis. Tanah-tanah yang dulu diwariskan dari leluhur, kini menjadi sasaran perebutan oleh para bangsawan asing dan kaki tangannya. Mereka datang dengan alasan membawa kemajuan, tetapi yang mereka bawa hanyalah penindasan dan kerakusan.
Politik Pecah Belah dan Penipuan Hukum
Para penguasa baru memanfaatkan perjanjian-perjanjian palsu, membuat surat kepemilikan yang tidak dipahami rakyat, dan menggunakan cap kerajaan yang tidak dikenal. Tanah petani diambil secara 'sah', padahal rakyat tidak pernah menjualnya. Di sisi lain, tokoh-tokoh desa yang jujur dibungkam atau dikriminalisasi. Hukum menjadi alat kekuasaan. Rakyat kecil tidak lagi punya suara. Tanah yang diwariskan turun-temurun menjadi milik para penindas hanya dengan selembar kertas.
Kekuasaan Menggunakan Kekerasan
Bagi yang melawan, aparat penjajah tak segan menggunakan kekerasan. Desa-desa dibakar dengan tuduhan menyembunyikan "pemberontak." Para kepala keluarga diculik malam hari, anak-anak dipisahkan dari orang tuanya, dan wanita dipaksa melayani tentara asing. Mereka menyebutnya "pengamanan wilayah", tetapi rakyat tahu: itu adalah penjajahan terang-terangan. Setiap mata yang menyaksikan, menyimpan luka. Setiap ladang yang digusur, menyimpan tangis.
Hancurnya Tatanan Sosial dan Budaya
Tak hanya fisik yang dirampas. Nilai-nilai adat dan budaya lokal pun ikut direndahkan. Rumah-rumah adat dihancurkan, tempat-tempat pemujaan leluhur dijadikan barak pasukan. Bahasa dan nama tempat diubah agar "lebih cocok dengan tata administrasi baru."
Rakyat dipaksa melupakan siapa mereka, agar mudah dikendalikan. "Mereka bukan hanya mengambil tanah kita," kata seorang tetua desa, "tapi juga ingin mengambil jiwa kita."
Tekanan Ekonomi: Pajak dan Kerja Paksa
Tak cukup dengan pengambilalihan tanah, rakyat juga dikenakan pajak yang mencekik. Bagi yang tak mampu membayar, akan dikenai kerja rodi di tambang, pelabuhan, atau jalan raya. Siang dan malam mereka bekerja tanpa upah, hanya diberi makan seadanya. Sebagian besar yang dikirim kerja paksa tak pernah kembali. Mereka mati di negeri sendiri sebagai budak kekuasaan.
"Konflik besar ini bukan sekadar soal tanah, tetapi soal kemanusiaan dan harga diri. Rakyat Jawa Timur tidak lagi hidup di bawah naungan kerajaan yang melindungi, tetapi dalam cengkeraman kekuasaan yang hanya tahu menjarah."
Sawunggaling yang menyaksikan ini semua, tidak tinggal diam. Ia tahu bahwa penderitaan ini harus diakhiri. Dalam hatinya, tumbuh semangat perlawanan bukan untuk kekuasaan, tetapi demi membela rakyat yang terinjak dan menjaga warisan leluhur.
Sawunggaling Bangkit Memimpin Perlawanan
Setelah menyaksikan penderitaan rakyat yang kian menjadi-jadi, Sawunggaling tak lagi bisa berdiam diri di puncak gunung tempat ia bertapa dan memperdalam ilmu. Suara tangis ibu kehilangan anak, jerit petani melihat sawahnya digusur, dan ratapan anak-anak yang kelaparan semua itu menjadi api yang membakar semangatnya. Ia tahu, ini saatnya turun gunung.
"Kalau aku tidak bangkit sekarang, maka tidak akan ada yang tersisa dari negeri ini, selain cerita tentang penderitaan," kata Sawunggaling di hadapan murid-muridnya.
Menyatukan Rakyat dari Berbagai Daerah
Sawunggaling tidak langsung menyerang. Ia mengembara dari desa ke desa, menyusuri lembah dan pegunungan, membangkitkan kesadaran rakyat tentang hak mereka. Ia berbicara bukan sebagai bangsawan atau pangeran, tetapi sebagai anak negeri yang sama-sama terluka. Di setiap tempat yang ia datangi, ia menyalakan kembali harapan. Ia duduk bersama petani, berdialog dengan pemuka adat, dan menyatukan suara-suara yang selama ini tercecer.
"Kita bukan budak di tanah sendiri. Kita bukan kambing yang bisa digiring seenaknya. Kita adalah pewaris bumi pertiwi ini."
Dengan kharisma dan keberanian yang dimilikinya, Sawunggaling menjadi magnet perjuangan. Rakyat yang awalnya takut, perlahan mulai berani mengangkat wajah mereka. Dari para pemuda desa hingga tetua kampung, semua menyatakan kesiapan untuk berjuang.
Membentuk Pasukan Rakyat
Tanpa modal senjata modern, Sawunggaling melatih pasukan dari kalangan rakyat biasa: petani, tukang kayu, tukang batu, dan bahkan perempuan-perempuan pemberani. Mereka belajar menggunakan bambu runcing, keris pusaka, panah tradisional, dan jebakan alam. Pelatihan berlangsung di hutan dan lembah terpencil. Bukan hanya fisik yang dilatih, tetapi juga mental dan tekad perjuangan. Mereka diajarkan bahwa musuh bukan hanya tentara yang bersenjata, tapi juga rasa takut dalam diri sendiri.
"Kita tidak punya banyak senjata, tapi kita punya semangat. Dan itu, lebih mematikan dari segala pedang."
Sawunggaling juga menunjuk para panglima muda dari kalangan rakyat sendiri. Ia percaya, perjuangan rakyat harus dipimpin oleh rakyat. Ia tidak haus jabatan, tapi membangun sistem perlawanan yang adil dan kolektif.
Strategi Gerilya dan Penyadaran Kultural
Sawunggaling paham bahwa melawan kekuatan besar secara terbuka adalah bunuh diri. Maka ia mengandalkan strategi gerilya: menyerang pos penjajah secara tiba-tiba, menyabotase jalur logistik, dan menghancurkan gudang senjata musuh.
Lebih dari itu, ia juga menghidupkan kembali semangat budaya dan kearifan lokal. Ia menghidupkan ritual adat yang melambangkan perlawanan, seperti nyanyian perang, tarian roh leluhur, dan simbol-simbol perlawanan yang mengakar dalam tradisi. Ini menjadi alat pemersatu emosi dan identitas rakyat.
"Kita boleh kalah secara senjata, tapi jangan sampai kalah sebagai manusia. Kita harus ingat siapa kita, dan dari mana kita berasal."
Nama Sawunggaling Mulai Disebut di Mana-Mana
Dalam waktu singkat, nama Sawunggaling menjadi legenda hidup. Ia dijuluki oleh rakyat sebagai "Putra Gunung yang Menjaga Tanah Leluhur". Bagi musuh, ia dianggap hantu rimba yang tak bisa ditangkap. Bagi rakyat, ia adalah pelita di tengah kegelapan.
Desa-desa mulai bersatu. Rakyat yang awalnya takut, kini menyambut pasukan Sawunggaling dengan penuh harapan. Kemenangan kecil demi kemenangan kecil diraih, dan keberanian rakyat pun menyebar seperti api menjilat alang-alang.
"Sawunggaling bukan hanya seorang pemimpin perang. Ia adalah penyatu jiwa bangsa, pembangkit kesadaran, dan simbol kekuatan rakyat. Ia tidak menawarkan kekuasaan, tapi menghidupkan kembali harga diri. Di bawah kepemimpinannya, rakyat tak lagi merasa kecil. Mereka tahu, mereka bisa melawan. Mereka bisa menang."


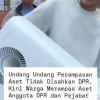
![[dpr] Gaji Tetap Mengalir, Tapi Hati Rakyat Sudah Pergi: Perlunya Etika dan Adab bagi Anggota Dewan](https://assets-a2.kompasiana.com/items/album/2025/09/02/file1b549156-2ec1-45a4-b331-a757f7fc9902-68b6499eed64152c5867fef4.png?t=t&v=100&x=100&info=meta_related)



