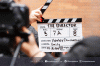Setelah kehadiran film animasi yang diklaim memecahkan rekor nasional (Jumbo), publik Indonesia kembali digegerkan dengan kehadiran animasi debutan yang bertepatan dengan momen jelang peringatan kemerdekaan. Film yang bertajuk Merah Putih : One For All ini mengangkat tema tentang petualangan sekelompok anak yang harus menemukan bendera sebelum upacara bendera digelar pada esok harinya. Sekilas ikhtisar sinopsis ini cukup menarik, namun tidak sebanding dengan umpan balik yang tendensius alih-alih mendapatkan apresiasi.
Respons publik dengan kemunculan animasi debutan ini kebanyakan negatif karena sejumlah faktor, mulai dari kualitas sinematografi, isu anggaran produksi, hingga tudingan atau klaim aset yang "dicomot" dari animator luar negeri. Beberapa seniman musik dan animasi turut melayangkan penilaian kritis pada konten yang disajikan. Bahkan ada yang menyerukan pemboikotan terhadap film animasi ini dengan alasan reputasinya yang kontroversial justru menguntungkan karena dapat menarik atensi publik untuk nekat menontonnya.
Posisi penulis terhadap isu ini cukup netral karena sama sekali tidak berniat menonton baik film Jumbo maupun film debutan ini (bukan karena boikot ataupun sentimen). Menurut penulis, setidaknya ada beberapa sudut pandang yang bisa dikulik dari kemunculan isu ini :
- Sudut pandang produser, tentunya para pelaku produksi film ini sangat berharap karyanya mendapatkan atensi yang luar biasa, walau panen kritik sekalipun, Pimpinan produsernya harus membela dan memperkuat argumentasi yang meyakinkan ketika publik meluncurkan serangan bertubi-tubi. Mereka tentunya telah mempersiapkan ide yang katanya telah disusun selama satu tahun dan kru animasi dengan biaya gotong-royong (sesuai klaimnya). Klaim-klaim para produser bisa dibaca kembali pada tulisan media massa dan tayangan berita terkini;
- Sudut pandang pelaku seni animasi dan musik, bagi orang-orang yang memiliki kapasitas pengetahuan tentang produksi film, khususnya animasi, film debutan ini masih kurang layak diedarkan, meskipun lembaga sensor telah meloloskannya (berdasarkan referensi, lembaga sensor hanya menguji isi konten, terlepas dari kualitas fisiknya). Teknik pengolahan objek animasi yang masih kasar, rigging atau kerangka gerak karakter yang belum mulus, hingga aset yang diklaim beli-tempel menjadi sorotan untuk film ini. Apalagi micro-expression (detail mimik wajah minor) juga masih perlu dipermulus lagi (penulis ingat seorang pengamat film juga memberikan catatan tentang microface pada film Jumbo). Seorang pengamat/penggiat musik pun menduga lagu latar yang digunakan seperti diproduksi dengan kecerdasan buatan (penulis belum mendalami lebih lanjut tentang isu ini). Lebih lanjut, teknik pelakonan suara (voice acting) yang diterapkan masih berkualitas rendah, terkesan membaca teks dengan penghayatan emosi minim;
- Sudut pandang penonton awam, bagi penonton dari khalayak umum, kualitas film ini secara keseluruhan bukan tandingan film sesukses Jumbo. Trailer resmi yang diedarkan seakan sudah cukup untuk menggambarkan bagaimana kualitas film debutan yang dibuat dalam durasi waktu produksi sangat pendek ini. Bahkan pada sebuah berita seorang penonton menggunakan kiasan "palung mariana" sebagai level kualitas film ini (baca berita ini);
- Sudut pandang psikologi sosial, penulis melihat kasus film "wan for ol" ini sebagai fenomena sosial yang kompleks. Banyak yang beranggapan film Jumbo menjadi tolok ukur atau standar baru film animasi Indonesia, sehingga film-film yang berkualitas sangat rendah disayangkan sekali. Di sisi lain, penilaian publik yang terlalu dini dengan menonton trailer (cuplikan film) kemudian melontarkan respons-respons tendensius (bahkan melebarkan isu) tidak ubahnya seperti perilaku psikologi yang pragmatis, yaitu penilaian yang cepat hanya dengan pengetahuan berupa sepotong berita atau konten serta "baca judul langsung komen" (Sebagai pembanding argumen ini, terbaru bacalah berita dari sutradara film ini). Hal ini yang kemudian dibalas oleh produser dengan meminta masyarakat untuk menonton versi penuh dari film ini. Di sisi yang lain lagi, titel "produk lokal" sepertinya dipertanyakan karena menjadi tameng untuk menutupi ruang kritis terhadap karya animasi lokal. Ada pula sorotan terhadap celah amannya konten yang disajikan, misalnya munculnya properti yang diduga senjata laras panjang pada sebuah adegan. Properti tersebut disorot karena bertentangan dengan esensi film yang diklaim ramah untuk semua umur.
- Sudut pandang pemerintah, pemerintah menepis tudingan adanya insentif dana untuk film ini. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif mengaku pihak produser memang sempat mendatangi Kementerian, namun pihaknya hanya memberikan masukan tentang isi film tersebut.
Solusi yang Konstruktif Dibutuhkan Setelah Publik Meradang
Pada tulisan ini penulis merekomendasikan solusi yang bisa dipertimbangkan, tentunya dalam kapasitas sebagai warga awam yang apriori :
1. Penggarapan Ulang
Film debutan ini mendapatkan kesan terburu-buru hingga sengaja dipaksakan untuk tayang. Oleh karena itu penulis menyarankan agar. Apalagi terdapat isu bahwa pihak produser ingin merilis film baru untuk momen peringatan kemerdekaan pada tahun depan.
Penggarapan ulang tersebut tidak berarti meninggalkan kasus yang sedang berjalan. Pihak produser tetap harus bertanggung jawab penuh atas karya yang dihasilkan, sekalipun jika nantinya ada delik hukum.
2. Perekrutan Talenta Sinematografi
Sama halnya dengan kebijakan politik yang dinilai kurang melibatkan partisipasi lintas kalangan, dalam sebuah proyek sinematografi kontribusi banyak pihak sangat esensial. Pihak produser tidak bisa hanya mengandalkan beberapa pihak dalam menggarap sebuah proyek karena sebuah karya pada akhirnya akan dikonsumsi publik. Selain produser, ada pihak konsultan seperti pakar sinematografi, budayawan, pengamat perfilman, hingga orang biasa yang memiliki selera film bagus. Bahkan dalam membuat sebuah karya novel saja banyak yang menganjurkan agar hasil karya tulis tersebut diperlihatkan kepada orang terdekat terlebih dahulu untuk dikoreksi.
Sebagai langkah awal, talenta sinematografi harus direkrut dari berbagai kalangan, bahkan dari anak sekolah sekalipun jika film yang akan digarap bertema anak-anak. Talenta sinematografi yang direkrut dalam sebuah animasi bisa berupa kru pembuatan storyboard, karakter, properti, latar belakang, penata artistik, penata suara, hingga konten promosi. Adapun sutradara, penulis naskah, penyunting naskah, dan lain-lain tetap dibidangi produser. Proses rekrutmen talenta ini harus transparan dan benar-benar teliti. Para calon talenta harus menguasai bidang yang akan dikerjakannya dan mampu bekerja sama sebagai tim.
Kemudian, khusus untuk talenta pembuatan desain karakter, mereka bisa ditarik dari sekolah/universitas vokasi dan pengembang yang bergerak di bidang animasi. Jika film animasi yang akan diproduksi berfokus pada cerita khas Indonesia, maka talenta-talenta ini harus memiliki wawasan yang luas tentang kemajemukan bangsanya tersebut. Selain desain karakter, talenta pembuat properti hingga detail latar minor juga bisa ditarik dari instansi spesialisasi animasi tersebut. Pihak produser bertanggung jawab atas pengawasan dan pengaturan jam kerja mereka, apalagi jika sejumlah kru yang dipilih masih berstatus pelajar atau mahasiswa.
Khusus pengisi suara (voice actor), pihak produser sangat disarankan untuk merekrut talenta yang berkompeten serta memiliki gairah sastra dan teatrikal yang bagus. Hal ini bisa dipelajari salah satunya dari studio animasi Malaysia, Monsta, yang baru-baru ini gencar melakukan pembukaan rekrutmen untuk voice actor ini dalam rangka penggarapan salah satu seri film-nya. Jika film yang akan dihadirkan mengangkat tema keindonesiaan dan kebinekaan, maka produser harus membuka rekrutmen untuk mendapatkan talenta yang merepresentasikan setiap suku bangsa. Logat daerah yang khas, apalagi jika benar-benar melakonkan bahasa daerah, menjadi "nilai jual" yang tinggi sesuai semangat persatuan.