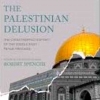Dibuat oleh: Dr. Syamsul Yakin, M.A. dan Prima Akbar Priatna (Dosen dan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah)
Dakwah Politik al-Ghazali
Sebagai tokoh pemikiran politik Islam Sunni masa klasik al-Ghazali adalah tokoh yang kehidupannya begitu lekat dengan berbagai gerakan religius dan politik yang saling bertentangan pada masanya. Bahkan ketika al-Ghazali masih bersama dengan kekuasaan, tidak ada satupun keputusan politik-pemerintahan yang tidak melalui dirinya. Pemikiran politik Islam Sunni masa klasik mengalami dinamika dan perkembangan, dari tema yang bersifat idealis, misalnya, sebagaimana tampak dalam pemikiran politik al-Farabi menjadi bertema realis seperti tergambar dalam pemikiran politik al-Ghazali
Begitu pula dalam tema hubungan agama dan kekuasaan, pada awalnya bersifat integratif, seperti terlihat dalam pemikiran politik al-Juwayni, kemudian mengalami perkembangan dalam pemikiran politik al-Ghazali menjadi bersifat simbiosis. Namun dalam pemikiran politik Islam Sunni tema mengenai pola hubungan antara penguasa dan rakyat tidak berubah, tetap bersifat kontraktual, setidaknya hingga masa al-Ghazali.
Sebagai seorang realis al-Ghazali melakukan justifikasi dan legitimasi terhadap pemerintah Abbasiyah dan Saljuk. Hal itu dilakukan al-Ghazali karena ia ingin mengenalkan suatu pendekatan realistik dalam melakukan rekonsiliasi antara idealitas agama dan realitas penyelenggaraan negara, di samping kehendaknya untuk mempertahankan eksistensi negara dan kekuasaan. Untuk mempertahankan eksistensi negara dan kekuasaan, al-Ghazali memberikan justifikasi dan legitimasi terhadap al-Mustazhir, khalifah Abbasiyah ke-28 yang baru berusia enam belas tahun. la menolak syarat-syarat bagi khalifah yang ditetapkan oleh mayoritas pemikir politik Sunni, seperti al-Mawardi dan al-Juwayni.
Akibatnya, al-Ghazali dikecam oleh cendekiawan dari kalangan Sunni sendiri dan juga Syi'ah karena banyak melakukan konsesi (kelonggaran). Konsesi al-Ghazali dalam hal syarat-syarat khalifah. teknik pengangkatan kepala negara, pola-hubungan khalifah dan sultan mengundang perdebatan sejumlah cendekiawan pada masa selanjutnya.
Dalam realitas politik, al-Ghazali mengembangkan pola hubungan antara agama dan kekuasaan menjadi bersifat simbiosis untuk tujuan politis-pragmatis, tepatnya untuk membangun komunikasi politik yang harmonis antara Abbasiyah sebagai pemangku kekuasaan de jure (spiritual-keagamaan) dan Saljuk sebagai penguasa de facto (pemegang kendali kekuasaan).
Untuk tujuan itu, al-Ghazali menggunakan isu teologis, di mana keduanya sama-sama bermazhab Sunni. Padahal pada saat Saljuk berhasil merebut Baghdad dari tangan Buwayhi yang berhalua Syi'ah, penguasa Abbasiyah waktu itu mengharapkan kembalinya supremasi kekuasaan mereka secara mutlak, bukan "didamaikan" oleh al-Ghazali dengan "teori maslahat" yang dikembangkannya.
Dalam "teori maslahat" yang ditujukan bagi Abbasiyah itu, al-Ghazali melarang memberontak kepada penguasa de facto karena akan menimbulkan anarki. Bagi al-Ghazali seperti diungkap Bernard Lewis, tirani lebih disukai ketimbang anarki. Untuk mendukung teori maslahat ini, al-Ghazali mengatakan: "Sesungguhnya keteraturan agama tidak akan tercapai tanpa keberesan dunia, sedangkan keteraturan negara sangat tergantung kepada pemimpin yang ditaati".
Pandangan al-Ghazali ini menempatkan bahwa agama akan baik dan oleh karena itu harus sangat tergantung kepada khalifah Berdasar ungkapan di atas, bisa dikatakan bahwa pemikiran politik al-Ghazali dalam kaitannya dengan manajemen negara dan kekuasaan lebih dekat kepada model sentralisme khalifah ketimbang institusionalisme, dan organisme. Dari ungkapan itu pula dapat diketahui bahwa paradigma pemikiran politik al-Ghazali lebih dekat dengan paradigma simbiotik antara agama dan negara, bukan integralistik atau instrumentalistik.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI