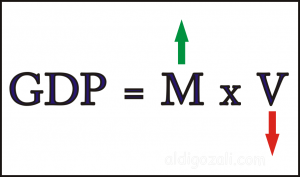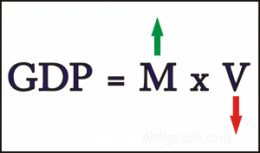Menyebar ke Semua Penjuru Pembayaran yield dapat menyebabkan tergeneralisasinya permasalahan dari negara emiten ke negara investornya. Dalam kasus surat utang AS, ketika negeri liberalis itu membayarkan yield-nya pada negara-negara seperti Jepang, China, UE, dsb., seketika itu pula negara-negara tersebut harus menanggung risiko dari dolar yang dipegangnya. Terlebih jika AS mengalami masa-masa krisis (likuiditas kering) dimana keadaan tersebut dapat membuat yield lebih sulit untuk dibayarkan. Keadaan seperti ini jelas akan mengancam perekonomian. Ketika para investor menganggap para dealers mengalami gagal bayar (default), mereka akan menarik kembali dana mereka. Penarikan dana ini sama saja dengan melenyapkan uang dari peredaran dan akan mengakibatkan kelesuan pada pasar yang berujung pada matinya velocity. Didasarkan keengganan akan hal ini, otoritas AS melakukan pelonggaran likuiditas agar para dealers dapat terus memenuhi kewajibannya kepada para entitas: membayarkan yield.
Akan tetapi, permasalahannya, upaya pelonggaran likuiditas ini tidak konstitusional dan hanya akan membuat yield yang diharapkan lebih tinggi---berarti utang membengkak dan berkepanjangan: yield yang lebih tinggi berarti lebih banyak dolar yang akan dibayarkan. Selain itu supply uang di pasaran pun akan meningkat dan membuat nilai uang susut serta menjadikan harga-harga barang melambung. Inilah inflasi! Dan ini pulalah risiko yang dimaksud: inflasi merubah struktur biaya (cost structure) menjadi lebih tinggi yang tak hanya akan dirasakan oleh AS melainkan pula negara-negara lain yang terikat dalam suatu rantai bisnis dengan AS.
Selain melalui struktur biaya, neraca perdagangan (trade balance) pun dapat menjadi skema alternatif penyebaran dampak QE dari AS. Dikarenakan statusnya sebagai standar mata uang dunia (global reserve currency), dolar AS akan selalu digunakan sebagai alat transaksi dalam segala bentuk perdagangan dunia (paling tidak ini yang terjadi sekarang). Kas surplus (pihak yang surplus) dan kas defisit (pihak yang defisit) pun sudah barang tentu di sini. Surplus perdagangan (trade surplus), membuat dolar yang diterima lebih banyak, sedangkan defisit perdagangan (trade deficit) membuat kas negara berkurang. Pada kas surplus, dolar yang masuk dijadikan cadangan devisa (foreign exchange reserves) yang berfungsi sebagai penjamin mata uang lokal yang akan diterbitkan. Sementara kas defisit (dalam keadaan tertentu) mungkin saja memilih langkah utang sebagai solusinya.
China menjadi contoh menarik dalam hal ini. Negeri komunis itu menjadi salah satu negara yang sangat rawan terkena imbas dari program cetak uang (khususnya di AS) dikarenakan neraca pembayaran (balance of payments) yang terus mengalami surplus atas rival-rivalnya. Terlebih surplus perdagangan China dengan negara-negara kuat seperti AS dan Uni Eropa terus melebar. Hal ini membuat China harus mengkonversikan lebih banyak dolar ke dalam bentuk mata uangnya, yuan. Maklum saja, China memang dikenal sangat konservatif dalam mengontrol uang yang masuk ke negaranya sehingga ketika ada dolar masuk, mereka akan langsung menahannya dalam brankas bank sentral mereka (People Bank of China/PBOC) dan mengkonversikannya dengan yuan. Semakin banyak dolar yang masuk, semakin banyak pula yuan yang dicetak. Dari sini, Inflasi pun merebak. Ujung-ujungnya, ini akan berdampak pada pengerekan struktur biaya di China dan negara-negara partner dagangnya.
Melalui skema yang sama, hal serupa dapat terjadi dimana pun, termasuk di negara-negara berkembang (emerging markets). Pada negara-negara seperti Brazil, India, Indonesia, Korea Selatan, Thailand, dan Vietnam, inflasi yang datang tak hanya melalui neraca perdagangan dan pengerekan struktur biaya melainkan pula skema yang lebih dinamis, yakni hot money. Pencetakan uang di AS telah menyebabkan pasar kebanjiran likuiditas sehingga dana menjadi lebih mudah didapat. Sebagian dana tersebut kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia terutama negara-negara berkembang. Dana inilah yang disebut hot money. Derasnya hot money yang masuk (hot money inflow) membuat uang yang beredar semakin banyak. Sebagai hasilnya, harga-harga merangkak naik---lagi-lagi inflasi. Kenaikan harga-harga aset seperti pada perdagangan saham menjadi contoh empiris dalam kasus ini. Tak aneh, ketika dana tersebut pergi, pasar saham pun seperti "kekurangan gizi".
Inflasi akan lebih menakutkan ketika hal-hal yang bersifat prinsipil ikut terkena imbasnya. Misalnya saja harga-harga makanan. Ini bisa terjadi apabila komoditas yang notabene merupakan bahan pokok pembuatan makanan seperti gandum, gula, kopi, jagung, kedelai, dan minyak terkerek harganya. Jika hal yang mendasar saja naik, sudah barang tentu harga-harga barang lainnya pun ikut naik. Tenet ini berlaku di semua negara, terutama negara-negara pengimpor bahan baku makanan. Negara-negara di Timur Tengah barangkali boleh kita jadikan sampel dalam hal ini. Sekedar tambahan, kerusuhan yang terjadi di Tunisia dan dengan cepat merambat ke Mesir, Jordania, Moroko, Libya, dan sekitarnya diyakini tak terlepas dari persoalan ekonomi. Beban fiskal akibat subsidi bahan baku makanan membuat negara-negara tersebut lebih sulit bertahan dari "terjangan ombak" inflasi. Ketika pemerintahnya mulai fokus membenahi kondisi fiskal dengan menaikkan pajak atau pun mencabut subsidi, rakyat menjadi semakin tercekik. Kesejahteraan rakyat yang carut marut---sementara para diktator tetap arogan dengan segala kemewahan---sangat mungkin menjadi katalis yang bersifat provokatif. Tak heran, ini memicu terjadinya demonstari besar-besaran. Kerusuhan pun pecah dan dengan cepat menyebar, revolusi pun tak terhindarkan (fenomena ini kemudian dikenal dengan sebutan Arab Spring). Rasanya sudah bisa ditebak, apa yang akan terjadi apabila perekonomian negara-negara Arab sampai mati akibat fenomena tersebut. Betul sekali, melambungnya harga minyak dunia! Bagaimana selanjutnya jika harga minyak dunia melambung? Silakan Anda tebak sendiri.
Begitulah quantitative easing dengan produk utamanya: inflasi. Inflasi pada dasarnya memang tidak terkendali. Ia bisa menyebar dari satu sisi ke sisi lain, dari satu sektor ke sektor lain, dan dari satu negara ke negara lain, dengan cepat dan dengan cara yang tak bisa diprediksi. Saat ini naif, berbicara menghindari dampak inflasi karena ia sudah tergeneralisasi. Ia pun seakan sudah menjadi afirmasi yang mengukuhkan opini akan buruknya deflasi yang selalu dibumbui kata resesi. Kalau sudah begini, harus diakui, jika inflasi telah menjadi suatu hal yang pasti selain mati. Tak perlu berandai-andai bagaimana dunia ini tanpa inflasi. Berdoa saja supaya Ibu Pertiwi bisa terhindar dari konfrontasi krisis ekonomi baik yang ada saat ini maupun nanti.