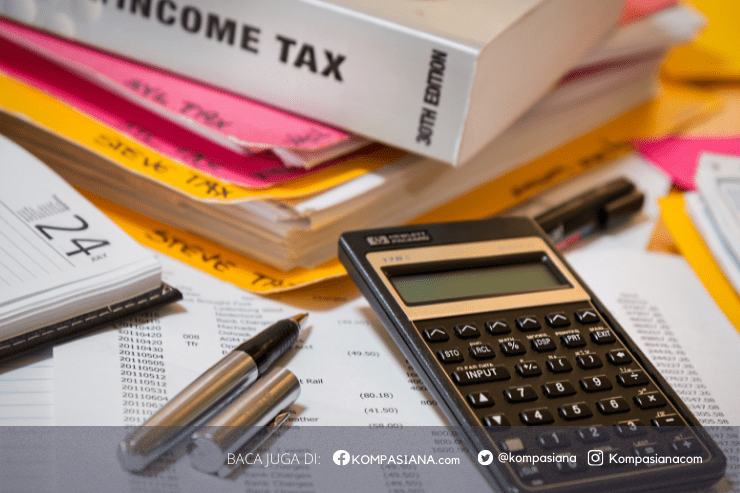APBN itu ibarat dompet besar milik negara. Dari sinilah gaji guru dan nakes dibayar, jalan diperbaiki, air bersih disalurkan, sampai bansos digelontorkan waktu keadaan sulit. Masuk 2025, kita dapat "PR ganda": defisit harus tetap rapi biar ekonomi stabil, tapi layanan publik juga harus makin cepat dan merata. Susah? Iya. Mustahil? Nggak juga---asal uang rakyat dipakai makin cerdas.
Beberapa tahun kemarin, negara gaspol belanja buat nahan dampak pandemi. Sekarang mesinnya harus disetel ulang. Ruang fiskal nggak selebar kemarin, sementara kebutuhan warga justru naik. Di sinilah pertanyaan penting muncul: setiap rupiah yang keluar, bikin hidup orang banyak beneran lebih gampang nggak? Kalau jawabannya belum, berarti ada yang perlu dibenahi.
Dalam teori kebijakan, APBN punya tiga "tugas super": mengalokasikan (biayai barang/jasa publik yang penting), mendistribusikan (biar manfaatnya nggak numpuk di segelintir orang), dan menstabilkan (jadi bantalan saat ekonomi goyang). Kedengarannya teknis, tapi gampangnya begini: negara pastikan layanan dasar jalan, bantuan tepat sasaran, dan ekonomi nggak mudah oleng. Tantangannya, eksekusi di lapangan sering kali ruwet---makanya kualitas desain dan pelaksanaan jadi penentu.
Masalah paling sering kita dengar tentu soal infrastruktur dan layanan dasar. Kebutuhannya besar, tapi uang APBN nggak cukup kalau ditanggung sendiri. Solusinya? Jadikan APBN sebagai pengungkit, bukan "dompet sakti" yang bayar semuanya. Pemerintah bisa gandeng swasta lewat skema kerja sama (KPBU) dengan aturan yang jelas: standar layanan harus terukur (airnya bersih, tekanannya cukup, listriknya stabil, transportasinya tepat waktu), risikonya dibagi dari awal kontrak, dan tarifnya tetap masuk akal buat warga. Negara fokus di hal-hal yang sangat publik---perizinan, tulang punggung jaringan, penjaminan secukupnya---sementara swasta membangun dan mengoperasikan aset dengan efisien.
Contohnya layanan air minum di kota-kota besar. Banyak daerah masih mengandalkan air tanah, padahal ini bisa bikin amblesan kalau kebablasan. Dengan skema yang tepat, komponen hulu dan pipa utama bisa dibiayai pemerintah, sedangkan instalasi pengolahan dan operasional jangka panjang ditangani mitra swasta. Dampaknya berlapis: cakupan air bersih naik, kualitas hidup membaik, dan beban APBN nggak jebol. Yang penting, semua diikat target layanan yang jelas, bukan sekadar "asal bangun."
Lalu soal pajak---topik yang sering bikin kening berkerut. Idealnya, penerimaan negara bukan cuma soal naikin tarif. Basis pajaknya harus meluas, administrasinya simpel, dan kepatuhan dibantu sistem digital yang rapi. Buat UMKM, kepastian aturan dan kemudahan ngurus pajak itu krusial; jangan sampai usaha kecil kesandung aturan yang ribet. Di sisi lain, insentif pajak sebaiknya diarahkan ke kegiatan yang benar-benar bikin ekonomi naik kelas: teknologi bersih, hilirisasi yang berkelanjutan, dan penguatan rantai pasok lokal. Jadi bukan sekadar "murah pajak", tapi "tepat sasaran".
Bagian yang paling sensitif: subsidi energi. Kita paham subsidi itu penting buat jaga daya beli. Tapi kalau harga komoditas dunia naik atau rupiah melemah, biayanya bisa membengkak. Supaya adil dan kuat di fiskal, perlu pembenahan: bedakan tegas mana subsidi (untuk yang berhak) dan mana kompensasi, pakai data yang akurat biar bantuannya tepat orang, dan kalau pun harus ada penyesuaian harga, lakukan bertahap sambil kasih bantalan sosial. Intinya, lindungi kelompok rentan tanpa bikin APBN megap-megap.
Nah, bicara belanja, kita juga harus move on dari mindset "yang penting terserap". Serapan tinggi itu bagus, tapi yang lebih penting adalah hasil nyatanya. Layanan dasar harus jadi prioritas: air dan sanitasi bikin warganya lebih sehat; transportasi massal menghemat waktu, nurunin kemacetan, dan biaya logistik; layanan kesehatan primer mencegah biaya mahal di rumah sakit; pendidikan vokasi dan micro-credentials bantu pekerja upgrade skill biar siap pindah ke sektor yang lebih bernilai. Satu lagi yang sering dilupakan: dana operasi dan pemeliharaan (O&M). Infrastruktur tanpa O&M ibarat beli motor tapi nggak pernah servis---awalnya kenceng, lama-lama ngadat dan makin mahal merawatnya.
Supaya manfaatnya terasa di seluruh Indonesia, transfer ke daerah juga perlu makin berbasis kinerja. Kalau indikator layanan jadi patokan---bukan cuma "berapa persen anggaran terserap"---pemerintah daerah punya insentif kuat buat berinovasi. Misalnya, siapa yang berhasil nambah sambungan air bersih, ngurangi waktu tempuh, atau nurunin biaya layanan per pengguna, dapat bonus atau akses program tertentu. Dengan begitu, ketimpangan layanan antarwilayah bisa dipersempit tanpa harus nambah pos belanja baru terus-terusan.
Kalau diringkas, resep APBN 2025 yang "sehat" kira-kira begini: penerimaan yang adil dan efektif (basis luas, aturan sederhana), belanja yang bikin kapasitas baru (bukan cuma habiskan anggaran), subsidi yang lebih presisi (tepat sasaran dan bisa diaudit), serta pembiayaan kreatif seperti KPBU dengan standar layanan yang jelas. Dengan formula itu, APBN bukan cuma alat bayar, tapi juga kompas yang nunjukin arah---menuju pertumbuhan yang lebih cepat, merata, dan tahan banting.
Di ujung hari, angka-angka defisit dan target belanja memang penting. Tapi yang lebih penting lagi: apakah kebijakan di balik angka itu bikin hidup orang banyak jadi lebih gampang. Apakah jam layanan air makin panjang? Apakah waktu tempuh kerja makin singkat? Apakah anak muda lebih mudah dapat skill baru? Apakah keluarga rentan tetap aman saat harga bergejolak? Kalau jawabannya "iya", berarti APBN bekerja sebagaimana mestinya.