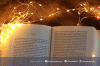Ilmu yang Menggerakkan atau Sekadar Mengajar?
Oleh: A. Rusdiana
Perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2025/2026 telah dimulai sejak 1 September 2025 hingga 19 Desember 2025. Di berbagai kampus, termasuk di program S1 Metode Penelitian dan S2 Manajemen Sumber Daya Pendidikan serta Sistem Informasi Manajemen Pendidikan, dosen kembali menghadapi tantangan klasik: bagaimana membuat ilmu yang diajarkan tidak berhenti di ruang kelas, tetapi benar-benar menggerakkan perubahan sosial. Konsep Ilmu yang Menggerakkan, Bukan Sekadar Mengajar berpijak pada teori Job Demand--Job Resources (JD-R) yang menekankan bahwa keterlibatan kerja (work engagement) tumbuh saat individu memiliki keseimbangan antara tuntutan dan sumber daya pekerjaan. Dalam konteks akademik, dosen dan mahasiswa menjadi lebih produktif ketika ilmu tidak hanya ditransfer, tetapi diterapkan dalam komunitas pembelajar nyata. Hal ini sejalan dengan teori Etienne Wenger tentang community of practice dan Lev Vygotsky tentang social learning, di mana pembelajaran bermakna lahir melalui interaksi sosial dan praktik bersama. Namun, realitas menunjukkan masih ada kesenjangan (gap) antara dunia akademik dan kebutuhan sosial. Banyak dosen masih fokus pada publikasi jurnal, sementara mahasiswa berorientasi pada nilai indeks prestasi. Kolaborasi lintas jenjang dan profesi, misalnya antara dosen universitas dan guru madrasah ibtidaiyah (MI), masih jarang dilakukan. Padahal, sebagaimana pepatah bijak menyebutkan, "Jika suatu pekerjaan dikerjakan bukan oleh ahlinya, tunggulah kehancurannya."
Tulisan ini bertujuan untuk merefleksikan pentingnya paradigma baru: bahwa ilmu sejati adalah ilmu yang menggerakkan, bukan sekadar mengajar. Berikut lima pilar pembelajarannya. Berikut lima pilar Ilmu yang Menggerakkan atau Sekadar Mengajar:
Pilar 1. Akademisi sebagai Agen Pemberdayaan Sosial; Ilmu yang menggerakkan harus hidup dalam aksi nyata. Contohnya, kegiatan life skill di PKBM YPSM Tresna Bhakti Ciamis (Juli 2023), di mana pelatihan tata boga dan kewirausahaan bukan hanya pelajaran teknis, melainkan proses pemberdayaan. Dosen dan mahasiswa yang turun langsung menciptakan kelas tanpa tembok, menjadikan masyarakat sebagai laboratorium sosial. Dari sinilah nilai akademik bertemu dengan kepedulian sosial.
Pilar 2. Pembelajaran Kolaboratif antara Dosen dan Mahasiswa; Mahasiswa bukan objek pembelajaran, melainkan mitra berpikir. Dalam semangat JD-R dan social learning, dosen perlu menumbuhkan ruang dialog dua arah agar mahasiswa berani bereksperimen dan berinovasi. Contoh nyata terlihat dari kolaborasi proyek penelitian lokal di desa-desa, di mana mahasiswa dilatih menganalisis data, mengelola sumber daya, dan menawarkan solusi bagi UMKM.
Pilar 3. Komunitas Praktik dan Jembatan Sosial Akademik; Teori Wenger tentang community of practice menegaskan bahwa komunitas menjadi wadah belajar paling efektif. Inisiatif seperti Pena Berkarya Bersama (PBB)---komunitas penulis yang baru berdiri sejak 16 September 2025 dan kini beranggotakan 673 orang---menjadi contoh bagaimana ilmu menembus batas hierarki. Tidak semua profesor mau bekerja sama dengan guru MI, tetapi kolaborasi lintas jenjang ini justru memperkaya wawasan dan nilai kemanusiaan dalam pendidikan.
Pilar 4. Branding Akademik Melalui Aksi, Bukan Publikasi; Era digital menuntut akademisi memiliki brand berbasis karya sosial, bukan hanya indeks sitasi. Ketika mahasiswa dan dosen terlibat dalam kegiatan nyata---seperti pelatihan kewirausahaan, penulisan bunga rampai bersama guru, atau pelatihan teknologi pendidikan---maka reputasi akademik akan tumbuh secara organik. Branding sejati lahir dari konsistensi aksi.
Pilar 5. Penguatan Soft Skills Global untuk Indonesia Emas; Menghadapi tantangan Indonesia Emas 2045, kualitas SDM tidak cukup diukur dari kompetensi teknis, melainkan juga soft skills: empati, komunikasi, kolaborasi, dan kepemimpinan sosial. Dosen yang mengajarkan dengan hati menanamkan growth mindset pada mahasiswa. Dengan begitu, kampus bukan hanya mencetak sarjana, tetapi pemimpin perubahan yang siap berkontribusi bagi masyarakat.
Ilmu yang menggerakkan adalah ilmu yang hidup dalam praktik sosial. Perguruan tinggi perlu menata ulang paradigma pendidikan: menyeimbangkan tuntutan akademik dengan kebutuhan masyarakat. Para dosen hendaknya memanfaatkan pendekatan JD-R dan community of practice untuk membangun keterlibatan dan kolaborasi. Mahasiswa perlu diberi ruang untuk belajar dari lapangan, bukan sekadar dari literatur. Lembaga pendidikan wajib menjadikan aksi sosial sebagai indikator keberhasilan akademik baru.