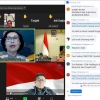Kembali ke masalah cinta, bisakah materi membelinya? Apakah cinta dapat terbeli dengan materi? Jawabannya: relatif. Tergantung pada diri tiap individu.
Ada yang berpendapat, lebih baik miskin tapi bahagia dari pada kaya tapi menderita. Mereka yang miskin membanding-bandingkan kebahagiaan diri mereka dengan orang kaya. Katanya, kekayaan tak menjamin kebahagiaan. Materi yang berlimpah bukan segalanya. Menurut mereka, orang kaya terlalu sibuk mengumpulkan harta sampai-sampai lupa meluangkan waktunya untuk orang yang mereka cintai. Kasih sayang terlupa, hanya harta yang selalu dipikirkan. Sementara orang miskin merasa paling bahagia. Walau tak berharta, tapi mereka punya cinta tanpa batas.
Apakah cinta saja cukup? Rasanya tidak. Bayangkan bila dalam sebuah pernikahan dilakukan hanya karena cinta. Lantas, dari mana sepasang suami-istri itu membiayai hidup mereka? Dari mana mereka mendapat pemasukan untuk mencukupi kebutuhan hidup? Belum lagi bila mereka memiliki anak. Tentunya perlu lebih banyak biaya lagi untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga baru yang mereka bangun bersama. Tak perlu jauh-jauh soal anak. Segala kemungkinan harus dipikirkan. Bagaimana salah satu atau keduanya mempunyai masalah kesehatan sehingga tak bisa mendapatkan keturunan? Perlu biaya besar untuk melakukan pengobatan dan konsultasi pada dokter spesialis Urologi? Apa semua itu dapat tercukupi hanya bermodalkan cinta? Dapatkah pernikahan tanpa materi bertahan lama? Pertengkaran, konflik, lalu perceraian. Masalah ekonomi rawan membuat sebuah keluarga hancur.
Sekarang ini, kita realistis saja. Wanita jauh lebih memilih pria mapan dibanding pria yang belum mapan. Setiap orang butuh materi. Tanpa materi, hidup takkan berjalan sebagaimana mestinya. So, pilihan mereka jatuh pada pria mapan.
Sekarang, bagaimana bila ada pria yang belum mapan ditawari peluang untuk hidup lebih baik? Pria yang cerdas dan logis tentunya akan menangkap peluang ini dengan mudah. Sebaliknya, pria yang idealis dan pemikirannya klise akan menolak peluang itu dengan angkuh dan penuh harga diri. Alasannya bermacam-macam: faktor pengaruh doktrin dari luar, ajaran keyakinannya, utang budi, keterikatan dengan suatu hal tertentu, gengsi, harga diri terlalu tinggi, kesombongan tingkat akut, dan pandangan idealis yang menyatakan "lebih baik miskin tapi bahagia".
Terus terang saja. Menurut saya, pendapat orang miskin itu bahagia sangat tidak realistis. Tidak logis dan terlalu klasik. Pandangan seperti itu sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman.
Contoh nyatanya sering saya saksikan sendiri. Di dekat rumah saya, seorang anak kecil tinggal bersama ayah dan kelima saudaranya. Pekerjaan sang ayah tak menentu. Mereka hidup berdesakan di sebuah rumah kecil. Sang ibu telah lama meninggal setelah melahirkan anak bungsunya. Kelima anak itu selalu saja kelaparan. Dulu, sewaktu ibunya masih hidup, si ibu pernah menyuruh anaknya mencuri buah-buahan milik Mama saya. Itu terjadi saat mereka benar-benar kelaparan dan tak mampu membeli makanan. Kini ibu mereka telah meninggal. Anak kecil itu dan saudara-saudaranya selalu saja terlihat muram dan sedih. Sering kali Mama memberikan makanan untuk mereka. Pada awalnya, mereka hanya menerima box berisi makanan itu begitu saja tanpa ucapan terima kasih. Tanpa senyuman pula. Sekarang mereka sudah mulai berubah. Bisa mengucapkan terima kasih dan lebih ceria. Nah, begitukah potret keluarga miskin yang bahagia?
Masih di dekat rumah, ada sebuah keluarga yang memiliki tiga anak. Si bungsu masih kecil. Dia satu-satunya anak perempuan di keluarga itu. Si anak bungsu dekat dengan Mama saya. Mama sering mengajaknya masuk ke rumah. Memperlihatkah koleksi boneka-boneka cantik di sana. Anak perempuan itu ingin mempunyai koleksi boneka yang sama. Sayangnya, orang tuanya tak mampu membelikan. Sering sekali anak itu menangis dan memohon-mohon pada orang tuanya untuk membelikan koleksi boneka seperti yang ada di rumah saya. Anak itu tak sadar kondisi ekonomi orang tuanya. Mama saya yang baik dan murah hati itu beberapa kali membawa boneka-boneka itu keluar rumah.
Membiarkan si anak bermain dan berfoto dengan koleksi boneka milik saya. Melihat itu, saya hanya bisa bersyukur dalam hati. Sepanjang ingatan, tak pernah saya meminjam mainan milik teman atau tetangga waktu kecil. Mama pun melarangnya. Karena apa? Karena di rumah saya semua jenis mainan telah tersedia. Mau boneka, puzzle, Barbie, buku bacaan, bahkan mobil-mobilan pun semuanya ada. Hanya karena kami pindah rumah, banyak barang kami yang hilang. Termasuk sejumlah koleksi mainan masa kecil. Tapi kalau urusan boneka, kami masih membelinya sampai sekarang. Kembali lagi ke anak perempuan dan keluarganya, ternyata mereka sering berutang untuk mencukupi kebutuhan hidup. Seperti inikah potret keluarga bahagia tanpa kecukupan materi?
Lain lagi dengan mantan supir keluarga kami. Dia memiliki banyak anak dan cucu. Anak-anaknya hanya bisa disekolahkan sampai tingkat sekolah menengah. Menikah muda dan hidup miskin, nampaknya sudah menjadi kebiasaan si mantan supir dan keluarganya. Kini saat keluarga kami sudah tidak memerlukan supir lagi, kami masih berhubungan baik dengannya. Tiap Lebaran, saat keluarga kami membukakan pintu lebar-lebar dan menyambut para tamu, mantan supir kami itu selalu datang. Ia selalu datang paling akhir saat para tamu lainnya sudah pulang. Mama tak pernah lupa menyiapkan uang dan bingkisan untuknya. Apakah keluarga semacam itu bahagia dengan kemiskinannya?
Waktu masih sekolah dua tahun lalu, saya mencoba berteman dengan siapa saja. Tidak memandang etnis, agama, dan status sosial ekonomi. Saya sering dicurhati teman-teman yang terhimpit secara ekonomi. Mereka sering mengeluh tidak punya cukup uang untuk membeli peralatan sekolah, tak bisa jalan-jalan dan wisata kuliner, serta bermacam keluhan lainnya. Selama berinteraksi dengan mereka, saya perhatikan ada beban keletihan di wajah mereka. Ada pula rasa pesimis dan putus asa. Selain itu, mereka cenderung underestimate dan menarik diri dari pergaulan. Berbeda dengan "geng OSIS" dan "grup ekstrakurikuler" yang saya ikuti. Lebih percaya diri, ekstrovert, optimis, dan dianggap anak populer serta idola sekolah. Anak-anak hits pokoknya. Bagaimana tidak hits? Rapat organisasi saja bisa di cafe? So, lebih bahagia mana? Mereka yang dari keluarga miskin atau keluarga yang berkecukupan?