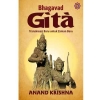Ini jalan Wastukencana, yang saya tahu, salah satu jalan yang masih menyimpan rimbun pepohonan. Membuat saya betah berlama-lama nongkrong di halaman Balai Kota, menghirup udara hijau dan memperhatikan orang-orang yang lalu lalang baik di jalan maupun di dalam taman. Tapi saya harus segera pulang, ini sudah jam dua siang, Ibu akan meradang dan mengatai saya anak perempuan jalang kalau saya terlambat datang.
Saya adalah pelajar, penerus bangsa dan negara, bagaimana jadinya kalau saya selalu mangkir dari jadwal hidup yang sudah ditetapkan Ibu sang perdana menteri rumah tangga? Maka saya berjalan lunglai keluar dari taman, keluar dari udara siang yang segar menuju udara berbau karbon monoksida yang akan membuat paru-paru saya meradang.
Tapi saya tidak punya ongkos pulang. Ah, sial. Kenapa menjadi pelajar sangat menyiksa? Uang bekal saya sudah habis dibelikan mie ayam untuk mengganjal perut saya yang lapar sehabis latihan mengibarkan bendera.
Itu di sana ada bapak-bapak memakai setelan dinas baru keluar dari mobil, saya hampiri dia.
“Selamat siang, Pak,” sapa saya.
Dia menoleh sebentar, tatapannya curiga. Bukan, Pak. Saya bukan pengemis atau teroris. Mana ada teroris yang memakai seragam abu-abu. “Ada apa?” tanyanya.
“Saya mau pulang, tapi saya tidak punya ongkos,” kata saya lugas. Saya tidak memasang tampang memelas atau intonai suara yang lemas. Untuk apa? Toh saya bukan sedang berakting di acara reality show.
Dia memandang saya sebentar. “Kamu murid SMK 1 Bandung ya?” dia menunjuk jas almamater berwarna biru muda yang tersampir di bahu saya.
Saya mengangguk.
Dia merogoh dompet dan memberikan uang lima ribu rupiah.
“Ongkos angkot Sarijadi hanya dua ribu lima ratus, Pak. Kasih saja uang pas.”
Keningnya berkerut. “Ambil saja kembaliannya,” dia lalu berjalan tergopoh. Sangat terburu-buru. Mungkin ia mau menghadiri rapat untuk membicarkan nasib bangsa, ah sudahlah.
Tapi harus saya kemanakan uang dua ribu lima ratus sisanya? Saya berikan kepada pengemis? Tidak ada pengemis di sekitar jalan Wastukencana sampai ke Viaduct. Membeli minuman dingin? Tidak, itu sama saja saya berkhianat terhadap bapak tadi. Saya kan bilang tidak punya ongkos pulang, bukannya haus dan ingin membeli minuman.
Ah, sepanjang jalan saya merenung, mencari jalan yang pantas untuk menghabiskan uang dua ribu lima ratus itu. Tak jua saya temukan sampai saya naik angkot St.Hall – Sarijadi.
Sampai di depan kampus UKM (Universitas Kristen Maranatha) saya turun dari angkot, memberikan selembar uang lima ribu tersebut dan mendapat uang kembalian; uang yang membuat saya bingung. Saya selipkan uang tersebut di saku seragam sekolah. Saya berjalan pulang masih dengan hati gundah. Tidak terpikir lagi wajah Ibu yang pasti akan memberenggut marah.
Uang kembalian itu masih saya simpan di saku seragam keesokan harinya. Tidak berani saya pakai untuk membeli lumpia basah waktu istriahat tiba. Tidak berani saya pakai untuk membeli limun berasa jeruk yang warna dan dinginnya begitu menggoda.
Tapi saya menyerah ketika perut saya bergejolak marah. Saya membeli dua buah gorengan dan segelas minuman gelas. Bukan, bukan dari uang kembalian itu, melainkan uang bekal saya sendiri yang diberikan Ibu tadi pagi.
Sepulang sekolah saya kembali duduk di taman Balai Kota untuk mengisi paru-paru saya dengan udara pepohonan. Mohon maklum, di tempat tinggal saya sendiri, pepohonan sudah berganti pohon-pohon beton dan kebun aspal. Saya perlu udara segar.
Biarlah Ibu kembali marah karena saya telat pulang satu dua jam, asalkan paru-paru saya ramah. Saya duduk selonjoran sambil membaca novel Ronggeng Dukup Paruk yang saya pinjam dari perpustakaan. Teman-teman saya yang lain saat ini sedang berdesakan di BIP, beberapa mungkin sedang nongkrong di café, beberapa yang lain mungkin sedang berpacaran. Saya tidak, saya lebih senang duduk selonjoran di taman dan membaca. Bukan karena saya aneh atau tidak gaul atau tidak mau pacaran, tapi karena saya tidak memiliki modal untuk nongkrong di café atau jalan-jalan di mall.
“Eh, kamu anak perempuan yang kemarin kan?” tanya seseorang.
Saya membetulkan letak kaca mata, mendongak. Ah, itu dia bapak yang memberi saya ongkos angkot kemarin.
“Masih tidak punya ongkos pulang?” tanyanya, duduk di sebelah saya, di trotoar taman.
“Nggg… ini ada uang kembalian dua ribu lima ratus, apa saya boleh pakai untuk ongkos pulang?”
“Uang yang kemarin saya beri itu?”
Saya mengangguk.
“Kenapa kamu tidak langsung pakai saja? Uang itu kan sudah saya berikan ke kamu, semuanya.”
“Tapi kan kemarin saya minta untuk ongkos kemarin, saya tidak minta untuk ongkos hari ini. Nah, kebetulan sekali kita bertemu, jadi sekalian saja saya minta ijin.”
Dia tertawa. Dia mengeluarkan dompet dan mengangsurkan selembar uang lima puluh ribu. “Ini untuk kamu, cukup lah untuk ongkos satu minggu.”
Saya menggeleng. “Tidak usah, terima kasih.”
“Lho, kenapa? Daripada nanti kamu tidak bisa pulang karena kehabisan ongkos seperti kemarin, lebih baik simpan saja uang ini,” dia berusaha membuat saya menerima uangnya.
“Saya kan tidak tahu apakah besok saya kehabisan ongkos atau tidak. Lagipula, tidak setiap hari saya kehabisan ongkos, kok. Biasanya uang jajan yang diberikan ibu saya cukup untuk jajan dan ongkos pulang pergi. Bapak simpan saja uang itu, Bapak kan punya anak, punya istri. Pasti lebih butuh uang itu daripada saya yang hanya pelajar ini. Saya kan belum punya tanggung jawab finansial terhadap siapa-siapa,” itu penjelasan saya. Saya sendiri juga heran, bagaimana mungkin saya bisa berbicara panjang lebar.
Kening bapak di samping saya berkerut, berlipat-lipat. “Saya yakin kamu lebih butuh uang ini.”
“Karena saya orang miskin?”
“Bukan, tapi karena saya tidak mau melihat kamu luntang-lantung di balkot dan mencari ongkos untuk pulang ketika seharusnya kamu belajar di rumah,” wajahnya serius, lebih serius dari wajah Bapak jika sedang memarahi saya kalau hobi saya menclok di atas genting kumat.
Saya mengangkat bahu. “Saya senang berada di sini, bisa membaca tanpa dimarahi Ibu. Lagipula saya senang berada di tengah pepohonan rimbun, udaranya bagus.”
“Ambil lah!” ia menyelipkan uang lima puluh ribu itu ke telapak tangan saya. “Dengan begini, kamu bisa pulang kapan saja. Saya tidak mau melihat kamu kesulitan, mengerti? Tidak semua orang di sini bisa memberi dengan suka rela kalau dimintai ongkos pulang oleh pelajar,” dia bangkit, berjalan menjauh sebelum saya sempat mengembalikan uang yang dia berikan.
“Terima kasih!” saya berteriak.
Dia melambaikan tangan, tersenyum, kemudian kembali berjalan.
“Orang baik, jarang ada,” gumam saya. Saya kembali duduk, membaca, tapi kali ini saya tidak perlu khawatir memikirkan ongkos pulang.
**
Ilustrasi: wallpaper bawaan netbook