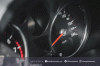Liburan Ramadan kali ini, saya memutuskan untuk pulang kampung. Bukan ke kota besar dengan kereta cepat (KAI) seperti di Jakarta, melainkan ke kampung halaman di Flores, tempat di mana bus kayu masih menjadi salah satu moda transportasi andalan. Di tengah perkembangan teknologi transportasi, pengalaman naik bus kayu ini terasa seperti menembus ruang waktu, ada aroma kenangan, kesederhanaan, dan kehangatan yang tak tergantikan.
Hari itu, usai menyelesaikan pekerjaan, saya buru-buru mencari ojek menuju terminal. Jam di tangan saya menunjukkan pukul 12.00 siang. Bus kayu yang akan membawa saya ke arah Manggarai Timur dijadwalkan berangkat pukul 13.00, jadi masih ada waktu satu jam. Terminal kecil itu ramai seperti biasa. Sambil menunggu, saya sempatkan diri belanja kebutuhan rumah, beberapa bahan makanan dan jajanan untuk cemilan di perjalanan.
Setelah belanja, saya menyapa sopir bus, sosok yang ramah dan sudah terbiasa melihat wajah-wajah penumpang kampung yang selalu membawa cerita. "Pak, kapan berangkat?" tanya saya. Ia menjawab, "Lima belas menit lagi, kita jalan." Jawaban itu langsung memacu saya untuk bergerak cepat. Saya segera mencari tempat makan terdekat, menyantap makan siang seadanya, lalu membeli beberapa cemilan untuk bekal di perjalanan dan mungkin juga untuk dibagi.
Akhirnya, mesin bus kayu mulai meraung pelan. Beberapa penumpang mulai menaiki kendaraan yang sudah tak muda lagi, tapi masih setia mengaspal jalanan Flores. Begitu bus mulai melaju, pemandangan yang terbentang di luar jendela seolah menyambut hangat. Sawah-sawah menghijau kekuningan, pertanda musim panen telah tiba. Beberapa petani tampak sibuk memotong padi, membawa hasil bumi dengan wajah penuh syukur.
Suasana di dalam bus pun hangat. Alunan musik yang diputar oleh sopir menemani perjalanan kami. Tidak ada AC atau kursi empuk, tapi suasana kekeluargaan terasa begitu kental. Saya membuka kantong plastik berisi cemilan, lalu membagikannya kepada penumpang lain. Tawa kecil dan ucapan terima kasih menjadi teman perjalanan yang tak tertulis dalam tiket.
Setelah beberapa jam, bus akhirnya tiba di perbatasan antara Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Ngada. Di sinilah saya harus turun karena jalur bus tidak sampai ke kampung saya. Perjalanan masih harus dilanjutkan dengan berjalan kaki. Medan yang menanti tidak main-main. Saya harus menempuh dua jam perjalanan melewati tanjakan terjal berbatu, jalan tanah yang licin dan becek akibat hujan sebelumnya, serta menyeberangi dua anak sungai.
Air sungai tidak terlalu deras, hanya sebatas pinggang, tapi cukup membuat celana saya basah dan sedikit dingin. Airnya keruh, mungkin karena baru beberapa jam lalu hujan turun cukup deras di daerah itu. Tapi semua itu saya jalani dengan hati yang gembira. Ada semacam rasa syukur dalam setiap langkah meski medan terasa berat. Di antara desir angin, suara dedaunan, dan gemericik air sungai, saya merasa kembali ke akar, ke tempat di mana kehidupan mengalir dalam irama yang sederhana.
Akhirnya, sekitar pukul lima sore, saya sampai juga di rumah. Disambut pelukan hangat orang tua dan sapaan hangat dari sanak saudara. Rasa lelah langsung berubah menjadi rasa bahagia yang tak bisa diukur.
Perjalanan ini memang tak seperti naik kereta cepat atau pesawat terbang. Tapi inilah keindahan dari kampung halaman. Perjalanan panjang yang mengajarkan kesabaran, kehangatan, dan rasa syukur. Naik bus kayu mungkin sederhana, tapi cerita yang ditinggalkannya akan selalu melekat di hati.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI