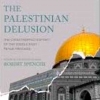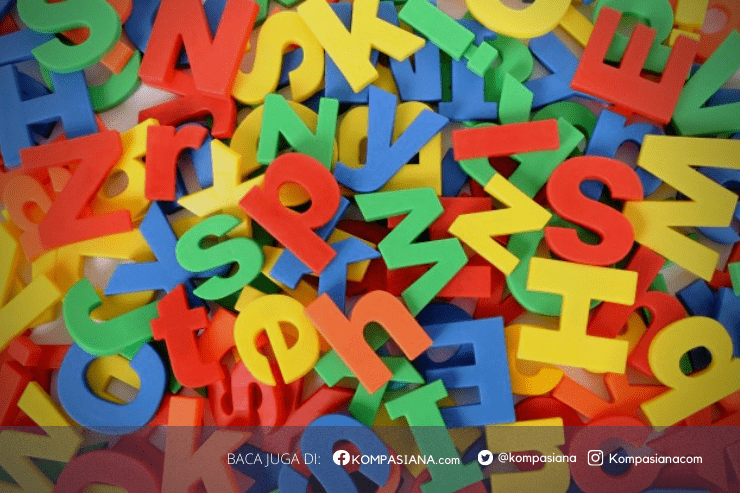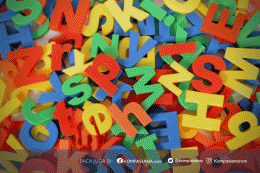Indonesia dikenal sebagai negeri yang memiliki kekayaan bahasa luar biasa---sebuah mosaik linguistik yang tak tertandingi di kawasan Asia Tenggara. Nasrullah, dkk (2024) dalam data Risalah Kebijakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2024 menyatakan terdapat 718 bahasa daerah yang teridentifikasi dan masih digunakan di berbagai penjuru Nusantara. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah bahasa terbanyak di dunia, hanya kalah dari Papua Nugini dan Nigeria. Kekayaan tersebut tidak sekadar angka; setiap bahasa adalah representasi budaya, sistem nilai, dan cara pandang unik terhadap dunia. Bahasa daerah bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga penyimpan pengetahuan lokal---tentang flora, fauna, adat istiadat, bahkan filosofi hidup yang diwariskan lintas generasi.
Namun, di balik kebanggaan itu, terdapat paradoks yang mengkhawatirkan. Dalam laporan UNESCO (2023) bertajuk Making Indonesian Indigenous Language Scripts Available Online, disebutkan bahwa lebih dari 11% bahasa daerah Indonesia kini berstatus terancam punah, dan sebagian bahkan sudah kehilangan penutur aktif. Fenomena ini bukan semata akibat perubahan zaman, tetapi hasil dari pergeseran bahasa (language shift) yang terjadi secara sistematis: dari bahasa ibu menuju Bahasa Indonesia atau bahasa asing seperti Inggris. Dalam konteks modernisasi, banyak keluarga---terutama di wilayah perkotaan---lebih memilih berkomunikasi dengan anak-anak mereka dalam Bahasa Indonesia demi alasan prestise, akses pendidikan, dan kemudahan integrasi sosial. Ironisnya, pilihan ini perlahan mengikis transmisi bahasa ibu, menjadikan banyak bahasa lokal kehilangan penutur muda dan hanya bertahan di kalangan lanjut usia.
Bahasa Ponosakan di Sulawesi Utara adalah contoh nyata dari krisis linguistik tersebut. Penelitian Rahima (2024) menunjukkan bahwa bahasa ini kini hanya dituturkan oleh tiga orang lansia di daerah Tombatu. Kondisi serupa terjadi pada bahasa Nedebang di Alor, bahasa Hukumina di Maluku, dan sejumlah bahasa kecil di Kalimantan yang kini nyaris tidak lagi digunakan secara aktif. Setiap kali sebuah bahasa mati, hilang pula cara unik suatu masyarakat memahami dunia. Sebagaimana dinyatakan oleh Crystal (2000), "When a language dies, it takes with it an entire intellectual heritage." Kehilangan satu bahasa berarti kehilangan satu jendela kebijaksanaan manusia.
Di Indonesia, ancaman kepunahan bahasa daerah juga diperparah oleh keterbatasan dokumentasi dan akses pendidikan. Banyak bahasa daerah belum memiliki sistem tulisan baku, belum terdokumentasi dalam bentuk kamus, rekaman, atau teks digital. Hadiwijaya, dkk (2023) menemukan bahwa 78% bahasa daerah Indonesia belum memiliki bahan ajar formal dan belum masuk ke kurikulum sekolah dasar. Selain itu, ketimpangan infrastruktur digital membuat upaya pelestarian sulit dilakukan di daerah terpencil. Padahal, seperti diingatkan oleh UNESCO (2022) dalam program Decade of Indigenous Languages (2022--2032), "Digital presence is a lifeline for endangered languages"---kehadiran di ruang digital adalah syarat hidupnya sebuah bahasa di abad ke-21.
Kesadaran akan ancaman tersebut mendorong pemerintah Indonesia mengambil langkah sistematis melalui kebijakan Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD). Program ini, diluncurkan oleh Kemendikbudristek dalam kerangka "Merdeka Belajar Episode 17" sejak tahun 2021, bertujuan "menekan laju kepunahan bahasa daerah dengan pendekatan berbasis komunitas dan pendidikan." (Radjalewa, 2024; Rohana, dkk, 2024). Nasrullah, dkk (2024) dalam data Risalah Kebijakan Badan Bahasa 2024, revitalisasi dilakukan dengan melibatkan siswa, guru, dan budayawan lokal melalui kegiatan kreatif seperti lomba mendongeng, menulis puisi, mencipta lagu daerah, hingga festival bahasa. Hingga tahun 2024, tercatat 96 bahasa daerah di 21 provinsi telah direvitalisasi, dengan target 120 bahasa pada 2025--2029. Program ini tidak hanya berfokus pada pelestarian, tetapi juga pada penguatan identitas linguistik di kalangan generasi muda.
Meskipun demikian, efektivitas program RBD masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Studi yang dilakukan oleh Andina (2023) menunjukkan bahwa kendala utama pelaksanaan program adalah lemahnya koordinasi lintas lembaga, keterbatasan dana, dan kurangnya guru bahasa daerah yang terlatih. Banyak sekolah di tingkat SD dan SMP belum mampu memasukkan bahasa daerah dalam kegiatan belajar karena ketiadaan bahan ajar dan standar kurikulum yang seragam. Selain itu, Kartika (2023) menambahkan bahwa banyak program revitalisasi masih bersifat event-based---sekadar festival tahunan tanpa tindak lanjut berkelanjutan di tingkat kebijakan daerah. Akibatnya, meskipun kesadaran publik meningkat, hasil jangka panjangnya belum signifikan terhadap vitalitas bahasa.
Dalam menghadapi tantangan ini, para ahli sosiolinguistik menekankan pentingnya menerapkan model multilingualisme fungsional (functional multilingualism). Model ini mengakui bahwa setiap bahasa memiliki domain penggunaannya masing-masing: Bahasa Indonesia digunakan sebagai lingua franca dalam pendidikan, media, dan administrasi publik; sementara bahasa daerah tetap hidup dalam ranah budaya, keluarga, dan komunitas lokal. Pendekatan ini terbukti efektif di negara multibahasa seperti Swiss dan India, di mana keberagaman linguistik justru menjadi kekuatan nasional. Penelitian Sewell (2022) menegaskan, "Harmony in language policy is achieved not by suppressing linguistic diversity, but by defining functional boundaries among languages."
Selain pendekatan kebijakan, teknologi digital kini membuka jalan baru bagi pelestarian bahasa. AI (Artificial Intelligence) dan teknologi Natural Language Processing (NLP) digunakan untuk mendokumentasikan dan mempelajari bahasa-bahasa minoritas secara efisien. Proyek NusaX, yang dikembangkan oleh komunitas riset Indonesia bekerja sama dengan HuggingFace (Winata, dkk, 2023) telah menciptakan dataset multibahasa paralel yang mencakup sepuluh bahasa daerah seperti Jawa, Sunda, Bali, Minangkabau, dan Bugis. Inisiatif ini memungkinkan pengembangan aplikasi pembelajaran, kamus daring, dan sistem pengenalan suara berbasis bahasa lokal. Selain itu, Nasrullah (2024) melaporkan bahwa AI kini dimanfaatkan untuk melakukan transkripsi otomatis bahasa lisan dan membantu peneliti membuat korpus digital yang bisa diakses publik. Dengan demikian, bahasa daerah tak lagi sekadar milik komunitas kecil, tetapi dapat hadir di ruang global---diakses, dipelajari, dan digunakan oleh siapa saja.
Namun, teknologi hanyalah alat; keberlanjutan bahasa tetap bergantung pada manusianya. Revitalisasi sejati hanya terjadi bila komunitas penutur merasa bangga dan aktif menggunakan bahasa mereka dalam kehidupan sehari-hari. Itulah sebabnya program RBD 2024 memfokuskan pelibatan siswa dan guru dalam kegiatan kreatif. Hingga kini, lebih dari 200.000 pelajar di seluruh Indonesia terlibat dalam lomba menulis dan mendongeng dalam bahasa ibu. Kepala Badan Bahasa, Aminudin Aziz (2024) dalam Portal Jabar (2024), menegaskan bahwa "Revitalisasi tidak bisa dipaksakan dari atas; ia harus tumbuh dari bawah, dari komunitas yang mencintai bahasanya." Di sinilah letak kekuatan sejati kebijakan linguistik Indonesia: memadukan pendekatan top-down (kebijakan negara) dan bottom-up (inisiatif masyarakat).
Kedepannya, strategi revitalisasi perlu diarahkan pada kolaborasi lintas sektor: pemerintah menyediakan dukungan regulasi dan anggaran; perguruan tinggi mendokumentasikan dan meneliti bahasa; komunitas lokal menjadi pelaksana; dan perusahaan teknologi membantu digitalisasi. Selain itu, penting untuk menetapkan indikator keberhasilan berbasis bukti (evidence-based metrics), seperti peningkatan jumlah penutur muda, kehadiran bahasa di media sosial, serta jumlah karya sastra dan materi ajar berbahasa daerah yang terbit setiap tahun. Hal-hal ini menjadi ukuran konkret yang menandakan bahwa bahasa daerah bukan sekadar diselamatkan, tetapi dihidupkan kembali dalam konteks modern.
Akhirnya, upaya menjaga keragaman bahasa adalah bagian integral dari menjaga perdamaian dan keindahan Indonesia. Semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" menemukan maknanya yang paling dalam ketika diterjemahkan ke dalam konteks linguistik: kita berbeda dalam bahasa, tetapi bersatu dalam makna. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jembatan nasional, sementara bahasa daerah menjadi akar yang menjaga keseimbangan budaya. Seperti ditegaskan oleh Risalah Kebijakan Badan Bahasa (2023): "Bahasa adalah pelindung nilai, bukan sekadar sistem bunyi. Jika bahasa terawat, maka bangsa akan terjaga."